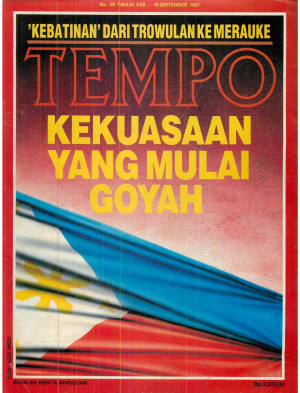ANWAR terbaring di ranjang, masih mengenakan seragam lengkap. Lengan bajunya tergulung, barangkali bekas transfusi darah. Aku menjatuhkan diri di dadanya. Entah berapa lama aku terbenam dalam kesedihan. Itulah saat yang paling sulit dalam hidupku. Memandang tubuh seorang lelaki yang terbaring kaku, yang senyumnya beberapa jam lalu bagai cahaya ribuan lilin. Aku menangis, tanpa suara. Aku harus hati-hati. Resminya, belum seorang pun tahu Presiden Sadat gugur. Dan tak seorang pun boleh tahu sampai kami yakin betul bahwa keadaan sudah dapat diatasi dan negara dalam keadaan aman. Saya mengusap rambutnya, mencium pipi dan tangannya. Betulkah ia telah mati? Aku tak melihat bekas luka atau bekas darah. Aku ingin betul membangunkannya. Hassan, menantuku, menghampiriku. Aku menyuruhnya memanggil semua anakku yang masih berada di ruang tunggu. "Tidak, tidak," ia tak mau percaya bahwa mertuanya sudah mati. Ratap tangis pun meledak, mereka berulang kali mencium pipi dan tangan ayah mereka seraya membasahi tubuh itu dengan air mata. Inna lillahi, wa inna ilaihi raji'un. La illaha ill Allah wa Muhammad Rasul Allah. Dari Allah kita berasal dan kepada-Nya kita kembali. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. "Tuan Presiden," kataku kepada Mubarak ketika aku sudah berada kembali di ruang tunggu. "Anwar telah pergi dan tak akan kembali lagi. Ini semua kehendak Allah. Tapi Mesir masih ada dan kini dalam keadaan bahaya. Kini saatnya Anda memimpin kami." Di halaman banyak yang menunggu, di antaranya para anggota parlemen. Mereka ini belum tahu keadaan sesungguhnya, tapi tampaknya mereka sudah menduga. Dalam perjalanan pulang, sopirku tak henti-hentinya menangis keras. Karena tangisnya itulah, para staf yang bekerja di rumah kami tahu yang menimpa majikan mereka. Aku sendiri tak kuasa mengatakan apa-apa. Begitu sampai di rumah aku segera lari ke balkon, di luar kamar Anwar, tempat ia biasa duduk merenung sambil melihat Sungai Nil. Akhirnya, di tempat ini, aku bisa menangis bebas, melepaskan semua kesenduan dan kedukaan ditinggal seorang lelaki yang telah 32 tahun menjadi suamiku, seseorang yang telah membayar mahal untuk pandangannya tentang perdamaian dan demokrasi. Sehari telah berlalu. Di tengah kesibukanku menerima ucapan belasungkawa, Perdana Menteri Fuad Muhi meminta izin mengambil peluru yang bersarang di tubuh suamiku untuk keperluan penyelidikan. Aku bilang boleh saja, tapi aku harus berada di sana ketika otopsi dilakukan. Aku juga minta, agar mereka menunggu anakku Gamal."Berilah ia kesempatan mengucapkan kata perpisahan dengan ayahnya yang mati ketika ia tak berada di sisinya," kataku. Sebetulnya, aku punya alasan lain yang tak mungkin kukatakan kepada Perdana Menteri. Gamal anggota klub menembak dan sering pergi berburu dengan ayahnya. Dia tahu banyak tentang jenis dan tipe peluru. Aku ingin agar ia melihat jenis peluru yang menewaskan ayahnya. Benarkah peluru itu berasal dari senjata teroris, atau berasal dari senjala lain. Siapa tahu, Anwar ditembak dari belakang oleh seorang Islam fanatik, atau oleh pejabat pemerintah yang memanfaatkan kekacauan. Dalam keadaan begini, aku ak mempercayai siapa pun. Gamal akhirnya tiba. Setelah kunasihati agar jangan terlalu berduka, ia harus menunjukkan sebagai anak Sadat yang tabah, kucertakan perlunya menunggui otopsi. Aku tak pernah melihatnya begitu tenang. Biasanya aku selalu membangunkan dia pukul 9 pagi. "Biarkan aku tidur 10 menit lagi," begitu katanya setiap kali aku membangunkannya. Matanya sering kelihatan bengkak karena kurang tidur. Badannya masih begitu sempurna. Yang aku lihat hanya tiga luka kecil, satu di kaki dan dua lagi di dada. Rasanya aku tak percaya, luka sekecil itulah yang telah menjatuhkan dan merenggutkan hidup seorang lelaki. Aku mendekat, menyentuhnya. Aku mencium kepalanya untuk terakhir kali. Dia telah beku bagai es. Gamal tak dapat menahan air mata begitu melihat tubuh kaku ayahnya. Sambil selalu mengusap air mata yang meleleh di pipinya, ia memperhatikan dokter yang sedang membedah dada ayahnya dan mengeluarkan sebutir peluru. Gamal mengambil anak peluru itu dan menelitinya beberapa saat. Peluru itu memang berasal dari senjata otomatis seperti yang digunakan oleh para teroris ketika menyerang suamiku. * * * Enam bulan setelah peristiwa itu, pemerintahan Mubarak mengajukan lima anggota kelompok Islam militan ke depan pengadilan. Mereka kemudian dieksekusi sesuai dengan vonis yang dijatuhkan. Tak tahan dengan berbagai kritik yang dilemparkan musuh-musuh politik suaminya justru setelah ia mati, pada 1985, Jehan meninggalkan Mesir menuju Amerika. Kini sisa hidupnya ia habiskan di dua tempat, Mesir dan Washington. Ia mengajar di universitas. (Lihat Selanjutnya: Pilihan Jehan)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini