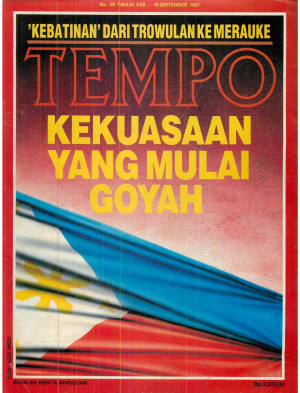DEBURAN ombak di Pantai Pariaman, Sumatera Barat, sayup ditingkah suara gendang tasar yang ditabuh bertalu-talu. Dum-drum-dum-dum . . . dum. Dan menjelang pagi, Bagindo Syahbuddin, 72 tahun, di Desa Jawi-jawi, bersama delapan anak buahnya, belum lelap sepicing pun. Mereka tengah merampungkan tabut. Jarak satu kilo -- di Desa Pasar -- sekawanan penduduk lainnya juga sama. Kemudian mereka siap mahoyak tabuik untuk mengenang Hosen. Cucu Nabi itu tewas secara tragis di medan Perang Karbala, 10 Muharam 64 H. Menurut para penganut Syiah, jasad Hosen yang tercincang cerai-berai, lalu dijemput malaikat dan digotong ke langit dengan buraq. Dalam versi kaum Syiah di Pariaman, tabut adalah lambang sang buraq. Ratap tangis atau mahatam lalu juga khas dalam upacara mahoyak tabuik hingga ke laut lepas. Tapi selebihnya memang keramaian. Ada pasar kaget, ada turis bule, ada perantau yang pulang kampung -- melepas taragak alias rindu tontonan ini. Tahun ini peringatannya jatuh pada 6 September lalu. Disiapkan selama sembilan hari, biaya sekitar Rp 6 juta, yang dikumpulkan dari penduduk 50 desa. Tradisi ini tumbuh di sana sejak seabad silam, dibawa bangsa Cipei dari India yang kala itu sebagai serdadu Inggris di Bengkulu. Namun, acara ini sempat lenyap 10 tahun, karena pernah menjadi ajang baku hantam masal. Gawat. Acara mahoyak hidup lagi tujuh tahun belakangan ini, setelah Anas Malik menjadi bupati Padang Pariaman. Aturan main diperbaiki, dan Tabuik Piaman kini berperan sebagai, ha-ha-ha, komoditi nonmigas. Dan dengarlah apa kata Anas Malik, "Tabut ini saya namakan tabut adat, tabut pariwisata, dan tabut pembangunan. Yaah? tabut untuk kita semua, lah." Aa . . ., rancak bana tu Jo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini