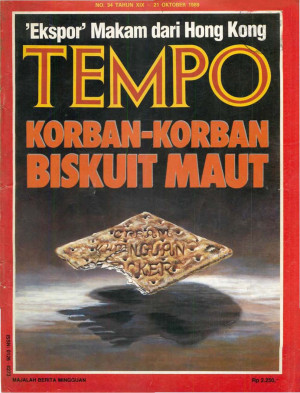MASIH pagi. Matahari belum sepenggalah. Mahmudin terus mengayunkan kapaknya yang bergagang panjang. Kulitnya yang berwama tembaga terbakar matahari, dimabuk oleh keringat. Lalu, pangkal pohon meranti berlingkaran lebih dari semeter itu menganga dan berderak keras, bagaikan raungan hantu di tengah belantara. Kraaaaak... grusak.... Pohon setinggi 20 meter itu tumbang dan nyangsang di pohon lain. Mahmudin dan teman-temannya berusaha keras menyingkirkan penghalang. Namun naas. Markamin, 17 tahun, yang baru dua kali menyatroni hutan, mendadak berteriak kesakitan. Jeritannya bagaikan mengoyak hutan. Kaki kirinya tertimpa pohon. Baru satu jam kemudian, rombongan dalam petak penebangan beranggota sepuluh orang itu berhasil menyingkirkan pohon sialan ini. Markamin yang tak sadarkan diri segera digotong. Dengan speed boat, anak muda yang celaka itu dibawa ke kota kecamatan. Malang, tak ada dokter di sana. Ia harus dibawa ke Sintang, enam jam perjalanan dari lokasi. Syukur, kaki Markamin tak perlu diamputasi. Hanya saja, lima jari kakinya gepeng. "Celake memang se'an bemate (Sial memang tak bermata)," tutur Mahmudin, kepala kelompok petak tebang, menceritakanmusibah enam bulan lalu itu. Kecelakaan semacam itu bukan barang baru. Mahmudin sendiri pemah mengalaminya beberapa tahun silam. Jempol dan satu jari kanannya tersabet kapak, lantas terpental beberapa meter. Namun, petaka macam itu sudah dianggap jamak dalam proyek penebangan hutan. "Masih untung, hanya kehilangan jari tangan atau kaki," kata Husin Matulamar, buruh tebang asal kampung Telukkalong, Sambas, Kalimantan Barat. "Ada teman kami, setelah satu malam terjepit pohon, baru ketahuan. Ya, mati. Namanya Undak," tambah laki-laki berusia 36 tahun ini dengan logat Sambas yang kental. Kecelakaan paling banyak terjadi di awal penebangan pada 1970-an. Saat itu hutan masih rapat. Sedangkan para buruh tebang sangat bernafsu mengejar uang karena harga kayu balok sedang meroket. Kini kendati hutan untuk dibabat semakin merasuk ke jantung Kalimantan, taraf hidup mereka -- yang telah bersatu dengan kapak dan pepohonan selama bertahun-tahun tak juga mencuat. Alih profesi? Mustahil. "Mau kerja apa di kampung, apalagi di kota," ujar Mian, 40 tahun, ayah tiga anak yang meningkat remaja, "anak dan bini kan harus makan dan sekolah. Belum lagi kalau Lebaran." Seperti Mian dan Mahmudin, untuk menyambung hidup, para buruh hutan hanya mengandalkan kapak. Mereka menyusuri hutan dari satu proyek ke proyek yang lain. Tak hanya merambah hutan pekat di Kalimantan. Mereka juga tak segan-segan menyeberang ke Sumatera, bermodalkan kapak dan keuletan yang dimiliki warga Sambas turun-temurun. Apa yang sudah mereka peroleh? "Hanya anak," kata Mahmudin lagi. Laki-laki kekar, berasal dari Kampung Pimpinan, Sambas, ini mulai bekerja sebagai buruh PT (potong-tarik) sejak berusia 16 tahun. "Kami di kampung tak cukup hanya berladang. Hasilnya tidak memadai," katanya lebih lanjut. Suatu hal yang menyakitkan hatinya, ia harus membesarkan anak-anak sendirian. Dua kali ia ditinggal istrinya. Istri pertama meninggal saat melahirkan anak ketiga. Sedangkan istri kedua minggat dengan menitipkan satu anak. Dalam sejarah eksploatasi hutan, kisah tragis bukan sekadar dongeng. Tidak sedikit istri kehilangan suami. Entah karena tertimpa kayu, disambar buaya, digerogoti malaria, tifus, atau penyakit lain. Jangan tanya dokter, mantri saja tidak ada. Sering terjadi, ayah atau kakek kehilangan keturunannya tanpa sempat melihat seperti apa rupa mayat anak dan cucunya. Demi sesuap nasi, belasan ribu buruh tebang asal Kabupaten Sambas meninggalkan kampung, menjelajah pelosok rimba. Tak ada kata putus asa. Hutan sepekat apa pun mereka tusuk. Mereka dilahirkan untuk menundukkan belantara. "Dalam sebulan, seorang penebang menebang sedikitnya 150 pohon," kata Sugeng Widodo, Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Barat. Seorang buruh mengaku bahwa ia mampu menumbangkan delapan batang setiap hari. Malah, kalau lingkarannya hanya 60 sentimeter, bisa dua belas batang. Umumnya, tenaga manusia dipakai di kawasan hutan rawa. Sebab, biaya eksploatasinya jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan menggunakan alat-alat berat. Lebih dari itu, tenaga mekanik alat berat yang beroperasi di hutan tergolong langka. Sering tenaga asing disewa untuk proyek dataran ffnggi. Namun, kenyataannya jenis hutan dipteroceae cenderung hidup di dataran rendah. Sebenarnya, upah yang diterima karyawan tebang lebih dari lumayan. Untuk jenis meranti mereka bisa mengantungi Rp 4 ribu hingga Rp 5 ribu per m3. Sementara itu, untuk pohon campuran, rengas dan sejenisnya, Rp 3 ribu. "Kedengarannya be, basar. Mun, diitung-itung be bise jadi tekor" (Kedengarannya sih, besar. Tapi, kalau dihitung-hitung, malah tekor)," kata Sabran, bujangan berumur 20 tahun, yang sudah dua tahun sebagai buruh PT. Yang aneh -- tapi nyata -- setiap buruh bergantung pada calo. Lewat calo inilah calon penebang memperoleh persekot antara Rp 30 ribu dan Rp 50 ribu sebagai uang muka guna menghidupi keluarganya selama ditinggal pergi -- lamanya bisa sampai tiga bulan. "Pinjaman" itu sudah termasuk biaya membeli peralatan. Belum lagi mesti membuat surat jalan dan surat keterangan lain dari RT atau lurah. Bahkan komisi untuk calo pun harus dibayar di muka. Calo mungkin juga merangkap sebagai kepala rombongan. Tapi, tugasnya berbeda dengan kepala kelompok petak tebang. Setelah sejumlah buruh tebang terkumpul, segera calo mengirim mereka dengan motor tambang. Dijejalkan saja seperti ayam potong yang dikirim ke pasar. Ongkos angkut, ke lokasi dan kembalinya, ditanggung tauke alias kontraktor. Setelah sehari di base camp, para buruh tebang siap mengayun kapak di petak-petak tebangan. Sejak itu pula seluruh biaya hidup jadi tanggungan masing-masing. "Kalau tiga hari tidak ada kayu, berarti kami tekor," ucap Mahmudin, sang kepala petak. Kalau masih melompong, para buruh harus pindah petak. Berarti uang bekal makin menipis. Untung, ada tauke. Mereka boleh mengebon makanan, rokok, dan kebutuhan lain, tentu, dengan harga mencekik leher. Kalau tak pandai-pandai berhemat, mereka akan terbelit utang sampai batas kontrak yang tiga bulan berakhir. Dalam keadaan terjepit, mereka terpaksa memperpanjang satu atau dua bulan hingga utang impas. Praktis, kalaupun ada kelebihan uang, jumlahnya tak sebanding dengan keringat yang menetes. "Paling besar, kalau bersih tak berutang, pulang bawa Rp 100 ribu," kata seorang buruh. Malah, ada yang membawa pulang cuma uang rokok. Toh, mereka tetap bersyukur bisa kembali dengan selamat. Jadi, siapa yang menikmati hasilnya? Sudah tentu, para kontraktor. Sedangkan penghasilan calo pun ternyata cukup besar. Buktinya, ada yang bisa membeli mobil, tanah, dan rumah. Ahmad Hitam, misalnya, bisa membeli kolt setelah bertahun-tahun jadi pencari tenaga kerja. Lalu ia pensiun. Alasannya? "Payah, sekarang banyak kontraktor yang lari atau memberi cek kosong," kata sopir angkutan dengan trayek Pontianak-Sambas itu. Meskipun demikian, yang jadi calo tak berkurang jumlahnya. Sedangkan para buruh tetap jadi buruh, menunggu kesempatan bergulat di belantara. Kendati telah mempertaruhkan segalanya, sedikit pun tak ada jaminan bagi buruh. Asuransi kecelakaan atau asuransi jiwa tak dikenal. Maklum, mereka tidak terdaftar di Departemen Tenaga Kerja, baik di tempat pengiriman maupun penerimaan. Seandainya dikirim ke luar daerah, status mereka tetap sebagai pihak yang lemah. Harus ulet, rajin, tahan menderita, dan mampu menelan sejuta kesulitan. "Kami ini cuma buruh kecil yang cari makan," kata Bastian, 41 tahun. Suatu kali, sebelum kontrak selesai, ia pulang karena ada berita bahwa anaknya sakit keras di kampung. Akhirnya anak itu meninggal. Lalu ia kembali ke proyek untuk mengambil sisa upah satu bulan yang jadi haknya. Bukan uang yang diperoleh, malah ia berurusan dengan pihak yang berwajib. "Yah, itulah nasib kami yang mungkin memang harus begini," tambahnya. Toh ia tetap setia menjalani garis nasibnya. Namun, bagaimanapun, ternyata bahwa menebang kayu masih lebih baik daripada tinggal di kampung karena hampir tak mungkin mencari nafkah di desa asal. Kalaupun ada -- menoreh getah di kebun karet rakyat yang sudah tidak produktif tak bisa dijadikan jaminan. Ekspor kayu di Kal-Bar tetap jadi primadona. Sayang, keuntungannya tidak jatuh ke tangan para buruh tebang, tapi kepada para pemilik modal. Di kampung-kampung di kawasan Kabupaten Sambas, yang tinggal hanya orang tua, perempuan, dan anak-anak. Tugas mereka sehari-hari adalah mengurus keluarga, menggarap ladang, atau menoreh karet peninggalan masa lalu. Para lelakinya bekerja mati-matian di tengah rimba suasana perkampungan, dari tahun ke tahun, hampir tidak berubah. Rumah-rumah masih berdinding kayu beratap daun. "Beginilah kami, menunggu ayah anak-anak pulang bawa uang. Mana harus bayar utang di warung," cerita Rabiah, 32 tahun. Ibu lima anak itu harus pandai mengatur putaran roda rumah tangganya. Anaknya yang sulung sudah di SMP. "Bayar SPP sering nunggak. Baru dibayar setelah ayahnya balik dari hutan," sambung istri Sirajudin yang sudah empat bulan bekerja di hutan Pulaupisau, Kalimantan Tengah. Rabiah tak tahu apakah sang suami bakal pulang. Yang ia tahu, anaknya butuh uang. Yang penting buat para penebang adalah pulang membawa uang. Jika sebatang pohon tumbang, berarti rezeki. Kraaaakk. . . bruk . . . adalah senandung yang selalu dirindukan. Mereka hampir tak peduli bahwa kini hutan sudah menipis atau tersapu gundul. Mereka tak peduli ekosistem terguncang dan habitat babak belur. Meranti, agathis, ramin, dan kayu ulin sudah semakin langka. FAO meramalkan kepunahan hutan tropis basah di Brasil, juga Indonesia. Kalau itu terjadi, ke mana mereka harus pergi nanti? YHE
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini