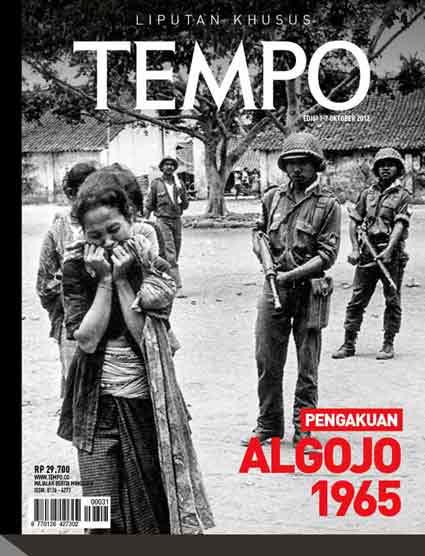Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Setelah tragedi politik 1965, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) menggelar Operasi Kalong dan Operasi Trisula. Mereka menangkap, menahan, dan menginterogasi orang-orang yang dituduh PKI di berbagai tempat.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo