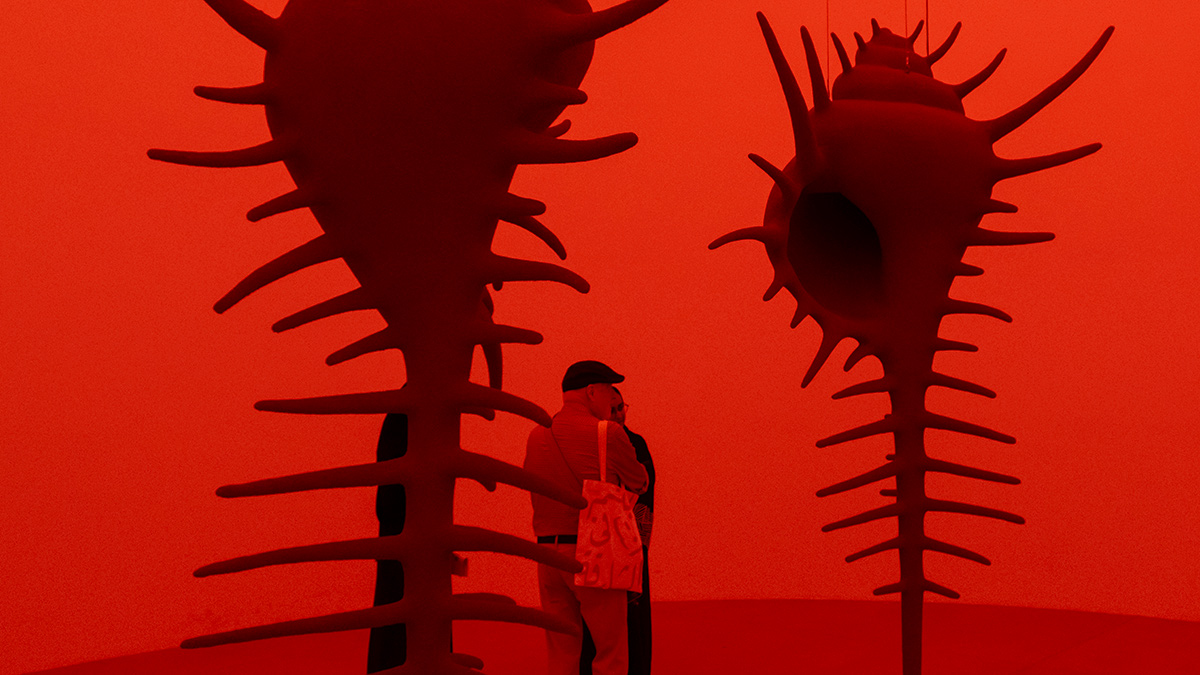Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

BUTUH dua hari bagi Agoeng Wijaya dan fotografer Wahyu Setiawan untuk mengumpulkan nyali terjun di tebing Sungai Yeh Kebus di Buleleng, Bali. Tak ada jalan selain melayang dari ketinggian 14 meter untuk menyusuri sungai berbatu itu. Yeh Kebus terpilih sebagai sungai nomor satu untuk kategori olahraga karena keindahan sekaligus kengerian tebing dan sungainya.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo