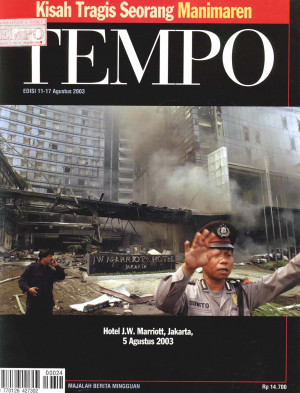Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
MALAM hari, sekitar pukul 22.00, mendekati perairan Karimun Jawa. Gelombang tiba-tiba datang begitu cepat saat layar kapal Borobudur belum sempat dikerek. Didera oleh angin yang bertiup kencang, gulungan air membukit hingga 3 meter, lalu menerjang kapal berkali-kali tiada henti. Perahu yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, pada siang hari ini menjadi bulan-bulanan alam.
Dikepung kecemasan yang luar biasa, duduk di dek perahu itu rasanya seperti berada di jet coaster. Tidak cuma diguncang dari kiri dan kanan, terkadang perahu mendadak naik ke atas diusung gelombang, lalu dibuang lagi ke bawah secara mendadak.
Kebuasan gelombang malam itu betul-betul menguji perahu itu, yang disiapkan untuk pelayaran ekspedisi Jakarta-Ghana (Afrika) dengan mengarungi Samudra Indonesia. Inilah perjalanan napak tilas "Rute Kayu Manis" (The Cinnamon Route), yang dahulu kala pernah dilalui para pelaut Nusantara untuk berdagang rempah-rempah. Tujuannya buat mengenang kembali kejayaan bahari bangsa Indonesia pada sekitar abad ke-8. Ketangguhan para pelaut Nusantara ini telah terbukti jauh sebelum para penjelajah Eropa datang dan menguasai pasar rempah-rempah di negeri ini pada abad ke-15.
Sebelumnya, perahu yang dibuat di Pulau Pagerungan Kecil, Madura, ini sudah dites menempuh perjalanan dari Bali ke Semarang. Kemudian Selasa, awal Agustus lalu, perahu Borobudur berangkat dari Semarang menuju Jakarta. Beruntung, TEMPO bisa menjadi salah satu awak dalam perjalanan uji coba ini.
Dinakhodai oleh Kapten (Laut) I Gusti Putu Ngurah Sedana, perahu ini membawa 15 awak dan penumpang. Mereka terdiri dari delapan warga negara Indonesia, empat warga Inggris, satu warga Australia, satu berkebangsaan Swedia, dan seorang Amerika. Di antara delapan orang Indonesia, tiga orang adalah peserta yang lolos seleksi untuk mengikuti ekspedisi ke Afrika. Bayangkan, mereka semua mesti berdesak-desakan dalam perahu yang panjangnya hanya 18,29 meter dengan lebar 4,25 meter itu.
Adalah Philip Beale, 42 tahun, yang menjadi tokoh utama di balik ekspedisi ini. Terinspirasi oleh sebuah gambar kapal tradisional yang terpahat di salah satu relief Candi Borobudur, orang Inggris ini bertekad mewujudkannya dalam bentuk nyata. Itu sebabnya perahu ekspedisi itu kemudian dinamakan "kapal Borobudur". Impian ini sempat dipendam selama 10 tahun dan baru mulai dilaksanakan setelah bertemu dengan Nick Burningham, arkeolog maritim asal Italia yang sering membuat replika perahu tradisional. Hanya, yang mengerjakan langsung perahu itu adalah Abdullah As'ad, ahli perahu dari Pulau Pagerungan Kecil. Karena itu pula, sejumlah nelayan dari pulau ini yang terlibat dalam pembuatan perahu juga diikutkan menjadi awak, bahkan menjadi tulang punggung pelayaran.
Menurut Nick Burningham, kapal rancangannya itu dibuat semirip mungkin dengan bentuk aslinya, yang terpahat di salah satu relief Candi Borobudur. Selain itu, kapal tersebut juga dipersiapkan untuk bisa mengarungi samudra luas dan menerjang ombak yang ganas. Karena itu, "Saya berkeyakinan kapal ini bisa sampai ke Afrika," kata Nick optimistis.
Hanya, saat diterjang gelombang menjelang perairan Karimun Jawa, keyakinan seperti itu nyaris rontok. Hampir semua awak perahu amat cemas dan panik menghadapinya. Toh, Nick Burningham berusaha tetap tenang. Begitu pula Kapten Sedana, sang nakhoda. Ia malah memberi komando agar bersiap-siap memasang layar. Menurut dia, kondisi angin cukup bagus untuk mengembangkan layar. Semua awak kapal diminta ikut terlibat.
Kami semua bersicepat mendekati tiang layar utama di dek haluan. Semua bersiap di tempatnya masing-masing. Dua awak perahu memanjat tiang untuk melepas tali yang membelit layar. Sementara itu, Nick Burningham dibantu awak lainnya memegang tali pengerek layar. Ketika nakhoda memberi aba-aba, semua awak bahu-membahu menarik tali untuk menaikkan layar. "Satu, dua, tiga...!" teriak mereka. Layar pun terkembang sempurna.
Kelar memasang layar utama, kami bergegas ke tiang layar kedua di bagian buritan. Kali ini tak ada kesulitan ketika mulai memasangnya. Yang agak berat adalah saat mengikat ujung layar yang telah terkembang. Soalnya, kami harus bergulat menahan layar yang berkibar-kibar ditiup angin kencang. Bila meleng sedikit, bahaya mengintai. Bukan tidak mungkin layar itu akan menghantam kepala.
Setelah kedua layar terkembang, mesin motor yang ditempel di perahu dimatikan. Seketika itu juga suasana menjadi tenang. Tak lagi terdengar raungan mesin. Yang terdengar hanya embusan angin kencang dan deburan ombak yang menghantam dinding kapal. Laju kapal masih diombang-ambingkan gulungan ombak cukup besar itu, berkisar enam hingga tujuh knot.
Keesokan harinya, saat rona merah membayang di ufuk timur, Kepulauan Karimun Jawa tampak di depan mata. Puluhan perahu berjejer di sepanjang pantainya. Di latar belakang, deretan atap rumah menyembul. Pagi itu, kondisi laut di sekitar pantai pulau tersebut cukup tenang. Ombaknya jinak. Semakin mendekati pantai, layar pun segera digulung. Karena lautnya dangkal, kami lego jangkar sekitar lima ratus meter menjelang garis pantai.
Ujian yang berat telah dilalui. Toh, ada segumpal kesangsian menggerayangi. Jika di Laut Jawa saja kapal ini gampang terombang-ambing, mampukah ia menaklukkan Samudra Indonesia menuju Afrika? Tantangan yang amat berat tentu saja menghadapi gelombang dan badai yang ganas di samudra lepas itu. Kalau tersesat atau salah arah, itu sulit terjadi karena perahu ini—tidak seperti perahu nenek moyang dulu—dilengkapi peranti global positioning system (GPS) untuk mengetahui koordinat secara tepat. Selain itu, perahu Borobudur juga memiliki NavTex untuk mendeteksi kedalaman air di bawah kapal serta benda-benda di bawah air, dan telepon satelit Inmarsat yang bisa digunakan meskipun di tengah samudra.
Tak hanya mengandalkan layar, perahu ini juga dilengkapi motor tempel berkekuatan 22 PK untuk keperluan darurat. Mesin ini akan dinyalakan saat keluar atau masuk pelabuhan, atau saat angin bertiup lemah. Tapi, jika menggunakan mesin, kecepatan perahu justru lebih rendah, hanya bisa 3-4 knot. Bandingkan dengan jika layar sedang terkembang dan angin bertiup kencang, perahu bisa meluncur dengan kecepatan sekitar 7 knot.
Keamanan awaknya juga cukup terjamin karena masing-masing mendapatkan satu set jaket pelampung penyelamat. Juga ada pemancar sinyal darurat (emergency beacon), yang memungkinkan tim SAR menemukan lokasi kapal apabila tenggelam. Namun, bisakah semua itu menjamin keselamatan perjalanan kapal itu hingga ke Ghana? Inilah tantangan yang mesti dijawab Beale dan kawan-kawan.
Yang pasti, pada hari ketiga dalam perjalanan dari Semarang, tiada hambatan yang berarti. Pada Kamis dua pekan lalu itu, gelombang dan angin cukup bersahabat. Ini memungkinkan perjalanan nonstop dari Karimun Jawa ke Jakarta, yang berjarak sekitar 240 mil laut. "Mudah-mudahan Sabtu pagi kita sudah bisa masuk Jakarta," kata I Putu Sedana, yang tengah memegang kemudi.
Praktis tak ada kesibukan berarti pada hari ketiga. Hiruk-pikuk baru muncul ketika hari mulai menggelap, saat nakhoda memberi komando agar membalikkan posisi layar karena arah angin berubah. Seperti saat memasang layar, semua awak kapal diminta bahu-membahu membalik layar. "Supaya lebih ringan dan cepat," ujar sang nakhoda beralasan.
Setelah mengubah posisi layar, para awak kemudian kembali ke tempatnya masing-masing. Sebagian ada yang kembali tidur di kabin, dan ada juga yang duduk di ujung haluan sembari mengisap rokok. Mereka hanyut dalam pikiran masing-masing. TEMPO dan tiga orang awak lain memilih duduk di dek dekat haluan.
Malamnya, cuaca malam juga amat bersahabat. Langit bertabur bintang dan bulan bersinar lembut. Cahayanya berpendar-pendar di atas permukaan laut membentuk garis lurus nan menawan. Di kejauhan, kerlap-kerlip lampu perahu nelayan yang melintas juga tak kalah menariknya. Sayup-sayup terdengar bunyi kincir pengukur kecepatan angin yang bertengger pada sebatang tiang di ujung buritan.
Sambil menikmati suasana malam yang mengesankan itu, TEMPO berbincang-bincang dengan tiga peserta yang lolos seleksi menjadi awak kapal. Salah satunya adalah Niken Maharani, 26 tahun. Salah satu peserta yang terpilih ikut ekspedisi itu membuka obrolan. Gadis berdarah Sunda itu tak menyangka dirinya akan menjadi awak kapal Borobudur tersebut. Sebab, Niken melamar karena dalam lowongannya dibutuhkan pemuda untuk dijadikan duta bangsa, memperkenalkan budaya Indonesia. Bersama awak kapal lainnya, ia ikut berlayar menuju Afrika. Berangkat dari Jakarta pada 15 Agustus, ekspedisi ini dilepas oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.
Niken mengaku bangga bisa terpilih di antara 1.000 pelamar yang diseleksi. Alumni Jurusan Biologi Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu berkesempatan menangguk pengalaman berharga selama berlayar. "Yang paling berkesan adalah belajar bekerja sama dalam sebuah tim," kata perempuan berjilbab itu.
Lontaran senada diungkapkan Shierlyana Junita Chandrady, 21 tahun, peserta perempuan lainnya. Shierly juga bangga berkesempatan menjadi salah seorang peserta ekspedisi kapal Borobudur. Apalagi pelayaran itu merupakan pengalaman pertama bagi mahasiswi Arsitektur Universitas Bina Nusantara, Jakarta, ini. "Meski kerap dikepung kejenuhan selama berlayar, saya tetap merasa senang," kata gadis keturunan Tionghoa ini.
Satu lagi peserta yang akan ikut menjajal jalur pelayaran nenek moyang kita adalah Bayu Arif Fiantoro, 32 tahun. Sehari-hari ia menjadi konsultan di sebuah lembaga psikologi di Jakarta. Saat terpilih menjadi peserta ekspedisi kapal Borobudur, Bayu dihadapkan pada pilihan sulit. Kalau ikut ekspedisi, ia harus rela melepas pekerjaan yang telah digelutinya sekitar lima tahun itu. Tapi, kalau tak ikut, "Ini kesempatan langka yang tak semua orang bisa mengalaminya," ujarnya. Akhirnya, lajang berambut lurus dan berkacamata minus itu memilih meninggalkan pekerjaannya untuk ikut berlayar. Seperti juga dua rekannya, Bayu dites daya tahannya dalam pelayaran di Laut Jawa sebelum menghadapi tantangan yang lebih berat di Samudra Indonesia.
Begitulah. Malam itu hampir seluruh awak kapal tampak ceria. Kami bercanda-ria hingga larut malam. Sesekali tawa kami membuncah memecah kebisuan malam. Embusan angin malam yang menebarkan hawa dingin nan menggigit memaksa kami beranjak menuju peraduan. Hanya awak yang sedang piket yang tetap berjaga-jaga. Sementara itu, kapal terus melaju memburu waktu.
Hanya, memasuki hari keempat, kejenuhan mulai mengepung. Pada Jumat itu perahu tengah melaju di perairan sebelah utara Cirebon, Jawa Barat. Sebenarnya cuaca amat cerah. Kondisi laut lumayan ramah. Tinggi ombak berkisar setengah hingga satu meter. Hari itu, kapal melaju cukup cepat—sekitar 8 knot. Meski begitu, TEMPO tetap merasa laju kapal tersebut sangat lamban. Rasanya seperti naik pedati yang ditarik kerbau.
Jika perjalanan Semarang-Jakarta saja terasa amat lama, bagaimana rasanya berlayar menuju Afrika selama empat bulan? Di luar gelombang maut yang mesti dihadapi, tak terbayangkan kebosanan yang bakal mendera. Tak terbayangkan pula apa yang dirasakan para pelaut Nusantara sekian abad silam saat menaklukkan samudra lepas dengan perahu bercadik. Apalagi, mereka tidak sedang berekspedisi atau bertualang, tapi demi berdagang menjual kulit kayu manis dan rempah-rempah.
Lamunan itu segera buyar ketika nakhoda berseru. "Sekitar dua atau tiga jam lagi kita akan sampai di Marina, Ancol," ujarnya seraya menunjuk ke arah daratan. Kejenuhan yang sempat menyergap tiba-tiba hilang, berganti dengan seribu harapan untuk segera mencium daratan.
Nurdin Kalim
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo