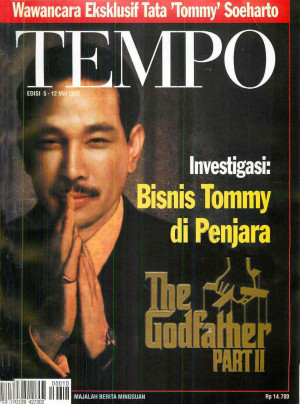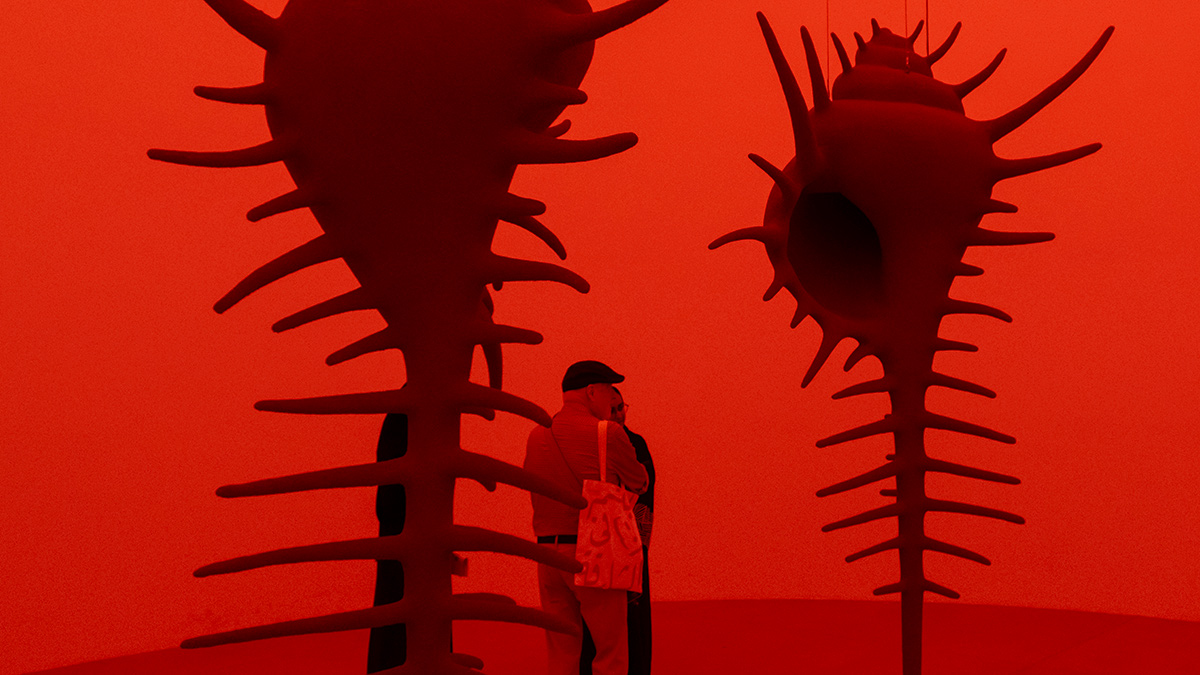Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

KAMI bertemu di Ruang Pameran Taman Ismail Marzuki—ruang pameran yang tinggal kenangan itu. Sebuah pameran lukisan besar (melibatkan pelukis seluruh Indonesia), pada 1976, sedang disiapkan. Sejumlah orang tengah memasang lukisan-lukisan di dinding, sementara kami berjalan berkeliling. Sesampai di depan sebuah dinding, saya mengatakan kepadanya, ini lukisan terbaik, seraya tangan saya menunjuk ke potret Affandi karya Hardi. Kira-kira karya itu sebuah ”karikatur” tentang Affandi yang dua tahun sebelumnya menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Singapura. Saya bergurau sebenarnya.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo