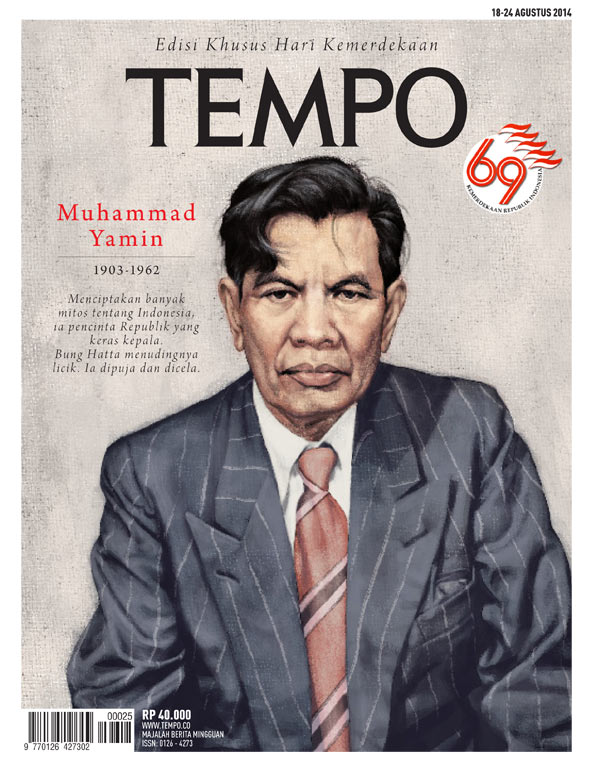Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sapardi Djoko Damono*)
Salah satu bait sajak Muhammad Yamin yang ditulis ketika usianya masih belasan tahun di majalah Jong Sumatra berbunyi:
Sampai mati berkalang tanah
Lupa ke bahasa tiada kan pernah
Ingat pemuda, Sumatera malang
Tiada bahasa, bangsa pun hilang
Ada tiga kata kunci dalam kutipan itu: "bahasa", "Sumatera", dan "bangsa". Majalah yang memuat sajak Yamin itu adalah media dari sebuah organisasi pemuda asal Sumatera, yang pada awalnya memang mendasarkan pandangannya pada prinsip teritorialisme dan bukan primordialisme. Sumatera adalah sebuah teritori yang mencakup sejumlah suku bangsa yang masing-masing memiliki adat, bahasa, dan teritori.
Masalah dasar yang boleh diperkarakan berkenaan dengan organisasi itu adalah justru aspek bahasa: Jong Sumatranen Bond merupakan bahasa Belanda. Bahasa yang disuratkan dalam sajak Yamin tentulah bahasa Melayu. Sajak itu mengajak pemuda Sumatera menggunakan bahasa Melayu dalam komunikasi, bukan bahasa Belanda yang mereka pelajari di sekolah—meski tetap digunakan sebagai nama organisasi.
Bangsa yang dikaitkan dengan bahasa dalam sajak itu adalah Melayu. Bahasa itu dianggap berlaku bagi semua suku bangsa karena dalam kenyataannya suku-suku bangsa yang memiliki bahasa berlainan harus sepakat menggunakan sebuah bahasa sebagai sarana komunikasi. Dalam sajak yang sama, Yamin menulis:
Dalam bahasa sambungan jiwa
Dimana Sumatera, di situ bangsa
Dimana Perca, di situ bahasa
Mula-mula memang demikian adanya: bahasa yang diperjuangkannya agar menjadi pilihan pemuda dalam organisasinya "hanya" dikaitkan dengan Sumatera atau Perca. Namun kisah anak muda yang brilian ini rupanya sudah diatur "dari sananya". Pikiran yang masih "kosong" (kalau boleh meminjam istilah yang kemarxis-marxisan) diisinya dengan pengetahuan, pengalaman, dan penghayatan baru yang pada akhirnya mengubah pikirannya hingga ke tahap yang paling mendasar.
Yamin bukan satu-satunya pemuda yang menjadi bagian dari proses pembentukan pemikiran mengenai Indonesia. Harus diakui, proses itu berlangsung berkat pemikiran pejabat kolonial Belanda yang menentukan Jawa sebagai "pusat"—di hampir segala bidang, terutama pendidikan.
Itu bukan kebetulan, tentu saja. Sejak bangsa-bangsa di Anak Benua Asia mengenal jajaran pulau di khatulistiwa ini, yang menjadi fokus adalah Jawadwipa. Teritori yang menjadi tumpuan berpikir mereka itulah kemudian yang menerima kebudayaan yang berlimpah yang, alhamdulillah, sebagian besar dicatat dengan baik oleh para empu dalam kitab-kitab klasik yang ditulis sejak abad ke-11.
Catatan itu mendahului segala bentuk catatan tertulis lain di teritori mana pun di jajaran pulau yang kemudian dinamai Indonesia. Konsep "jawadwipa" ini—meskipun tentu tidak disengaja—akhirnya diadopsi pemerintah kolonial ketika merencanakan pendidikan. Pada masa itu, sejak awal abad ke-20, kita tidak mengatakan "belajarlah ke Negeri Cina", tapi "belajarlah ke Jawa", karena terutama di Jawa pemerintah kolonial menyelenggarakan pendidikan menengah atas dan tinggi.
Bahasa adalah komunikasi, kebudayaan adalah komunikasi, jadi bahasa adalah kebudayaan. Itulah sebenarnya "masalah" kita selama ini, yang dicoba diselesaikan dalam "Congres Pemoeda" tahun 1928 dengan menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu sebabnya harus dijunjung tinggi. Butir ketiga keputusan kongres itu adalah "Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia". Kongres tidak pernah menyatakan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa (seperti yang sangat sering dinyatakan oleh politikus, budayawan, dan orang cerdik pandai). Pernyataan semacam itu niscaya akan membunuh bahasa lain, yang ratusan jumlahnya, serta berpotensi menimbulkan kerusuhan pikiran dan tindakan.
Kita berhak menyimpulkan atau menduga atau menganggap bahwa Yamin berperan dalam memecahkan masalah "gawat" tersebut. Ketika itu, ia merupakan sekretaris Kongres Pemuda dengan ketua Djojopoespito. Saya pikir, kita juga berhak menentukan bahwa "anak-anak" yang terlibat dalam kongres tersebut adalah "jenius-jenius muda" yang mampu melihat jauh ke depan.
Dalam proses semacam itu, Yamin bisa dijadikan contoh mewakili anak-anak muda cerdas yang datang dari berbagai daerah ke Jawa untuk belajar. Mereka belajar segala jenis ilmu yang disediakan pemerintah. Standarnya tentu saja Belanda. Nah, di sinilah terjadi suatu proses lagi yang perlu dimunculkan ke permukaan. Yamin mula-mula ke Jawa untuk belajar ilmu pertanian dan kehewanan di Bogor. Namun ambisinya ternyata tidak di situ, sehingga ia memutuskan ke Yogya menjadi murid AMS agar bisa belajar bahasa dan ilmu kebudayaan.
Proses selanjutnya pun berlangsung: pikirannya yang relatif masih "kosong" itu dengan penuh gairah menyerap inti ilmu yang tak lain dan tak bukan adalah kebudayaan Barat dan Jawa. Sistem pendidikan Belanda saat itu "hanya" atau "terutama" mengenal kebudayaan Barat (via Belanda) dan Jawa. Yang disebut terakhir itu memiliki khazanah kitab tua yang sudah lama dikaji sarjana-sarjana kampiun dari Eropa, terutama Belanda. Merekalah yang kemudian mendiktekan pengetahuan itu ke sistem pendidikan.
Demikianlah maka anak-anak muda yang masih "kosong" itu kemudian diisi bahasa-bahasa klasik Jawa dan modern Eropa. Proses ini jelas sejalan dengan beringsutnya konsep tumpah darah dari Perca ke Indonesia. Pengetahuan tentang kitab-kitab klasik Jawa membuat mereka sadar bahwa masa lampau bangsa terutama telah berlangsung di Jawa—dan dengan penuh semangat anak-anak muda itu menerjemahkan, merekam dalam pikiran, dan mengungkapkannya dalam karya sastra.
Masa lampau memang berlangsung di mana-mana, tapi di Jawa para pujangga sejak mengenal aksara telah merekamnya—lebih dari yang terjadi di daerah lain. Itu tentu tak lain argumentasi yang bisa diberikan mengapa Yamin menulis buku seperti Gadjah Mada, Pangeran Diponegoro, Ken Arok dan Ken Dedes, dan Kalau Dewi Tara Sudah Berkata.
Menjalani proses seperti itu, yang tidak jarang ditafsirkan sebagai "jawanisasi", ia jelas tidak sendirian. Sanoesi Pane lebih jauh lagi langkahnya. Ia menerjemahkan karya Mpu Kanwa, Arjuna Wiwaha, serta menulis Kertajaya dan Sandhyakalaning Majapahit, di samping Eenzame Garoedavlucht dan Airlangga dalam bahasa Belanda. Juga jelas bahwa penyair yang suka mengagungkan India purba ini sama sekali tidak mendengarkan ajakan Yamin untuk hanya berkomunikasi dalam bahasa Melayu, yang kemudian disebut Indonesia.
Namun sumbangan Yamin yang sangat penting bagi perkembangan sastra Indonesia adalah bentuk soneta yang digunakannya dalam sebagian besar sajaknya. Soneta, yang lahir di Italia pada abad ke-12 dan berkembang di Eropa sampai hari ini, dikuasainya dengan sangat baik tentu berkat pendidikan kesusastraan Barat yang diterima di sekolah. Sajak 14 larik yang rumit penulisannya itu tidak bisa dipisahkan dari gerakan Romantisisme Eropa, yang melalui filter sastra Belanda diajarkan sebagai pengetahuan kesusastraan Barat. Yamin boleh dianggap sebagai pelopor, setidaknya penyair yang paling setia pada bentuk tersebut, yang dimanfaatkan oleh Chairil Anwar dan sampai sekarang oleh Sitor Situmorang.
Sejak Yamin menyiarkan soneta-sonetanya dalam majalah Jong Sumatra pada 1920-an, hampir tidak ada penyair di majalah Poedjangga Baroe yang luput dari cipratannya. Soneta Yamin tidak sekadar menawarkan wujud visual soneta, barang baru di zamannya, tapi juga gagasan dasar Romantisisme, yang kemudian disuratkan dalam esai atau puisi oleh penyair-penyair lain. Bagi Yamin, "bangsa" tentu tidak bisa dipisahkan dari "wangsa" dan kata turunannya, "bangsawan". Penguasaan bahasa memang prinsip elite, ternyata. n
*) Penyair, guru besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo