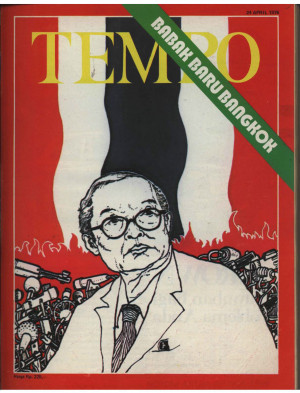FILM Gone With The Wind tetap laris. Umurnya, sekitar 37 tahun,
lebih tua dari banyak penontonnya di Indonesia kini. Ia dibikin
ketika Clark Gable masih tampak belia dan ramping, dan ketika
nama Vivien Leigh masih dipersoalkan. Ia terasa sebagai bayangan
Hollywood yang super-gemerlapan di zaman dulu. Dan ditonton
dengan ingatan seperti itu, film lama ini seakan-akan
menggaris-bawahi ceritanya sendiri. Yakni, tentang suatu
peradaban, yang "hilang, bersama angin".
Margaret Mitchell, penulis dari novel yang difilmkan ini,
mungkin dengan pandangan sedih mengingat apa yang hilang di
akhir Perang Saudara Amerika Serikat di pertengahan kedua abad
ke-19: tanah-tanah perkebunan yang luas, kehidupan
keluarga-keluarga kaya yang tenteram, gaya hidup yang mirip kaum
aristokrat, dan anak-anak muda yang tanpa cemas kekurangan. Ada
yang indah dalam peradaban macam itu. Sebab di sana, di atas
sistim perbudakan yang membebaskan para majikan dari kerja
keras itu, justru sempat lahir kehalusan budi, penghormatan
kepada ethika, keluhuran sikap. Tapi ketika perang pecah dan
masyarakat macam itu hancur, yang menggantikannya adalah sesuatu
yang lain: hidup yang bertopang pada industri, perdagangan dan
kesibukan kota. Dan runtuhlah tokoh macam Ashley Wilkes, yang
halus, gemar sastra dan filsafat, yang sadar akan kewajiban dan
kehormatan diri. Sebaliknya, tokoh macam Scarlett O'Harra,
wanita yang liat itu, justru maju: pekerja keras ini
menghalalkan semua cara untuk hidup terus, dan kaya. Dialah yang
cocok dengan aman.
Scarlett O'Harra mungkin contoh dari pribadi yang "kapitalis"
atau "burjuis". Dalam perbendahataan kaum ningrat dan priyayi
Jawa, dia mungkin contoh dari jenis yang dikecam sebagai "orang
berhati saudagar".
Sungguh menyedihkan memang: makin sedikit orang yang cukup punya
kehormatan untuk tak mengemis-ngemis, yang cukup luhur untuk
melihat dirinya justru sebagai orang yang melayani kewajiban,
yang tahu mana yang jadi haknya, dan mana yang tidak. Namun tak
selamanya nenyedihkan bila yang menggantikan orang-orang
berhati bangsawan itu adalah "para saudagar" -- mereka yang
bekerja keras tak suka sastra atau filsaft, dan hanya sibuk
dengan kemakmuran. Sebab yang lebih tragis ialah bila yang
muncul sebagai lapisan atas suatu masyarakat adalah jenis ini:
orang yang gemar kemakmuran duniawi, tapi tak ingin terlibat
dalam keringat, orang yang menginginkan kehormatan, tapi tak
ingin setia pada ethika.
Sebab sebenar-benarnyalah mereka parasit bermuka dua: priyayi
tanpa jiwa bangsawan, kapitalis tanpa usaha.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini