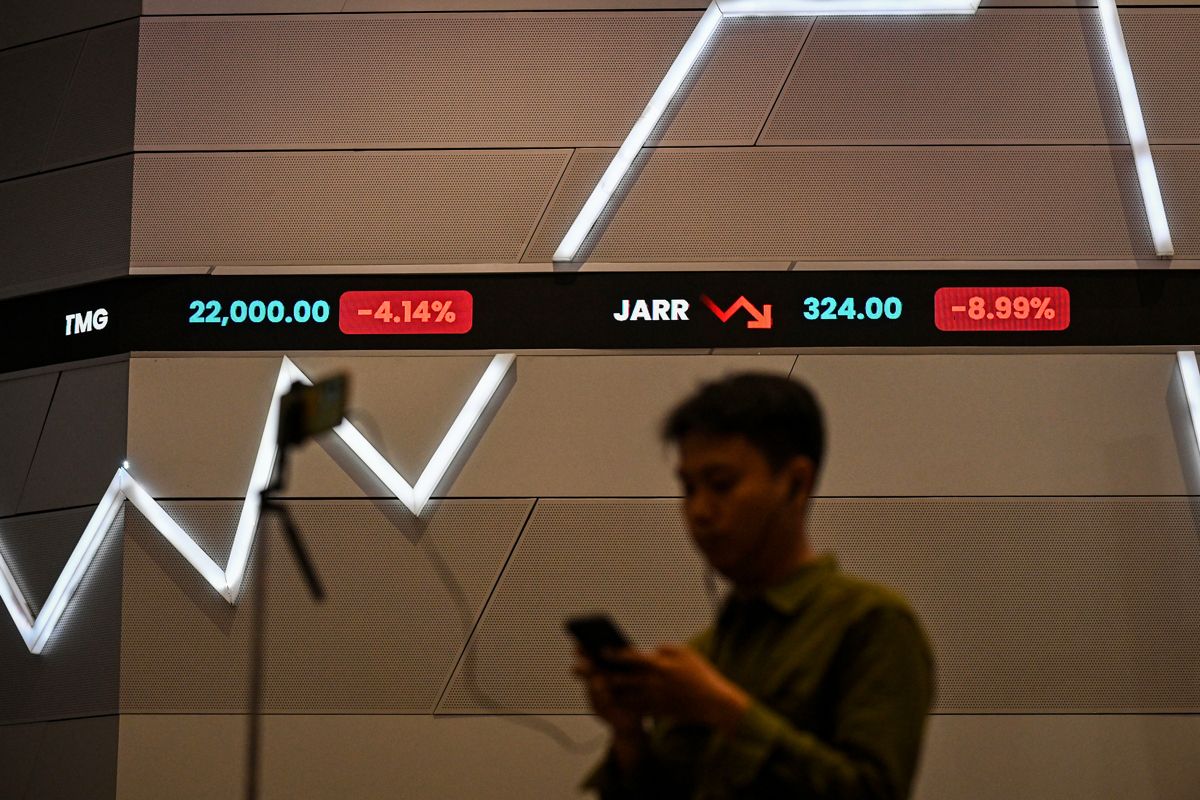Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

TEMPO.CO, Jakarta - Memegang teguh filosofi ‘kudu bisa ngigelan zaman, tapi ulah kabawa zaman’ membuat masyarakat adat di Kasepuhan Ciptagelar, Cisolok, Kabupaten Sukabumi bisa mengimbangi kehidupan modern meski berjarak sekitar 180 kilometer dari DKI Jakarta dan berada di pedalaman Gunung Halimun-Salak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

“Kalau belanja online, kami juga bisa COD (cash on delivery) sampai ke kampung-kampung,” kata Yoyo Yogasmana, juru bicara Kasepuhan Ciptagelar, pada Tempo, Kamis, 20 Oktober 2022. Ia menuturkan warga biasa menggunakan internet untuk menjual hasil pertanian dan kerajinan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kasepuhan Ciptagelar merupakan salah satu kampung adat di Indonesia yang masih memegang erat tradisi leluhur tanah Sunda dalam segala aktivitasnya. Di sisi lain mereka berhasil membuang jauh pandangan bahwa masyarakat adat itu tertutup, terisolir, dan kuno. Hal ini sejalan dengan filosofi mereka di atas yang bermakna harus mampu mengimbangi perkembangan zaman, tapi adat istiadat jangan ditinggalkan.
Kebiasaan pemerintah yang asal dalam menjalankan program prorakyat justru menjadi pemicu Kasepuhan Ciptagelar mengimbangi perkembangan teknologi. Yoyo bercerita tempat tinggalnya sudah memiliki infrastruktur internet sejak 2009 lewat program Internet Masuk Desa, tapi tak berumur panjang. “Alat-alatnya kami miliki. Katanya untuk sekitar 4 tahunan, tapi dalam kurun tahun kedua sudah tidak berfungsi dengan baik,” tuturnya.
Keadaan mulai membaik empat tahun kemudian. Didampingi organisasi non-profit Common Room Networks Foundation, masyarakat Ciptagelar mencoba mengembangkan dan mengelola infrastruktur internet mandiri atau internet berbasis komunitas.
“Setelah program pemerintah berhenti akses internetnya enggak berjalan. Nah, dari situ sebenarnya kebutuhan (masyarakat Ciptagelar) muncul untuk mengembangkan infrastruktur dan menyediakan layanan internet sendiri,” kata Direktur Common Room, Gustaff H. Iskandar, Senin, 17 Oktober 2022.
Gustaff mengatakan saat ini ada sekitar 15 warga Ciptagelar yang berstatus sebagai teknisi, yang mengelola dan mengembangkan layanan internet dengan lebih dari 900 pengguna (user). Pihaknya juga membuka “Sekolah Internet” sebagai fasilitas literasi digital bagi warga. Selain itu, ia mengklaim lewat layanan internet komunitas ini, masyarakat Ciptagelar bisa mengantongi Rp100 juta-Rp160 juta per bulan.
 Jokowi meresmikan proyek ‘Tol Langit’ Palapa Ring, Senin, 14 Oktober 2019.
Jokowi meresmikan proyek ‘Tol Langit’ Palapa Ring, Senin, 14 Oktober 2019.
Pemerintah Dinilai Belum Optimal
Pertemuan Keempat Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau 4th G20 Digital Economy Working Group (DEWG) Meeting memunculkan tiga isu prioritas, yakni konektivitas digital pascapandemi Covid-19, kecakapan dan literasi digital, dan keamanan data.
Namun, gembar-gembor transformasi digital yang pemerintah gaungkan dalam presidensi G20 dinilai belum menjangkau kelompok rentan seperti masyarakat adat. Tak meratanya infrastruktur fisik, terutama, di pelosok-pelosok menjadi salah satu kendalanya.
Kesenjangan jaringan internet ini tergambar dalam data Badan Pusat Statistisk (BPS) yang menunjukkan proporsi individu pengguna internet menurut provinsi pada 2019 masih didominasi oleh daerah-daerah Indonesia bagian barat. Tiga posisi teratas diisi oleh DKI Jakarta (73,46 persen), Kepulauan Riau (65,02 persen), dan DI Yogyakarta (61,73 persen). Adapun tiga provinsi terbawah, yaitu Papua (21, 70 persen), Nusa Tenggara Timur (26, 29 persen), dan Maluku Utara (29,13 persen). “Prinsip universal akses bahwa setiap orang, setiap warga di mana pun memiliki hak yang sama untuk menikmati atau mendapatkan akses informasi melalui internet,” kata Gustaff.
Gustaff menilai pemerintah sudah bekerja baik dengan menghadirkan infrastruktur telekomunikasi lewat proyek Palapa Ring. Namun, pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36 ribu kilometer itu belum mampu menjangkau hingga ke pedalaman. “Analoginya kita sudah punya jalan tol, tapi jalan-jalan yang sampai ke level desa itu yang kelihatannya perlu kita dorong,” kata Gustaff.
Tak Bisa Seenak Jidat
Apa yang terjadi di Kasepuhan Ciptagelar menjadi contoh bagaimana masyarakat adat bisa bertransformasi terhadap perubahan sosial.
Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum, dan HAM PB Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Muhammad Arman, mengatakan ada lebih dari 2.449 komunitas adat di Indonesia. Ia menuturkan mereka tidak anti dengan digitalisasi. Hanya saja perlu ada jaminan transformasi itu dilakukan dengan baik.
“Bukan soal infrastruktur saja, tapi juga soal sumber daya. Apalagi kita sampai hari ini Indonesia belum punya sistem sekuritas pengamanan data yang cukup kuat. E-KTP saja bobol (datanya) dan seterusnya,” ucap dia saat dihubungi Tempo.
Arman menilai pemerintah harus memikirkan pula soal fase transisi yang dialami oleh masyarakat adat. Salah satunya dengan gencar memberikan edukasi bagi publik. “Jangan sampai yang sukses itu adalah pembangunan fisiknya, tapi kualitas sumber dayanya ditinggalkan,” tuturnya.
 Warga bersama barisan olot, berbondong-bondong mengusung padi induk untuk diikutserakan dalam prosesi Ngadiukeun Pare di Leuit Si Jimat pada puncak Seren Taun yang ke 646 di Kampung Ciptagelar, Sukabumi, Jawa Barat. 24 Agustus 2014. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Warga bersama barisan olot, berbondong-bondong mengusung padi induk untuk diikutserakan dalam prosesi Ngadiukeun Pare di Leuit Si Jimat pada puncak Seren Taun yang ke 646 di Kampung Ciptagelar, Sukabumi, Jawa Barat. 24 Agustus 2014. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Sementara itu, peneliti dari Center Digital for Society (CfDS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Irnasya Shafira, mengatakan pemerintah harus rajin-rajin berdialog dengan masyarakat adat untuk mengetahui layanan yang dibutuhkan mereka di era digitalisasi ini.
Pasalnya, kata Irnasya, masyarakat adat selama ini sudah memilki cara hidup dan nilai yang berjalan dengan baik tanpa adanya intervensi digital. “Gak bisa seenaknya jidat. Gimana cara meyakinkan masyarakat adat kalau itu memudahkan, bukan mengancam value mereka” paparnya.
Dosen Hukum Adat Fakultas Hukum UGM, Tody Sasmitha, mengatakan salah satu elemen yang penting dalam menciptakan digitalisasi yang inklusif adalah kepercayaan (trust). Alasannya saat mengakses internet, pengguna menyerahkan sebagian besar hal pribadi mereka kepada orang yang tidak pernah ditemui. Sebabnya harus ada pemahaman yang diberikan soal ini kepada kelompok rentan.
Selain itu, kata Tody, pemerintah harus menjamin masyarakat adat memiliki kontrol dan terlibat dalam konten-konten yang dihadirkan dalam digitalisasi ini “Berikan kesempatan bagi masyarakat adat menentukan sendiri arah transformasi digitalnya. Bukan kita yang datang bawa ukuran-ukuran elite. Bagaimana masyarakat didukung menemukan tujuannya sendiri dalam menggunkan teknologi,” ucap dia dalam sebuah diskusi.
Selaras dengan Tody, Gustaff menilai selama ini upaya transformasi digital di Indonesia sebagian besar masih diputuskan oleh elite. Berkaca pada kesuksesan di Ciptagelar, kata dia, salah satu upaya untuk mengatasi kesenjangan digital, terutama di sektor infrastruktur internet, adalah dengan melibatkan langsung warga