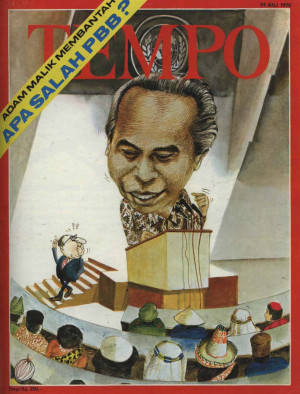LIECHTENSTEIN bukanlah negeri dongeng. Ia negara kecil
berpenduduk 21 ribu, terletak di Eropa Barat. Tapi lebih lima
puluh tahun yang silam ia ditolak masuk menjadi anggota Liga
Bangsa-Bangsa. Bukan karena tak memenuhi syarat sebagai negara
berdaulat. Bahkan negara itu secara de jure telah banyak diakui
negara lain. Ia juga telah menutup perjanjian dengan beberapa
negara. Ia punya pemerintahan yang stabil. Negeri itu juga punya
batas-batas negara yang pasti. Tapi karena luas wilayahnya yang
amat kecil, penduduk yang sedikit serta posisi geografisnya.
Lieihtenstein telah menyerahkan beberapa atribut kedaulatannya
kepada negara-negara lain. Swiss misalny dalam dinas Pos dan
Bea Cukai. Juga di bidang diplomatik, pengadilan banding, serta
mempergunakan mata uang.
Liechtenstein juga tak punya tentara. Fakta ini dianggap
sebagai penyebab ketidakmampuan negara itu untuk menjalankan
kewajiban Internasional sebagaimana disebut dalam Covenant
LBB. Menurut para penulis hukum internasional baik Covenant
LBB maupun piagam PBB menunjukkan dengan jelas bahwa hanya
negara berdaulat penuh dan punya kemampuan untuk memenuhi
kewajiban imternasional yang dapat diterima sebagai anggota.
Stephen M. Schwebel, anggota Dewan Redaksi Majalah hukum
internasional yang terkemuka menilai sikap lBB itu sebagai
mencerminkan tanggung jawab internasional yang tinggi. Lebih
daripada sikap Majelis Umum PBB tahun 1971 ketika badan ini
menyetujui masuknya Qatar, bersama-sama dengan Bahrain dan
Bhutan ke dalamnya. Mengapa sikap kedua organisasi itu berbeda?
tanya anggota Redaksi American Journal of International itu.
Liechtenstein. kata Schwebel yang juga Deputi Legal Aviser,
State Department AS itu. pada tahun 1920 telah lebih 200 tahun
merdeka. Sedang Qatar pada 171 baru merdeka beherapa minggu.
Liechtenstein memang lebih kecil (62 mil persegi) dari Qatar (4
ribu mil persegi). Penduduk Qatar 80 ribu, juga lebih besar
dari Liechtenstein. Tapi negara terakhir ini berindustri tinggi
dan kaya di bidang pertanian,sedang Qatar hanya mengandalkan
minyaknya (189.348.000 barel selama 1974). Negara pertama
bebas buta huruf sedangkan di Qatar masih banyak yang belum bisa
membaca menulis. Yang pertama punya pengalaman dalam hubungan
internasional, sedang negeri kecil di Timur Tengah itu boleh
dikatakan nol -- walaupun karena minyaknya ia adalah anggota
OPEC.
Masih untung Qatar dan Bahrain (195 ribu jiwa, 231 mil
persegi), biar kecil-kecil tapi punya minyak. Ada sebilangan
lagi negara yang lebih kecil dari keduanya baik dari sudut
penduduk, sumber-sumber alam serta wilayah. Mereka lahir
sejalan dengan menderasnya proses dekolonisasi setelah PD II.
Merekapun segera mengurus keanggotaan di PBB. Tak heran kalau
jumlah anggota badan dunia cepat meninggi. Dari hanya puluhan di
tahun 1950-an. menjadi 144 hingga 1975 (lihat daftar). Dan
sekitar 2/3-nya adalah negara-negara yang merdeka setelah PD II.
Walaupun keanggotaan di PBB tak menjadi syarat bagi berdaulatnya
negara, tapi negara-negara baru merasa. bahwa keanggotaan di
lembaga internasional itu merupakan pengakuan terakhir bagi
kemerdekaan mereka. Perdana Menteri Mauritius (negara
berpenduduk 810 ribu yang juga memperjuangkan prinsip nusantara
seperti Indonesia) di tahun 1968 berkata di PBB bahwa dengan
diterimanya negerinya sebagai anggota. "tuan-tuan telah
mentahbiskan Mauritius secara resmi ke dalam status sebagai
negara yang merdeka dan berdaulat". Sedangkan Menlu Singapura
tiga tahun sebelumnya menyatakan bahwa bagi Gambia (370 ribu
penduduk) dan Maldive ( 100 ribu) "keanggotaan di organisasi ini
merupakan dukungan dari kedaulatan dan integritas mereka
sebagai bangsa.
Masih ada lebih 50 negara mini yang masih di luar menunggu
ke-sempatan bisa masuk. Tapi ada yang memang tak mau masuk,
seperti Western Samoa (114.000 penduduk) Tonga ( 71.472 ) dan
Nauru. Rupanya mereka menuruti beberapa negara mini Eropa yang
sudah tua: Liechtenstein, San Marino (18.360 penduduk, luas 64
km persegi). Monaco ( 21.873 manusia di daerah 22 km persegi)
serta kota Vatikan (1000 orang, 1/2 km persegi wilayah). Tidak
masuk PBB bukan berarti tidak dapat masuk lain-lain asosiasi
internasional. Mereka tetap berwenang untuk mengadakan
perjanjian dengan negara-negara lain.
Sebagai produk dekolonisasi setelah PD II negara-negara baru ini
dalam banyak hal punya kepentingan yang amat berbeda. Bahkan
bertentangan dengan negara-negara yang sudah mapan. Mereka
misalnya harus membina perekonomian sementara arus perekonomian
internasional memberat kepada negara-negara yang sudah maju.
Maka, ekonomi dunia harus ditata kembali, kata mereka.
Tak heran kalau negara-negara maju, terutama yang di Barat.
merasakan momok kekuatan sekitar 2/3 dari 144 angota PBB itu.
Perimbangan kekuatan sudah berobah. PBB bukan lagi PBB Barat
seperti di tahun 1950-an, tapi PBB Dunia ketiga, seperti kata
Ruslan Abdulgani (TEMPO ,20 Desember 1975 ). Dan itu mungkin,
karena PBB menganut prinsip persamaan (equality): satu negara,
besar atau kecil, punya satu suara.
Terutama AS yang kelihatan amat khawatir makin membanyaknya
negara-negara kecil ini masuk PBB. Setiap satu masuk, tambah
satu suara bagi kelompok yang disebut sebagai dunia ketiga itu
Permohonan Swaziland (Afrika) untuk masuk ke PBB menghidupkan
kembali persoalan negara mini di organisasi bangsa-bangsa itu di
tahun 1968 Swaziland (287 ribu jiwa) bersama rekannya dari
Afrika yang juga baru merdeka, Equatorial Guinea (281 ribu jiwa)
ternyata lancar saja diterima di PBB, tanpa ada yang memberikan
komentar mengenai kecilnya wilayah mereka. Sementara itu
Washington Post pada 26 September 1971 mempertanyakan apa yang
harus dibuat PBB dengan negara-negara mini itu?
Dan tahun yang lalu Kissinger marah-marah tentang apa yang
dikatakannya sebagai "tirani" dunia ketiga itu. Waktu itu
kelompok mayoritas itu tak tanggung-tanggung menghantam Israel,
supaya keluar dari PBB dan memukul Afrika Selatan agar negara
putih di benua Afrika itu keluar dari sidang-sidang MU PBB.
Kissinger juga menambahkan, bahwa bangsa-bangsa baru merdeka
dari Asia, Afrika dan merika Latin itu telah memaksa
negeri-negeri industri untuk memenuhi keinginan ekonomis mereka
yang tak realistis.
Masih banyak isyu lain. Misalnya tuduhan bahwa"zionisme" sama
dengan "imperialime". Dan adalah atas alasan takut kalah suara
maka AS dan Uni Soviet dalam Konperensi Hukum Laut PBB III yang
masih belum kelar itu mengusulkan dipakainya sistim konsensus
dalam pengambilan keputusan. Keputusan tentu saja lambat
tercapai.
Karena itu adalah berita aneh, ketika di minggu-minggu pertama
bulan ini, terbetik bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia telah
mengecam adanya "tirani mayoritas" dari negara-negara kecil.
Dalam acara tanya jawab di hadapan National Press Club di
Washington, 30 Juni, Adam Malik menurut Reuter, yang dikutip
Antara menyebutkan perlunya diadakan perbaikan sistim perwakilan
di PBB. Perlu diadakan sudi untuk itu misalnya apakah anggota
badan tersebut perlu didasarkan atas jumlah penduduk ataupun
faktor-faktor lain. Soalnya, keluh Adam Malik, Indonesia sebagai
negara berpenduduk terpadat ke lima didudukkan sejajar dengan
negara-negara yang penduduknya hanya satu prosen dari 130 juta.
Sepekan kemudian berita itu dibantah Direktorat Penerangan
Luarnegeri Deplu karena katanya telah disajikan menyimpang dari
konteks Minggu lalu, di rumahnya Adam Malik memberi penjelasan
lagi kepada TEMPO (lihat box Nasional). Ide Adam Malik itu
memang baru, mungkin segar. Tapi apakah bisa dipraktekkan, dan
apakah dasarnya cukup benar dan adil, masih bisa dipersoalkan.
Pendeknya, PBB perlu diubah. Tapi, Adam Malik menegaskan bahwa
biar banyak keluhan terhadap PBB, Indonesia tetap menganggap
badan dunia satu-satunya itu harus terus dipertahankan,
PBB memang bertahan hingga sekarang. Kecuali Indonesia yang
pernah angkat kaki tahun 1965 (kemudian masuk kembali setahun
kemudian), tak satupun anggota-anggotanya yang keluar -- lain
dengan Liga Bangsa-Bangsa dulu, dan itulah yang menyebabkan
rapuhnya badan dunia pra PD II itu. Entah benar seperti
dikatakan Kissinger tahun lalu bahwa yang sebenarnya
berkepentingan dengan PBB adalah negara-negara dunia ketiga.
Menurut dia, AS dapat makmur tanpa tergantung dari badan itu.
PBB dimaksudkan untuk mengajukan kemajuan sosial dan standar
hidup dalam kemerdekaan yang lebih luas. Tapi ia bukanlah badan
pemerintahan dunia yang mendiktekan hubungan subordinatif dengan
negara-negara anggotanya. Tak ada yang lebih tinggi dari
masing-masing anggota organisasi itu sendiri-sendiri, tak pula
ada kepala PBB yang jadi petinggi bagi kepala negara
masing-masing. Azas persamaan, kesederajatan equality) jelas
terbaca dalam Piagam yang dibuat di San Francisco 31 tahun yang
lalu.
Sebaliknya para penulis hukum internasional sendiri mengakui
bahwa azas persamaan negara yang melahirkan satu negara satu
suara ini telah diterobos oleh adanya hak veto serta
keanggotaan tetap pada Dewan Keamanan. Alasan pokok
dilahirkannya veto pemungkas itu adalah karena lima anggota
tetap DK itu (AS, US, Inggeris, Perancis dan Cina) harus
menjalankan beban tanggung-jawab mempertahankan perdamaian dan
keamanan. Karena itu tak satu dari si berlima itu yang dapat
dipaksa hanya dengan pemungutan suara, menurut sesuatu tindakan
yang tak disetujuinya. Itulah suasana pada saat Piagam dibikin.
Teoritis, memang ada kemungkinan veto tak dapat digunakan. Yakni
dalam keputusan yang berkenaan penyelesaian sengketa secara
damai (Bab VI) dan tentang penyelesaian sengketa secara regional
(pasal 52 ayat 3 Piagam), di mana salah satu fihak yang
terlibat, baik anggota tetap maupun tidak DK, harus abstain.
Keanggotaan tetap di DK plus hak veto ini terbawa-bawa dalam
beberapa urusan di luar DK sendiri. Mereka dapat mencegah
negara-negara kandidat menjadi anggota PBB, mereka berkuasa
menghalangi dirombaknya Piagam, dan mereka berwenang mem-veto
tindakan PBB sehubungan masalah pelanggaran perdamaian dan
agresi. Semua persoalan itu harus mendapatkan rekomendasi
tuan-tuan berlima,anggota tetap DK itu.
Maka di masa depan mungkinkah misalnya AS akan mempergunakan
vetonya di DK, untuk memblok permohonan negara-negara mini,
selama belum ada ketentuan standar masuk minimal yang
disepakati?
Kasus masuknya Maldive ke PBB menarik perhatian. Apakah Republik
Maldive yang berumat 100 ribu jiwa itu, dapat memenuhi
kewajiban-kewajiban internasional? Jika PBB tak punya peraturan
untuk membayar ongkos transpor lima orang dari tiap anggota
untuk menghadiri MU, sebutnya ada keraguan apakah Maldive dapat
membayar delegasinya ke New York, untuk menberikan suara. Dan
dalam kenyataannya di tahun 1971 wakil Maldive tak muncul pada
sidang ke 6 -- pada saat penting karena soal perwakilan Cina.
Rupanya dengan kasus Maldive, AS dapat alasan bahwa persoalan
negara mini di lain kali harus diperhatikan benar. Tahun 1965
wakil AS di DK biarpun menyokong masuknya Maldive itu --
akhirnya mengingatkan dewan yang beranggota 15 orang (dengan 5
anggota tetap) itu: "Dewasa ini banyak negara yang baru
tumbuh, yang mungkin tak mempunyai sumber-sumber ekonomis dan
penduduk sedemikian rupa sehingga memenuhi kriteria kedua ini
(yakni kemampuan menjalankan kewajiban-kewajiban seperti disebut
Piagam) Kami karena itu menyerukan agar anggota DK dm anggota
PBB umumnya memberikan perhatian dan pertimbangan yang cermat
terhadap problem ini, dalam usaha untuk menda[atkan satu
standar, yang agak rendah, untuk ditrapkan dalam kasus pelamar
keanggotaan PBB yang akan datang.
U Thant (masih Sekjen) menjembatani ide ini dengan usul yang
disampaikan dalam laporan tahunan 1967, agar badan-badan yang
kompeten melaksanakan studi yang konmprehensif terhadap
kriteria keanggotaan di PBB. Disarankan perlunya
pembatasan-pembatasan tentang keanggotaan penuh, sambil juga
memberi definisi bentuk asosiasi lain. Ini diharapkan akan
dapat menguntungkan baik negara-negara mikro maupun PBB
sendiri.
Tapi tak banyak sambutan atas saran Sekjen itu. Hanya AS
di tahun 1969 menggagaskan ddiadakannya lembaga
associate-member bagi negara-negara baru yang diragukan
kemampuan ekonomi dan manusianya dalam pengelolaan
kewajiban-kewajiban internasional Sebab keanggotaan penuh bagi
negara-negara mini tertentu dirasakan hanya akan merupakan beban
berat . Sebuah associate member kelak akan menikmati hak-haknya
sebagai anggota, kecuali untuk memberikan suara serta membayar
sumbangan. Setahun kemudian ada usul Inggeris. Menurut negara
ini sebagai anggota biasa, suatu negara mini akan tetap
menikmati hak-haknya sebagai anggota, tapi diharapkan, atas
kemauan sendiri serta pilihan yang berdaulat, melepaskan hak-hak
tertentu, khususnya hak bersuara dan memilih dalam organ-organ
tertentu. Inggeris menujukan rancangannya ini bagi negara-negara
amat kecil yang ingin menjadi anggota, tapi menemukan kesukaran
dalam memenuhi kewajiban finansiil dan administratif.
TENTU saja usul-usul begini amat bertentangan dengan Piagam
PBB yang pro azas persamaan dan kesederajatan negara itu.
Kecuali kalau Piagam hendak dirubah. Tapi toh masalah associate
member ini sudah dipakai di tiga komisi ekonomi regional PBB:
ECAFE, ECLA dan ECA -- tanpa merobah konstitusi organisasi itu.
Sebaliknya beberapa badan- khusus PBB, terutama UNESCO dan FAO.
memandang perlu merobah konstitusi mereka dulu untuk dapat
mengakomodir lembaga perwakilan tanpa suara ini. Sementara itu
IMF adalah organisasi internasional pertama yang sistim
pemungutan suaranya tidak sederajat (unequal), yakni disesuaikan
dengan kriteria ekonomis dari anggotanya. Semua ini dapat
terjadi, karena menjadi anggota suatu badan atau organ khusus
PBB tidak selalu harus jadi anggota organisasi induknya lebih
dahulu.
Walaupun beberapa anggota DK sepakat adanya problem negara mini
atau mikro ini, tapi umumnya mereka merasa segan juga
menciptakan lembaga baru semacam associate member itu. Tentu
saja. Ada anggapan bahwa AS-lah yang bersikeras menggolkan
konsep tersebut. Sedangkan Aleksei Zakharov, wakil US waktu
itu, memandang pemasukan usul AS dalam agenda pembicaraan DK
sehagai prematur. Prancis berpendapat jika kategori
keanggotaan baru itu hendak diadakan, perobahan substansif
Piagam harus dilakukan. Padma BahadulKhatri dari Nepal marah
keras atas adanya perkiraan bahwa pertambahan jumlah anggota PBB
sebagai akibat tumbuhnya negara-negara kecil akan melemahkan
organisasi internasional itu Abdou Salam M'Bengue dari Senegal
mengatakan, pembatasan keanggotaan negara-negara kecil sama
dengan pukulan terhadap bangsa-bangsa baru merdeka. Maka,
katanya, PBB supaya tidak meladeni keinginan-keinginan semacam
itu.
Di samping itu, masalahnya bakal terbentur pada soal ukuran.
Hingga kini belum ada batasan ukuran bagi negara-negara untuk
dapat diterima jadi anggota. Definisi negara "kecil", atau
"mini", atau "mikro''. juga belum terumuskan. U Thant, dalam
pengantar laporan tahunannya tahun 1967 pernah mengartikan
negara Mikro" (micro-states) sebagai kelompok yang kecil dalam
pengertian wilayah penduduk dan sumber-sumber ekonomis, dan yang
sekarang tumbuh sebagai negara-negara merdeka. Jumlah penduduk
diperkirakan tak kurang dari 10o ribu. Wakil AS di PBB,
Charles Yost, dalam suatu pertemuan di DK tahun 1969 juga
mencanangkan angka yang sama untuk faktor penduduk. Laporan
terakhir menunjukkan bahwa dalan pikiran AS ada tiga faktor
lain: wilayah 500 Km persegi, belanja tahunan AS $ 15 juta dan
perdagangan luarnegeri beromzet AS $ 15 juta juga. Kandidat
anggota yang memenuhi tiga saja dari persyaratan itu dapat
dipertimbangkan masuk PBB.
Tapi apakah dengan pembatasan seperti itu PBB akan lebih lancar
berperan dalam memperbaiki suasana dunia" Orang boleh ragu.
Barangkali kita telah terlalu lama mengharapkan hal-hal yang
mustahil dari PBB. Organisasi ini mungkin dibebani harapan dan
peranan yang terlampau besar buat dirinya. Banyak masalah
internasional, yang gawat seperti Timur Tengah, ataupun yang
kurang gawat seperti di bidang bantuan dan perdagangan, ternyata
lebih perlu diselesaikan di luar badan itu.
Mungkin akhirnya PBB hanya jadi tempat pertemuan pelbagai
wakil bangsa, untuk saling mendengarkan tanpa harus terikat
buat mengambil keputusan bersama.
Mungkin itulah alasan mengapa negara kecil ataupun besar boleh
hadir sama-sama.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini