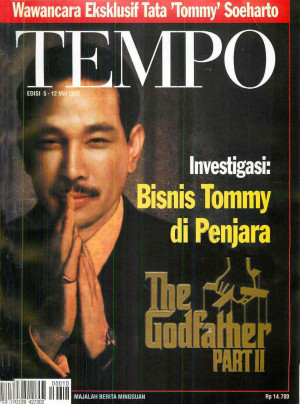Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
HASSAN Millal kini sungguh sibuk. Sepanjang pekan lalu, staf wali kota di Evry—kota kecil sekitar 30 kilometer dari Paris—itu lebih kerap berada di jalan. Sebagai warga negara Prancis keturunan Aljazair yang beragama Islam, Millal merasa hidupnya terancam. Bila Jean-Marie Le Pen jadi presiden, sosok seperti dirinya mungkin tertendang dari negeri itu. ”Le Pen itu fasis,” katanya melalui telepon jarak jauh kepada TEMPO.
Kekhawatiran seperti itu tak hanya melanda Millal. Hasil pemilihan umum babak pertama dua pekan lalu menunjukkan bahwa Le Pen punya kesempatan jadi presiden setelah mengalahkan PM Lionel Jospin. Ia akan menantang Presiden Jacques Chirac dalam pemilu tahap kedua, awal Mei nanti. Gelombang waswas itu menyebabkan selama empat hari berturut-turut berbagai jalanan utama di Paris berubah menjadi lautan manusia. Bahkan, Kamis silam, peserta unjuk rasa di ibu kota Prancis itu—menurut radio France-Info—telah mencapai 300 ribu jiwa. Riaknya terus merambat hingga ke Nantes, Bres, Lyon, Toulouse, dan be-berapa kota lainnya di selatan Prancis. Pesan mereka seragam: cegah naiknya Jean-Marie Le Pen ke kursi presiden.
Le Pen, Ketua Partai Front Nasional, memang membuat warga Prancis yang tidak berkulit putih ataupun beragama Katolik deg-degan. Sejak masa kampanyenya, politisi ekstrem kanan ini mengusung panji-panji partai berbau rasis, antara lain sikapnya yang anti-imigran, mendukung pemutusan hubungan dengan Uni Eropa, dan penolakan pembangunan masjid.
Nyatanya, ”dagangan” Le Pen ini laku di tengah situasi Prancis yang setiap hari menerima kedatangan ribuan imigran. Dengan mengantongi 17,02 persen suara dari total 41 juta pemilih, mantan prajurit di Legiun Asing Prancis ini menjungkirkan calon dari Partai Sosialis, Jospin.
Namun, naiknya Le Pen membuat para pemilih bersatu untuk melawannya. Unjuk rasa di Paris pekan lalu, misalnya, diikuti oleh anggota Partai Komunis Prancis, Partai Hijau, Serikat Buruh, Kelompok Antirasisme, hingga beberapa rabbi Yahudi serta pemuka masyarakat muslim di Prancis. Sebuah kombinasi aliansi yang mungkin tak bakal terwujud jika Le Pen tersisih di babak awal pemilu.
Berangkat dengan ragam latar belakang politik dan agama, mereka kini sibuk merapatkan barisan. ”Kami tak punya pilihan lain. Bahkan pendukung ekstrem kiri pun akan memilih Chirac untuk mencegah naiknya Le Pen men-jadi presiden,” ujar Arnaul Pujal, mahasiswa pendukung tokoh kiri Arlette Laguiller.
Kalau begitu, apa rahasia sukses Le Pen? Peluang politisi kelahiran La Trinite-sur-Mer di kawasan Britanny di barat laut Prancis, 74 tahun lalu, itu bukan membesar dalam semalam. Adalah sikap warga Prancis juga yang melambungkannya dengan berjangkitnya demam anti-imigran sejak tahun 1980-an. Gelombang pendatang ke Prancis, menurut pengarang buku Les Politiques d’Immigration en Europe, Virginie Guiraudon, mencapai angka seratus ribu jiwa per tahun pada 1990-an. Tak mengherankan apabila dalam sensus 1999 silam jumlah pendatang asing di negeri anggur ini mencapai 3,2 juta jiwa.
Masuknya imigran membuat warga Prancis terdesak. Utamanya dalam berlomba mencari lapangan kerja dengan upah yang lebih murah. Kalangan kelas pekerja, yang merasa dicuekin oleh duet Chirac dan Jospin, umumnya mengambil sikap apatis dengan tidak mengikuti pemilu babak pertama. Le Pen juga menuding masuknya imigran sebagai faktor pendorong laju angka kriminalitas di berbagai kota di Prancis. Kejelian memainkan isu domestik seperti ini yang membuat sosok kontroversial seperti Le Pen berhasil memancing perhatian publik.
Bagi Hassan Millal, naiknya Le Pen ini bisa terjadi karena buruknya performa pemerintahan Jospin selama lima tahun terakhir. ”Ditambah dengan tema-tema kampanyenya yang terlalu intelektual, warga berharap Le Pen bisa memberi perubahan, seperti dalam lapangan kerja,” ujar Millal, aktivis Partai Sosialis yang kini terpaksa mendukung Chirac.
Gerakan anti-imigran rupanya tak hanya terjadi di Prancis. Dengan alasan yang sama—sempitnya lapangan kerja—ia juga melanda berbagai negara Eropa Barat sejak tahun 1990-an. Gaung suara makin keras gara-gara meningkatnya tingkat kejahatan yang mereka percaya karena ulah imigran di berbagai belahan Eropa.
Tak aneh apabila selama dua tahun terakhir sejumlah negara Eropa mengalami transisi kekuasaan dari koalisi gerakan sosialis atau kiri ke pangkuan gerakan ekstrem kanan. Coba tengok Austria, tempat politisi seperti Joerg Haider yang mengaku mengagumi ajaran Hitler bisa menjadi penguasa negeri. Pada pemilu tujuh tahun lalu, Haider dengan Partai Kebebasan-nya hanya mendulang 22 persen suara. Namun, dua tahun silam langkah tokoh ekstrem kanan ini tak terbendung lagi dan membentuk koalisi dengan kalangan konservatif.
Begitu pula dengan Italia. Di negeri piza ini Silvio Berlusconi muncul kembali ke tampuk kekuasaan dengan membentuk Koalisi Nasional bersama Gianfranco Fini, yang memiliki basis pendukung dari kalangan fasis Mussolini.
Negara-negara Skandinavia juga tak luput dari pengaruh ekstrem kanan. Misalnya, gerakan kiri di Norwegia yang kehilangan kekuasaannya pada September silam. Nasib serupa dialami sekutu mereka dari Partai Sosial Demokrat di Denmark tiga bulan kemudian.
Gerakan ekstrem kanan di Belanda, melalui partai Leefbar Nederland, kini juga tengah mengincar kursi parlemen dalam pemilu Mei mendatang. Kendati begitu, pendukung partai ini mengaku berbeda dengan kubu Le Pen karena mereka berasal dari para pengikut Marxisme.
Le Pen mencatat naiknya rekan-rekan sealiran dengannya ke tampuk kekuasaan tak lepas dari kegagalan koalisi partai sosialis dan kiri di beberapa negara Eropa, tidak cuma karena ketidakbecusan dalam menghadapi persoalan imigran dan tingkat kejahatan. Pertumbuhan ekonomi yang lebih banyak dinikmati oleh kalangan berduit juga turut berperan mendongkrak sukses gerakan ekstrem kanan.
Pergeseran perhatian pada isu ekonomi membuat gerakan ekstrem kanan di Prancis dan Eropa pada umumnya lebih kaya strategi menghadapi seteru mereka. Maklum, persoalan imigran dan kejahatan juga bisa menjadi andalan bagi pesaing mereka. Inggris, yang kini di bawah pemerintahan Partai Buruh, misalnya, sudah lama berkutat dengan aliran pendatang ilegal yang menyeberang dari Prancis.
Widjajanto (AP, The Guardian, The Economist, BBC)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo