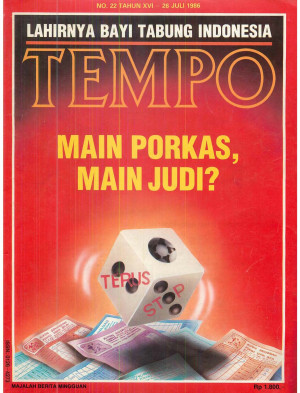SESUDAH batas waktu 11 jam terlewati Minggu malam berselang, India akhirnya menjatuhkan boikot terhadap Pekan Olah Raga Persemakmuran yang pembukaannya dijadwalkan Kamis pekan ini di Edinburg, Inggris. Sebagai negara yang tidak biasa mencampuradukkan politik dan olah raga, India sengaja meluangkan waktu 11 jam agar PM Inggris Margaret Thatcher mau meninjau kembali sikap politiknya terhadap rezim apartheid Afrika Selatan. Tapi wanita besi ini tidak tergugah. Ia tetap menolak sanksi ekonomi terhadap pemerintahan Botha. Dan bagi New Delhi tidak ada pilihan lain kecuali menarik diri seraya membubarkan tim olah raga yang beranggotakan 126 orang. Thatcher tampaknya meremehkan aksi boikot itu, bahkan tidak sudi memperhitungkan India, negara anggota Persemakmuran dengan penduduk 700 juta jiwa. Semula diprakarsai negara-negara Afrika hitam gelombang boikot kemudian diperkuat beberapa negara di Asia dan kawasan Karibia. Sesudah India, menyusul Sri Lanka, Siprus, dan Seychelles, hingga barisan boikot mencakup 29 negara, lebih dari separuh anggota Persemakmuran. Dikhawatirkan pekan olah raga itu terancam gagal, apalagi telah tercipta jurang antara sesama anggota Persemakmuran, yang bisa saja menjurus ke permusuhan. Melihat gelagat buruk ini, Ratu Inggris Elizabeth II konon mcrasa tidak senang. Menyadari Commonwealth terancam bubar, sebagai pemimpin organisasi ini -- Ratu tidak dapat menahan rasa gusarnya. Tersiar desas-desus tentang adanya keretakan antara Ratu dan PM Thatcher, sementara surat kabar The Sunday Times melaporkan bahwa Elizabeth tidak saja melancarkan kritik terhadap Thatcher, tapi juga kecewa melihat approach Perdana Menteri yang dianggap "tanpa pertimbangan, konfrontatif, dan memecah belah". Keterangan ini dikutip koran itu dari beberapa penasihat Istana Buckingham yang tidak mau disebut namanya, tapi yang karena alasan tertentu bersedia membocorkan suasana pembicaraan antara Ratu dan Thatcher, Selasa pekan silam. Juru bicara Istana, Michael Shea, membantah Sunday Times beberapa hari kemudian. "Laporan itu tidak berdasar sama sekali," katanya singkat. Tapi keterlambatan reaksi Istana justru memperkuat kecurigaan orang akan adanya keretakan antara Ratu dan PM Thatcher. Pemberitaan Sunday Times bukan saja menyulut desas-desus, tapi juga memancing berbagai komentar di radio dan televisi. Tidak heran jika para pengamat berkesimpulan bahwa krisis Afrika Selatan telah berkembang menjadi krisis Kerajaan Inggris. Disebut-sebut juga adanya rencana jahat untuk menyingkirkan Thatcher, yang tingkat popularitasnya kini merosot tajam. Dalam poll pekan lalu, Partai Konservatif Thatcher berada pada urutan ketiga, di bawah Partai Buruh dan Partai Centrist Sosial. Kisruh tingkat atas antara Ratu dan PM yang sama-sama berusia 60 tahun itu telah mendorong pers bebas di Inggris untuk menyorot dari berbagai sudut pandang, sesuai dengan selera mereka. Sebagian keberatan terhadap campur tangan Ratu yang bertindak terlalu jauh, mencampuri wewenang PM sebagai kepala pemerintahan. Kecenderungan bahwa Ratu lebih mementingkan Persemakmuran ketimbang Kerajaan Inggris oleh sebagian orang juga dianggap tidak bijaksana. Pendapat ini antara lain disuarakan oleh Anthony Beaumont-Dark, seorang anggota parlemen. Di pihak lain ada pula yang meragukan berita tentang kritik Ratu terhadap Thatcher, sedangkan politikus kawakan Enoch Powell menilai berita The Sunday Times semata-mata bertujuan mendiskreditkan Margaret Thatcher. Dewasa ini tidak banyak yang dapat dilakukan pemerintah Inggris untuk memperbaiki citra, khususnya dalam menghadapi Dunia Ketiga. Menlu Geoffrey Howe direncanakan berkunjung ke Pretoria pekan ini sebagai upaya terakhir agar Presiden Piet Botha sedia berunding dengan para pemimpin mayorits hitam Afrika Selatan. Tapi misi Howe diperkirakan gagai, karena sampai kini belum ada tokoh hitam, apakah Mandela, Uskup Agung Desmod Tutu, atau Allan Boesak, yang sedia berdialog dengannya. Howe memang berusaha melakukan terobosan bersejarah, menembus kebuntuan politis di Afrika Selatan. Tapi usaha ini dianggap sia-sia, konon pula rencana memperjuangkan pembebasan pemimpin organisasi terlarang Africa National Congress, Nelson Mandela. Besar kemungkinan, ketegaran sikap Thatcher -- yang menolak sanksi ekonomi dengan tidak semena-mena -- telah memojokkan Inggris sebagai juru damai yang tidak bisa dipercaya. Pemimpin mayoritas hitam seperti Desmond Tutu dan Mandela bukan tidak tahu bahwa penolakan itu berpangkal pada kepentingan Inggris juga adanya. Thatcher harus mengamankan investasi sebesar US$ 17 milyar yang dipertaruhkan Inggris di Afrika Selatan, plus ekspor senilai US$ 1,5 milyar per tahun ke negeri itu. Tentu saja Thatcher tidak percaya pada sanksi ekonomi, karena tindakan serupa ini pada akhirnya hanya akan merugikan Inggris, berikut negara industri seperti AS, Jer-Bar, dan Jepang. Sekalipun sikap tidak kenal kompromi wanita besi itu erat kaitannya dengan kepentingan Inggris sendiri, tidak sedikit negara Barat yang tidak sepaham dengannya. Prancis umpamanya, tidak sependapat kalau dikatakan bahwa sanksi ekonomi hanya akan membuat rakyat hitam jadi lebih menderita. Menimbang bahwa mayoritas hitam itu sudah lama tertindas, sanksi ekonomi belum tentu ada efeknya pada mereka. Masyarakat hitam sudah terlalu kenyang dengan berbagai pelanggaran hak asasi, hingga kekhawatiran Thatcher dianggap tidak beralasan sama sekali. Sebaliknya, yang akan kewalahan oleh sanksi ekonomi itu justru minoritas kulit putih, setidaknya begitulah menurut pendapat para pemimpin Afrika hitam. Sementara itu, ada teori yang menyatakan bahwa hanya dengan mengacaukan pasaran emas dan berlian -- dua produksi utama Afrika Selatan -- barulah pemerintahan Botha bisa ditekan. Yang pasti pemerintah konservatif Thatcher sudah dua kali terpukul, pertama oleh aksi boikot, kemudian oleh sikap tidak senang Elizabeth II. Masih harus dilihat adakah Ratu akan "mempermalukan" Thatcher dalam sidang puncak 8 negara Persemakmuran 3 Agustus depan. Isma Sawitri, Laporan Kantor-Kantor Berita
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini