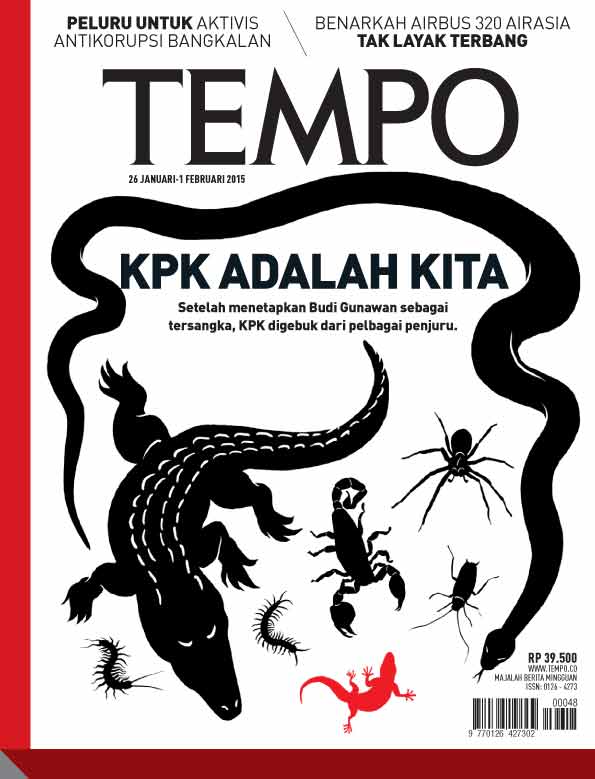Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dari kejauhan di dermaga Corigliano, Italia selatan, seorang pria yang berdiri dengan kruk berteriak lantang, "Italia, bagus. Terima kasih, Italia. Terima kasih banyak!" Ia baru saja turun dari kapal berbendera Sierra Leone, Ezadeen, yang sempat terombang-ambing di laut karena ditelantarkan awaknya, sebulan lalu.
Boleh dibilang nasib pria itu, juga lebih dari 350 penumpang lain, sebenarnya belum jelas. Di beberapa kota besar di Italia, seperti Roma, Milan, dan Turin, protes anti-imigran semakin marak, juga negara-negara Eropa lain, seperti Jerman. Pada saat yang sama, Eropa kian ketat terhadap imigran setelah serangan teroris di Prancis, tiga pekan lalu. Tapi pria asal Homs, Suriah, itu tetap wajar mengucapkan rasa gembiranya. Ia terbebas dari pertumpahan darah di negerinya yang telah menewaskan lebih dari 200 ribu orang.
Perjalanan ilegal penuh derita tak terlihat telah membuatnya sengsara. Padahal, selain terombang-ambing dan dalam keadaan lapar karena tak makan dan minum selama beberapa hari, di kapal yang seharusnya untuk mengangkut hewan ternak itu ia harus berdesak-desakan dengan penumpang lain.
"Mereka mengatakan penyeberangan tersebut sangat sulit dan sangat berbahaya," kata Giovanna di Benedito, juru bicara Save the Children di Italia, yang mengatur penerjemah buat para migran.
Benedito menyatakan orang-orang di kapal itu berangkat dari Mersin, Turki, 10 hari sebelumnya. Tapi asal penumpangnya beragam, meski hampir semuanya orang Suriah. Ada yang berangkat dari Libanon menuju Turki, baru berangkat dari Antalya. Ada juga yang berasal dari Kobani.
Menurut Laksamana Giovanni Pettorino, komandan operasional penjaga pantai Italia, Ezadeen adalah kapal ketiga yang ditelantarkan awaknya dengan ratusan orang—terutama dari Suriah—di dalamnya.
Orang Suriah penumpang kapal tersebut terhitung mereka yang memiliki duit—ongkos naik kapal itu US$ 5.000 (sekitar Rp 63,5 juta) per kepala—dan tak tahan lagi hidup di negerinya, atau juga di pengungsian di negeri tetangga. Kabur menuju kota lain di Suriah tak membuat mereka bebas dari pertempuran antara pasukan pemerintah dan pemberontak serta dengan kelompok-kelompok Islam militan, seperti Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), plus pasukan asing. Ke negeri tetangga, kehidupan tak jauh lebih baik. Belum lagi penderitaan akibat musim dingin karena mereka tak memiliki "senjata" cukup untuk melawannya.
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejak perang berkecamuk di Suriah pada 2011, warga Suriah yang menjadi pengungsi telah mencapai 10,8 juta. Jumlah terbesar mengungsi di daerah lain di Suriah. Sekitar 3,3 juta terdaftar mengungsi ke negeri tetangga dan sebagian kecil ke Barat. Hingga awal Desember tahun lalu, jumlah terbesar pengungsi yang tercatat dan yang masuk daftar penempatan berada di Turki, sekitar 1,16 juta. Menyusul Libanon sekitar 1,15 juta, kemudian Yordania, mendekati 620 ribu.
Di pengungsian itu ada yang tinggal dengan saudara, ada pula yang menyewa rumah. Tapi jauh lebih banyak yang harus berteduh di tenda-tenda tempat penampungan pengungsi, atau di bangunan telantar dan belum jadi. Krisis pengungsi Suriah ini dinyatakan terbesar sejak Perang Dunia II.
Karena jumlah pengungsi yang begitu besar dan waktu pengungsian yang belum terlihat kapan berakhir, negara penerima menjadi kesulitan. Warga dan pemerintah jiran yang tadinya ramah dan enteng membantu kini bergeser menjadi lebih sangar.
Misalnya Libanon. Di negara itu jumlah pengungsi Suriah merupakan seperempat dari total penduduk yang jumlahnya sekitar 4 juta. Beberapa desa dan kota telah menerapkan jam malam karena khawatir atas keamanan di daerahnya. Maklum, beberapa kali kekerasan melanda "kawasan pengungsi", dan terakhir ledakan bom di Tripoli sekitar sebulan lalu. Jabhat al-Nusra Suriah mengklaim sebagai otaknya.
"Jika melihat kami di luar setelah pukul 8, mereka akan memukuli kami," kata Ammar al-Hussein, pengungsi di Ebrin, kepada NPR. "Rasanya seperti di penjara," ayah enam anak ini menambahkan.
Pengungsi lain, Abdullah, dipukuli dengan tiang lampu oleh sekelompok orang Libanon ketika akan pulang dari tempat kerjanya di sebuah proyek konstruksi. Alasannya, "Karena saya orang Suriah," kata Abdullah. Tak cukup itu saja, para penyerang mengultimatum agar sebelum pukul 6 pagi ia dan keluarganya sudah meninggalkan rumahnya di Ouzai, selatan Beirut. Ia pun kabur.
Anak-anak pun tak lepas dari cercaan dan tindak kekerasan. Seperti yang dialami Moatassem, yang tinggal bersama orang tuanya di Libanon timur, di perbatasan dengan Suriah. "Setiap kali saya naik bus ke sekolah atau pulang sekolah, mereka menendang saya, memukul saya, dan memaksa saya tetap di luar bus sampai semua anak Libanon masuk bus dulu," ujar bocah 11 tahun ini, seperti disitir di situs World Vision. Kata-kata yang memanaskan telinga biasa dia dengar, seperti disebut sampah.
Dalam sebuah survei yang laporannya dikeluarkan pada Maret tahun lalu disebutkan lebih dari 90 persen warga Libanon di Lembah Beka dan kawasan utara Libanon—tempat dengan begitu banyak pengungsi Suriah—menganggap pengungsi sebagai ancaman, termasuk dari segi ekonomi. Lapangan kerja terebut. Juga kesempatan ekonomi.
Mohammed Yasin, warga Masnaa di dekat perbatasan Suriah, menuduh orang-orang Suriah mencurangi sistem. "Mereka bekerja, bukan pengungsi," kata pemilik bisnis penukaran uang berusia 60 tahun ini. Menurut dia, orang Suriah yang membuka penukaran uang tak jauh dari tempatnya telah membuat bisnisnya turun hingga 75 persen.
Di Turki dan Yordania, pengungsi juga tak bebas dari berbagai tekanan. "Mereka memang telah kehilangan segalanya. Tapi, semakin banyak kami menerima mereka, semakin besar masalah yang timbul," kata Tanrioglu, warga Turki.
Sebagian pengungsi sudah hilir-mudik di jalanan untuk mengemis atau mengamen. Meski polisi kerap merazia mereka, terutama di Istanbul, Ankara, dan kota-kota lain, banyak yang kembali ke jalanan karena bantuan yang ada memang tak cukup.
Pemerintah negara-negara jiran Suriah pun telah meneriakkan SOS kepada masyarakat internasional karena sudah kewalahan mengurusi pengungsi, meski selama ini sudah ada bantuan, tapi jauh dari cukup. Sebagian negara Barat seolah-olah jauh lebih berfokus dengan target menghabisi kelompok pimpinan Abu Bakar al-Bagdadi dan kelompok militan lainnya. "Alarm tak henti berbunyi," kata Menteri Sosial Libanon Rashid Derbas.
Belakangan, Libanon pun menerapkan aturan yang membatasi pengungsi. Bulan lalu Menteri Tenaga Kerja Sejaan Qazzi mengeluarkan peraturan yang mulai berlaku tahun ini: pengungsi hanya bisa bekerja di sektor pertanian, konstruksi, dan pembersihan.
Selain itu, pemerintah Libanon kembali mengeluarkan peraturan untuk menghalangi pengungsi dari Suriah, dengan mensyaratkan visa. Menurut Menteri Rashid Derbas, sejak 5 Januari, tak ada satu pun pengungsi dari Suriah masuk negerinya.
Yordania juga berteriak. "Tanpa dukungan internasional, sangat sulit bagi Yordania untuk terus mengurusi masalah besar ini," kata Menteri Dalam Negeri Hussein Hazza al-Majali.
Turki tak kalah pusing. Negeri pimpinan Racep Tayyip Erdogan ini telah menggelontorkan dana US$ 5 miliar untuk mengurusi pengungsi Suriah, baik buat memberi pelayanan kesehatan, beasiswa pendidikan, maupun bantuan penampungan dan makanan. Sedangkan bantuan internasional yang diterima hanya US$ 265 juta, meski janji-janji manis telah ditebar.
Keadaan yang semakin buruk menyebabkan Turki mulai bersikap keras di pintu masuk.
Memang sudah ada respons terhadap situasi itu. Komisioner Tinggi untuk Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, menyatakan 28 negara siap menerima lebih dari 100 ribu pengungsi dari Suriah. Amerika Serikat, menurut Asisten Menteri Luar Negeri Urusan Populasi, Pengungsi, dan Migrasi Anne Richard, tahun ini akan menerima 10 ribu pengungsi Suriah. Ini jauh meningkat di banding tahun lalu yang hanya 400.
Tapi bantuan itu masih jauh dari cukup. Apalagi masalah dana. Tahun lalu saja, dari US$ 3,7 miliar yang dibutuhkan, dana yang mengalir hanya sekitar separuh. Biaya untuk mengurusi jutaan pengungsi sangat besar, dan dibutuhkan entah sampai kapan.
Maka sejauh ini para pengungsi hanya bisa bergantung pada harapan. "Kami tidak boleh menyerah," kata Raya, pengungsi di kamp penampungan Zaatari, Yordania, seperti dinyatakan di situs Komite Penyelamatan Internasional. "Saya berpegang erat pada harapan sekecil apa pun itu, karena saya tak ingin jatuh. Kalaupun saya jatuh, saya harus berdiri lagi di kaki saya sendiri, demi anak-anak," ujar ibu empat anak ini.
Purwani Diyah Prabandari (The Guardian, The Washington Post, CNN, Xinhua, Wall Street Journal, Al Jazeera)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo