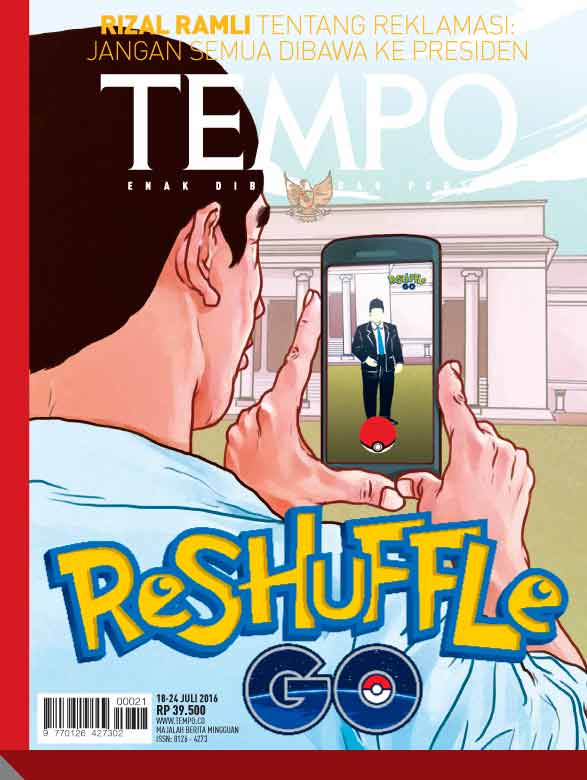Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
MEREKA telah kehilangan kepercayaan terhadap bahasa verbal. Maka meletuslah pistol di tangan polisi kulit putih Amerika—yang belakangan acap dicurigai menyimpan sangka buruk kepada warga kulit hitam—lalu rebahlah Philando Castile dengan tubuh bersimbah darah. Di luar Kota Minneapolis, karena lampu belakang mobilnya tak menyala, Philando Castile, 32 tahun, pemuda kulit hitam, diseret kemudian ditembak oleh seorang polisi lalu lintas di jok mobilnya.
Setelah sebuah video yang merekam adegan Castile perlahan-lahan kehabisan darah di kursi depan mobilnya itu beredar luas, gemparlah masyarakat Amerika. Namun apa yang kemudian terjadi pada Kamis pagi dua pekan lalu di tengah-tengah Kota Dallas, Texas, sungguh di luar dugaan. Tatkala ribuan orang menyambut seruan kelompok kulit hitam Black Lives Matter untuk turun ke jalan memprotes kebrutalan itu, diam-diam seorang pemuda setempat memanjat sebuah gedung bertingkat, kemudian mulai menembaki polisi. Dari atap gedung, Micah Xavier Johnson, 25 tahun, menembak sambil berpindah-pindah, dan hasilnya benar-benar menyesakkan: lima orang polisi tewas dan sembilan lainnya luka-luka—semuanya berkulit putih.
Dua jam lebih tembak-menembak yang sesekali diselingi negosiasi yang menegangkan itu berlangsung. Terkecoh oleh kelincahan bekas prajurit dalam pasukan cadangan Amerika yang pernah bertugas di Afganistan ini, dan melihat korban di pihaknya bertambah banyak, akhirnya polisi memutuskan untuk menyudahi "drama" itu. Teror Micah Johnson berakhir setelah mereka mengirim robot untuk menghampirinya, dan meledakkannya dari jarak jauh. Johnson pun tewas—beberapa blok dari lokasi penembakan Presiden John F. Kennedy pada 1963.
Tatkala polisi lalu memeriksa apartemennya di lingkungan Pecan Creek, Mesquite, pinggiran Dallas, mereka menemukan rompi antipeluru, aneka senjata laras panjang, amunisi, dan ramuan untuk merakit bom. Rupanya, penembakan itu hanya satu dari serangkaian rencana Micah Johnson dalam perang pribadinya melawan polisi kulit putih.
Seseorang yang lelah dengan perlakuan buruk polisi terhadap orang-orang kulit hitam telah menempuh jalan ekstrem. Seorang anak tetangganya di Mesquite, yang setiap minggu suka menghabiskan waktu bermain bola basket bersamanya, mengatakan bahwa Johnson tidak banyak bicara. Ia tampak berpendidikan, katanya, dan sepertinya sudah meresapi buku-buku gerakan pembebasan kulit hitam di Amerika.
Tentu seorang Micah Johnson sudah bergulat dengan gagasan antikekerasan Martin Luther King Jr, ide separatis Elijah Mohammad (pendiri kelompok The Nation of Islam), dan pergulatan aktivis antikulit putih Malcolm X. Seorang pendiam telah menanamkan ajaran-ajaran itu dengan khidmat ke dalam sanubarinya sendiri, dan sekarang ada "sesuatu" yang membuat ia pelan-pelan bergerak dari keyakinan yang mengharamkan kekerasan jadi menghalalkan kekerasan.
Orang banyak menyebut mereka kelompok kebencian (hate group). Tak lama setelah hidup Micah Xavier Johnson yang singkat itu berakhir, salah satu di antara mereka memperlihatkan diri dengan sebuah komentar yang tegas di situs Facebook.
"Kami tak punya pilihan! Kita harus membunuh polisi di seantero negeri ini," kata Mauricelm-Lei Millere, pendiri kelompok Liga Pertahanan Amerika Afrika atau African American Defense League (AADL). Orang mencurigai grup ini karena sebelum Micah Johnson mengokang senapan, AADL telah menyerukan pembalasan. Johnson bukan anggota kelompok ini, tapi dia salah satu dari 170 orang yang setia mengunjungi situs itu.
"Kami meminta kelompok-kelompok The Nation, seranglah semuanya yang berseragam biru (polisi), kecuali para tukang pos," begitu seruan AADL dalam situsnya, beberapa saat setelah televisi memberitakan penembakan Philando Castile di mobilnya.
Didirikan pada Agustus 2014 setelah gelombang protes terhadap penembakan remaja kulit hitam Michael Brown oleh seorang polisi kulit putih di Missouri, AADL bukan kelompok yang populer. Namun Millere dan grup itu juga bekerja sama dengan beberapa kelompok ekstrem lain, seperti Gereja Baptis Bintang Pagi di Jonesboro, Louisiana.
Di antara ramainya penembakan warga kulit hitam oleh polisi kulit putih akhir-akhir ini, AADL, New Black Panther Party, The Nation of Islam, dan beberapa kelompok ekstrem lain seperti menemukan momentum yang tepat untuk bergerak. Dan seorang pencari identitas yang telah lama menyimpan amarah dan kecewa seperti Micah Johnson merupakan sasaran empuk grup itu.
"Kelompok-kelompok ekstrem mendorong penyerang individual seperti Johnson atas nama ideologi yang diyakininya," kata J.M. Berger dari Universitas George Washington, yang mengepalai Program Ekstremisme. Organisasi teroris Negara Islam atau ISIS menggunakan cara-cara ini untuk melancarkan teror, dan kini kelompok kulit hitam mulai melakukannya.
Tom Fuentes, Wakil Direktur Badan Penyelidik Federal (FBI), mengakui kemiripan sepak terjang propaganda ISIS dengan kelompok-kelompok militan itu. "Pertanyaannya, apa perbedaan antara kebebasan berpendapat dan penyebaran kebencian," katanya. "Susahnya lagi, orang-orang ini warga Amerika Serikat yang memiliki perlindungan hukum untuk menyampaikan pendapat."
Setiap orang pernah menyimpan kekecewaan. Micah Johnson, yang semenjak kecil membayangkan diri menjadi tentara Amerika, akhirnya kecewa karena diberhentikan dari dinas militer—lantaran kasus pelecehan seksual terhadap rekan perempuannya di Afganistan. Tak banyak penjelasan dan informasi tentang kelakuannya itu. Yang jelas, tatkala kembali ke tempat tinggalnya di Mesquite, ia seperti layang-layang putus, hingga akhirnya menemukan idola seperti Malcolm X dalam perjalanan hidupnya.
Ia menangkap bagaimana seorang Malcolm X yang sejak usia enam tahun ditinggalkan ayahandanya, seorang pendeta Baptis yang dibunuh setelah menerima ancaman dari kelompok rasis kulit putih Ku Klux Klan, dan ibunya terguncang jiwanya. Malcolm kecil dan tujuh saudaranya telantar. "Semua orang negro marah, dan saya yang paling marah," katanya getir, seakan-akan memberi penjelasan mengapa ia sampai memimpin orang kulit hitam yang hendak memisahkan diri dari Amerika yang putih.
Identitas kulit hitam memang menjadi pertanyaan yang senantiasa diuji. Malcolm X yang keras itu kemudian berubah. Pada 1964, ia mulai membaca Al-Quran dan sadar bahwa manusia, juga dalam amarahnya, tetap seorang manusia yang terbatas, dan sebab itu harus adil juga kepada musuhnya yang berkulit putih.
Idrus F. Shahab (CNN, The Daily Beast, The Guardian, The Independent)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo