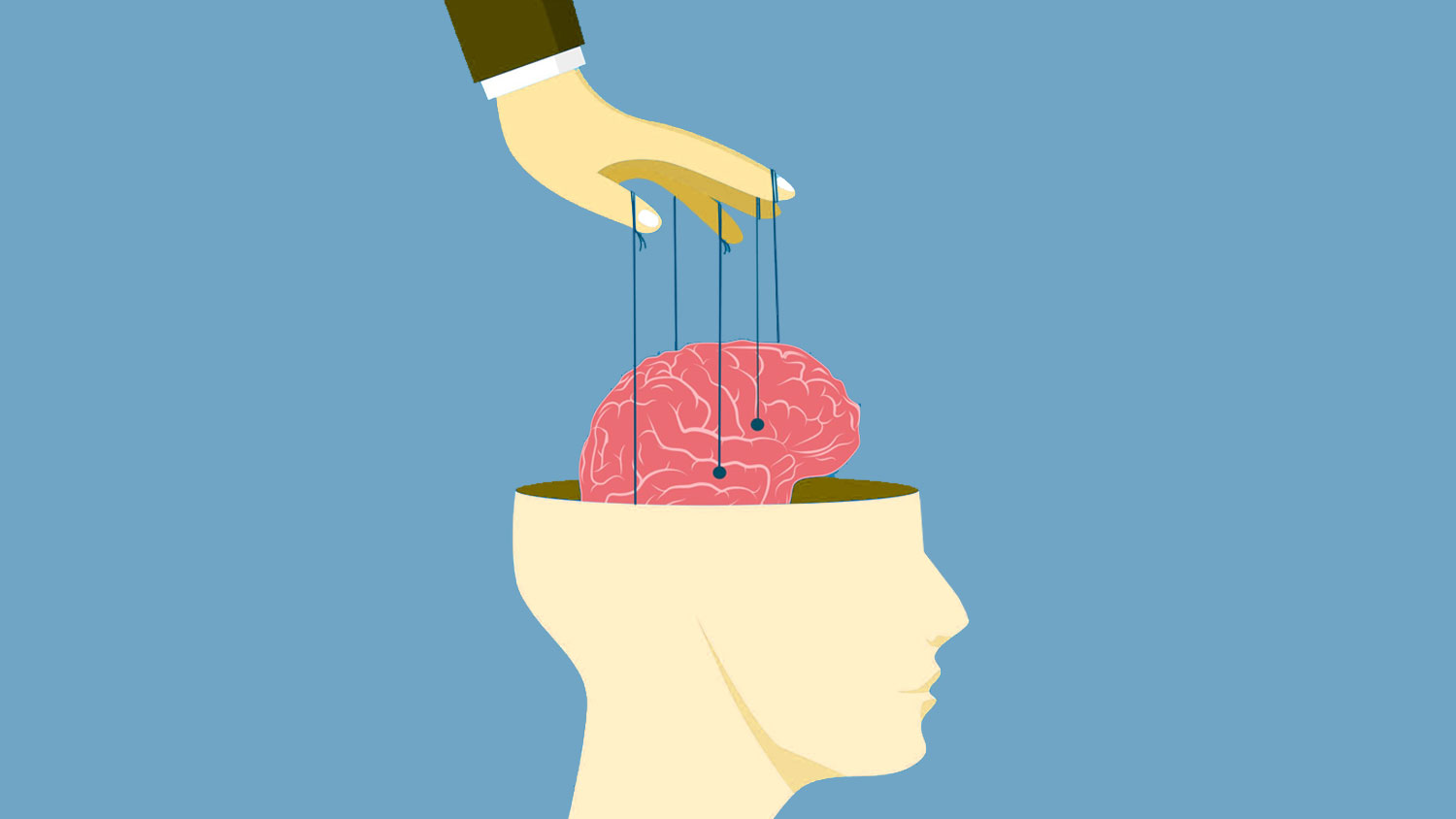Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Benarkah ini "akhir sejarah", ketika semua pergulatan untuk dunia yang lebih baik sudah tak berguna lagi? Francis Fukuyama-25 tahun yang lalu menulis The End of History and the Last Man, kita ingat-menguraikan "akhir sejarah" sebagai masa ketika "pergulatan untuk diakui, kesediaan orang mempertaruhkan nyawa buat tujuan yang sepenuhnya abstrak, dan benturan ideologis sedunia yang memanggil tekad, keberanian, imajinasi, dan idealisme" telah habis. Semua itu digantikan "perhitungan ekonomi" dan penyelesaian persoalan-persoalan teknis.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo