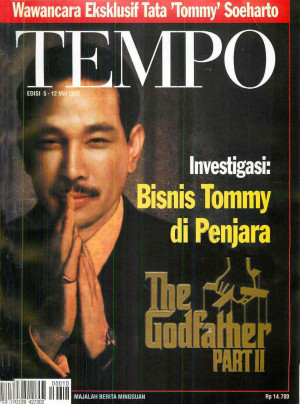Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

K.H. Abu Bakar Ba'asyir agaknya menjadi lakon hukum kontroversi tahun ini. Dulu, tahun 1985, pemimpin Pondok Pesantren Al-Mukmin di Desa Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, itu divonis sembilan tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan Undang-Undang Antisubversi Tahun 1963, ia diputus bersalah karena menolak asas tunggal Pancasila. Tapi vonis kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap itu tak sempat dijalani Ba'asyir lantaran ia pergi (kabur?) ke Malaysia. Baru pada 1998, setelah rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto tumbang, tokoh Majelis Mujahidin Indonesia ini pulang kampung.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo