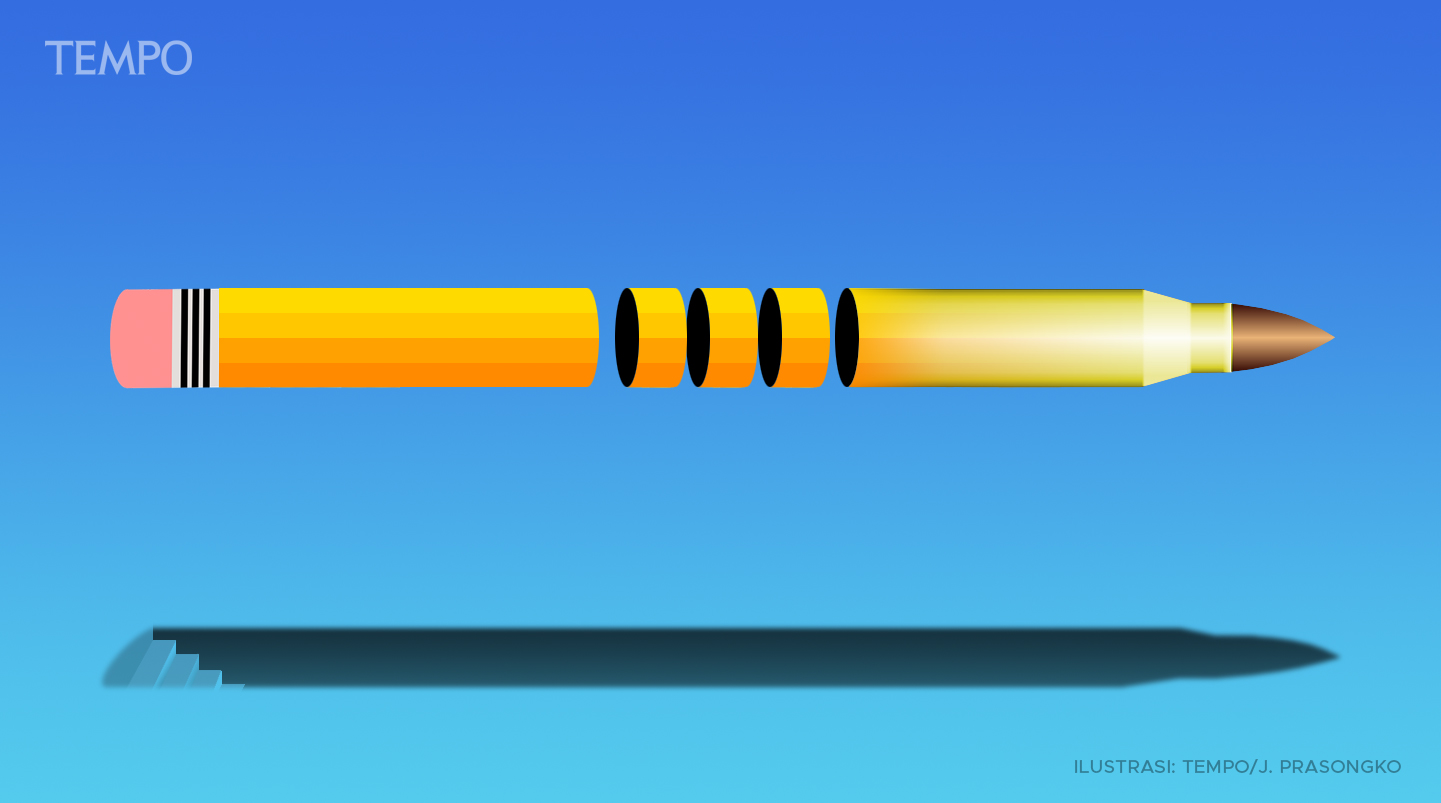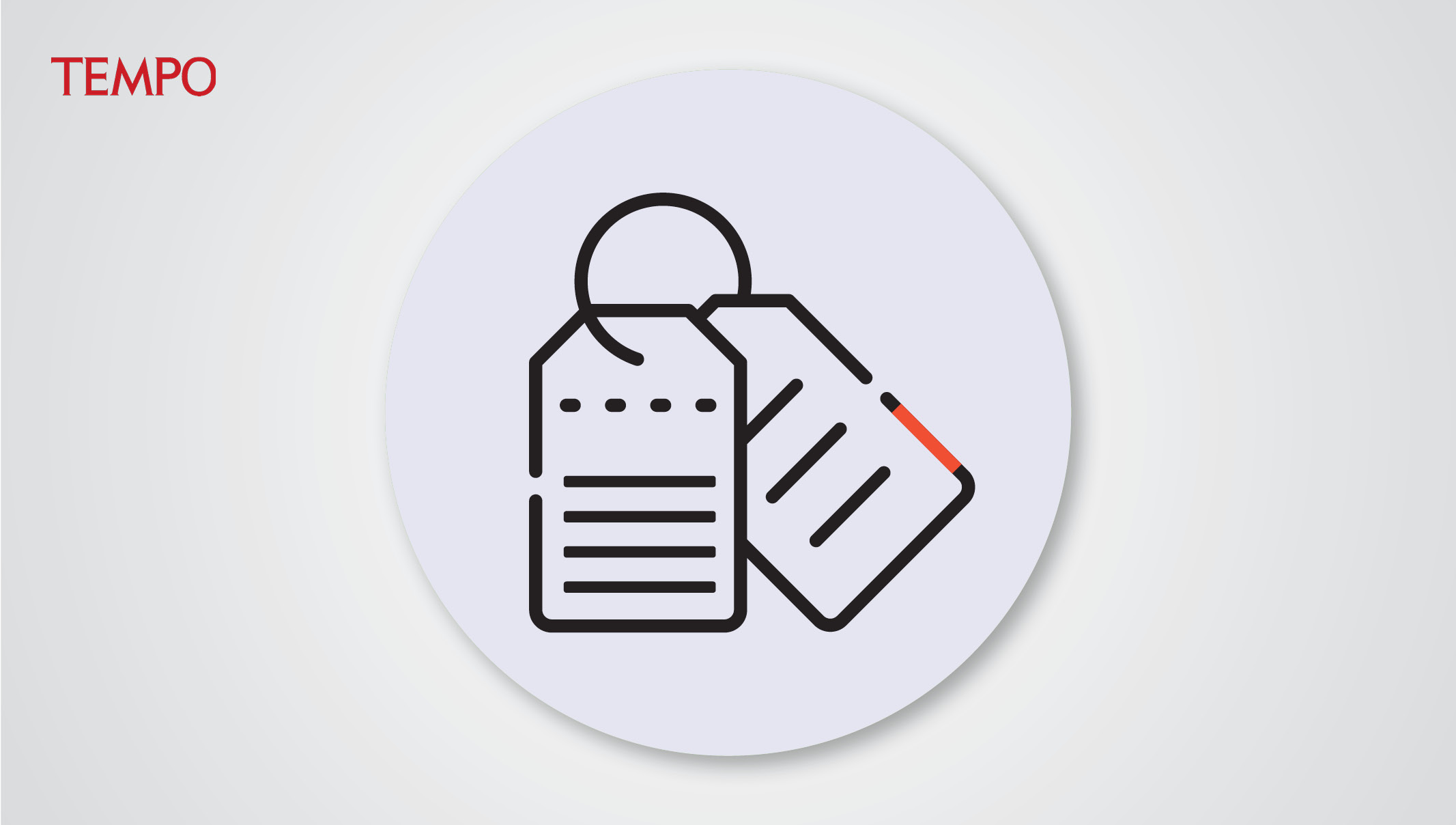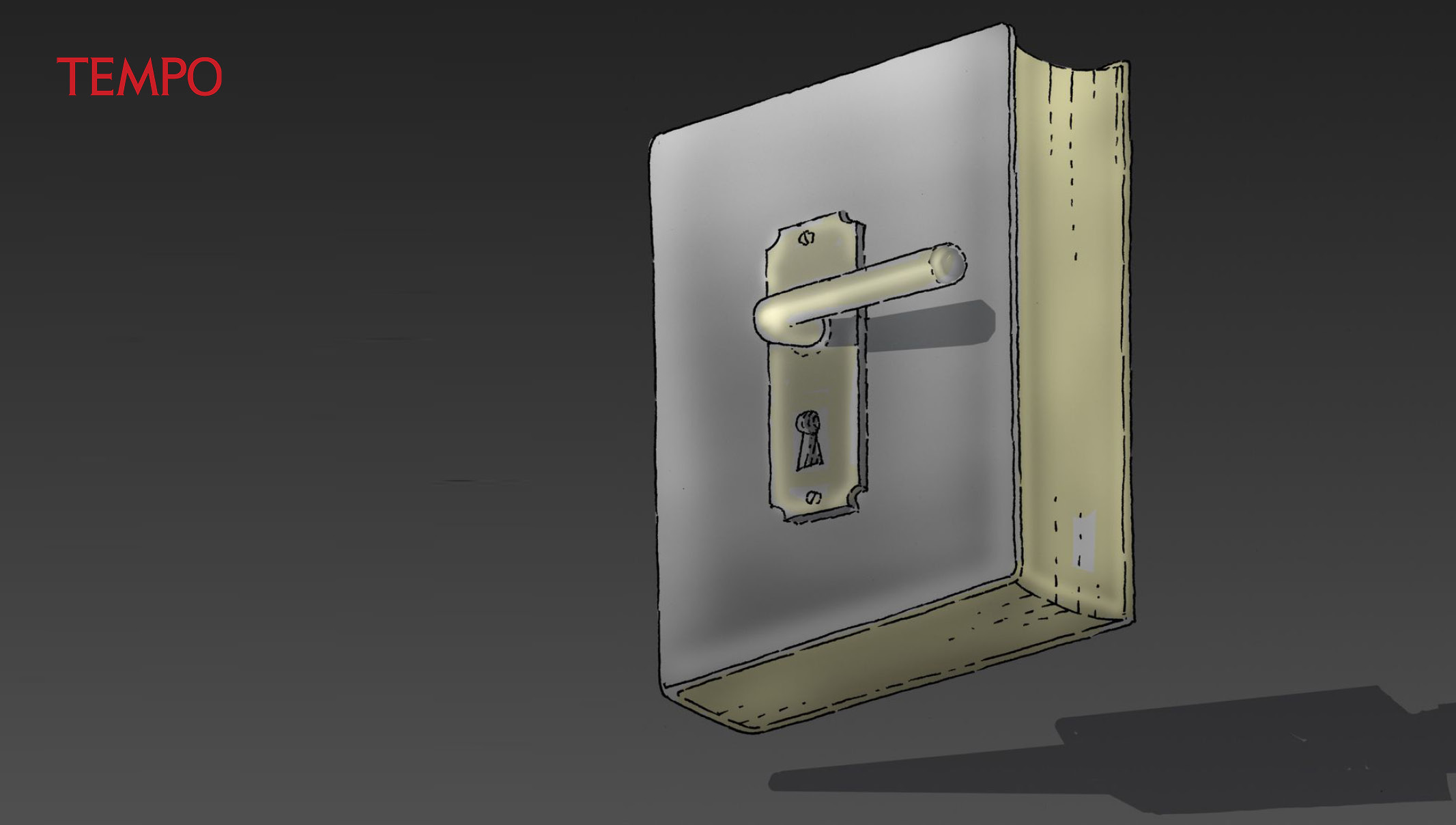Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Alek Karci Kurniawan
Analis Hukum dan Kebijakan Komunitas Konservasi Indonesia
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Program perhutanan sosial sebenarnya masuk kebijakan pemerintahan sejak 2004. Hal ini dapat kita temukan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat. Ketika itu, para pemikir dan praktisi kehutanan barangkali belum menemukan istilah yang cocok sehingga memakai "social forestry". Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, social forestry memiliki target 1 juta hektare.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pergantian rezim dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo pada 2014 tidak menghentikan agenda social forestry. Setelah itu, istilah "perhutanan sosial" juga semakin dikenal. Kemudian target pelaksanaan dinaikkan menjadi 12,7 juta hektare. Pejabat di bawah Kementerian Kehutanan yang khusus menangani perhutanan sosial dibentuk, kelompok kerja penanganan kasus disusun, dan birokrasi disederhanakan.
Melambungnya target pelaksanaan perhutanan sosial ini dipengaruhi oleh misi Presiden Jokowi dalam membangun Indonesia dari pinggiran dan mengatasi kemiskinan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar hutan. Tim transisi pemerintahan ketika itu, menurut Menteri Kehutanan Siti Nurbaya pada Maret 2018, malah mengusulkan target agenda ini seluas 30 persen dari hutan Indonesia. Artinya, 37 juta dari 125 juta hektare hutan dibayangkan bisa disulap menjadi perhutanan sosial (KLHK, 2018).
Dengan segala instrumen, pemerintah berusaha mengimplementasikan agenda tersebut. Sayangnya, hingga berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019, perhutanan sosial baru terlaksana 18 persen. Pada akhir-akhir periode pemerintahan sebelumnya, pemerintah mulai menyadari bahwa target program ini memang tidak realistis, bahkan bila target itu dipotong dua dan dibuang satu kepingnya. Maka, pada Maret 2018, target perhutanan sosial direvisi menjadi 4,38 juta hektare.
Untuk melanjutkan program perhutanan sosial pada periode keduanya, Presiden Jokowi sebaiknya mengevaluasi total perencanaan program tersebut. Pertama, tim transisi harus diambil dari orang yang benar-benar ahli dalam hal kehutanan dan kemasyarakatan. Bukan hanya pakar secara akademik, tapi juga berpengalaman dalam mendampingi masyarakat di sekitar hutan sehingga tidak berhalusinasi ketika menyusun agenda kehutanan.
Kedua, data-data tutupan hutan serta konsesi yang ada dalam kawasan hutan harus terkonsolidasi. Salah satu faktor penyebab penyusunan peta indikatif dan areal perhutanan sosial tidak jernih adalah tumpang-tindihnya data kehutanan.
Ketiga, anggaran pelaksanaan. Indonesian Budget Center menghitung, agar mampu mencapai target 12,7 juta hektare, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran sedikitnya Rp 830,58 miliar setiap tahun. Biaya itu diperlukan untuk sejumlah kebutuhan, seperti pendampingan masyarakat, sosialisasi, fasilitasi, dan verifikasi usulan penerbitan izin perhutanan sosial.
Namun alokasi anggaran yang disediakan pemerintah untuk pemberian akses kelola perhutanan sosial punya keterbatasan. Selama 2015-2017, misalnya, pemerintah hanya sanggup menganggarkan untuk penyiapan area perhutanan sosial rata-rata Rp 38,76 miliar setiap tahun. Lalu bagaimana menutupi kekurangannya? Sebaiknya pemerintah betul-betul bersinergi dengan berbagai organisasi masyarakat sipil (CSO) yang berfokus pada isu ini. Kenyataannya, cukup banyak CSO di Indonesia yang memiliki projek perhutanan sosial.
Keempat, masih banyak pemerintah daerah yang tidak mendukung atau bahkan menolak agenda perhutanan sosial dengan asumsi bakal menghambat pembangunan daerah. Pandangan tersebut sangatlah parsial dan perlu diluruskan. Secara langsung pemasukan daerah mungkin akan berkurang dengan beralihnya izin pemangkuan penguasaan hutan dari perusahaan ke masyarakat. Namun pemerintah daerah seharusnya tidak menutup mata bahwa dengan terlaksananya program perhutanan sosial juga meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Secara tidak langsung, dengan mendukung agenda dari pusat ini, pemerintah daerah telah menyejahterakan masyarakatnya sendiri.
Kelima, bagaimanapun, keberhasilan pengembangan perhutanan sosial bukan semata karena ada legalitas atau bantuan permodalan. Ini adalah agenda dari bawah ke atas dengan syarat mutlak mewujudkan kesuksesannya lebih ditentukan oleh sejauh mana masyarakat yang menjadi subyek dari agenda ini mampu membangun kelembagaan secara solid, baik dalam mengatur maupun membagi manfaat hutan secara adil.
Mobilisasi, menurut Suhardi Suryadi (2017), kadangkala dapat mendistorsi makna keberlanjutan kemakmuran masyarakat yang bergantung pada sistem pengelolaan hutan. Tanpa proses pelembagaan yang solid, adil, dan partisipatif, perhutanan sosial hanya berhasil di atas kertas tapi gagal di tingkat realitas.