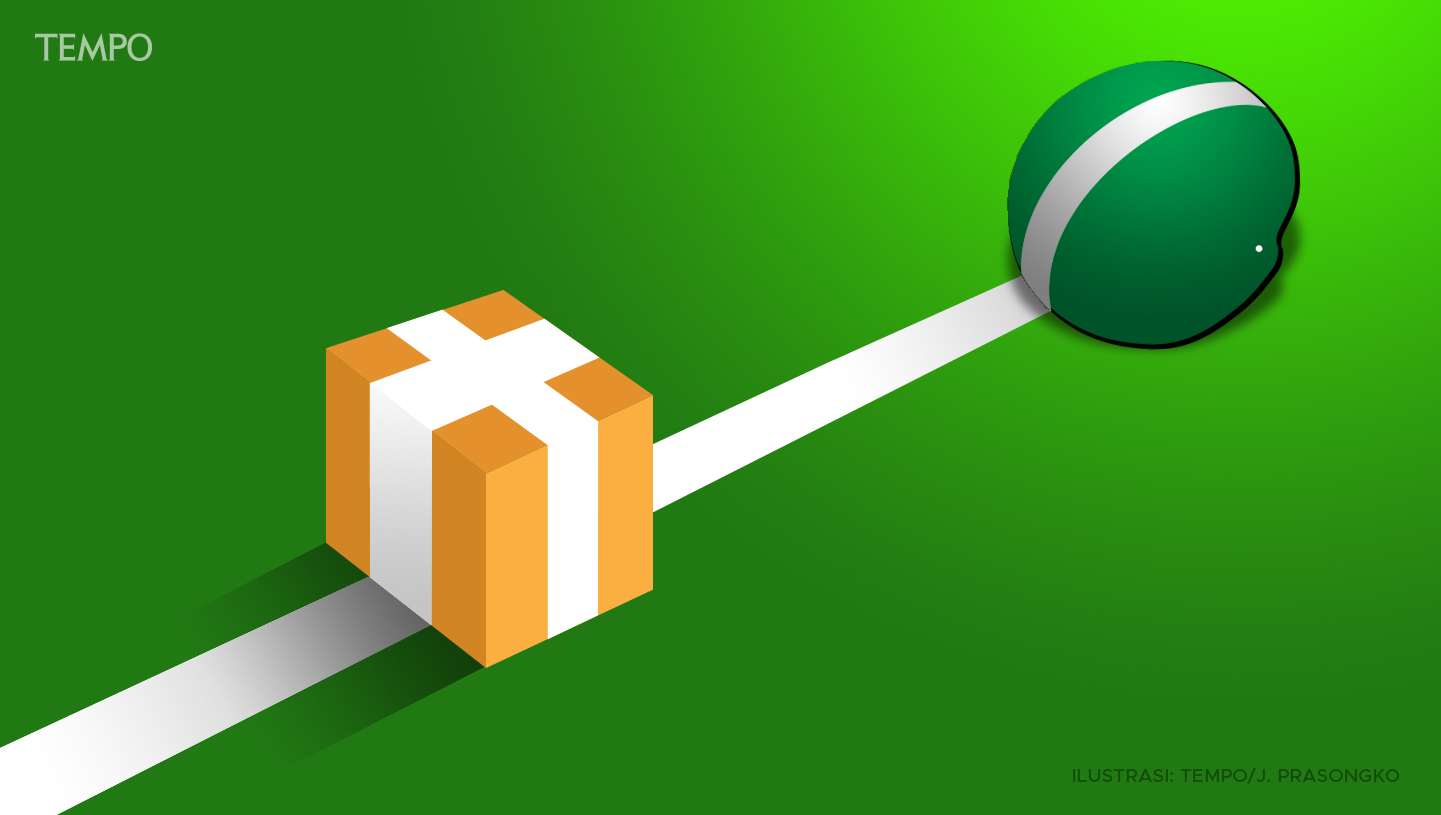Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Anak-anak muda kini mendapat pendidikan dari hal-hal viral di media sosial.
Sebagian yang tampil di media sosial tidak sesuai dengan kenyataan.
Perlu daya kritis untuk menapis konten negatif.
Anggi Afriansyah
Peneliti Sosiologi Pendidikan di Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo