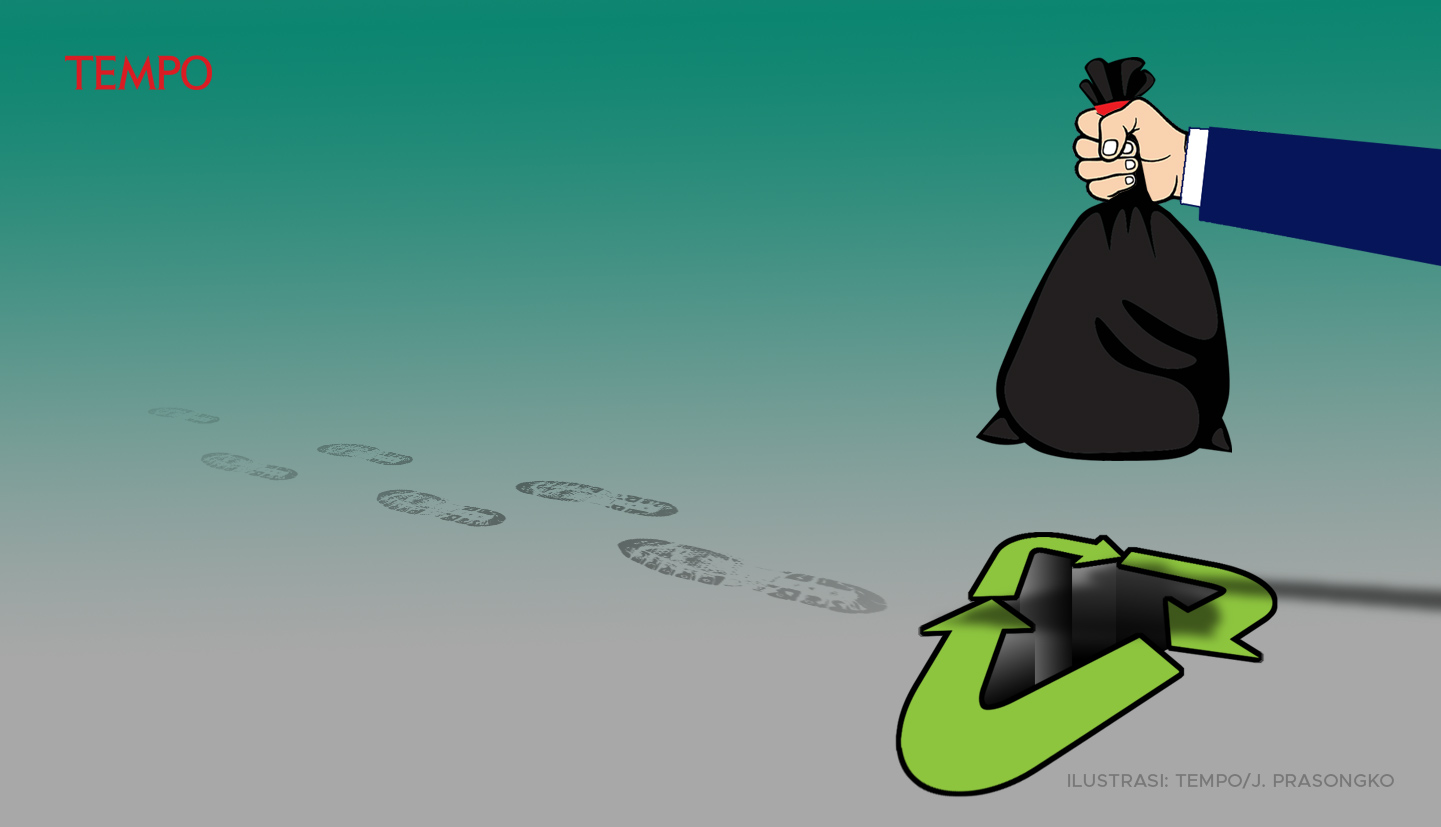Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Sejak Undang-Undang Cipta Kerja disahkan DPR, berbagai kalangan mereponsnya dengan pro dan kontra.Tak terkecuali substansi di bidang kehutanan. Salah satu substansi yang diperdebatkan adalah penghapusan ketentuan luas minimal kawasan hutan 30 persen yang tertuang dalam Undang-Undang Kehutanan. Dari masyarakat awam hingga akademisi menganggap penghapusan ketentuan ini akan memperparah penggundulan hutan. Di sisi lain, ketentuan 30 persen ini memang tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini. Ada beberapa penyebabnya.
Pertama, penetapan 30 persen membawa konsekuensi merugikan baik dari segi ekologi, sosial, dan budaya. Contohnya, provinsi dengan kawasan hutan di atas 30 persen, maka ketentuan ini justru memicu daerah untuk berlomba-lomba mengkonversi kawasan hutan. Tidak heran banyak provinsi mengubah kawasan hutan menjadi perkebunan, pertambangan, dan peruntukan lainnya.
Sebaliknya, provinsi dengan kawasan hutan dengan luas di ambang atau di bawah 30 persen, kesulitan dalam menata ruang dan menyelesaikan permasalahan konflik pertanahan. Apabila ingin mengubah tata ruangnya maka harus membeli lahan untuk dijadikan kawasan hutan sebagai pengganti. Hal ini tentu saja sangat mahal dan tidak memungkinkan, khususnya provinsi di Pulau Jawa,. Akibatnya, banyak permasalahan keterlanjuran dalam kawasan hutan—berupa pemukiman, fasilitas umum dan sosial—tidak pernah terselesaikan. Padahal, semakin lama isu tumpang tindih tenurial ini, permasalahan akan semakin larut dan kompleks. Sementara itu, terdapat lahan yang memiliki kualifikasi sebagai hutan di area penggunaan lain (non kawasan hutan).
Kedua, masyarakat awam masih rancu tentang makna hutan dan kawasan hutan. Kita sepakat hutan sangat berarti bagi kehidupan manusia. Melestarikan hutan memang suatu keharusan. Namun, angka 30 persen yang ada dalam Undang-Undang Kehutanan itu mengacu pada kawasan hutan, bukan hutan secara biofisik. Dari definisi dan kriteria, hutan berbeda dengan kawasan hutan. Untuk memudahkan membedakannya: hutan adalah hamparan tanah yang didominasi oleh pepohonan, sedangkan kawasan hutan adalah area yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, kawasan hutan adalah status suatu ruang saja, terlepas di dalamnya sudah berbentuk perumahan, perkebunan, pertambangan, dan fasum fasos. Di Indonesia, kawasan hutan tanpa pohon ini mencapai 34 juta hektare.
Sementara itu, arti hutan tidak pernah bulat baik di kalangan nasional maupun global. Di internasional, kriteria yang disepakati pada forum antar bangsa, Food and Agriculture Organization (FAO), menjadi definisi yang paling banyak digunakan. Meski demikian, definisi dan kriteria FAO mengundang perdebatan dan multi tafsir. Hutan bukan lagi dilihat dari aspek biofisik, tapi juga aspek politis. Sebagai contoh, sebelum 2015, perkebunan kelapa sawit dianggap sebagai hutan oleh FAO. Kini, sawit justru dituding sebagai penyebab utama deforestasi.
Ketiga, alasan lain penghapusan angka 30 persen adalah karena angka ini memang doktrin pemerintahan kolonial. Menurut dua cendekiawan Amerika, Davis dan Robbins, konsepsi penetapan luas minimal hutan berawal pada abad ke-18. Kemudian, ide tersebut menyebar ke berbagai kalangan rimbawan di seluruh dunia. Termasuk rimbawan kolonial yang saat itu menjajah Indonesia. Sebuah studi karya Nancy Peluso (akademisi Amerika) menyebutkan awal pengenalan angka 30 persen ini diinisiasi oleh tokoh rimbawan Belanda, Van Arstson. Tujuannya saat itu adalah untuk mengelola hutan di Jawa. Menurutnya, sekitar 30 persen wilayah daratan pulau Jawa seharusnya tertutup hutan.
Saat Indonesia merdeka, angka minimal hutan 30 persen diadopsi dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan pada 1967. Meski ada upaya merevisi pada era reformasi, namun angka 30 persen kembali muncul dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Angka luas minimal 30 persen pun dijadikan kurikulum pendidikan kehutanan baik formal maupun non formal. Tidak heran doktrin itu tertanam kuat di masyarakat Indonesia terutama kaum rimbawan.
Bertolak berbagai permasalahan di atas, maka penghapusan ketentuan 30 persen luas minimal kawasan hutan merupakan suatu terobosan nyata. Sebagai alternatif batasan minimal, sebenarnya terdapat alat analisis yang lebih komprehensif, yaitu analisis multi kriteria. Metode ini dapat mengintegrasikan berbagai nilai, seperti nilai jasa ekosistem, nilai daya dukung dan daya tampung, aspek sosial, dan juga nilai ekonomi.
Pada 2019, penulis pernah mengaplikasikan metode tersebut dengan judul “Rasionalisasi Kawasan Hutan Indonesia”. Data dan informasinya yang digunakan mencakup 31 peta tematik mewakili kriteria daya dukung daya tampung, sosial-politik, dan aspek ekonomi. Khususnya aspek daya dukung daya tampung, terdapat beberapa variabel: (1) nilai keanekaragaman hayati, (2) cadangan karbon atau kualitas hutan, (3) daya dukung daya tampung untuk air dan pangan.
Berdasarkan hasil studi, seluruh daratan Indonesia yang layak dikatakan hutan—dalam arti memberikan jasa ekosistem—adalah sekitar 65 juta hektare (34 persen daratan). Jika menempatkan hutan untuk kepentingan ekonomi, maka luasannya mencapai 110 juta hektare (59 persen daratan Indonesia).
Meskipun demikian, penentuan batas minimal tidak dapat diberlakukan sama rata secara nasional. Perlu penyesuaian berdasarkan karakteristik dan kondisi tiap pulau. Hal ini mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki ciri biofisik dan faktor sosial yang berbeda-beda. Selain itu, faktor demografi juga sangat berpengaruh terhadap penentuan batas minimal kawasan hutan. Pulau dengan kepadatan penduduk tinggi dan menjadi pusat perekonomian serta didukung kondisi geografi yang menguntungkan, bisa jadi hanya membutuhkan kawasan hutan kurang dari 30 persen. Sedangkan pulau lain dengan kondisi berbeda membutuhkan kawasan hutan lebih dari 30 persen.
Misalnya, pulau Jawa hanya membutuhkan 7 persen kawasan hutan untuk fungsi perlindungan. Namun, apabila memasukkan urusan produksi, maka area yang menjadi kawasan hutan menjadi sekitar 18 persen. Pulau lain seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, kawasan hutan patut mempertahankan hutan lebih dari 30 persen. Sebagai contoh Papua, kawasan yang cocok disebut sebagai hutan mencapai 48 persen. Tapi jika memasukkan fungsi produksi, maka kawasan hutan Papua mencapai 91 persen.
Singkatnya, ketentuan batas minimal kawasan hutan 30 persen sudah tidak relevan lagi bagi pembangunan Indonesia terkini dan masa depan. Penghapusan ketetapan tersebut justru dapat dijadikan momentum untuk menata kembali hutan Indonesia. Analisis komprehensif diperlukan untuk mengganti ketetapan tersebut. Batas minimal hutan tentu tidak boleh diputuskan di atas meja saja dan top down. Verifikasi lapangan—tentu saja secara partisipatif dan transparan—menjadi pekerjaan bersama. Dengan begitu pembangunan kehutanan di Indonesia lebih terencana dan holistik, seperti yang pernah dicita-citakan oleh Bung Karno: Pembangunan Nasional Semesta Berencana.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini