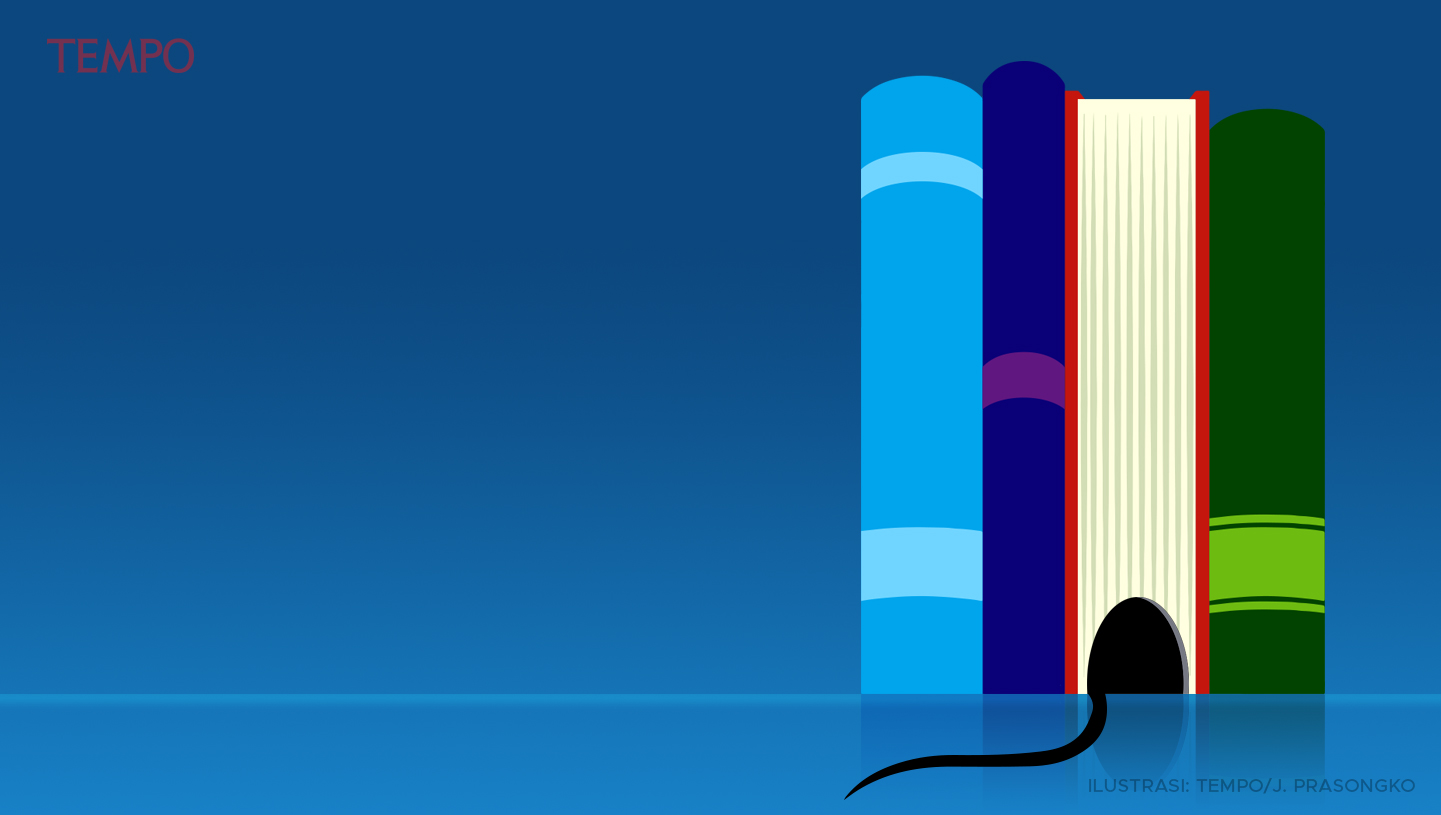Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

AKHIR Agustus itu musim bediding yang terlambat—peralihan hujan ke kemarau. Dingin angin sore lereng Merapi berembus saat kami tiba di Omah Petroek. Patung Sukarno setinggi enam meter menyambut, agak terlampau besar dan mendadak. Monumen itu dua hari sebelumnya diresmikan Megawati Soekarnoputri dalam acara yang bersahaja namun meriah.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Omah Petroek"