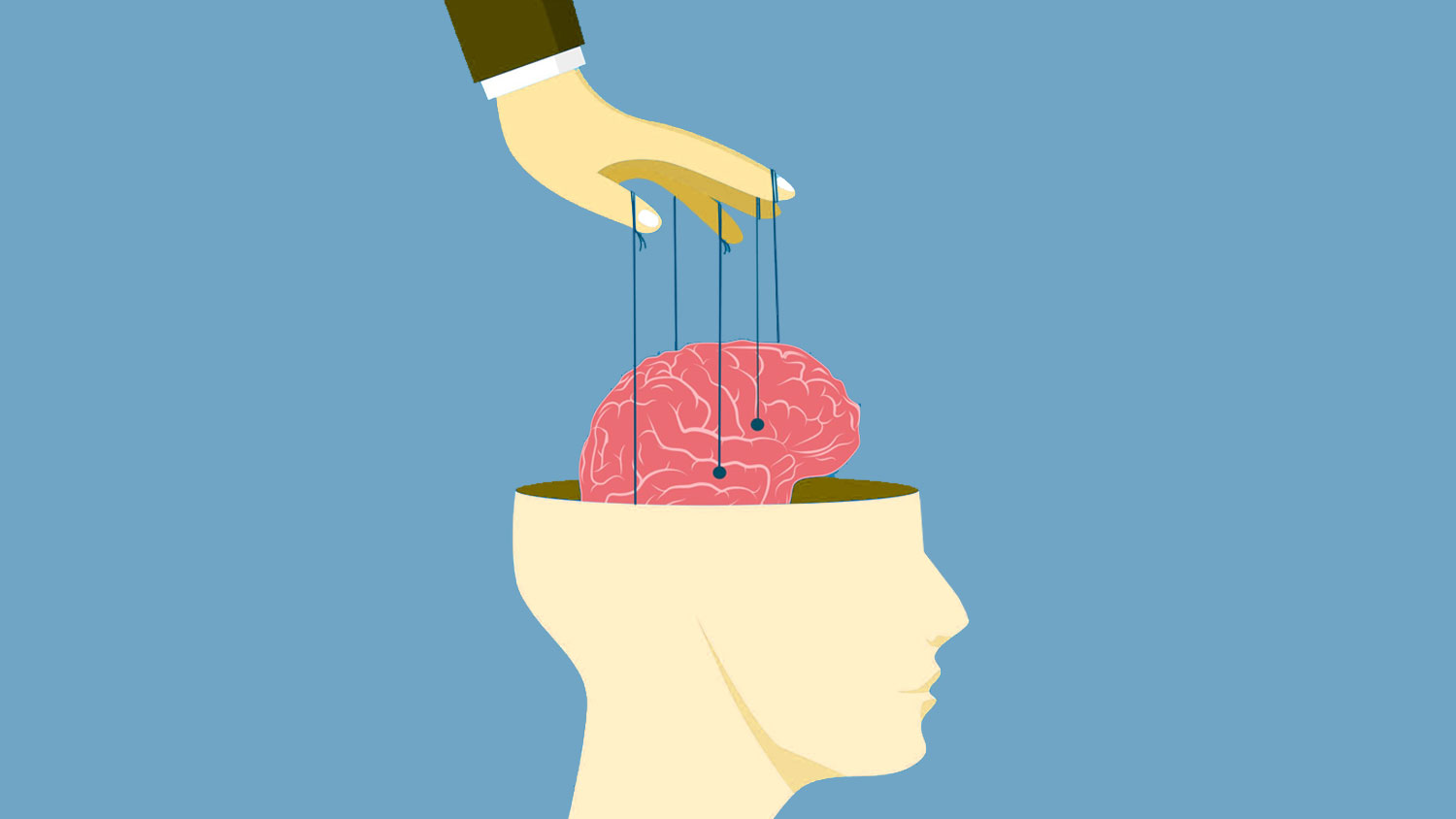Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Pada suatu hari, beberapa puluh tahun yang lalu, ketika saya masih di sekolah dasar, kepala sekolah kami yang baru memperingati hari 10 November dengan kekhidmatan istimewa. Pak Sumadi berdiri di atas sebuah bangku. Para guru dan murid berkeliling mendengarkannya di halaman belakang gedung yang dulu gudang seorang saudagar Tionghoa.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo