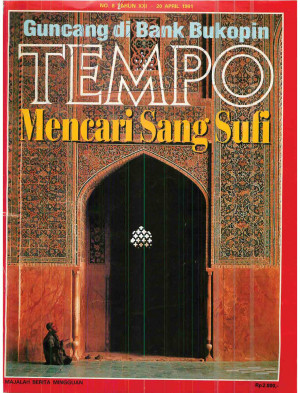Suku Korowai hidup selaras dengan alam, di rumah di atas pepohonan. Jumlah mereka terus menyusut karena penyakit. MUNGKIN kita perlu belajar dari suku Korowai. Mereka mungkin digolongkan sebagai masyarakat "terbelakang", tapi betapa banyak yang bisa kita pelajari dari cara hidup mereka, khususnya dalam memelihara lingkungan. Suku Korowai baru Januari lalu resmi tercatat oleh Dinas Sosial Irian Jaya, ketika tim ekspedisi "menemukannya". Masyarakat ini mendiami dataran yang diapit oleh hulu Sungai Becking dan Sungai Eilander yang bermuara di pantai barat Irian Jaya. Secara administratif, kawasan tersebut terletak di Kecamatan Kouh, Kabupaten Merauke. Lokasi ini bisa ditempuh dari Merauke dengan menyusuri Sungai Eilander dua hari semalam, dilanjutkan berjalan kaki dua minggu lamanya. Bisa juga dicapai dengan menumpang pesawat terbang misi sampai ke Yaniruma, kampung terdekat dengan tempat tinggal masyarakat Korowai. Korowai menarik perhatian karena mereka membangun rumah di atas pohon dengan jarak sekitar 6-20 meter di atas tanah, hal yang juga dilakukan oleh suku Citak Mitak dan Kombai pada dataran yang sama. Di ketinggian ini mereka merasa aman dari ancaman musuh hewan berbisa, kubangan rawa di musim hujan, dan roh jahat. Mereka tinggal berkelompok dalam lautan hutan nipah. Tiap kelompok merupakan satu keluarga besar yang disebut fam. Satu fam terdiri dari 7 sampai 20 rumah. Jarak tempat tinggal antar-fam sekitar lima kilometer. Yang menarik, mereka tak punya kepala suku, panglima perang, atau dukun. Semua perselisihan diselesaikan sendiri. Meski baru resmi tercatat tiga bulan lalu, falsafah hidup mereka yang selaras dengan alam sudah terekam oleh tim peneliti Balitbang Depsos dan pembuat film Dea Sudarman sejak enam tahun lalu. Bagaimana mereka menyelaraskan diri dengan alam bisa dilihat dari cara mereka "mengamankan" persediaan makanan. Kebun sagu -- makanan pokok mereka -- dibagi dalam petak-petak tebangan. Dengan peralatan batu, seluruh keluarga bekerja membuat makanan. Sagu digarut dengan kapak batu, dan tepung yang sudah dialiri air dan diperas dalam bongkahan besar dibawa ke rumah untuk persediaan beberapa hari. Jika sagu sudah habis, baru mereka turba -- turun ke bawah -- mengumpulkan sagu dari petak yang sama. Kalau sebuah petak mulai botak, mereka segera melakukan penanaman pengayaan. Prinsip petakan sesuai dengan masa tumbuh tanaman, seperti yang diterapkan dalam HPH ini, amat dipatuhi, sehingga mereka akan kembali ke petak awal di saat sagu siap panen. Makanan pokok lain, babi, juga ditangkap dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Selain diburu dengan panah (tanpa racun), yang lebih sering dilakukan adalah mencari sarang babi. Bila sudah ditemukan, tak semua anak babi diangkut. Beberapa ekor ditinggalkan supaya berkembang biak. Menurut Dea Sudarman, yang tiga kali mengunjungi suku Korowai (di antaranya tinggal enam bulan di sana pada 1986), di sana sejak kecil anak-anak sudah diajari mandiri. Anak perempuan ikut mengambil sagu, sedang anak laki-laki sejak mulai pandai berlari diajari berburu. Kegiatan turun rumah ini dilakukan selepas sarapan. Rumah mereka yang nangkring di atas pohon itu dibangun sendiri. Tiap rumah yang bisa sampai berukuran 6 x 11 x 7 meter itu didiami oleh 4-5 keluarga. Paling tidak, dibutuhkan waktu dua tahun untuk menyelesaikan rumah itu. Bahan dinding rumah dari pelepah daun nipah -- pohon penghasil sagu -- di sekitar tempat tinggalnya. Pelepah ini dipotong dengan kapak batu dan digepengkan. Sedang alas rumah diperoleh dari kulit kayu balsa yang disayat dan diserut memakai pisau kerang. Hanya ada dua ruangan dalam rumah itu, ruang laki-laki dan wanita, lengkap dengan beranda masing-masing. Tabu untuk para lelaki memasuki ruang wanita, begitu juga sebaliknya. Sampai ngobrol pun harus berbatas penyekat. Semua anak, termasuk laki-laki, tinggal dalam bilik wanita sampai mereka berhenti menyusu. "Padahal, sampai besar-besar mereka masih menyusu," kata Dea. Semua harta kekayaan dan binatang peliharaan pun ditimbun dalam ruang wanita. Maka, terhamparlah kalung taring babi, gigi anjing, kalung kerang, sampai babi dan anjing di sana. Bayangkan, kerepotan mereka memanggul naik turun anjing melewati tangga dari sebatang pokok kayu yang dipangkas menyerupai tangga dan hanya diikat di bagian atas. Aktivitas turba dimulai bersama oleh penghuni satu fam. Kalau tidak mengambil sagu, para laki-laki berburu babi dan kasuari atau menangkap ikan, dan wanita turun ke sungai. "Umumnya yang dijaring adalah ikan arowana perak," ujar seorang peneliti Balitbang Depsos yang pernah tinggal dua tahun (1985-1987) di sana. "Kini ada juga yang sudah memakai jaring dari plastik, yang diperoleh dari zending," kata Dea. Untuk mempercantik diri, wanita Korowai membuat beberapa lubang pada hidungnya yang bisa digantungi perhiasan dari rotan dan kalung dari kerang. Lengan mereka pun digantungi akar rotan. Bukan tanpa alasan para wanita hanya mengenakan cawat kecil atau para lelaki bertelanjang bulat. Lokasi kediaman mereka yang terletak 40 meter di atas permukaan laut sangat lembap dan banyak hujan. Sehingga, menurut Dea, pakaian yang melekat di badan tidak pernah kering. Jadi, kalau berpakaian malah bisa menimbulkan panu. Setelah matahari tenggelam, seluruh penghuni rumah akan naik ke atas. Inilah waktu untuk menyiapkan makan malam, walau tiap bilik menyiapkan makanan masing-masing. "Masakan mereka rasanya fantastis," kata Dea. Makanan yang dibakar terdiri dari sagu dengan lauk racikan bermacam cendawan, pucuk paku-pakuan, tunas pohon nipah, sayur lilin ("Rasanya seperti asparagus"), dan ulat sagu. Mereka mengenal pelbagai bumbu. Ada daun yang rasanya asin, buah asam, buah manis, atau daun wangi untuk penyedap. Tempat masak berupa batu-batuan yang berongga dengan lapisan tanah di bawahnya. Racikan makanan tadi diapit oleh dua talam pisang dan ditindih dengan batu. Api dibuat dari gelang rotan perhiasan wanita tadi yang digosokkan pada kayu api, lalu disulutkan pada rumput kering. Makanan yang menurut Dea rasanya seperti pizza itu juga disantap anjing dan babi yang tinggal di atas. Minuman dari air dalam bumbung, yang mempunyai rasa dan warna seperti teh karena rendaman daun dalam sungai. Air tidak dimasak, tapi bersih karena ada larangan buang hajat di sungai. Sifat menjaga kebersihan ini juga dipelihara di atas rumah. Ini diperlukan agar pohon penopang hidup mereka tidak busuk. Tidak ada sampah berserakan, semua dibakar dalam tungku. Bahkan anjing dan babi pun tidur dan membuang kotoran di atas tumpukan rumput di pojok bilik, yang dibersihkan tiap pagi. Untuk menjaga kebersihan rumah, para wanita yang sedang haid dan akan melahirkan harus tinggal dalam bivak sementara. Bermain cinta pun harus dilakukan di dalam hutan. Para lelaki tinggal mendesiskan kode khusus untuk mengundang istrinya. Masa perkawinan pada suku ini biasanya sesudah bulan September-Desember. Itulah saat mereka mengadakan Pesta Ulat Sagu yang diprakarsai oleh satu keluarga atau satu rumah. Ribuan orang dari fam lain akan hadir. Pesta berlangsung beberapa hari. Suguhan utama adalah ulat sagu bakar. Pesta inilah ajang saling mengenal. Seorang wanita Korowai akan mengedipkan mata pada laki-laki idamannya dan mengantarkan masakan padanya. Kalau gayung bersambut, mereka akan berjabat tangan erat-erat. Setelah itu, janji kawin pun dibuat. Meski mengenal lembaga perkawinan, masyarakat ini memperkenankan poligami. Namun, tindakan serong yang sering terjadi dalam Pesta Ulat Sagu diharamkan. Tindakan ini yang biasanya berbuntut dilarikannya seorang wanita, yang sering berakibat perang. Perang ini, ditambah serangan penyakit, membuat populasi mereka terus menurun. Walau mengenal obat-obatan tradisional, masyarakat ini rentan penyakit baru yang dibawa pendatang. Flu saja bisa mengakibatkan kematian. Akibat perang bisa dilihat dari banyaknya suku Korowai yang dibawa ke pos kesehatan misi di Yaniruma dengan luka-luka kena panah karena perang. Tak jelas berapa jumlah anggota suku ini sekarang. Dalam data Depsos, pada 1983 masih ada 2.000 keluarga, dan 92 keluarga di antaranya dicoba dirumahkan tahun 1987. Tapi sebagian kembali ke atas pohon. Apakah merumahkan mereka di atas tanah memang cara paling tepat agar mereka tidak lagi dianggap " terbelakang"? Diah Purnomowati dan Dwi S. Irawanto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini