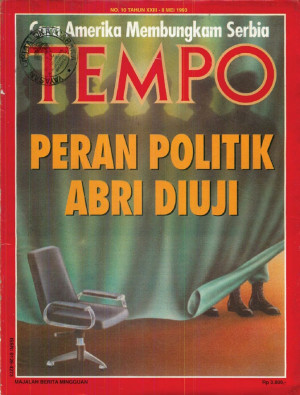ADA pemandangan yang menyedihkan ketika melintas di atas Sungai Siak, Provinsi Riau. Tak jauh dari bekas bangunan Istana Sultan Siak Sri Indrapura, tampak sepetak hutan yang merana. Ratusan pohon yang tumbuh di tepi rawa yang airnya hitam itu mencuat mirip tonggak-tonggak kering meranggas. Pemandangan seperti itulah yang pekan lalu ditemui tim pencari fakta yang dipimpin oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal). Tim ini datang untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara perusahaan minyak PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) dan penduduk Sei Limau. Perselisihan yang tercetus sejak tahun 1990 itu semakin rawan setelah beberapa lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) lantang angkat bicara. Hipalhi, misalnya, lewat media pers telah menuduh limbah CPI sebagai penyebab meranggasnya hutan yang ditaksir seluas 10 hektare itu. Apalagi sejak dua tahun silam penduduk tidak dapat lagi memanfaatkan air Sungai Sagu, yang sebelumnya merupakan sumber air dan ladang perburuan ikan. ''Air sungai makin menghitam dan ikan-ikan banyak yang mati,'' ungkap Syarif, Kepala Desa Sei Limau. Kuat dugaan, pencemaran itu berasal dari limbah CPI, terutama karena rawa yang merupakan mata air Sungai Sagu telah pula dijadikan tempat pembuangan limbah minyak oleh CPI. Perusahaan ini juga membangun kanal penyalur limbah sepanjang 2 kilometer dari Stasiun Pusaka salah satu pusat pengumpul dan pengolah minyak ke rawa tersebut. Sejak air rawa meluap ke kebun-kebun karet, pohon-pohon di situ mati bagaikan dijilat api. Penduduk khawatir, jangan-jangan pohon karet milik mereka akan bernasib sama. Keluhan itu dijawab CPI dengan membangun kanal sepanjang 5 kilometer untuk mengalirkan limbahnya ke Sungai Siak. Kanal yang semula mengalirkan limbah ke rawa lalu ditutup. Untuk memenuhi kebutuhan warga akan air bersih, pihak CPI juga membuat tiga buah sumur. Bahkan, Agustus tahun lalu CPI mengundang lembaga penelitian independen, PT Corelab, untuk memeriksa limbah yang dihasilkannya. Maklum, perusahaan minyak terkenal di dunia ini memproduksi 700 ribu barel minyak mentah per hari, kira-kira 50% dari total produksi minyak Indonesia sejak mula telah memiliki instalasi pengolah limbah. Investasi CPI untuk itu mencapai sekitar Rp 8 miliar, sementara biaya operasinya saja Rp 9 miliar. Hasil penelitian Corelab pernah disodorkan ke Menteri KLH pada waktu itu. ''Ternyata kadar baku mutu limbah CPI jauh lebih rendah daripada yang ditetapkan,'' kata Anton Wahjoesoedibjo, Vice President General Affairs CPI. Kadar minyak dalam limbah, misalnya, cuma 0,1 ppm, dan suhu air 41 Celsius. Sedangkan ambang batas kadar minyak adalah 25 ppm, dan suhu 45 Celsius (TEMPO, 30 Januari 1993). Penelitian Sucofindo juga memperkuat hasil Corelab itu. Berdasarkan hasil penelitian itu, hampir tak masuk akal bila air limbah CPI bisa membuat air Sungai Sagu kehitam-hitaman. Maksudnya? Warna air limbah CPI ternyata lebih bening mirip air mineral. Sedangkan air Sungai Sagu justru kehitaman, mirip Coca-Cola. Dan warnanya bisa seperti itu bukanlah karena tercemar air limbah CPI seperti yang diyakini pihak CPI melainkan karena air Sungai Sagu merupakan air tanah gambut. Selain itu, masih ada alasan lain. Anton mengatakan bahwa minyak dari penampungan di Stasiun Pusaka tak mungkin bercampur dengan air sungai lalu menebarkan warna hitam. Soalnya, minyak itu memiliki sifat khas, yakni akan mengental dan menggumpal pada suhu di atas 40 Celcius. Jadi, pada ketinggian suhu di Riau, minyak itu bila tercampur air pasti menggumpal dan mengapung di permukaan. Katakanlah ''teori Anton'' benar. Namun, di sisi lain harus dipertanyakan berapa tinggi suhu udara di Riau. Apa mungkin mencapai 40 Celcius? Rasa-rasanya masih di bawah 40 derajat. Berarti, minyak itu belum menggumpal, sehingga masih terbuka kemungkinan untuk bercampur dengan air Sungai Sagu. Tak mengherankan bila Herman, Camat Sungaiapit, masih saja penasaran. ''Kalau limbah tak mengandung minyak, apa sebabnya hutan menjadi seperti terbakar?'' usutnya agak curiga. Pertanyaan ini terlontar dalam diskusi pekan lalu di Duri, Riau, yang diikuti oleh pihak CPI, penduduk, Bapedal, dan ilmuwan, termasuk Prof. Gunarwan Suratmo, Ketua Program Studi Pascasarjana Kajian Bidang Lingkungan di IPB. Menurut Gunarwan, kematian pohon-pohon itu mungkin disebabkan oleh miskinnya zat hara dalam rawa akibat salinitas (kadar garam) yang tinggi. Proses penggaraman ini mungkin saja terjadi dari unsur-unsur kimia lain di luar minyak yang terdapat dalam limbah minyak CPI. ''Tapi daerah gambut pada dasarnya adalah daerah yang sangat miskin hara, dengan keasaman yang rendah,'' lanjut Gunarwan pula. Bahwa warna air sungai menjadi hitam akibat sifat tanah gambut, hal itu tentu masih harus diperiksa pula kebenarannya. Sementara itu, CPI diharapkan tidak lepas tangan. Deputi Bapedal, Nabiel Makarim, sebagai pimpinan tim pencari fakta, telah menegaskan bahwa ada dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh usaha CPI. Indikatornya pohon yang bermatian itu. ''Namun, selain itu, kami juga melihat adanya usaha-usaha CPI untuk mengendalikan dampak lingkungan tersebut,'' ujar Nabiel. Tokoh Bapedal ini lalu mencari jalan tengah, yakni membiarkan pihak CPI dan penduduk berdialog langsung. ''Pelaku kasus ini hanya CPI dan penduduk, jadi tidak perlu perantara. Baik Bapedal, pengacara, maupun LSM tidak perlu turut campur,'' Nabiel menandaskan. Untuk dialog itu, pihak Bapedal memberi batas waktu tiga bulan, sementara penelitian akan terus dijalankan. Diharapkan, dengan dialog langsung semacam itu, kesalahpahaman yang tidak perlu bisa dihindarkan. Apalagi penduduk tidak menuntut ganti rugi. Mereka hanya mengharapkan agar sumber air bersih bagi mereka Sungai Sagu bisa berfungsi kembali seperti semula. Priyono B. Sumbogo dan G. Sugrahetty Dyan K.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini