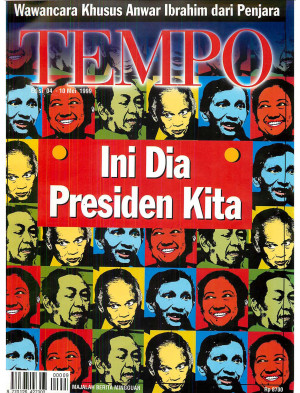Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
LEDAUNAN bukanlah sekadar helai-helai yang hijau menyejukkan. Bagian dari pohon yang tak diperdagangkan itu kelak sangat berpotensi untuk menjadi sumber uang. Makin rimbun sebuah hutan karena lebatnya daun-daun di hutan itu, makin banyak menghasilkan uang daripada batang dan cabangnya. Bagaimana mungkin? Tunggu saja tahun 2008 ketika perangkat peraturan yang disebut Protokol Kyoto diterapkan.
Peraturan itu antara lain mewajibkan negara-negara industri maju memiliki sertifikat tidak melanggar batas emisi yang disepakati. Sertifikat tersebut?punya harganya sendiri?bisa didapat dari negara-negara berkembang, pemilik hutan tropis yang mampu menyerap emisi, terutama karbon. Daya serap ini diperoleh dari daun-daun di hutan yang hijau menyejukkan itu.
Pertanyaan yang segera mencuat: bagaimana mengonkretkan perdagangan udara dengan menghitung karbon yang dihasilkan dan daya serap daun-daun hutan? Pada zaman teknologi ini, ternyata hal itu mungkin saja dilakukan. Pada konferensi kedua tentang "Pasar Potensial Perdagangan Emisi" di London, akhir April lalu, beberapa usul mengenai harga karbon sudah diajukan.
Kalau ditelusuri, timbulnya pembicaraan soal perdagangan karbon dimulai pada Konferensi Bumi (Earth Summit) di Rio De Janeiro, Brasil, pada 1992. Saat itu muncul kekhawatiran yang amat besar akan pemanasan global (global warming) disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang bisa menambah lebar lubang di lapisan ozon.
Semula, yang dituding sebagai biang keladi adalah negara-negara pemilik hutan tropis. Sebab, pengusaha di sana menebang pohon sembarangan, tanpa menghiraukan kelestarian hutan. Belakangan, tudingan itu dirasa tidak adil. Soalnya, negara-negara pemilik hutan mengandalkan perekonomiannya dari penjualan kayu yang nilainya lumayan besar, sekitar US$ 100 miliar per tahun. Lagipula, mengapa hanya negara pemilik hutan yang disalahkan? Bagaimana dengan negara industri yang hutannya sudah lebih dulu gundul dan banyak memproduksi emisi gas rumah kaca?
Dari situ lahirlah Kyoto Protocol, hasil dari konferensi pihak-pihak yang punya kepentingan dengan hutan, Desember 1992. Dalam pertemuan itu dihasilkan tiga hal penting, yaitu kerja sama antara negara industri maju dan berkembang, mekanisme pembangunan yang bersih lingkungan, dan pengaturan perdagangan emisi. Protokol Kyoto ini, menurut Benny Luhur dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), dianggap sebagai win-win solution karena memberikan insentif kepada negara yang memelihara hutannya.
Sedangkan dalam acara di London, yang terutama dibahas adalah cara membakukan lisensi perdagangan penyerapan karbon (tradeable permit system), yang kelak dapat dimanfaatkan oleh negara-negara pemilik hutan untuk menghitung banyaknya karbon yang bisa diserap oleh hutan mereka. Di sana, dipresentasikan beberapa cara penghitungan karbon. Perlu diketahui, 3,67 ton CO2 sama dengan 1 ton karbon. Peserta dari Kosta Rika dan Bolivia sebagai pemilik hutan tropis mengusulkan harga jasa penyerapan sebesar US$ 10/ton karbon/tahun. Sebuah perusahaan minyak di Inggris yang menghasilkan emisi malah mengusulkan angka lebih tinggi: US$ 22/ton karbon/tahun. Harga karbon ini sebenarnya pernah diteliti oleh sebuah lembaga Moura Costa & Stuart pada 1988 dan dari situ diperoleh harga US$ 5-20/ton karbon.
Sampai kini memang belum ada kata putus. Harga pasti untuk penyerapan karbon diharap akan didapat dalam konferensi selanjutnya di Bonn, Jerman, awal Juni mendatang. Yang menarik, acara seperti ini ternyata diminati oleh para produsen karbon, seperti perusahaan-perusahaan besar di bidang pengelolaan minyak dan bahan-bahan kimia. Menurut Ismid Hadad dari Yayasan Keanekaragaman Hayati?hadir dalam Konferensi London?sikap aktif dipilih karena ingin diperhitungkan untuk keterlibatan awal dalam mengurus lisensi penyerapan karbon. Hal ini dapat dimengerti karena, dengan membayar harga karbon tersebut, mereka tak bisa disalahkan lagi sebagai pihak yang menyebabkan efek rumah kaca.
Sebagai kelanjutan dari konferensi itu, sebuah tim yang beranggotakan berbagai pihak yang terkait telah dibentuk oleh pemerintah untuk merumuskan tolok ukur perdagangan karbon. "Ini merupakan kesempatan untuk semakin meningkatkan motivasi dalam menerapkan manajemen hutan lestari," kata R. Robianto Koestomo, Ketua Bidang Luar Negeri Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.
Ismid sendiri berpendapat bahwa perdagangan karbon bisa menguntungkan Indonesia. Tapi dia juga wanti-wanti kepada pemerintah agar lebih dulu menghitung jumlah emisi yang dihasilkan oleh industri, sarana transportasi, dan penghasil polusi lainnya di Indonesia. "Jika kita belum punya ukurannya, jangan-jangan nanti kita lebih menjadi penghasil karbon daripada penyerap karbon," kata Ismid mengingatkan. Begitulah, niatnya untung, malah buntung!
Bina Bektiati
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo