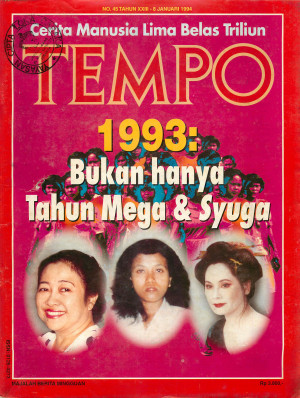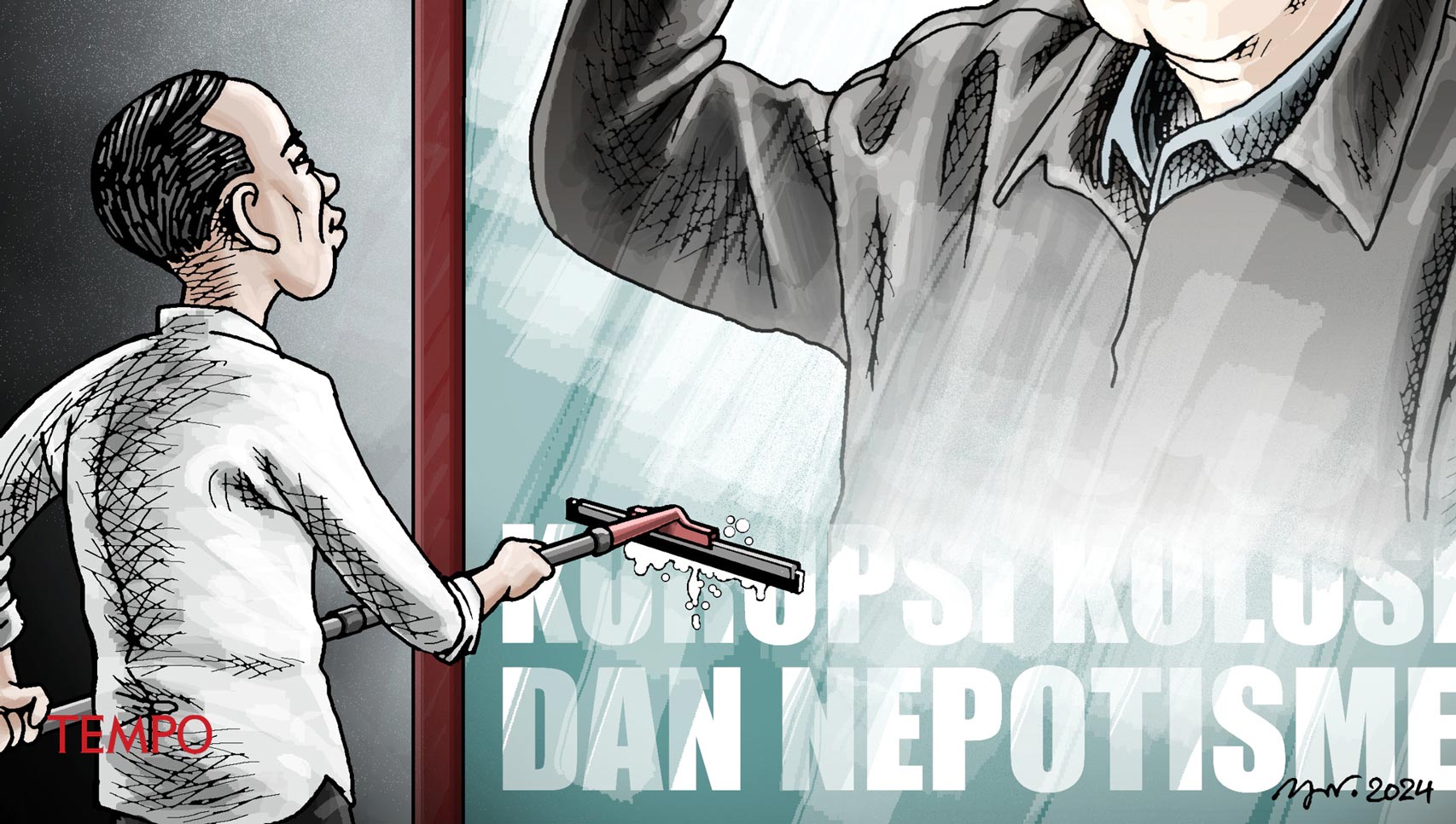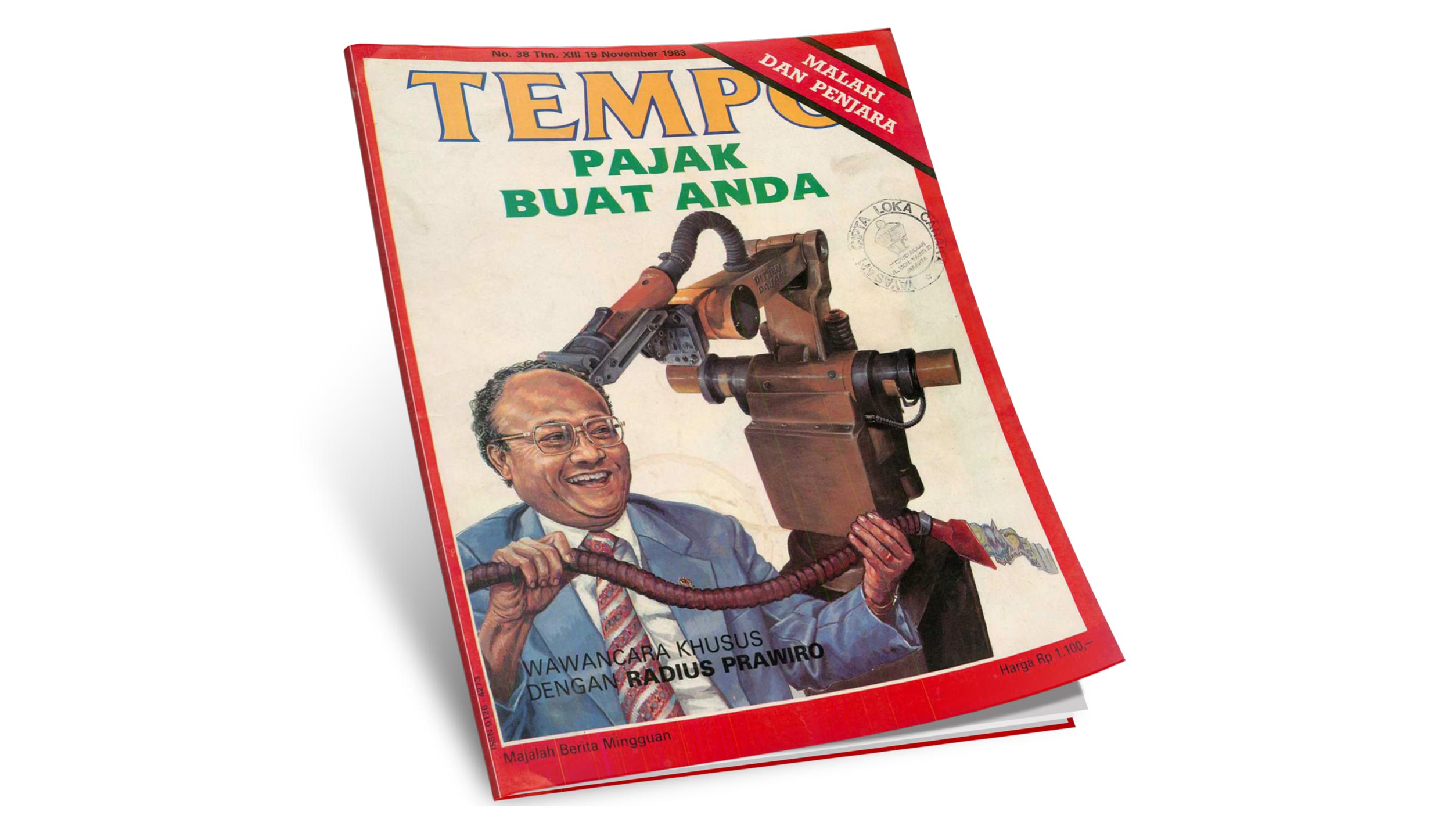Sungguh mengenaskan nasib buruh penyelam mutiara di Dobo, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara (TEMPO, 6 November, Selingan). Saya jadi teringat nasib yang sama menimpa para pencari sarang burung walet di Desa Sei Lunuk, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Seperti halnya buruh-buruh di daerah lain, tetap saja warga asli setempat sulit memperoleh kesejahteraan dari hasil bumi mereka sendiri. Penduduk asli "pemungut" sarang burung, Dayak Punan, hanya jadi "sapi perahan" tauke-tauke yang datang dari kota. Setiap datang masanya panen sarang burung, para pemungut sarang burung tersebut mengadu nyawa masuk ke dalam gua-gua (tentu saja tanpa asuransi), sementara tauke tinggal menunggu dengan membawa helikopter dari kota. Nah, begitu hasil diperoleh, semuanya harus diserahkan kepada tauke dengan harga yang, tentu saja, miring. Lalu tauke tersebut menjualnya ke restoran yang mengolah sarang burung tersebut yang, konon, berkhasiat. Sedangkan "si pemungut" sarang burung harus membayar pinjaman yang dipakainya untuk hidup di hutan selama masa pemungutan kepada tauke mereka. Seandainya ada kelebihan, uang itu biasanya habis dalam beberapa malam untuk berfoya-foya. Ujung-ujungnya nasib mereka tetap tidak berubah, masih seperti sedia kala. Memang di Desa Sei Lunuk ada lima buah antena parabola, tapi antena itu merupakan sumbangan pemerintah untuk menarik suku Dayak Punan agar mau menetap di Desa Sei Lunuk. Jadi, antena parabola tersebut bukanlah hasil jerih payah orang-orang Punan memungut sarang burung. Pada saat sedang gencar-gencarnya program "mengentaskan kemiskinan", sudah selayaknya pemerintah berupaya mengatasi hal ini. Salah satu alternatif adalah lewat peningkatan mutu pendidikan orang-orang Punan. Atau, perlu semacam proteksi terhadap usaha tradisional pemungutan sarang burung oleh orang- orang Punan tersebut.EKA M. RUSKANDAJalan Tongkol 28 RT 01/1 Samarinda 75115
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini