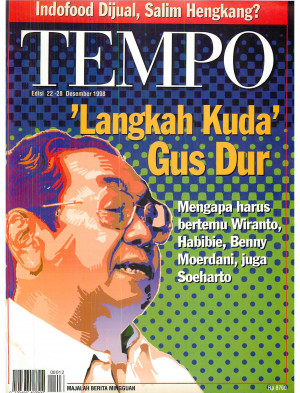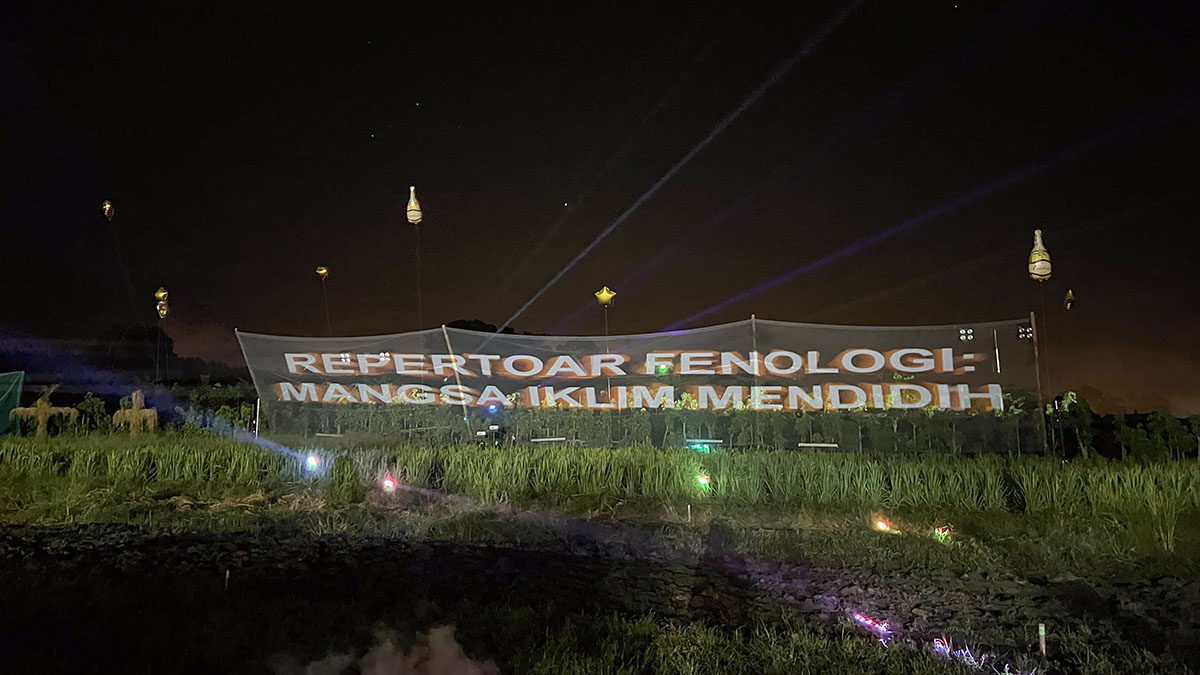Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

SEORANG perampok yang dimuliakan sebagai pemimpin agung, didewakan, dan dianggap sebagai bapak dari semua orang, bukan saja merupakan fiksi yang lumrah, melainkan juga menjadi fakta sejarah. Lakon Umang-Umang Atawa Orkes Madun IIA karya Arifin C. Noer dengan bagus berkisah tentang hal itu. Naskah ini berkisah tentang sebuah masyarakat yang menganut sistem kleptokrasi (pemerintahan maling) di bawah komando Waska, berandal tua yang gelap silsilahnya.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo