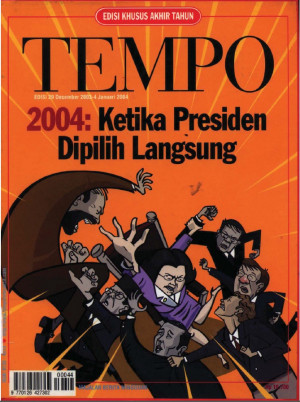Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Jakarta sudah memasuki sebuah senja bulan November silam. Seorang ibu tergopoh-gopoh menggandeng dua anaknya yang masih kecil. Dengan mata penuh harap, si anak tak kalah berjalan dengan cepat. Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki hari itu penuh sesak. Film animasi Finding Nemo—yang sebetulnya sudah per-nah diputar di bioskop jaringan 21—diputar kembali dalam acara Festival Film Animasi Internasional. Meski film sudah berjalan separuh cerita, mereka tak peduli. Ketiganya tetap menyesakkan tubuh ke dalam untuk menikmati kisah ikan-ikan di laut itu.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo