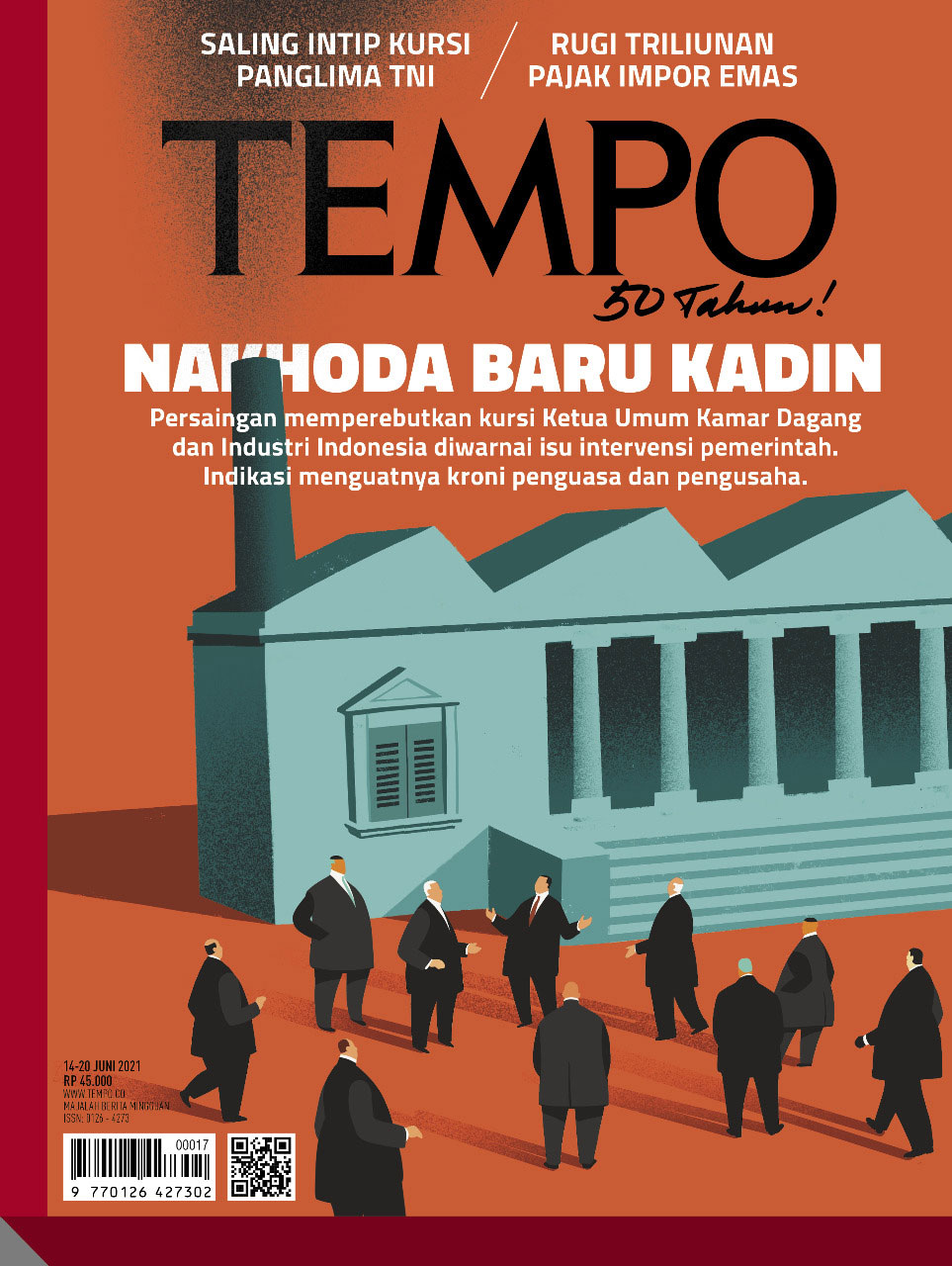Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita
Periode Marzuki Darusman menjadi Jaksa Agung banyak menjerat koruptor dan kroni Suharto
Marzuki Darusman menjadi Jaksa Agung di masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur
SAYA menjadi Jaksa Agung pada 1999, saat era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Semula saya menolak permintaan beliau karena merasa jabatan itu amat berat. Saya lebih sreg dengan posisi Menteri Luar Negeri ataupun Menteri Dalam Negeri. Namun, kata Gus Dur, pos Menteri Luar Negeri sudah untuk Alwi Shihab. Gus Dur ingin saya menjadi Jaksa Agung menimbang sejarah saya di Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang cocok untuk mengejar para koruptor.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo