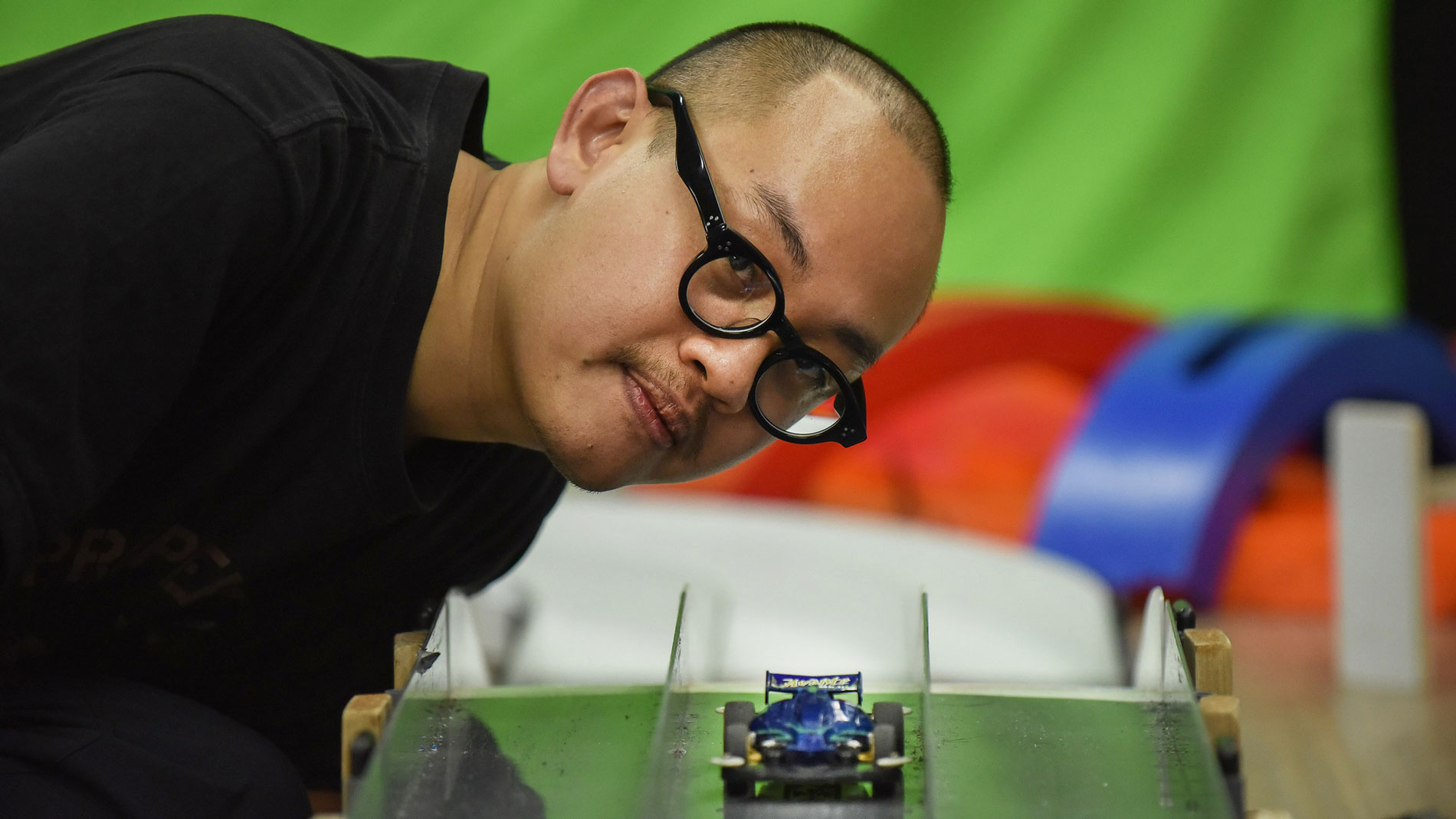Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Waktu itu masalah Irian Barat—masih belum menjadi wilayah Indonesia—tengah dibahas di New York, Amerika Serikat. Pada 1962, saya dan sejumlah musikus, seperti Bing Slamet, Gordon Tobing, Ellya Khadam, Sampan Hismanto, dan Iskandar, diminta Brigjen S. Sukowati datang ke Gambir, Jakarta Pusat. Ini untuk persiapan keberangkatan ke Irian Barat sebagai Tim Kesenian Tri Komando Rakyat (Trikora) III. Trikora dideklarasikan Bung Karno di Yogyakarta pada 19 Desember 1961 untuk memasukkan Irian Barat, yang merupakan jajahan Belanda, ke Indonesia.
Kami dikirim ke pedalaman selama sebulan, 12 November sampai 12 Desember, dengan tugas menaklukkan perasaan hati rakyat Irian. Sebelum kami berangkat, Presiden Sukarno berpesan agar kami ikut berjuang lewat misi kesenian. "Ingat pesan Bapak! Kalian ini sekarang sebagai duta bangsa Indonesia dan mempunyai tugas yang mulia. Laksanakanlah! Ever onward, never retreat, maju terus."
Rombongan kami mendarat di lapangan terbang Sentani. Dari sana, kami melanjutkan perjalanan darat ke rumah bekas gubernur Plateel di Hamels Poort, yang terletak di puncak bukit. Pada malam hari, saya diminta membawakan solo biola dengan iringan piano. Tamu yang hadir bertepuk tangan panjang.
Malam berikutnya kami menghibur penduduk di lapangan. Sebenarnya, sewaktu kami datang, mereka tidak tahu siapa kami. Tapi mereka memang suka menyanyi. Kami menyanyikan lagu perjuangan, seperti Maju Tak Gentar dan Halo-Halo Bandung. Hanya, kata Bandung kami ganti dengan Irian Barat. Mereka tertarik. Lapangan penuh.
Tapi, di tengah pertunjukan, listrik mati. Penonton panik dan mulai meninggalkan lokasi. Kami sudah siap mati. Tapi keadaan itu tidak membuat kami berhenti. Pentas kami berikutnya digelar di sejumlah kota, seperti Biak, Manokwari, Jefman, Fakfak, Kaimana, dan Merauke. Sempat terjadi insiden ketika di Merauke. Segerombolan pria dengan wajah bercoreng menyerang dari kejauhan. Mereka melemparkan tombak dan melepaskan anak panah. Kami refleks tiarap mencari tempat berlindung. Untunglah tidak ada satu pun dari kami yang terluka.
Panggilan Ibu Pertiwi tak berhenti di tanah Papua. Saat masih bersama Orkes Simfoni Jakarta, saya pernah ikut dalam misi muhibah ke seluruh Malaya. Pertunjukan selama sembilan bulan itu digelar di sembilan kerajaan untuk masyarakat luas. Turut serta dalam rombongan itu Bing Slamet, Sam Saimun, Masnun, Titiek Puspa, dan beberapa penari dari Medan. Jadwal kami kala itu sangat padat. Jadi harus punya disiplin waktu. Pernah suatu ketika kami meninggalkan Bing Slamet. Dia sampai menangis gara-gara telat.
Pada 1964, saya bersama beberapa musikus kembali dipercaya menjadi duta seni di New York World's Fair. Karena waktu itu Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia, Bung Karno berpesan agar kita mengantisipasi paviliun Malaysia. Jangan sampai permainan kami kalah bagus dengan mereka. Makanya, untuk menarik minat pengunjung, kami menyiapkan gadis-gadis cantik sebagai penjaga meja informasi.
Acara bertema Perdamaian Melalui Saling Pengertian itu berlangsung enam bulan. Selama menggelar pertunjukan, saya dan kawan-kawan memainkan lagu Barat, seperti I Left My Heart in San Francisco dan Blue Moon, dengan aransemen keroncong. Permainan kami mendapat banyak pujian dari musikus papan atas, seperti Tooth Thielemans, Harry Belafonte, dan Miriam Makeba.
Tidak lama setelah acara tersebut, yakni pada 1965, saya dan sejumlah musikus, seperti Bubby Chen, Jack Lesmana, Bing Slamet, Laody Item, Munif Bahaswan, dan Sudarmono, ditugasi ke Eropa. Tujuannya memperkenalkan irama lenso. Kami juga sempat menjadi duta perdamaian ke India untuk mendinginkan suhu politik Jakarta-New Delhi, yang ketika itu sempat memanas.
Namun tugas Merah Putih tak hanya ke luar negeri. Saya juga diminta melatih marching band Tentara Nasional Indonesia. Ceritanya berawal pada 1993. Ketika itu, saya berbincang dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Wismoyo Arismunandar. Di situ saya melontarkan kritik. Musik yang dimainkan personel TNI jelek sekali. Ketika mereka mengiringi lagu Indonesia Raya, alunan musik yang mereka mainkan masih terdengar sumbang. Padahal itu lagu yang sangat sakral.
Saya pun kemudian menerima tawaran melatih mereka. Bagi saya, permintaan itu adalah pilihan untuk mengabdi kepada Merah Putih. Sejak itu, saya menghilang dari gemerlap bisnis musik. Berbagai undangan tampil di Eropa bahkan saya lewatkan.
Tugas pertama yang saya lakukan adalah menyambangi komando daerah militer yang memiliki satuan musik. Saya memilih beberapa personel di antara mereka untuk dilatih di pusat pendidikan TNI di Lembang, Jawa Barat. Belakangan saya paham mengapa permainan musik TNI sangat jelek. Banyak dari mereka yang menjalani kegiatan itu karena terpaksa. Bergabung dengan satuan musik, bagi mereka, bukanlah sebuah kebanggaan. Satuan musik tidak lebih dari kumpulan orang buangan. Ketika saya tanya mereka: Kamu siap menjadi tentara musik? Dijawabnya: Siap, tidak!
Personel satuan musik militer juga banyak mengeluhkan kariernya. Begitupun dengan insentif yang mereka peroleh. Karena itu, saya bertekad membangkitkan kembali kebanggaan mereka. Saya bilang kepada mereka, "Kalian harus bangga. Kalau Idris Sardi main, Presiden tidak berdiri. Tapi, kalau kalian main, Presiden berdiri. Saya hanya mendapat tepuk tangan."
Itu rupanya menyentuh dan membangkitkan semangat mereka kembali. Sejak itu, mereka tekun berlatih. Apa yang saya lakukan ketika itu tidak hanya melatih kecakapan bermain musik. Saya juga mendengarkan curahan hati mereka tentang kehidupan, harapan, dan cita-cita mereka. Kadang saya datangi barak mereka. Dari obrolan itu, saya paham bahwa kesejahteraan mereka sangat kurang.
Akhirnya, terkadang kalau usai latihan, saya mengajak mereka makan di luar. Saya yang bayari. Mungkin karena metode itu, keterampilan mereka dalam bermusik semakin baik. Cerita makin bagus tersebut rupanya sampai ke Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta. Wismoyo lalu mengajak semua panglima komando daerah militer ke Lembang. Dia meminta saya menunjukkan hasil perkembangan dari apa yang saya kerjakan. Mereka terpukau ketika melihat permainan anggota TNI.
Yang dipersembahkan para personel TNI kala itu bukan hanya simfoni musik. Mereka juga memainkan atraksi gerakan laiknya pemain musik profesional. Wismoyo lantas meminta saya menyiapkan kemampuan personel musik untuk tampil dalam acara Hari TNI. Dia juga mengalokasikan dana Rp 2 miliar untuk membeli alat musik sebagai pengganti yang sudah rusak.
Pengabdian saya di TNI berlangsung dua tahun. Selama masa itu, tidak sekali pun gaji saya ambil. Buat saya, melatih musik personel TNI adalah sebuah pengabdian. Saya tidak pernah meminta uang untuk apa yang saya lakukan ketika mengajar dalam bermusik.
Saya pun diangkat sebagai warga kehormatan TNI AD. Saya juga mendapat pangkat kehormatan letnan kolonel corp ajudan jenderal tituler dan dianugerahi Tanda Kehormatan Negara Satyalancana Dwidya Sistha. Tapi penyakit kanker usus pada 1998 membuat saya undur melatih musik di TNI.
Purwani Diyah Prabandari, Riky Ferdianto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo