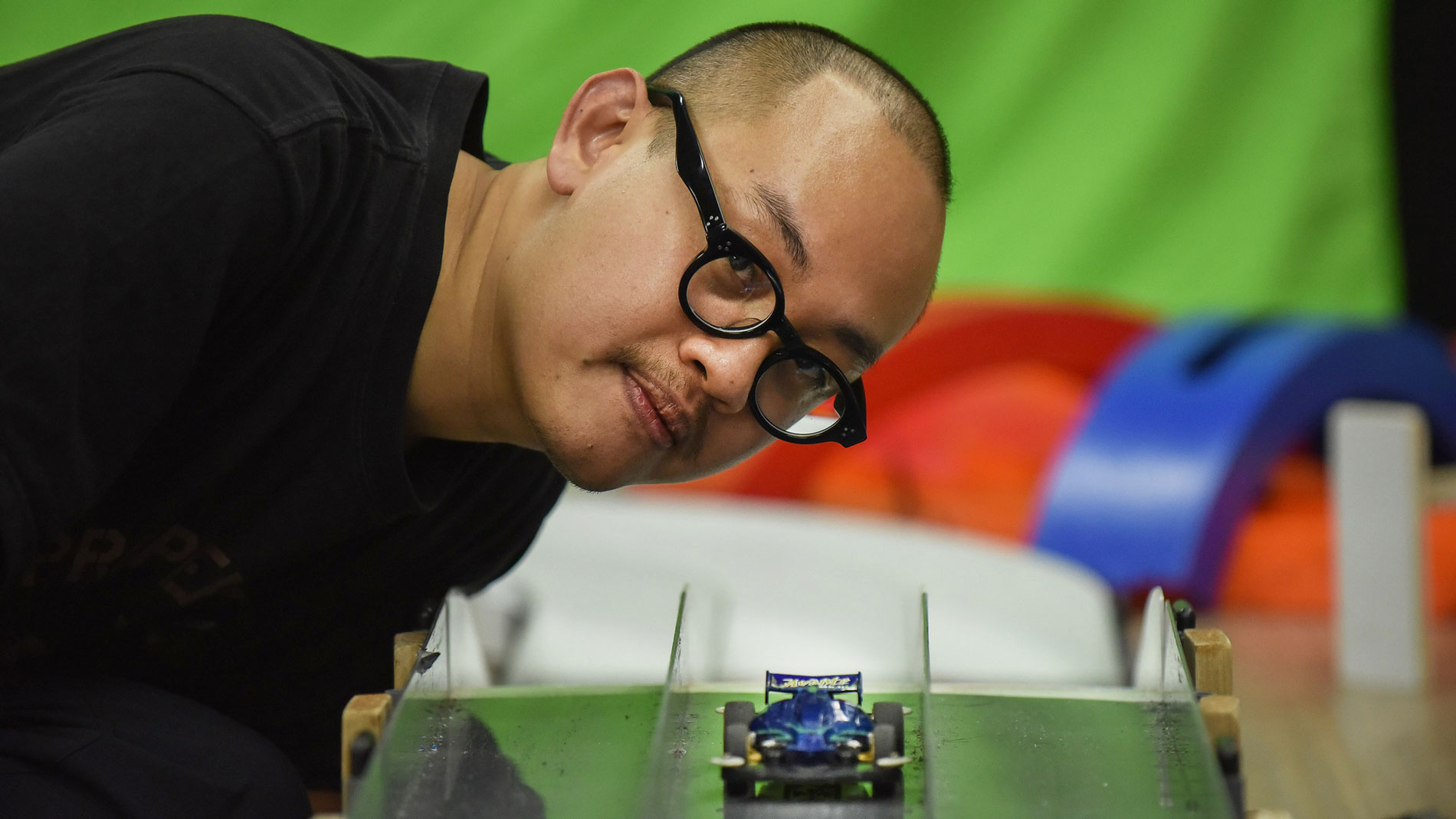Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Idris Sardi terbatuk-batuk. Namun sang maestro biola tak menghentikan obrolan. Bahkan, ketika suaranya seolah-olah tercekat, Idris terus mengisahkan kehidupannya. "Minum dulu," Santi Sardi, anaknya, menyarankan. "Papa kecapekan," kata Santi menjelaskan kondisi ayahnya.
Idris Sardi memang baru beberapa hari pulang dari Kuching, Sarawak, Malaysia, saat kami temui. Di sana ia menggelar konser "Tribute Concert to P. Ramlee". Selama satu setengah jam, audiens, termasuk Menteri Besar Pehin Sri Abdul Taib Mahmud, terpesona oleh permainan biola maut sang maestro dari Indonesia. "Orang tidak mau pergi," kata Idris mengisahkan konsernya. Ia juga membawa pulang penghargaan gelar Panglima Setia.
Begitu kembali ke Jakarta, Idris bukannya istirahat. Dia terus bekerja dengan musiknya. Bahkan, meski sakit, dia tetap bekerja di studio. "Ini bisa sampai pagi," kata Santi.
Rabu sore awal Oktober lalu itu, di ruang tamu studio musik Musica di bilangan Pancoran, Jakarta Selatan, bersarung santai, dengan panjang-lebar Idris Sardi mengungkapkan kisah dan berbagai prinsip hidupnya, termasuk kegalauannya akan dunia musik dan para musikus sekarang. "Saya mengkritik sistem, ya," ujarnya. Meski banyak selingan batuk dan tercekat saat berbicara, Idris tetap bersemangat. Bahkan berkali-kali pembicaraan disertai contoh permainan biolanya. Hingga tak terasa hampir dua jam obrolan berlangsung.
Pria 75 tahun ini memang sangat serius dengan musik. Ia tak terhentikan oleh sakit. Bahkan juga ketika terjadi heboh dengan "konser pamit"-nya pada Agustus 1994. Juga ketika dokter menyatakan Idris terkena penyakit yang tak ringan, kanker usus, pada 1998. Ia terus berkarya, hingga kini.
Pada Rabu itu, Idris juga seolah-olah tak terhentikan untuk menceritakan kisahnya. Ia menyilakan Tempo menambah kisahnya dari buku Idris Sardi, Perjalanan Maestro Biola Indonesia. Sang penulis, Fadli Zon, juga memberi izin.
Saya lahir di Jakarta pada 7 Juni 1938. Saya terlahir dari keluarga yang menekuni jalur musik. Bapak saya, Mas Sardi, adalah musikus yang bisa memainkan banyak instrumen musik, antara lain biola, saksofon, klarinet, dan piano. Bapak juga seorang ilustrator musik film. Semasa hidup, ia pernah bermain bersama rombongan Faroka Opera, bergabung dengan Sweet Java Opera dan Jazz Big Band, serta menjadi pemain biola di Orkes Studio Jakarta.
Kakek Bapak, Raden Mas Soeprapto, adalah pemain inti Orkes Keraton Yogyakarta, yang dibentuk Sri Sultan Hamengku Buwono VII pada akhir abad ke-18. Keterampilannya dalam bermain musik menurun kepada kakek saya, Soekamto. Kakek tinggal di dalam benteng keraton yang dikenal dengan nama Musikanan. Pada zaman penjajahan Jepang, ia berganti nama menjadi Sorno Waditro. Nama itu diberikan Sri Sultan Hamengku Buwono IX karena pengabdiannya di orkes keraton semasa hidupnya.
Adapun ibu saya, Hadidjah (meninggal pada 10 Oktober 2013), adalah aktris yang memulai debutnya lewat film Alang-Alang (1939). Begitu juga nenek saya, Habibah. Nenek pernah bermain film bersama buyut saya, Moesa Pancho, pada 1938 lewat film Fatima. Buyut saya adalah pemimpin sandiwara yang berkelana ke berbagai negara di Asia. Perkawinan Ibu dengan Ayah melahirkan delapan anak, dan saya anak pertama.
Kami tinggal di Ketapang, Sawah Besar Luar, Jakarta. Di rumah itulah saya mulai diperkenalkan dengan biola dan dunia musik. Saya mulai serius belajar biola pada umur lima tahun. Sebelum berlatih, Bapak yang mengenali bakat saya bertanya, "Kamu siap bermusik? Karena bermusik itu berat. Kamu tidak boleh menzalimi orang. Jadi kamu harus menyiapkan diri bermain bagus, jangan sumbang. Syarat kamu tidak jadi zalim, harus mulai jam lima pagi. Siap?" Saya pun bilang siap.
Pada usia itu, Bapak benar-benar meminta saya bangun di saat subuh untuk menyaksikannya memainkan tangga nada. Saya tidak diperbolehkan langsung bermain biola. Tapi, sebelum memulai kegiatan tersebut, Ayah selalu meminta saya mandi dulu. Kata Ayah, musik itu harus dimainkan dengan cara yang bersih. Dan mandi itu merupakan cerminan jiwa-raga yang bersih.
Teknik bermain biola saya pelajari lagi pada sore hari. Kadang saya diajak Ayah menonton permainan musik pada akhir pekan. Atau diajak ke RRI pada pagi hari. Saya baru diperbolehkan memegang biola pada usia sembilan tahun. Ukuran biola saat itu terasa sangat besar bagi saya. Dan saya harus belajar musik klasik dulu. Jadi tidak sembarang.
Sebagai permulaan, saya diminta menghafal 80 nada dari empat senar biola. Intonasi nada saya mainkan dengan tempo lambat, gesekan ke atas atau ke bawah. Tekanan jari harus berada di posisi yang tepat. Salah sedikit, suara yang keluar pasti berbeda. Ayah saya orang yang sangat keras dalam mendidik. Bila ada satu not yang salah, saya menerima hukuman: dijambak, dijewer, atau saya dihukum berlatih biola di depan kakus yang bau.
Karena saya sibuk dengan jadwal latihan bermusik, masa kecil saya hampir tidak mengenal kata bermain. Padahal saya suka main bola dan berenang. Jadi kadang kucing-kucingan. Kalau saya main bola, harus jauh dari rumah, sampai naik trem. Alasannya, kalau main bola kemudian jatuh dan sakit, habis. Tidak bisa main biola.
Tapi itu semua menjadi bekal saya masuk sekolah musik di Yogyakarta pada 1949. Di bawah bimbingan Nikolai Varfolomeyev, pemimpin sekolah tersebut, kemampuan saya bermain biola semakin terasah. Dia bahkan mengangkat saya menjadi pemain biola utama (soloist concertmaster) pada orkes sekolah musik. Umur saya ketika itu baru 11 tahun. Padahal rata-rata murid di sekolah itu usianya di atas 20 tahun. Bahkan uang bayaran juga dikembalikan dalam bentuk buku.
Pendidikan itu terpaksa terhenti pada 1953. Ayah saya meninggal, dan saya harus kembali ke Jakarta. Sebagai anak sulung, saya menanggung beban ekonomi keluarga. Tanggung jawab itu harus saya emban ketika usia saya masih 15 tahun. Saya bergabung dengan Orkes Studio Djakarta (OSD). Dengan bekal yang saya miliki, saya dipercaya sebagai concertmaster. OSD adalah orkes terbaik saat itu. Grup ini sering diminta mengisi acara kenegaraan dan acara di RRI. Jadi mengurusi keluarga bukan masalah bagi saya. Biasanya uang gaji saya langsung saya berikan ke Emak.
Di OSD, saya tidak hanya bermain lagu klasik. Repertoar keroncong, Melayu, Sunda, dan musik daerah lain juga harus bisa kami mainkan dengan baik. Tapi rupanya musik daerah yang saya mainkan masih berasa musik klasik. Musik klasik dan musik daerah punya watak yang sangat berbeda. Dengan teknik klasik, lagu Bengawan Solo terasa hambar dan datar.
Saya pun belajar lagi. Untuk menguasai roh musik Nusantara, saya sering menyaksikan latihan kelompok karawitan Jawa dan kesenian Sunda. Saya juga keliling menonton pertunjukan keroncong. Bahkan kadang saya mengikuti keseharian para pemainnya. Jadi, guru saya bisa siapa saja, termasuk tukang becak yang pernah menemani saya menonton orkes Melayu di pinggir jalan. Saya pun dianggap gila. Tapi saya tak peduli.
Wawasan saya semakin bertambah lewat pergaulan dengan Ismail Marzuki dan pemimpin Orkes Chandra Kirana, Iskandar. Pada masa-masa itu, saya sering bersentuhan dengan Orkes Melayu Bukit Siguntang pimpinan A. Halik dan Orkes Gumarang pimpinan Asbon. Lalu ada juga orkes keroncong pimpinan Isbandi. Semua pertemanan itu pada akhirnya membentuk identitas saya yang baru, seorang Idris Sardi yang ingin menjadi pelayan bagi perkembangan musik Indonesia.
Ketika ansambel saya tampil di sejumlah hotel, Es Lilin merupakan lagu favorit yang paling sering diminta penonton orang asing. Lagu itu bagi mereka terdengar berbeda dan unik karena punya sentuhan etnik. Kalangan menengah, mahasiswa, dan pelajar perlahan mulai mengenal saya. Pada masa itu, awal 1960, album pertama saya masuk dapur rekaman. Saya membuat aransemen lagu anak, seperti Dakochan dan Burung Kutilang, dengan irama combo. Beberapa tahun setelah itu, saya kembali meluncurkan sejumlah album.
Pada 1961, lagu saya dan Bing Slamet yang berjudul Jauh di Mata meledak. Saat itu, Presiden Sukarno melarang lagu-lagu rock. Jauh di Mata adalah keroncong yang saya buat rock. Jadi, kalau membawakan lagu itu, baru ngek… gedung pecah.
Kemudian pada 1962, saya dan enam musikus Tanah Air mendirikan band Eka Sapta. Formasi personelnya: Bing Slamet (bongo), Ireng Maulana (gitar pengiring), Itje Kumaunang (gitar melodi), Benny Mustapha (drum), Darmono (vibraphone), dan Mulyono (piano). Saya bermain biola dan bas. Kami memainkan berbagai aliran musik, seperti pop, rock and roll, cha-cha, jazz, keroncong, dan Melayu. Band ini sering diundang Presiden Sukarno tampil di Istana Bogor.
Pengalaman lucu pernah saya alami ketika Eka Sapta diundang bermain di Istana. Waktu itu saya didaulat jadi penggebuk drum. Seorang anggota Tjakrabirawa meminta saya menabuh drum sekeras mungkin, karena gaya itulah yang digemari Sukarno. Mendengar permainan saya, Sukarno, yang saat itu sedang menari, tiba-tiba datang menghampiri. Alih-alih mendapat pujian, saya malah disemprot. "Kamu tahu enggak, main musik itu kebersamaan. Ada harmoninya." Habislah saya dikerjain.
Pada 1976, saya dipercaya Dirjen Radio Televisi dan Film sebagai guest conductor untuk Orkes Simfoni Jakarta. Selama dua tahun, saya ditantang meningkatkan apresiasi pada musik simfoni. Mulanya itu bukan tugas mudah. Acara yang disiarkan lewat TVRI ini tidak banyak mendapat sambutan masyarakat. Karya repertoar klasik seperti karya Mozart dan Beethoven, bagi mereka, terasa berat saat didengarkan. Belakangan saya mengubah konsep orkestra dengan memadukan roh musik-musik etnik. Akhirnya banyak yang senang.
Setelah 40 tahun mengabdi di bidang musik, saya mengadakan pergelaran konser yang dikenal dengan konser pamit. Konser yang digelar pada 9 Agustus 1994 itu menuai kesalahpahaman dari sejumlah kalangan. Banyak yang mengira ketika itu saya mau gantung biola.
Waktu itu yang terjadi adalah saya mendapat kehormatan membuat konser perjalanan sejarah karier selama 40 tahun, dihubungkan dengan kemerdekaan Indonesia. Saya sudah siap. Tapi, sewaktu latihan, ada beberapa musikus yang tidak datang. Orang-orang tersebut menggerogoti jadwal saya. Akhirnya saya bilang pamit. Namun yang saya maksud dengan pamit ini adalah saya tidak mau konser selama tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya bukannya ingin berhenti bermain musik. Toh, buktinya sampai sekarang saya masih bermain musik di mana-mana.
Purwani Diyah Prabandari, Riky Ferdianto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo