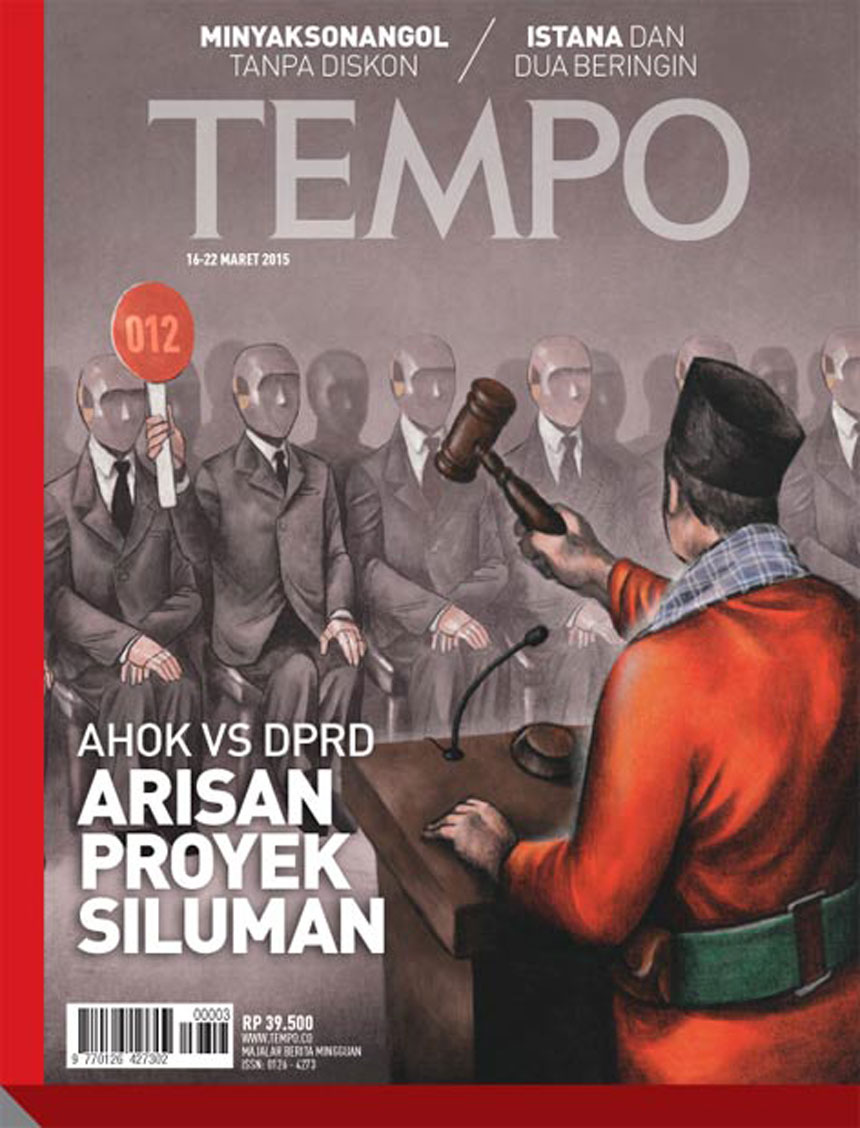Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Solihin Gautama Poerwanagara beruntung dilahirkan dalam keluarga menak. Sebab, semasa penjajahan Belanda, hanya anak keturunan priayi yang diperbolehkan bersekolah hingga tingkat lanjut. Dan di pendidikan formal inilah wawasannya tentang keadilan terbuka. Ia melihat perlakuan diskriminatif terhadap pribumi, dan bertekad ikut memperbaiki keadaan. Solihin meyakini, selama penjajah masih bercokol di Bumi Pertiwi, keadilan tak akan pernah terwujud. Bagi Mang Ihin, sapaan akrabnya, angkat senjata menjadi satu-satunya pilihan mengusir penjajah. Maka, sejak usia belasan tahun, dia memutuskan ikut berperang.
Berikut ini kisah si anak menak mengiringi perjalanan negerinya.
Solihin Gautama Poerwanagara adalah tokoh yang dihormati di tanah Pasundan. Ia tumbuh berkat didikan keras, disiplin, dan kejujuran yang ditanamkan kedua orang tuanya. Dengan itu, ia ikut bersaham dan berkeringat melewati perjalanan sejarah Indonesia dalam empat zaman: sebelum kemerdekaan, zaman Orde Lama, era Orde Baru, dan pasca-reformasi.
Sejak usia belasan tahun, Solihin sudah bercita-cita menegakkan keadilan di Tanah Air. Tekadnya itu muncul melihat perlakuan Belanda yang diskriminatif terhadap pribumi. Contohnya, banyak sekolah yang terlarang bagi warga biasa. Dia sendiri bisa bersekolah di Europeesche Lagere School (ELS) kemudian Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Tasikmalaya karena keturunan menak.
Pada 1942, tentara Jepang masuk Indonesia. Rakyat menyambut mereka bak pahlawan karena dianggap berhasil mengusir Belanda. Namun cita-cita Solihin menegakkan keadilan kembali mencuat. Pasalnya, tak butuh waktu lama bagi dia untuk sadar bahwa kelakuan Jepang sama saja dengan Belanda. Ia lantas berpikir, selama Indonesia masih dijajah, tak ada yang namanya keadilan. "Namanya penjajah, ya sama saja," katanya.
Solihin kemudian bergabung dengan wadah perjuangan kesatuan pelajar, yang kelak berubah nama menjadi Tentara Pelajar. Dia beranggapan hakikat dari kemerdekaan adalah terciptanya keadilan yang akhirnya membawa kemakmuran. Prinsip inilah yang ia pegang teguh hingga menjadi pejabat negara kelak di kemudian hari.
Ketika Jepang kalah oleh Amerika Serikat pada Perang Dunia II dan Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda kembali berusaha menyelinap masuk Indonesia dengan mendompleng pasukan penjaga keamanan Inggris. Ketika itu Solihin masih berstatus sebagai pelajar. Tekadnya menegakkan keadilan itulah yang membawa dia ke kancah pertempuran.
Ada satu kisah menarik tatkala ia hendak mengikuti ujian sekolah kelas III sekolah menengah tinggi. Pada saat itu, situasi medan pertempuran tengah sengit. Karena ujian sekolah dan perang dianggap sama pentingnya, Solihin memutuskan memakai seragam pejuang saat mengikuti ujian. "Setelah ujian, saya langsung ngacir ke lapangan untuk perang," ucapnya.
Solihin ikut perang dengan menenteng bedil milik Jepang. Itu adalah senjata rampasan yang diperolehnya di lapangan terbang Andir, Bandung. Lalu ia menggantinya dengan senapan bekas peninggalan Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL, karena bedil Jepang terlalu panjang dan pelurunya susah didapat.
Ada satu senjata selama masa perjuangan ia simpan baik-baik hingga kini, yaitu jungle rifle. Senjata ini ia dapat ketika ikut menghadang pasukan musuh di Cilacap, Jawa Tengah. "Masih ada dan saya simpan di rumah," kata Mang Ihin-demikian sapaan akrab Solihin.
Di rumahnya di Jalan Cisitu Baru VI Nomor 1, Bandung, itu pula Mang Ihin menerima Tempo, Rabu dua pekan lalu. Terdengar suara langkah kaki perlahan begitu suara bel berucap salam dua kali. Berkaus polo putih dengan bordiran benang emas bertulisan SGP di dada kiri, Mang Ihin terlihat santai dengan celana jins biru tua.
Ia memilih duduk di kursi teras dekat dua akuarium besar. "Rek naon, nggeus tereh paeh (Mau apa, [saya] segera mati)," katanya ketika mulai diajak wawancara. Sambil menikmati teh tawar hangat dengan gula pasir terpisah serta singkong goreng beserta saus sambal dan tomat, Mang Ihin berbagi kisah hidupnya yang telah dilakoni selama 88 tahun lebih.
SAYA dilahirkan di Desa Karangnunggal, Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 21 Juli 1926. Kami 13 bersaudara dan saya anak ke-10. Ayah bernama Abdulgani Poerwanagara, pada saat itu dipercaya menjadi wedana-pembantu bupati dan membawahkan beberapa camat. Ayah dan ibu saya, Siti Ningrum, keturunan menak atau priayi. Begitu juga leluhur mereka.
Sedangkan nama Poerwanagara itu sebutan bagi kelompok warga yang dulu menjaga Kerajaan Galuh di Ciamis (Jawa Barat) dan sekitarnya. Raja Galuh, yang kemudian mendirikan Kerajaan Pajajaran, memilih ibu kota di Pakuan, Bogor. Nama belakang saya, Poerwanagara, merujuk pada sebutan negara tua, bekas Kerajaan Galuh itu.
Saya beruntung lahir sebagai keturunan priayi sehingga tak susah bersekolah seperti warga pribumi lainnya. Zaman itu hanya anak keturunan priayi yang bisa bersekolah. Adapun kaum pribumi harus menjauh dari tempat pendidikan. Malah ada tulisan larangan di mana-mana yang sangat menghina, "Verboden voor inlanders en honden". Artinya, "Orang pribumi dan anjing dilarang masuk."
Saya mulai bersekolah di Europeesche Lagere School (ELS), kemudian Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Tasikmalaya. Semua guru utamanya orang Belanda. Karena sekolah kami cukup jauh dari rumah, saya dan semua saudara yang telah cukup umur untuk bersekolah dititipkan di rumah uak, kakak orang tua kami, di Kota Tasikmalaya.
Sewaktu Jepang masuk ke Indonesia pada 1942, saya lulus dari MULO dan lanjut ke sekolah menengah teknik di Bandung. Sedangkan kakak-kakak saya yang lelaki menempuh sekolah pamong praja di Tegalega, Bandung. Kalau tidak ada perang revolusi, saya juga mungkin bekerja di pemerintahan sebagai alat kolonial.
Ayah saya sebenarnya ingin kami masuk ke almamaternya, Middelbare Opleidingsschool Voor Irlandsche Ambtenaren (MOSVIA). Ini adalah sekolah pamong praja yang didirikan Belanda. Mirip seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sekarang. Bedanya cuma anak priayi yang bisa masuk kampus itu dan menjadi pegawai kolonial.
Ketika ayah masih menjabat wedana, saya kadang diajak ikut inspeksi ke pelosok kampung. Pernah suatu ketika kami kemalaman dan menumpang tidur di rumah warga. Sebelum masuk, ayah meminta saya tidak menunjuk apa pun, semisal burung, tanaman, atau buah-buahan.
Alasannya, jari telunjuk anak menak yang mengarah ke sesuatu bisa diartikan sebagai permintaan. Suka atau tidak harus mereka berikan. Larangan itu tentu harus saya patuhi. Sampai-sampai jari telunjuk ini sakit karena terus-menerus berada di dalam saku. (Sambil mencontohkan jari telunjuk kanannya yang dimasukkan ke saku celana.)
Cukup lama bagi saya untuk memahami makna di balik larangan itu. Ternyata cukup dalam, yaitu jangan mengambil punya rakyat dan jangan meminta apa yang sudah menjadi milik rakyat. Jadi pemimpin itu harus banyak memberi ketimbang meminta dan lebih baik menguntungkan orang lain daripada merugikannya.
Kalau Ibu lain lagi. Ibu orangnya sangat galak soal urusan disiplin. Ibu melarang kami melahap sajian suguhan tuan rumah tiap kali diajak nganjang atau bertamu. Pernah suatu ketika saya makan dengan rakus sajian kue-kue kampung. Sesampai di rumah, kaki saya disabet sapu lidi oleh Ibu. Sebagai anak menak, kata Ibu, kami harus menjaga citra dan perilaku. Didikan keras Ibu masih tertanam pada saya.
Sedangkan dari Ayah, saya juga belajar tentang harga diri. Suatu ketika beberapa guru sekolah yang orang Belanda itu mampir ke rumah kami. Mereka minta disediakan ayam milik warga sebagai oleh-oleh. Tersinggung oleh perintah itu, ayah saya memutar balik bendo (penutup kepala seperti blangkon khas Sunda). Dia bilang, "Masak, wedana disuruh cari ayam?"
Penolakan itu ternyata sampai ke pemerintah kolonial dan tercatat untuk yang kesekian kalinya. Setelah menjadi Gubernur Jawa Barat, saya sempat cari-cari arsip tentang ayah saya. Ternyata dari laporan kerja ayah saya sebagai wedana di Lembang, Bandung, dan Garut, namanya diberi garis merah hingga diputuskan untuk pensiun dini. Saya banyak belajar dari situ, bahwa harga diri tak bisa dibeli.
PADA Maret 1946 terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Solihin, yang kala itu sudah tergabung dalam Divisi Siliwangi, ikut menyingkir ke Yogyakarta. Sekembali ke Bandung, ia dihadang pasukan Belanda di sejumlah tempat dan menyaksikan pejuang berguguran. Dalam perjalanan ke Bandung, jumlah pasukan pejuang menyusut akibat sakit atau jenuh berperang sehingga memilih pulang kampung.
Tidak begitu dengan Solihin. Ia tetap memutuskan berjuang. Hingga suatu saat, di Desa Tawang Banteng, Tasikmalaya, kompi pasukan berpencar untuk bertahan hidup. Di desa itu, Solihin memakai nama samaran Gautama dan berpura-pura sebagai juru tulis desa. Pada saat itu pangkatnya adalah kapten dan menjadi target pencarian pasukan Belanda.
Suatu ketika Gautama alias Solihin diajak oleh mata-mata Belanda mencari Kapten Solihin. Bersama pasukan Belanda, mereka menuju kaki Gunung Galunggung, Garut. Solihin mengaku sangat menikmati "pencarian dirinya" itu dan menganggapnya sebagai sebuah pelesiran, meski suasana sering berubah menjadi tegang. Nama samaran Gautama ini yang kemudian melengkapi nama tengah aslinya.
Pertempuran demi pertempuran dilalui Solihin. Bukan hanya pasukan Belanda yang harus dihadapi, melainkan juga pemberontak, seperti Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan pasukan pemberontak Kahar Muzakar. Tidak seperti pasukan Belanda yang mudah dikenali, para pemberontak ini sulit ditebak lantaran mereka bersembunyi di antara rakyat. "Mereka adalah lawan yang berat."
DALAM dua pertempuran, melawan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, saya harus berhadapan dengan kawan lama di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (1954-1956). Yang pertama namanya Hutabarat. Dia senior saya dan seperti keluarga sendiri. Sayang, dia memilih menjadi pemimpin PRRI di Tarutung. Sedangkan di pasukan Kahar juga ada kawan baik saya. Namanya Gerungan.
Setelah membekuk pasukan Kahar, saya diangkat menjadi Panglima Kodam IV Hasanuddin. Kabarnya, panglima sebelum saya, M. Jusuf, yang menunjuk langsung saya sebagai penggantinya. Lima tahun saya menjabat Pangdam Hasanuddin sebelum dipindah tugas ke Magelang, Jawa Tengah, untuk menjadi Gubernur Akabri (27 Agustus 1968).
Di Magelang, saya memulai dengan pembenahan akademi, terutama soal pungutan dan pakaian taruna yang terlalu ketat. Di sini saya sering menyampaikan materi tentang kepemimpinan dan dwifungsi ABRI. Konsepnya adalah bagaimana mengubah tentara yang konsumtif menjadi produktif yang bersumber dari Perjuangan Rakyat Semesta. ABRI harus bisa tampil dalam keadaan darurat ketika kader sipil belum siap.
Saya melihat di Akabri belum ada program khusus bagi para instruktur yang tidak punya rencana setelah pensiun. Saya mengajak mereka bertransmigrasi ke Lampung, tentu setelah diberi pengertian dan lahan masing-masing dua hektare yang tersebar di dua desa. Ada sekitar 100 keluarga bersedia dan sukses dengan ternak sapi, sawah, dan punya lahan garapan baru.
SAAT Solihin G.P. menjadi Gubernur Akabri, terbetik kabar bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat mengusulkan dia sebagai Gubernur Jawa Barat. Solihin sempat menolak. Sebab, ia sudah berjanji akan pensiun setelah tak lagi menjabat Gubernur Akabri. Padahal usianya kala itu baru 42 tahun-masih jauh dari usia pensiun pada umumnya yang 55 tahun.
Sikap Solihin kemudian berubah ketika Presiden Soeharto memintanya menerima pinangan menjadi gubernur. Permintaan itu disampaikan Presiden ketika mereka bertemu saat meninjau lokasi bencana meletusnya Gunung Merapi di Yogyakarta. "DPRD Jawa Barat memilih kamu menjadi Gubernur Jawa Barat. Kamu harus bisa, kamu kan belum pensiun. Saya yang menentukan tugas kamu," kata Soeharto dalam pertemuan itu, seperti yang termuat dalam buku The Trouble Shooter: 80 Tahun Solihin G.P.
Solihin sempat bimbang dan terbebani hingga jatuh sakit. Sebab, ia sudah berjanji akan pensiun sebagai Gubernur Akabri dan janji itu harus ditepati. Namun, di sisi lain, atasannya memerintahkan dia menerima tugas itu. Akhirnya ia bersedia menjadi Gubernur Jawa Barat dengan catatan akan bertugas sesingkat mungkin agar bisa digantikan oleh kalangan sipil.
Firman Atmakusuma, Anwar Siswadi
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo