Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Peneliti BRIN menerbitkan lima buku tentang intelijen Indonesia.
Kajian mereka lebih banyak bersandar pada dokumen sekunder.
Badan intelijen belum profesional dan masih kuat nuansa politiknya.
PENERBITAN seri buku studi tentang intelijen tak sepenuhnya berjalan sesuai dengan rencana. Peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang kemudian dilebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), memulai penelitiannya sejak 2015. Buku pertama, Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru, terbit pada 2017 dan buku kedua, Intelijen dan Politik Era Soekarno, menyusul tahun berikutnya. “Tiga buku lainnya terbit tahun 2022 semua,” kata Muhamad Haripin, anggota tim peneliti, pada Rabu, 3 Agustus lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tiga buku yang terbit tahun ini adalah Intelijen dan Kekuasaan Soeharto, Intelijen dan Keamanan Nasional di Indonesia Pasca-Orde Baru, dan Membangun Intelijen Profesional di Indonesia. Di luar buku-buku tersebut, ada empat kertas kerja yang mengulas organisasi telik sandi ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

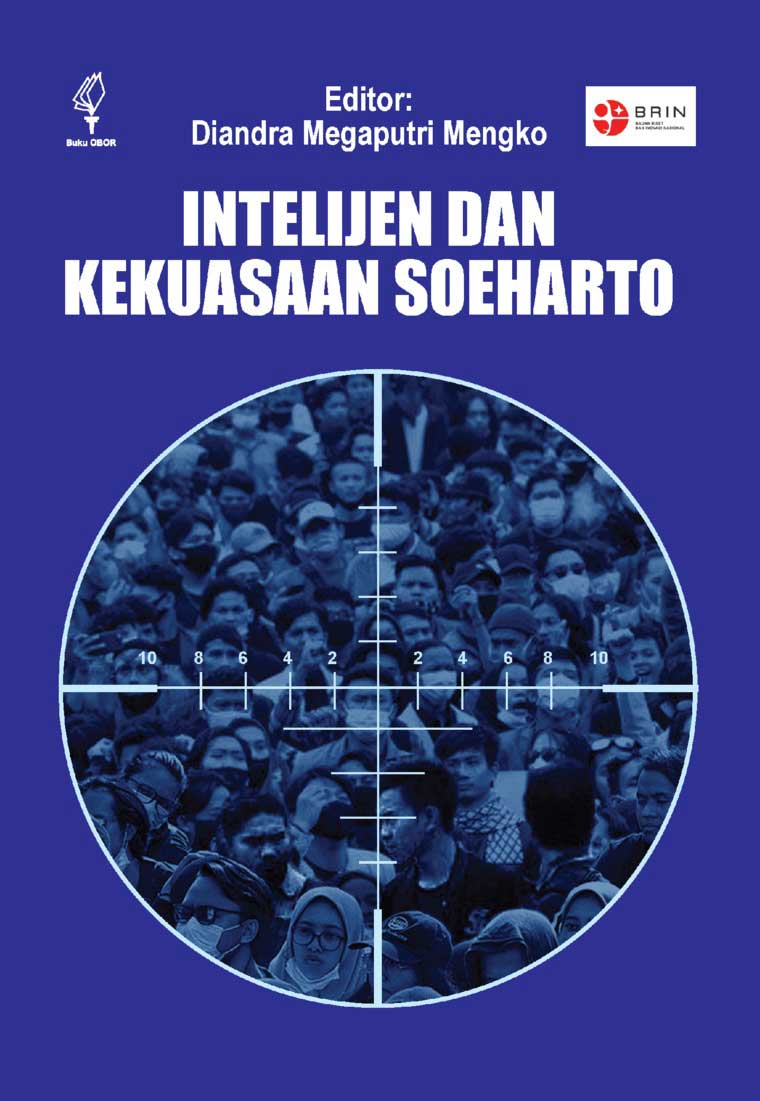
Intelijen Dan Kekuasaan Soeharto
Di Indonesia, yang disebut sebagai komunitas intelijen adalah Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian, serta intelijen kejaksaan. Namun fokus pembahasan studi ini adalah BIN, lembaga yang berperan sebagai koordinator untuk semua badan intelijen berdasarkan Undang-Undang Intelijen.
Penerbitan seri buku, menurut peneliti senior LIPI, Ikrar Nusa Bakti, merupakan rangkaian dari studi tentang reformasi keamanan yang dimulai sejak 1995. Saat itu, Presiden Soeharto memulai reformasi di tubuh militer dan meminta LIPI melakukan kajian. Penelitian itu kemudian yang menghasilkan buku Bila ABRI Menghendaki (1998), Bila ABRI Berbisnis (1998), dan Tentara Mendamba Mitra (1999). “Setelah itu dilanjutkan dengan studi tentang reformasi kepolisian dan intelijen,” ucap Ikrar dalam webinar peluncuran buku kajian ini pada Sabtu, 30 Juli lalu.
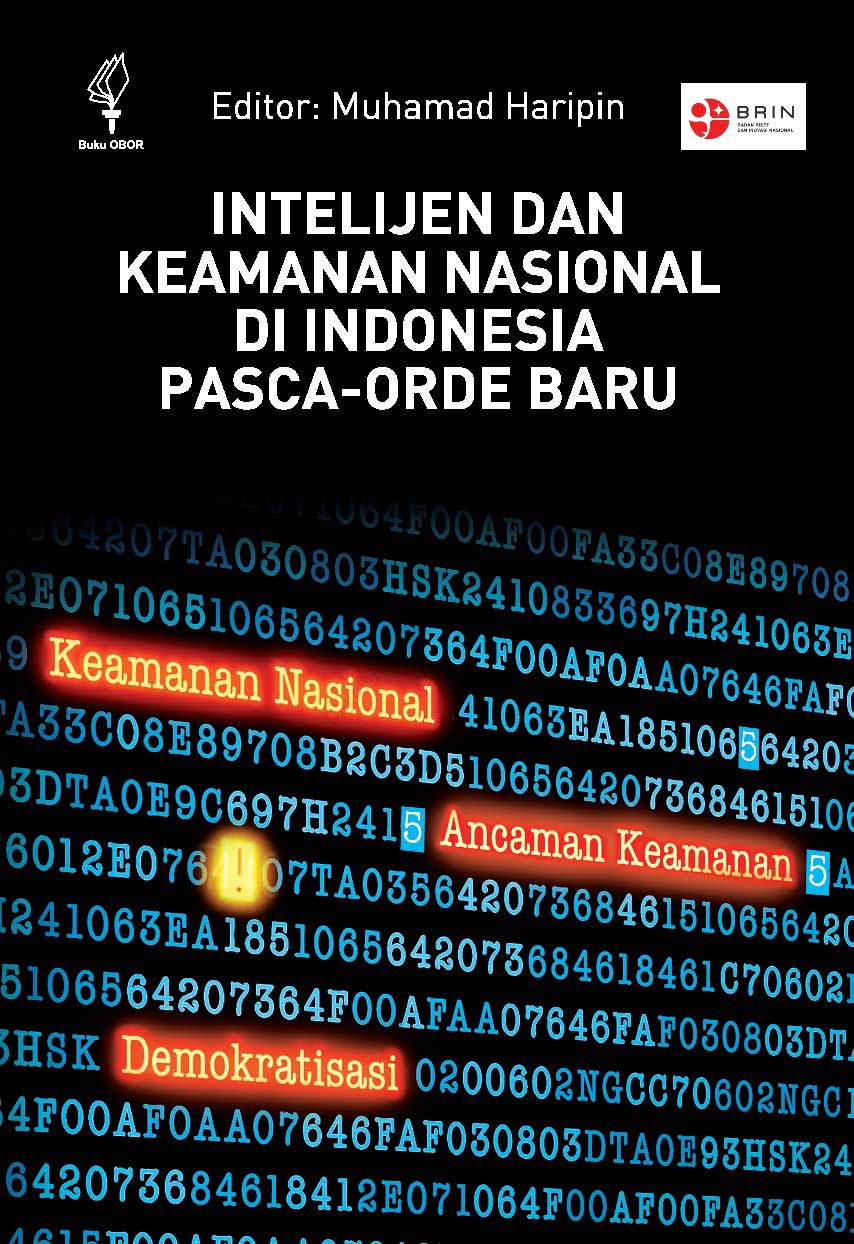
Intelijen Dan Kemananan Nasional Di Indonesia Pasca-Orde Baru
Ikrar mengakui bahwa penelitian mengenai badan intelijen bukan hal yang mudah karena watak organisasinya yang bersifat rahasia. Namun mantan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia itu bersyukur bahwa ia bersama para koleganya bisa masuk sedikit demi sedikit ke komunitas tersebut; mewawancarai sejumlah petinggi BIN, Bais, BIN daerah, Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian RI; dan pengguna akhir informasi intelijen, yaitu presiden.
Lima buku itu mengulas intelijen dengan berbagai pendekatan. Ada yang mengkajinya berdasarkan periode pemerintahan, yaitu era Sukarno (1945-1965), Soeharto (1966-1998), dan setelah Reformasi 1998. Ada juga yang berfokus pada topik tertentu, seperti hubungan badan intelijen dengan presiden atau praktik pengawasannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tiap buku berisi lebih dari lima bab dan tiap bab ditulis oleh satu-dua peneliti.

Membangun Intelijen Profesional Di Indonesia
Putri Ariza Kristimanta menulis hubungan kepala badan intelijen dengan presiden. Menurut dia, pola umum yang bisa dilihat dalam pemilihan kepala badan intelijen oleh presiden adalah kepercayaan. “Ketika presiden tak mempercayai kepala intelijennya, bagaimana dia bisa mempercayai hasil dari produk analisisnya?” katanya. Pola serupa terjadi di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat.
Menurut Muhamad Haripin, pola pengangkatan pemimpin intelijen itu bersifat paternalistik, patron-klien, atau hubungan politik murni. Ini tidak hanya terjadi di masa Soeharto, tapi juga diteruskan oleh presiden-presiden berikutnya, dari B.J. Habibie hingga Joko Widodo. “Kami bisa menarik garis-garis politik orang (yang ditunjuk menjadi kepala badan intelijen) ini,” tuturnya.
Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, BIN dipimpin secara berturut-turut oleh Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Syamsir Siregar, Jenderal Polisi Sutanto, dan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marciano Norman. Tim peneliti menilai orang yang diangkat Yudhoyono sebagai Kepala BIN adalah yang punya kedekatan politik dengannya, antara lain pernah menjadi bagian tim suksesnya.
Dalam wawancara dengan tim peneliti pada 2018, Yudhoyono menegaskan pentingnya peran BIN yang ia ibaratkan sebagai “mata dan telinga presiden”. Yudhoyono tak menyanggah soal kedekatan itu, tapi menekankan soal kemampuan calon sebagai pertimbangan utama.
Yudhoyono, kata Haripin, juga menyebutkan soal tantangan aktual yang dihadapi sebagai pertimbangan dalam memilih Kepala BIN. Pada periode itu, ancaman terbesar adalah terorisme. “Kalau ingat situasi 2004 dan 2006, memang (hal) itu yang sedang genting. Kita memang butuh orang yang bisa menangani masalah itu,” ucap Haripin mengutip jawaban Yudhoyono.
Peneliti juga menanyakan perihal intelijen sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan atau melindungi kepentingan politik presiden, seperti terjadi di masa Orde Baru. Atas pertanyaan ini, menurut Haripin, intinya Yudhoyono menyatakan bahwa ia menyampaikan kepada jajaran intelijen untuk tidak masuk ke area politik, misalnya dalam urusan partai politik.

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bersama mantan Kepala BIN Sutanto (kiri) di di Perairan Makassar Bontang, Kalimantan Timur, Juni 2008. TEMPO/Amston Probel
Johan Budi S.P., mantan juru bicara Presiden Jokowi, menilai wajar jika presiden memilih orang untuk menduduki jabatan penting berbasis pada kepercayaan. “Saya kira setiap pembantu presiden, apakah Panglima TNI, Kepala Polri, pasti orang yang dipercaya oleh presiden. Termasuk pemilihan Kepala BIN,” ujar pria yang kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Juru bicara BIN, Wawan Purwanto, menyebut politisasi terhadap badan intelijen sebagai isu yang tidak benar. “BIN bekerja untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. BIN non-partisan dan tetap profesional dalam bekerja serta diawasi oleh DPR terkait dengan kinerja ataupun BPK terkait dengan anggaran. BIN bekerja on the track,” tuturnya pada Kamis, 4 Agustus lalu.
Aspek lain yang juga dinilai penting dalam dinamika badan intelijen di Indonesia adalah pengawasan. Menurut peneliti BRIN, Diandra Megaputri Mengko, berkaca pada pengalaman Amerika Serikat, kegagalan mencegah tragedi biasanya menjadi pintu masuk untuk melakukan reformasi. Kongres Amerika membentuk komite penyelidik setelah badan intelijen negara itu dinilai gagal mencegah terjadinya serangan 11 September 2001.

Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden M. Jusuf Kalla, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, meninjau lokasi bom di kawasan Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Mei 2017. Dok. TEMPO/Rizki Putra
Menurut Diandra, Indonesia dilanda cukup banyak kasus pengeboman dan badan intelijen dalam sejumlah kesempatan mengaku kecolongan. Beberapa yang menonjol antara lain bom Bali I pada 2002, bom JW Marriot pada 2003, bom di depan Kedutaan Besar Australia pada 2004, bom Bali II pada 2005, bom Ritz-Carlton pada 2009, dan bom Sarinah pada 2016. Namun kasus-kasus itu tak menggerakkan DPR melakukan penyelidikan seperti yang dilakukan kolega mereka di Amerika.
DPR baru memiliki Tim Pengawas Intelijen pada 2014. Namun, kata Diandra, adanya tim itu juga tak membuat legislatif melakukan penyelidikan saat terjadi kasus pengeboman pada 14 Januari 2016 di kawasan Thamrin, Jakarta, yang menewaskan empat warga sipil. “Itu juga tidak ditindaklanjuti, meskipun DPR sudah punya Tim Pengawas Intelijen,” ucapnya.
Diandra melihat ada pola umum jika terjadi insiden semacam itu, yakni Kepala BIN diganti dan masalah seakan-akan dianggap selesai. Menurut dia, pendekatan seperti ini tidak membangun kultur intelijen yang profesional dan seharusnya yang dicari adalah penyebabnya di badan intelijen tersebut. “Itu kan kesempatan menilai apa yang kurang dari badan intelijen kita. Apakah kurang dari sisi teknologi atau dana? Jadi ini kesempatan untuk memperbaiki,” ujarnya.

Diskusi Publik dan Simposium Nasional terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang keamanan dan ketahanan siber. TEMPO/M Taufan Rengganis
Muhamad Haripin menambahkan, fungsi pengawasan DPR terhadap intelijen memang kurang berjalan. Tim pengawas intelijen cenderung reaktif atau hanya bekerja kalau ada pengaduan soal dugaan pelanggaran kode etik intelijen. Selama periode pertama tim (2014-2019), tidak ada satu pun pengaduan dari masyarakat. “Kami menyayangkan mengapa anggota Komisi I tidak proaktif,” katanya.
Ada sejumlah faktor yang bisa menjadi penyebab kurangnya pengawasan DPR terhadap intelijen. Diandra menduga ada masalah “inferiority complex” terhadap intelijen atau aparat keamanan yang berdampak pada pengawasan. Selama ini, sebagian besar rapat dengar pendapat DPR dengan badan intelijen tertutup. Ia membandingkan dengan sejumlah rapat Komite Badan Intelijen Senat Amerika dengan komunitas intelijen yang bisa disaksikan dari seluruh dunia.
Wawan Purwanto tak setuju dengan pandangan tersebut. “Pengawasan oleh DPR berjalan baik. Ada forum rapat dengar pendapat menyangkut hal-hal krusial yang perlu dibahas,” tuturnya. “Hal ini rutin dilakukan terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban kinerja. RDP (rapat dengar pendapat ) berlangsung secara berkala.”

Intelijen Dalam Pusara Demokrasi Di Indonesia Pasca Orde Baru
Haripin mengatakan, dalam studi ini, peneliti ingin melihat apakah intelijen kita mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Secara intuitif, jawabannya adalah dari dulu hingga kini masih sama, yaitu kuat dipengaruhi politik. Dari studi ini peneliti berkesimpulan bahwa karakter intelijen kita belum sepenuhnya profesional. Masih ada kepentingan politik di sana. “Jadi pandangan yang sebelumnya merupakan penilaian intuitif sekarang bisa mendapat penilaian secara akademis, lebih ilmiah,” katanya.
Namun bukannya tak ada perubahan sama sekali. Menurut Haripin, ada tiga kategori karakter badan intelijen, yaitu intelijen politik, polisi politik, dan intelijen profesional. Di masa Orde Baru, kategorinya adalah murni intelijen politik, yaitu bekerja untuk kepentingan rezim. Setelah reformasi, ada pergeseran dinamika. Sekarang pendulumnya bergeser ke polisi politik. “Otonomi operasi, pengambilan keputusan memang ada pertimbangan kepentingan politik elite, belum menjadi lembaga yang betul-betul mendedikasikan diri untuk kepentingan nasional yang obyektif,” ucapnya.
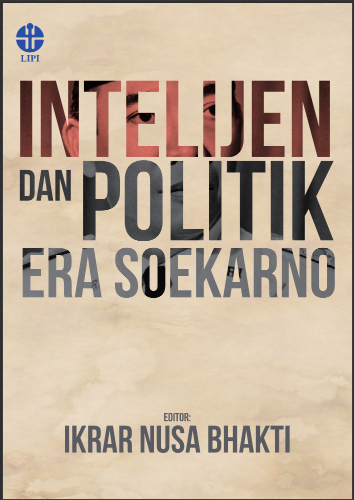
Intelijen Dan Politik Era Soekarno
Catatan positif lain, kata Haripin, adalah persepsi tentang ancaman. Dari studi LIPI, di masa lalu orientasi ancamannya banyak bersifat domestik. Setelah reformasi persepsi ancamannya ke eksternal atau ancaman yang bersifat obyektif. “Zaman dulu (intelijen) mendedikasikan ke ancaman internal. Sekarang ada semacam pelebaran. Soal politik masih ada, tapi ancaman kontemporer sudah masuk radar, seperti teror ISIS, ancaman di dunia siber,” ujarnya.
•••
MESKI peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sudah cukup lama menggeluti isu reformasi sektor keamanan, soal intelijen punya tantangan tersendiri. “Literaturnya masih minim,” kata Diandra Megaputri Mengko. Sebelum studi ini, lembaga yang lebih dulu melakukan kajian serupa serta menerbitkan hasil kajian dan buku adalah Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) dan Pusat Kajian Global Masyarakat Sipil (Pacivis) Universitas Indonesia.
Literatur lain yang mengungkap sejarah intelijen dari sudut pandang orang dalam adalah buku karya Ken Conboy, Intel: Inside Indonesia's Intelligence Service (2004), dan disertasi Richard Tanter, Intelligence Agencies and Third World Militarization: A Case Study of Indonesia, 1966-1989. “Buku Ken Conboy menjadi salah satu buku yang paling banyak dirujuk. Sejarahnya juga paling mendetail, dengan timeline yang panjang,” tutur Putri Ariza Kristimanta.
Mantan kepala badan intelijen juga sangat sedikit yang menuliskan pengalaman memimpin organisasi ini. Beberapa mantan agen intelijen yang menulis buku biografi atau autobiografi adalah mantan Wakil Kepala BIN, Asad Ali, dengan Perjalanan Intelijen Santri (2020); dan Slamet Singgih dengan Intelijen: Catatan Harian Seorang Serdadu serta Memori Jenderal Yoga (1990), autobiografi Yoga Soegomo.
Mantan Kepala BIN, A.M. Hendropriyono, juga menulis beberapa buku yang berisi pandangannya soal berbagai isu seperti terorisme dalam Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia (2013). Kepala BIN saat ini, Budi Gunawan, pun menulis buku bersama Barito Mulyo Ratmono berjudul Kebohongan di Dunia Maya (2018) dan Demokrasi di Era Post Truth (2021). Menurut Muhamad Haripin, meski buku Hendropriyono dan Budi Gunawan tak membahas pengalaman mereka saat memimpin badan intelijen, setidaknya menunjukkan perhatian besar pada topik tertentu saat memimpin lembaga itu.
Menurut Putri, beberapa presiden, petinggi, atau agen badan intelijen kurang mendalam ketika mengulas aspek intelijen di buku mereka. “Kebanyakan soal partai politik, hubungan politik luar negeri. Tidak ada soal intelnya juga,” ujarnya. Susilo Bambang Yudhoyono menulis buku Selalu Ada Pilihan (2014) dan B.J. Habibie menulis Detik-Detik Yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Yang Menentukan (2006).
Salah satu tantangan peneliti, kata Putri, adalah keterbatasan dalam mengakses dokumen internal. “Makanya kami, dalam menulis dan meneliti, banyak juga yang pada berpegang dokumen sekunder karena sulit juga untuk masuk ke dalam contoh kasus berdasarkan informasi dari informan atau dokumen internal BIN,” ujarnya.
Menurut Diandra, salah satu kunci tumbuhnya studi intelijen di luar negeri, yaitu Amerika dan Inggris, adalah dibukanya dokumen intelijen yang sebelumnya dikategorikan rahasia (deklasifikasi). Itu yang membuat banyak literatur tentang intelijen di sana lahir karena mendasarkan pada hasil pembukaan tersebut. “Cara semacam itu bukan hanya untuk bahan evaluasi terhadap intelijen, tapi juga pertanggungjawaban mereka kepada publik,” tuturnya.
Praktik deklasifikasi, baik yang dilakukan sendiri oleh badan intelijen maupun atas permintaan publik, membantu berkembangnya literatur mengenai intelijen. Sebagian dokumen Arahan Harian Presiden (PDB), yang disampaikan rutin oleh intelijen Amerika Serikat kepada presiden, dibuka oleh Dinas Intelijen Pusat (CIA) pada 2015 dan 2016. CIA juga banyak membuka dokumen yang sebelumnya dirahasiakan setelah masa retensinya, yang biasanya lebih dari 25 tahun, habis.
Di Amerika Serikat ada Badan Keamanan Nasional (NSA), lembaga nirlaba di Washington yang secara reguler meminta pembukaan dokumen yang sudah habis masa retensinya. Dokumen tersebut lantas dikaji dan diterbitkan dalam bentuk buku. Brad Simpson, peneliti NSA, misalnya, pernah menerbitkannya dalam laporan “U.S. Embassy Tracked Indonesia Mass Murder 1965” pada 2017.
Di Inggris, badan intelijen juga memberikan akses kepada peneliti atau akademikus untuk membaca dokumen intelijen, antara lain buat kebutuhan penyusunan buku sejarah resminya. Sejarah resmi badan intelijen luar negeri Inggris, MI6, ditulis oleh Keith Jeffery, profesor sejarah Inggris di Queen's University Belfast, Irlandia Utara; badan intelijen dalam negeri MI5 oleh Cristopher Andrews, profesor emeritus sejarah modern dan kontemporer di University of Cambridge; dan badan intelijen siber GCHQ oleh John R. Ferris, profesor di Departemen Sejarah University of Calgary, Kanada.
Di Amerika, referensi soal intelijen dari sudut pandang orang dalam banyak berasal dari biografi para mantan agen atau petingginya. Sejumlah kepala dan petinggi CIA yang menulis pengalamannya antara lain George Tenet dalam At the Center of the Storm: My Years at the CIA (2007), Michael V. Hayden dalam Playing to the Edge: American Intelligence in the Age of Terror (2016), dan Michael Morrel dalam The Great War of Our Time: The CIA's Fight Against Terrorism—From al Qa'ida to ISIS (2015).
Namun para petinggi dan agen intelijen Amerika tidak bisa sepenuhnya menulis secara bebas. Mereka terikat dengan lembaganya melalui perjanjian kerahasiaan sehingga buku yang diterbitkan juga harus diperiksa lebih dulu. Itulah yang terjadi dengan buku Valerie Plame Wilson, Fair Game: How a Top CIA Agent Was Betrayed by Her Own Government (2007), dan Ali J. Soufan, The Black Banners: The Inside Story of 9/11 and the War Against Al-Qaeda (2011). Berbeda dengan buku Soufan, buku Valerie Wilson lebih banyak disunting, yang ditandai dengan blok hitam.

Gedung Markas Besar CIA di McLean, Virginia, Amerika Serikat, Agustus 2008. REUTERS/Larry Downing
Sensor ini tidak hanya dialami oleh para perwira atau agen lapangan, tapi juga bekas pemimpinnya. Buku yang ditulis Direktur CIA periode 1977-1981, Stansfield Turner, Secrecy and Democracy: The CIA in Transition (1985), juga harus melalui proses pemeriksaan yang sama sebelum bisa meluncur ke publik.
Para peneliti BRIN tidak punya informasi soal apakah mantan agen intelijen Indonesia memiliki perjanjian kerahasiaan seperti di Amerika. “Dalam kode etik agen yang dikeluarkan Kepala BIN, tidak ada klausul yang mengatur itu,” kata Putri. Menurut Diandra, ini mungkin karena kultur kerahasiaan. Ada agen yang enggan berbagi cerita karena menyangkut pelaku yang masih hidup atau takut berdampak pada politik sehingga rahasianya bahkan bisa dibawa mati.
Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Beni Sukadis, mengatakan kurangnya tradisi keterbukaan dan sulitnya mengakses dokumen internal ini berkontribusi pada sedikitnya literatur soal intelijen. Ia menyebutkan situasi seperti ini memang bukan khas Indonesia. “Ini situasi khas yang dialami oleh negara yang berada dalam fase post-authoritarian,” tuturnya.
Muhamad Haripin menyebutkan studi BRIN ini masih dalam tahap awal. Ia berharap seri buku ini akan meningkatkan diskusi soal intelijen dan memicu mahasiswa atau peneliti lain untuk melakukan kajian lebih lanjut. Pengambil kebijakan diharapkan memahami peta bumi dunia intelijen sehingga bisa membuat kebijakan yang tepat. “Kami ingin badan intelijen kita profesional, bukan melayani kepentingan penguasa.”
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo




























