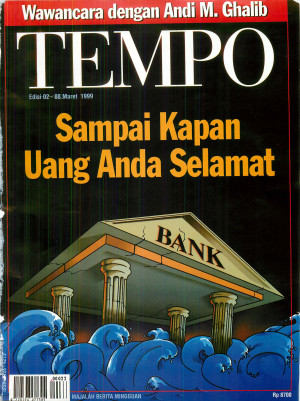Suatu sore di sebuah warung kopi di Kota Ambon. Belasan orang terlihat memenuhi warung kopi—sebutan untuk restoran di sana—yang terbesar di kota itu. Sejumlah laki-laki berkulit gelap, dengan rambut bergelombang, duduk melingkari meja. Sedangkan lelaki berkulit agak terang, dengan rambut lurus, mengikuti berita di pesawat televisi. Di dekat pintu masuk, terlihat seorang lelaki berkulit kuning, dengan mata sipit, asyik menikmati makannya. Masing-masing sibuk dengan keperluan mereka.
Mestinya tak ada yang istimewa dari pemandangan itu, sebagaimana dituturkan seorang periset yang baru saja balik dari sana. Tapi setting biasa tadi berlangsung di sebuah kedai kopi yang terletak di Jalan Sultan Babulah, kurang lebih 300 meter dari Masjid Alfatah, tempat konsentrasi masyarakat muslim Ambon.
Dan yang menarik, "potret" tersebut berlangsung di awal bulan ini, ketika kerusuhan atas nama suku yang berlanjut dengan perseteruan atas nama agama masih meminta korban. "Tak ada Islam, tak ada Kristen, tak ada soal suku, kami makan dengan tenang," kata mereka, seperti direkam sumber TEMPO itu.
Apakah penggalan "adegan" di atas cermin pela gandong yang kabarnya mulai rontok? Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi ada sederet cerita yang mengungkap sisi lain dari peristiwa kekerasan yang sedang mengharubirukan masyarakat yang menghuni kawasan dengan sebutan seribu kepulauan tersebut. Tak banyak pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap sisi plus yang perlu dijaga. Tak percaya?
Coba simak kejadian di Desa Poka, di Leihitu, di bagian barat Pulau Ambon, yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Ada beberapa penduduk Islam tinggal di sana. Tapi di desa ini tak pernah terjadi bentrokan. Kalaupun ada orang Kristen dari desa lain yang hendak menyerang warga muslim Desa Poka, penduduk Kristen di desa itulah yang maju menghadang mereka. Hingga kini pun beberapa masjid dan gereja di desa ini masih tegak berdiri.
Unik juga yang tercatat di Desa Larike, di ujung barat Pulau Ambon. Jumlah penduduk Islam dan Kristennya hampir berimbang. Ketika peristiwa Ambon pecah, penduduk desa itu saling melindungi. Jika ada orang Kristen yang datang untuk menyerang warga pemeluk Islam, warga desa yang beragama Kristenlah yang maju menghadang penyerang. Ketika giliran ada orang Islam yang akan menyerang, warga Islamlah yang menghadangnya. Alhasil, bentrokan tak terjadi di desa ini. Masjid dan gereja tak diusik.
Contoh lain terjadi pada 20 Februari lalu di Kampung Air Besar, di Kota Ambon. Warga Kristen yang ada di kampung tersebut tiba-tiba diserbu oleh warga Islam yang datang dari kampung tetangga. Tapi rombongan penyerbu ini akhirnya bisa dihalau karena kedatangan mereka sudah ditunggu oleh sekelompok warga Islam Air Besar di sebuah jembatan yang tak jauh dari kampung itu. Serangan pun urung dilakukan.
Begitu pula masyarakat di Desa Wakal, yang komposisi penduduk Islam dan Kristennya hampir sama. Mereka saling melindungi. Kalau ada serbuan yang dilakukan oleh pihak Kristen, yang menghadang adalah orang Kristen. Dan kalau ada serbuan yang dilakukan orang Islam, yang menghadang adalah orang Islam. Masjid dan gereja di tempat ini pun tak tersentuh bara kemarahan.
Cerita yang lebih dramatis terjadi di Dusun Wahatu, Desa Wakal, yang umumnya dihuni masyarakat asal Buton yang beragama Islam. Di dusun ini bermukim tiga keluarga beragama Kristen. Salah satu di antaranya guru SD di dusun itu. Sebelum 20 Januari—tanggal penyerbuan balasan oleh warga Islam—keluarga Kristen tadi diberi tahu bahwa mereka akan diserang. Karena itu, warga Buton menganjurkan agar mereka mengungsi. Untuk sementara ketiga keluarga tadi disembunyikan di rumah tiga orang Buton muslim.
Namun, sikap warga Wahatu asal Buton itu diketahui oleh para penyerang. Karena itu, pihak penyerang, yang juga beragama Islam, mencaci-maki orang Buton di Wahatu dan mengancam akan melanjutkan penyerangan. Khawatir ancaman itu benar-benar dilakukan, beberapa warga dusun ini lalu memindahkan keluarga Kristen itu ke rumah-rumah mereka yang ada di kebun-kebun di perbukitan. Keluarga Kristen tadi akhirnya diselamatkan oleh petugas keamanan yang datang setelah dipanggil oleh warga Buton itu.
Konflik yang terjadi di Ambon agaknya memang tak bisa dilukiskan secara hitam-putih. Masih banyak sisi lain yang mungkin tak begitu digubris pers: kerukunan warisan lama tradisi pela gandong yang tersisa di sudut-sudut desa. Tapi tak ada seorang pun yang bisa meramal, akankah nilai-nilai luhur tradisi ini bakal berumur panjang, meski cuma di secuil desa. Apalagi jika sumbu konflik makin kerap dinyalakan dengan api kemarahan yang kian panas.
Situasi keseharian yang terus mencekam bisa jadi pertanda buruk. Sebut saja peristiwa "Subuh Berdarah" tempo hari. Jika tak dijelaskan duduk perkara sesungguhnya, itu niscaya bakal memperburuk keadaan.
Dari gerakan Islam, mereka masih saja ngotot bahwa penembakan terjadi "di dalam masjid", meski dibantah berdasarkan keterangan resmi pemerintah setempat. Di sisi lain, kalangan Kristen malah mengungkit betapa pihaknya tak kalah menderita.
"Tapi jangan sampai kerusuhan di Ahuru-Rinjani itu didramatisasi untuk kepentingan politik," kata Ketua Klasis Gereja Protestan Maluku (GPM) Kota Ambon, Pdt. A.Z.E. Pattinaya. Ia menegaskan, warga jemaatnya tak pernah dan tak akan menyerbu sesama bangsanya. "Peristiwa itu musibah yang tak terpikirkan sebelumnya," kata Pattinaya.
Mungkin Pattinaya benar. Tapi di sejumlah desa yang sentimen suku dan agamanya menggumpal, maut tetap saja menghadang. Pendatang masih kerap ditanyai soal identitas agama dalam kartu penduduknya.
"Saya masih takut memasuki kawasan Kristen. Pernah saya masuk ke kantong penduduk muslim, tapi mereka tak yakin, sampai saya disuruh membaca syahadat," ujar seorang wartawan senior Antara yang telah bertahun-tahun bertugas di Ambon.
Dari cerita di atas, tak mengherankan jika salah seorang anggota Kontras, divisi antikekerasan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yang dikirim ke Ambon belum lama ini, berpendapat bahwa kekerasan yang terjadi bukanlah perang agama, melainkan lebih merupakan frustrasi sosial yang menjadikan agama sebagai identitas "pihak sana" lawan "pihak sini".
Rustam F. Mandayun dan Wenseslaus Manggut
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini