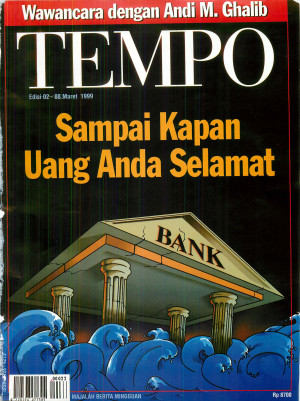Ambon manise kini sedang babak belur. Mardika, Batumerah, Aruhu, Rinjani, bahkan sampai Pulau Haruku dan Saparua, dihajar perseteruan antarwarga. Ratusan orang mati, ribuan bangunan rata dengan tanah, dan ribuan orang mengungsi. Benarkah ini semua hanya lantaran ulah provokator? Rasanya, tak segampang itu menyimpulkannya. Lalu, apa yang membuat Ambon begitu mudah koyak?
Ada banyak "teori" dikedepankan. Namun, bahan baku konflik Ambon boleh jadi terpendam dalam sejarah panjang di kawasan yang dijuluki Seribu Pulau ini. Siapa pun tak mengira jika akhirnya konflik itu bisa meledak seperti bom waktu—dahsyat dan, anehnya, berkepanjangan. Memasuki bulan ketiga sejak meletus di hari Idul Fitri, 19 Januari lalu, perseteruan itu sampai kini susah ditebak kapan redanya.
Sejak awal, Kepulauan Maluku sudah beraneka warna. Dua suku asli, Alune dan Wemale, menurunkan suku Akifuru, Togitil, Furu Aru, Ternate, Seram, Buru, Takabu, Tobelo, Banda, Rana, dan Moa. Dari keragaman inilah nama Maluku berasal. Para saudagar Arab—yang ramai singgah sejak abad ke-13—menjuluki kepulauan rempah ini sebagai Jazirah Al-Muluk, negeri banyak raja. Dalam perjalanannya, banyak raja di kawasan Maluku yang terpikat pada ajaran Islam, sehingga muncul kerajaan Islam yang menonjol: Bacan, Jailolo, Ternate, dan Tidore.
Memasuki abad ke-16, ajaran Nasrani masuk ke Maluku bersama dengan masuknya Portugis dan Spanyol. Seabad kemudian, Belanda mendirikan kongsi dagang Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) dan mencengkeramkan kukunya di negeri kaya rempah-rempah ini. Sejak saat itulah agama Kristen Protestan menyebar luas, terutama di wilayah selatan. Di bagian utara, karena pengaruh kuat Kerajaan Ternate, penduduknya masih banyak yang memeluk Islam. Gambaran lebih jelas terjadi di Pulau Ambon: bagian utara—disebut Jazirah Leihitu—dihuni mayoritas warga muslim, sedangkan bagian selatan—dinamai Jazirah Leitimur—dihuni mayoritas penduduk Kristen.
Sejalan dengan pendudukan Belanda, polarisasi masyarakat Maluku terbentuk. Penduduk yang beragama Kristen cenderung bekerja di lingkungan ambtenaar dan militer. Sedangkan penduduk yang muslim kurang suka bekerja sama dengan Belanda, yang dianggap sebagai orang kafir. Warga muslim lebih memilih bekerja di bidang pertanian dan perdagangan, bersama dengan pendatang dari Bugis, Makasar, Jawa, Cina, dan Arab. Benih konflik pun mulai ditabung. Perseteruan antara dua kutub selalu timbul tenggelam. Adalah tugas regent (pejabat pemerintah Belanda) dan kepala suku (soa) untuk meredam konflik antara penganut dua agama.
Namun, itu bukan berarti benih pertikaian sudah musnah. Setelah merdeka, konflik tetap muncul. Di pusat kota Ambon, perkampungan penduduk muslim dan Kristen tersekat dengan batas yang tegas. (Lihat infografik dan Peta Kota Ambon.) Hanya sedikit perkampungan yang dihuni warga Kristen dan Islam secara berdampingan. Dalam pergaulan sehari-hari, ketegangan juga terasa. "Sejak kecil, saya menyaksikan sesama orang Maluku saling memandang rendah pemeluk agama lain," kata Tamrin Tamagola, sosiolog asli Ambon yang tinggal di Jakarta.
Sampai kini, pengutuban masih terjadi. Bahkan situasi diperparah dengan adanya praktek kolusi dan nepotisme para pejabat. "Kalau gubernurnya Kristen, posisi strategis ditempati kerabat dekatnya yang juga Kristen," kata Tamrin kepada Hardy Hermawan dari TEMPO. Konflik makin menjadi saat Kolonel Dicky Wattimena menjabat Wali Kota Ambon, 1985-1991. Dengan pendekatan khas militer, Dicky menertibkan kawasan perdagangan yang didominasi pendatang muslim dari Buton, Bugis, dan Makasar. "Pukul, injak, dan hantam menjadi hal yang biasa bagi pedagang muslim," kata Dino Chresbon, tokoh pemuda Ambon yang rajin melakukan kontak telepon dengan para petinggi di sana. Sejak saat itulah muncul istilah BBM (Bugis, Buton, dan Makasar) yang memperuncing kutub pendatang dan penduduk asli.
Pada 1992, Mohamad Akib Latuconsina terpilih sebagai gubernur. Peta politik lokal pun berganti. Berbagai posisi penting yang tadinya didominasi warga Kristen—bermarga Tutupoli, Manuhutu, Wattimena, dan Talaut—lalu ditempati pejabat muslim yang bermarga Tuasikal, Latuconsina, dan Marasabessy. Pola ini dilanjutkan oleh gubernur pengganti Akib, Soleh Latuconsina. Malah ada komunitas penduduk muslim dari Desa Ori, Pelau, dan Kaliolo (populer dengan istilah Opek) yang sebagian besar bergelar sarjana dan menempati posisi penting di pemerintahan.
Tak dapat diingkari, bergesernya peta politik lokal ini berandil besar memperparah situasi. Maklum, bagi warga Kristen, jabatan birokrat adalah kehormatan marga yang dipegang sejak zaman pendudukan Belanda. Alhasil, bentrokan antarpemuda makin sering terjadi. Kelompok Coker (Cowok Kristen), misalnya, berhadapan dengan kelompok pemuda Islam dari Kampung Soabali, Waihaong, atau Waringin.
Kecemburuan marga yang dipadu dengan sentimen antar-penganut agama membuat pertikaian geng pemuda ini jadi seru. Sebagaimana yang terjadi di kawasan Manggarai, Jakarta, bentrokan di sini dilengkapi dengan adu senjata. Panah, parang, senapan, sampai bom molotov yang diramu sendiri dari potasium sulfat, pupuk KCl, dan solar menjadi senjata yang lazim. Dengan serem-nya persenjataan, "Korban meninggal juga biasa terjadi," kata Dino.
Nah, dengan situasi seperti ini, Ambon siap meledak setiap saat. Apalagi bila ditambah bahan bakar. Konon, seusai tragedi Ketapang, Jakarta, 9 Desember 1998, ratusan "preman" asli Ambon di Jakarta dipulangkan kembali ke Ambon. Memang, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah soal ini. Tapi, Des Alwi, tokoh masyarakat Banda, yang datang ke Ambon bulan lalu, menjumpai beberapa pentolan preman Ambon yang biasa mangkal di Ketapang. "Jumlahnya sekitar seratus orang," kata Des, anggota tim khusus yang dikirim Presiden Habibie ke Ambon.
Des punya temuan menarik. Kristian Tutuarima dan Heldi Riupassa, dua orang yang termasuk dalam daftar resmi preman kasus Ketapang, ditemukan tewas dalam kerusuhan di Ambon. Dengan motif uang dan harta, para preman ini menambah rumit persoalan Ambon. Mereka memalak warga etnis Cina pemilik toko yang ingin mengamankan tokonya. "Kalau tidak diberi, 'harimau liar' yang tak punya bos ini dengan gampang membuat rusuh dan membakar toko-toko," kata Des kepada TEMPO, "Banyak toko milik warga keturunan yang selamat karena sudah membayar mereka."
Sialnya, ternyata yang mengail di air keruh tak hanya kelompok preman, tapi juga oknum tentara ABRI dan birokrat. Tim investigasi yang dikirim Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menemukan beberapa fakta yang memprihatinkan ini. Misalnya, untuk mengawal penduduk yang akan mengungsi, aparat keamanan minta upah Rp 100 ribu. "Untuk mengawal ke bandara, harus tawar-menawar uang jasa Rp 200 ribu," kata Bambang Ekalaya, anggota tim investigasi Kontras. Akibatnya, penduduk tak percaya dan bersikap sinis terhadap kehadiran militer. Itu ditambah lagi dengan sikap mereka yang diragukan netralitasnya oleh pihak-pihak yang berseteru.
Begitulah, kecemburuan ekonomi dan status sosial antara pendatang dan penduduk asli—yang kebetulan dilengkapi dengan identitas Islam dan Kristen—bergabung dengan berbagai bahan bakar. Ada pertikaian antargeng, preman yang bagai harimau liar, serta aparat keamanan yang justru menggali untung, susah dikontrol, dan cenderung memihak, yang menjadi makin komplet dengan riuhnya pemberitaan yang simpang-siur. Gabungan kesemua faktor itu—lebih-lebih kalau memang betul ada perang intelijen yang dikendalikan Jakarta—sungguh berakibat dahsyat. Dan Ambon pun menangis.
Mardiyah Chamim, Ardi Bramantyo, Wenseslaus Manggut, Setiyardi
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini