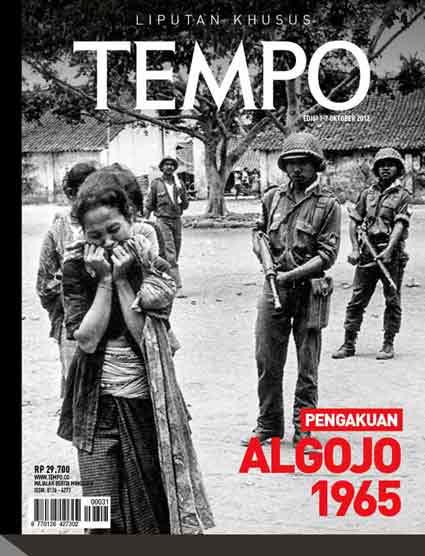Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Suatu pagi pada September 1971, C.H. Sumarmiyati diperintahkan berkemas. Ia melihat rekan-rekannya, 30-an tahanan politik perempuan penghuni penjara Wirogunan, Yogyakarta, juga diminta melakukan hal sama. Semua tanpa penjelasan. Menjelang tengah hari, mereka diangkut dengan truk.
"Ternyata kami dibawa ke Bulu, Semarang, untuk transit sebelum dibawa ke Plantungan," kata Sumarmiyati kepada Tempo di Yogyakarta, Kamis dua pekan lalu.
Sepanjang tiga jam perjalanan, tutur Mamik, begitu ia dipanggil, penumpang bak truk berusaha ceria. Semua bernyanyi, tapi menghindari lagu-lagu yang mengundang kesedihan. Mereka antara lain melantunkan Di Timur Matahari. Dua pekan di Bulu, Mamik dan kawan-kawan kembali diperintahkan berkemas.
Mereka diangkut ke Plantungan, Kendal, sekitar 70 kilometer dari Semarang. Mereka menuju "Tempat Pemanfaatan Sementara Tahanan G-30-S/PKI Golongan B Wanita". Mantan aktivis Ikatan Persatuan Pelajar Indonesia itu menuturkan, tempat tahanan tersebut berupa bangunan kosong yang ditumbuhi semak belukar. Tidak ada lampu. "Kami diminta membersihkan semuanya, ngepel, pasang lampu, nyapu, cabut rumput," ujar Mamik.
Tak sedikit tahanan disengat kalajengking. Ular juga banyak ditemukan. Namun ia mengatakan bukan hal itu yang dikeluhkan para tahanan. "Yang kami pikirkan cuma satu: sampai kapan kami di sana."
Tahanan "Golongan B" adalah mereka yang dituduh "nyata-nyata terlibat tidak secara langsung" G-30-S. "Tempat Pemanfaatan Sementara" Plantungan merupakan bekas rumah sakit militer yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Bangunan itu kemudian dijadikan rumah sakit pengidap lepra, yang ditutup pada 1960.
Kompleks itu berada di lembah Lampir, diapit Gunung Perahu, Gunung Butak, dan Kamulan, dataran tinggi yang membentang di selatan Kendal. Kamp di sana biasa disebut kompleks "inrehab", berdampingan dengan rumah tahanan anak negara yang hingga kini masih dipakai. Dua area ini dipisahkan Sungai Lampir. Adapun blok-blok kamp telah runtuh, diterjang banjir bandang 12 tahun silam. Tak ada yang tersisa.
Pada Juni 1971, kamp Plantungan dibentuk untuk "pusat rehabilitasi" tahanan politik dari berbagai kota di Jawa. Sebab, puluhan ribu orang berjejalan menjadi tahanan politik setelah peristiwa 30 September 1965. Amurwani Dwi Lestariningsih, Kepala Subdirektorat Pemahaman Sejarah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala serta penulis buku Gerwani: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan, menyebutkan pada 1968 tercatat 63.894 orang menjadi tahanan politik. Jumlah itu diperkirakan meningkat hingga 30 persen pada tahun-tahun berikutnya.
Pada 22 Maret 1971, Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban mengeluarkan surat perintah tentang pemindahan 500 tahanan politik B wanita di Jawa ke Plantungan. Tapi jumlahnya terus menggelembung. Dilam, mantan pembina kerohanian Katolik kamp Plantungan, mengatakan, pada awal dia bertugas, Mei 1974, kamp itu dihuni 870 tahanan.
Banyak tokoh penting menghuni kamp itu, baik aktivis Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) maupun organisasi lain yang dinyatakan sebagai onderbouw Partai Komunis Indonesia. Misalnya dokter Sumiyarsi Siwirini, aktivis Himpunan Sarjana Indonesia, yang dicap militer sebagai "dokter Lubang Buaya". Ada juga Siti Suratih, yang bekerja sebagai bidan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto. Ia istri anggota Politbiro PKI, Oloan Hutapea, yang ditembak mati di Blitar pada 1968. Juga ada Mia Bustam, istri pelukis S. Sudjojono.
Para tahanan sebelumnya menghuni beberapa lokasi interogasi dan penahanan. Misalnya, Sumiyarsi pernah ditempatkan di Markas Kepolisian Bandung Seksi VIII; sel di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta; Rumah Tahanan Pesing; Satgas Kalong Gunung Sahari; Lidikus Lapangan Banteng; juga penjara perempuan Bukit Duri.
Awalnya, para tahanan politik itu tak bersentuhan dengan penduduk sekitar. Tentara menjaga ketat mereka. "Masyarakat juga telah diindoktrinasi: anggota Gerwani adalah istri para anggota PKI yang jahat," ujar Slamet Shabu, 68 tahun, sesepuh Desa Pesanggrahan, di sekitar bekas kamp.
Meski Plantungan dianggap tidak nyaman, para tahanan mengatakan lebih menyenangkan berada di sana. Tempat-tempat tahanan lain dinilai menyeramkan. Dalam buku Bertahan Hidup di Gulag Indonesia, Carmel Budiardjo mengisahkan, tahanan politik di Bukit Duri berbisik-bisik mengenai tempat pembuangan terakhir. "Inilah penyelesaian final. Dicampakkan di tempat yang jauh dari keluarga dan sahabat-sahabat untuk selama-lamanya sejauh kita memperkirakan," ia menulis.
Di Plantungan, para tahanan menemukan kehidupan dan lokasi baru yang tak terlalu seram—seperti yang sebelumnya mereka bayangkan. Ada delapan blok besar di kompleks yang hanya dipagari kawat berduri. Tak ada sel tempat tahanan berdesak-desakan di dalamnya. "Kami tidak lagi terkungkung di sel," kata Pujiati, 87 tahun, mantan aktivis Serikat Buruh Unilever yang sebelumnya mendekam enam tahun di Bukit Duri. Tahanan sesekali dibolehkan keluar dari kompleks dengan pengawalan.
Di sana, kata dia, tak ada siksaan fisik walau tahanan tetap menanggung beban psikologis dan menerima pelecehan seksual. Ia menganggap kadar penderitaan di Plantungan jauh berbeda dibandingkan dengan saat ia diinterogasi dan ditahan di CPM dan penjara Wirogunan. Di dua tempat itu, pada saat interogasi, ia disiksa, dilecehkan secara seksual, dan diperlakukan keras.
Tetap saja, sesekali ada kejadian yang membuat tahanan tertekan. Misalnya, Mamik menyebutkan, tahanan asal Solo bernama Sumiyatun yang gila karena ditangkap hanya sebulan setelah menikah. Ada juga dua tahanan yang hamil oleh penjaga dari militer. Dilam membenarkan informasi ini. "Dipaksa atau suka sama suka, saya tidak tahu," ujarnya.
Para tahanan diberi pilihan kegiatan. Ada yang bercocok tanam, beternak, atau membuat kerajinan seperti menyulam. Dilam menyebutkan ada tahanan yang dipekerjakan di rumah-rumah dinas petugas kamp dan lembaga pemasyarakatan. "Tapi dipilih yang lolos evaluasi," ujarnya.
Setiap Kamis, tahanan menerima pelajaran agama. Sabtu merupakan hari indoktrinasi yang disebut "santi aji". Para tahanan diminta mempelajari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta pelajaran ilmu politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
Hubungan dengan masyarakat sekitar kian lama kian cair. Warga kerap memanfaatkan klinik di kamp yang dikelola dokter, bidan, atau perawat yang merupakan tahanan. Tak jarang merekalah yang mendatangi pasien di desa dengan pengawalan tentara. "Persalinan tiga dari enam anak kami dibantu bidan dari tapol," ujar Siti Chamidah, istri Slamet.
Selain pelayanannya sopan dan bersahabat, menurut Siti Chamidah, berobat ke klinik kamp "inrehab" dekat dan murah. Sebagai perbandingan, sementara biaya persalinan di puskesmas saat itu Rp 1.000, di klinik "inrehab" cuma Rp 100. Menurut Dilam, klinik di kamp menyingkirkan rumah sakit. "Sampai mobil-mobil, truk, bawa rombongan," tuturnya.
Hubungan baik terus terjalin hingga kamp kosong. Setelah didesak Palang Merah Internasional agar tahanan politik dikembalikan ke masyarakat pada 1975, pemerintah mulai membebaskan mereka. Dalam bukunya, Amurwani menyatakan 45 tahanan yang digolongkan die hard—berideologi komunis kuat—direlokasi ke "inrehab" Bulu, Semarang, pada 1976. Di antaranya dokter Sumiyarsi dan Mia Bustam, juga wartawan Istana, Roswati. Tahanan lain meninggalkan Plantungan pada 1978-1979.
Sebagian mantan tahanan masih menjalin hubungan kekeluargaan dengan penduduk di sekitar bekas kamp. Bidan Mujiati, misalnya, dua kali berkunjung ke rumah Slamet, termasuk kunjungannya setahun lalu. "Dia mengaku kangen dan napak tilas ke Plantungan," tutur Slamet. Dilam, yang kini tinggal di Playen, Gunungkidul, juga beberapa kali disambangi mantan tahanan politik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo