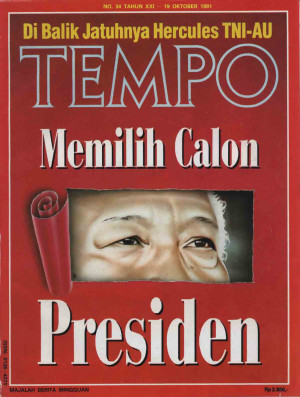Islam di Tepi Huangho Pertengahan September lalu, sebuah misi muhibah umat Islam Indonesia berkunjung ke Cina. Antara lain mereka mengunjungi Provinsi Ningxia, yang mayoritasnya Islam. Ternyata, Islam masih merayap di Cina. Banyak hambatan masih harus diatasi oleh Asosiasi Islam se-Cina, antara lain untuk mendapatkan kembali masjid-masjid yang disita pada masa Revolusi Kebudayaan. Wartawan TEMPO Yulizar Kasiri menyertai misi muhibah itu. Ia melaporkan bahwa umat muslim di Cina umumnya sudah tua. Generasi mudanya masih sangat sedikit. SABTU sore, pertengahan September lalu, suasana sepi di Masjid Najiahu berubah menjadi meriah. Dari luar terdengar tepuk tangan, berulang-ulang, dari ratusan jemaah di halaman dalam masjid yang sudah berusia sekitar lima ratus tahun itu. Terakhir ditutup dengan takbir Allahu Akbar, yang bergema tiga kali. Najiahu, sebuah desa kecil di Provinsi Ningxia, provinsi otonom di barat laut Republik Rakyat Cina yang mayoritas warganya beragama Islam. Hari itu desa kecil 30 km dari Yinchuan, ibu kota Ningxia, menerima kunjungan yang termasuk jarang. Satu misi muhibah umat Islam Indonesia menyempatkan terbang dari Beijing ke Najiahu. Di desa inilah monumen Islam tertua di provinsi ini masih terpelihara dengan baik, yakni Masjid Najiahu itu. Sebagaimana umumnya masjid di Cina, dari pekarangan luar Masjid Najiahu, kegiatan di dalam masjid tak dapat diikuti. Orang hanya dapat mendengar keramaian tepuk tangan. Soalnya, masjid dikelilingi tembok tinggi, yang merupakan ciri khas masjid-masjid di Cina. Hanya dengan melewati pintu gerbang besar, yang tak selalu dibuka, orang dapat sampai ke dalam dan menyaksikan yang sedang berlangsung di situ. Orang-orang itu bertepuk tangan menyambut khotbah seorang kakek bersarung, berpeci hitam, berselempang putih. Sebuah sambutan yang tidak spontan karena jemaah menunggu dahulu terjemahan khotbah itu ke dalam bahasa Cina. Khotbah sang kakek memang tidak dalam bahasa Cina, melainkan Indonesia. Bagi umat Islam Indonesia, khatib itu tak asing lagi: K.H. Syamsuri Baidhawi dari Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Kiai yang juga anggota DPR Republik Indonesia itu memang salah satu dari rombongan muhibah umat Islam Indonesia ke Cina. Di belakang kakek tersebut, tampak berdiri Dr. Amien Rais. Ini juga bukan warga Ningxia, atau warga negara Cina keturunan Turki, tapi seorang Indonesia, Wakil Ketua Muhammadiyah Pusat, anggota misi muhibah dari Indonesia itu juga. Di antara ke-13 anggota rombongan dari Indonesia itu, yang juga ikut bertepuk, ada yang nyeletuk, "Wah, rupanya Kiai sudah mulai kampanye." Celetukan itu tentu bergurau. Kiai Syamsuri tak sedang menganjurkan jemaah agar mencoblos PPP, nanti 9 Juni 1992, hari pemilu Indonesia. Umat di Masjid Najiahu tentu akan bertanya-tanya benda apakah PPP itu. Yang dikhotbahkan kiai Tebuireng ini adalah soal umat Islam yang mesti bangkit dan mengembangkan diri sendiri. Satu anjuran yang tidak istimewa, tapi di Najiahu khotbah terdengar simpatik. Masyarakat muslim Najiahu khususnya, dan di Provinsi Ningxia umumnya, sebagian besar adalah petani yang tak begitu berpunya. Minat memperdalam agama tampaknya kurang. Ini tercermin dari jumlah murid sekolah agama di Ningxia yang hanya 5.000 siswa, atau 0,3% dari 1,5 juta umat Islam Ningxia. Perbandingan jumlah masjid dan umat, dibandingkan dengan Indonesia, di provinsi mayoritas Islam ini pun terasa kecil. Kini di Ningxia ada sekitar 2.000 masjid, atau satu masjid untuk 750 umat Dari segi penyebarannya, juga termasuk jarang. Provinsi ini luasnya 66.400 km2, lebih kecil daripada Jawa Barat digabungkan dengan Jawa Tengah. Dengan luas seperti itu, praktis hanya satu masjid untuk 30 km2 (dengan perbandingan ini, di Jakarta hanya akan ada 20-an masjid). Padahal, Islam sudah masuk ke Ningxia dari Persia pada abad ke-13, pada masa dinasti Yuan. Bisa jadi, ini akibat masa pemerintahan Mao Zedong, yang menindas agama. Baru pada 1979, ketika Deng Xiaoping mengendurkan kekangan terhadap kegiatan agama, masjid-masjid yang pada zaman Mao disita dikembalikan pada umat. Pengembalian itu pun dengan melihat kondisi. Bila dianggap umat sekitar masjid adalah muslim radikal, masjid tak segera dikembalikan. Ditakutkan tempat ibadah muslim ini akan menjadi pusat kegiatan yang membahayakan pemerintah Beijing. Ini terjadi di Provinsi Xinjiang, provinsi otonom juga, yang mayoritas warganya muslim. Di Ningxia, tampaknya umat Islamnya mampu bersikap kompromistis. Setidaknya, tak terdengar pemerintah Beijing menghalangi berfungsi kembalinya masjid. Ada yang mengatakan bahwa karena sikap kompromistis itulah Islam di Ningxia tak pesat berkembang, bila dibandingkan dengan Islam di Xinjiang. Beberapa tahun lalu, ketika terbit sebuah buku yang dianggap menghina umat Islam di Cina, hanya di Xinjiang umat Islam turun ke jalan, memprotes buku itu. Namun, Anda jangan salah tangkap bila orang Ningxia yang disebut suku Hui itu meladeni Anda ketika Anda berwudu. Itu bukan cerminan sikap lemah mereka. Coba lihat di Masjid Najiahu itu. Di ruangan bersuci, yang letaknya terpisah di kiri masjid, para tamu dilayani bagaikan raja sewaktu berwudu. Di situ tersedia keran air, tapi orang berwudu tidak langsung menggunakan air keran tersebut. Para tamu dipersilakan duduk di bangku kecil, sejenis bangku yang sering digunakan orang di dapur, lalu seseorang menyodorkan sebuah cerek dari kuningan yang berisi air. Dengan air di cerek itulah orang berwudu. Setelah berwudu, para tamu disodori dua handuk kecil yang dihubungkan dengan peniti. Handuk ini untuk mengelap wajah, tangan, dan kaki yang terkena air. Hal seperti ini ternyata tidak hanya untuk tamu dari Indonesia, dan tak hanya terjadi di Ningxia. Hampir setiap masjid di Cina menyediakan pelayan di tempat bersuci. Untuk imbalannya, biasanya, di pintu keluar ruang untuk berwudu disediakan kotak zakat. Para jemaah dipersilakan mengisinya sehabis berwudu, seikhlasnya. Umumnya, masjid di Cina bersuasana gelap karena lampu yang dipasang memiliki watt kecil. Dalam keyakinan orang sana, suasana gelap itu sengaja diciptakan untuk membangkitkan rasa khidmat dalam beribadat. Tidak jelas seberapa benar alasan itu. Apakah ini bukan karena listrik di Cina memang mahal. Di sejumlah kota di luar Beijing dan kota-kota zone industri, sama sekali tak ada penerangan jalan. Begitu lepas magrib, jalan-jalan gelap. Yang cepat tampak dari arsitektur masjid di Cina adalah meleburnya budaya setempat dengan agam pendatang ini. Masjid di Cina jarang yang meniru model Arab atau Persia, yang memiliki kubah setengah lingkaran. Arsitektur masjid di Cina umumnya bergaya khas Cina, yang atapnya berbentuk atap kelenteng. Hal itu tak lepas dari pengaruh kebudayaan Han, kaum pribumi Cina, yang sudah berakar di beberapa tempat. Sebagai akibatnya, kaum muslim di Ningxia, yakni orang Hui, tidak dapat menolak pengaruh itu. Meleburnya budaya lokal ke dalam budaya Islam Tiongkok mungkin dapat menjadijadi bukti betapa kuatnya sudah budaya Cina. Hingga terjadi -- pinjam istilah Abdurrahman Wahid, Ketua PBNU -- "pribumisasi Islam". Misalnya saja, di beberapa masjid di Beijing, sembahyang Jumat didahului dengan pembakaran hio, yang lalu ditancapkan di sudut-sudut masjid. Keunikan lain dari masjid-masjid di negeri-negeri ini adalah arah kiblatnya yang menghadap ke timur. Ini dapat diduga sebabnya. Arah itu ditiru dari masjid pertama di Cina, yang terletak di Guangzhou. Masjid itu, konon, dibangun pada waktu Nabi Muhammad masih hidup. Menurut H. Ibrahim Tien Ying Ma, penulis buku Perkembangan Islam di Tiongkok, ini menunjukkan bahwa orang-orang Arab sudah mengenal bahwa bumi ini bulat. Tak terjadinya konflik yang berarti, antara masjid di Ningxia dan pemerintah Beijing, mungkin juga karena sejarah. Orang Persia yang masuk ke Ningxia pada abad ke-13 itu umumnya pria dan datang tanpa keluarga. Maka, terjadilah asimilasi dengan wanita suku Han, yakni penduduk Cina asli. Dari situ lahirlah suku Hui, yang kini tersebar di sepuluh provinsi di Cina. Sementara itu, suku Uighur di Xinjiang, yang keturunan Turki itu, tak berasimilasi dengan suku Han. Permusuhan antara suku Han dan Uighur di Xinjiang boleh dikata terjadi tiap hari. Barangkali masyarakat muslim di Ningxia dapat dijadikan cermin mengapa Islam di Cina tak begitu berkembang. Padahal, jauh sebelum agama ini masuk ke Indonesia, sudah ada sejumlah orang Cina memeluk Islam. Kini, jumlah umat Islam di seluruh RRC hanyalah sekitar 17,6 juta, atau sekitar satu setengah persen dari seluruh penduduk RRC yang sekitar 1,1 milyar itu. Menurut Haji Nu'man Ma Xian, Wakil Ketua Asosiasi Islam Cina, mengapa Islam tak berkembang, antara lain karena belum ada kekuatan untuk mendukung perkembangan Islam. Berabad-abad usia dinastidinasti di Cina, tak satu pun pernah berdiri kerajaan Islam. Sebagai hasil asimilasi antara suku Han dan orang Persia, orang Hui memiliki wajah sedikit berbeda dengan orang Han. Mata mereka tidak terlalu sipit dan memiliki batang hidung yang cukup tinggi. Namun, yang menjadi ciri khas mereka seperti yang terlihat di jalan-jalan di Kota Yinchuan, kota yang berlambangkan burung foniks, adalah peci kain berwarna putih yang mereka pakai. Lelaki Hui yang sudah berusia di atas lima puluh tahun boleh dipastikan memelihara jenggot. Tak jelas asal mula tradisi ini. Mungkin mereka meniru lelaki Persia yang memang bercambang itu. Sebelum Anda salah tangkap, peci-peci putih orang Hui bukanlah peci haji seperti di Indonesia. Hanya sebagian kecil orang Hui yang sudah pergi haji. Jadi, peci itu sekadar tanda bahwa mereka orang Hui. Syahdan, Mao Zedong, pemimpin Cina itu, sewaktu marah kepada kaum ini sempat mengatakan, "Si pembalut kepala itu usir saja ke gunung." Umumnya, bagi orang-orang Hui yang sudah menunaikan ibadah haji ke Mekah, pada kartu namanya dicantumkan gelar "haji"-nya. Ini persis seperti yang terjadi di Indonesia atau dunia Islam lainnya. Yang tak seperti di Indonesia, mereka ini juga punya nama Islam, di samping nama asli. Misalnya, Nu'man Ma Xian, Wakil Ketua Asosiasi Islam se-Cina itu. Kebiasaan memberi nama pada suku Hui itu tentulah berkaitan dengan sejarah mereka, yakni sejarah lahirnya Hui, yang merupakan hasil asimilasi antara suku Han dan orang Persia. Pada suku Uighur di Xinjiang, meski ini termasuk provinsi RRC juga, tak ada nama-nama Cina Han. Pada suku Uighur, nama-nama tetap seperti nama-nama Arab atau Turki. Ningxia beruntung karena Huang Ho, Sungai Kuning, lewat di wilayahnya. Tanpa sungai ini seluruh daerah Ningxia pasti sangat gersang. Lihat saja keadaan tanah yang letaknya jauh dari Huang Ho. Misalnya, dekat pelabuhan udara militer, sekitar 20 kilometer dari Yinchuan. Di sekitar pelabuhan udara, yang sementara ini juga digunakan untuk pendaratan dan pemberangkatan pesawat sipil, tanahnya berbatu-batu dan sulit menyerap air. Tidak tampak penduduk tinggal di tempat itu. Satu-satunya bangunan di kawasan itu adalah kantor militer. Bila hujan turun, air tergenang atau mengalir ke tempat yang lebih rendah sambil membawa pasir yang bercampur dengan batu. Setelah kering meninggalkan bekas seolah-olah tanah di situ habis dikeruk. Jangankan pohon-pohon, semak-semak tak kelihatan di sekitar daerah itu. Yang ada hanya pohon yangshu, sejenis pohon yang cocok hidup pada iklim daerah utara Cina, yang tumbuh di pinggir jalan. Pohon itu, yang berwarna keabu-abuan, tumbuhnya lurus-lurus dan cukup tinggi. Namun, di daerah sekitar Sungai Kuning, Ningxia amatlah subur. Menurut sejarah, rakyat Ningxia sudah mengenal irigasi sejak ribuan tahun yang lalu. Ada bekas-bekas irigasi yang dibangun pada masa Dinasti Qin, sekitar 220 sebelum Masehi. Bila kini tinggal bekasnya dan tentu saja tak berfungsi, itu akibat perang dan kekacauan yang lama melanda Cina. Pembangunan serius dimulai pada 1958, ketika sebuah bendungan dari beton bertulang sepanjang 660 meter di Qingtong Gorge, sekitar 30 kilometer dari Yinchuan, dibuat. Dibutuhkan sepuluh tahun sebelum Qingtong Gorge benar-benar bisa digunakan. Bendungan itu tidak hanya berfungsi untuk irigasi, melainkan juga berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik. Singkat kata, usaha pemerintah Ningxia membuat daerah gurun menjadi subur cukup berhasil. Musim kemarau, yang baru berakhir, ternyata tidak mempengaruhi kesuburan daerah pertanian rakyat. Sejauh mata memandang, sepanjang jalan menuju Kota Wu Zhong, salah satu ibu kota kabupaten di Ningxia, sekitar 40 kilometer dari Yinchuan, yang tampak hanyalah hamparan hijau padi. Sekali-sekali diselingi pepohonan. Menurut seorang karyawan pemerintah daerah setempat, daerah Ningxia pada saat ini merupakan lumbung pangan bagi provinsi lain di sekitarnya. Pada 1989, hasil panen padi daerah ini mencapai 1,5 juta ton. Angka ini memang jauh melampaui panen pada 1957 sekitar 500 ribu ton. Itu menunjukkan bahwa petani di daerah yang mayoritas Hui itu juga ikut makmur. Lihat saja kehidupan Muhammad Iskak Ma Lichen, seorang petani di desa yang terletak lebih kurang 20 kilometer dari Yinchuan. Sejak adanya perubahan kebijaksanaan di bidang ekonomi pada awal 1980-an, ia beruntung mendapat tanah seluas 2,5 hektare. Pembagian itu, kata Ma Lichen, dihitung berdasarkan jumlah anggota keluarganya. Kesempatan itu tidak disia-siakan Ma Lichen dan keluarganya, dan ternyata ia cukup berhasil. Buktinya, hasil dari pertaniannya dalam setahun bisa menghidupi delapan anggota keluarganya untuk dua tahun. Dari dana yang berlebih itu, ia mengembangkan usaha lain, yakni rumah makan. Dari usahanya itu, Muhammad Iskak Ma Lichen dan keluarganya bisa menikmati sebuah rumah beton berbentuk segi empat dengan enam belas kamar. Kini tiga orang anaknya sudah menikah. Tinggal dua orang lagi yang masih duduk di bangku SMA dan SMP. Sebagai seorang muslim yang baik, Ma Lichen tak lupa mengeluarkan sebagian rezekinya yang ia terima ke masjid-masjid yang terdapat di lima desa itu. Itu terutama pada hari-hari besar Islam. "Saya juga harus membantu saudara-saudara saya yang tak mampu," kata Ma Lichen kepada tamu-tamunya. Barangkali inilah salah satu kunci tetap hidupnya masjid-masjid: di antara ribuan petani Hui yang kurang beruntung, ada Ma Lichen-Ma Lichen yang mampu menyumbang masjid. Kelangsungan hidup di masjid penting karena pendidikan agama tidak diberikan di sekolah. Generasi muda belajar tentang Islam di masjid-masjid, atau dari orangtua sendiri di rumah. Anak-anak Ma Lichen, umpamanya, semuanya memperdalam Islam di masjid, dengan guru imam masjid. Dari masjid itulah anak-anak Ma Lichen fasih membaca Quran. Adapun imam masjid biasanya berpendidikan di Beijing, atau perguruan lain di ibu kota Ningxia. Inilah salah satu tugas Asosiasi Islam se-Cina: merekrut pemuda muslim yang bersedia jadi imam masjid. Mereka akan mendapatkan beasiswa untuk menjadi siswa di madrasah di Beijing. Sesudah lulus, mereka akan dikembalikan ke kampung halaman masing-masing untuk tetap mempertahankan umat, dan syukur-syukur dakwah mereka bisa menambah jumlah umat Islam. Inilah cerita Wakil Ketua Asosiasi itu pada TEMPO beberapa waktu lalu. Yang belum lancar benar bagi umat Islam Cina adalah soal haji. Sejauh ini pemerintah Beijing masih membatasi jumlah calon haji dari Cina. Maka, Ma Lichen itu masih, misalnya, harus sabar menunggu hingga ia bisa berangkat. Ia sudah menyiapkan biaya jauh-jauh hari, tapi namanya yang sudah terdaftar belum juga disebut. Sejak Deng Xiaoping menjalankan modernisasi ekonomi, para petani semacam Ma Lichen memang cukup hidup layak karena mereka hanya diharuskan menyerahkan sepuluh persen hasil panennya ke pemerintah. Selebihnya bisa mereka jual ke pasar bebas, dengan harga pantas. Bisa jadi, juga karena faktor ekonomi ini masyarakat Hui di Ningxia boleh dikata aman dan damai. Petani kaya yang muslim itu, lewat masjid, membagi zakat untuk sesama petani muslim yang kurang beruntung hidupnya. Bahkan, Asosiasi Islam se-Cina, yang berkantor pusat di Beijing, antara lain memperoleh dana dari petani-petani yang cukup sukses ini. Namun, upaya itu belum sepenuhnya bisa melajukan perkembangan Islam. Sudah disebutkan bahwa hanya 0,3% (5.000 orang) dari seluruh orang Hui di Ningxia yang masuk sekolah agama, dan di tingkat akademi jumlah itu sangat merosot. Pada 1985, di Yinchuan berdiri Akademi Al Quran, atas bantuan Bank Pembangunan Islam di Arab Saudi. Sejak berdirinya sampai bulan lalu, sekolah yang bangunannya bergaya arsitektur Arab Modern itu tidak pernah memiliki mahasiswa lebih dari seratus orang. Sebagai akibatnya, suasana kompleks yang megah dan besar itu terasa kosong melompong. Hanya segelintir orang ada di tempat itu. Di sinilah keberhasilan rezim Mao dalam menghancurkan agama. Secara resmi agama dilarang di RRC. Namun, di provinsi yang telanjur mayoritasnya Islam, orang-orang tua tetap dibiarkan menjalankan praktek agamanya. Meskipun demikian generasi mudanya diindoktrinasi sedemikian rupa hingga mereka jauh dari agama. Maka, dalam waktu tertentu pemeluk agama pun merosot. Ini bisa dilihat, pada sembahyang Jumat di sejumlah masjid, sebagian besar sekali yang datang adalah orang-orang tua di atas 50 tahun. Malangnya, ketika Deng Xiaoping mulai mengendurkan pengekangan agama, ada daya tarik lain pula yang menyeret generasi muda dari keluarga muslim, yakni ekonomi. Jumlah pemuda yang bercita-cita menjadi profesional di luar agama jauh lebih besar daripada yang mau masuk sekolah agama. Inilah yang menjadi keprihatinan Haji Abdulrahim Amin, Wakil Ketua Asosiasi Islam se-Cina itu. Itu sebabnya pihak Asosiasi menyediakan beasiswa bagi mereka yang mau bersekolah agama. Usaha ini pun belum begitu menggembirakan. Kata Haji Abdulrahim, banyak yang menerima beasiswa hanya karena terpaksa, bukan karena niat menyebarluaskan atau mendalami agama. Di Masjid Nanguan di Yinchuan, masjid yang bergaya arsitektur Timur Tengah, umpamanya, misi muhibah Indonesia hanya menemukan tak lebih dari 10 anak muda yang giat di masjid. Seolah-olah umat Islam di kota ini tidak memiliki generasi pelanjut. Mungkin untuk meninggikan semangat anak-anak muda itu, seorang anggota misi muhibah Indonesia menghadiahkan sebuah tasbih kepada seorang anak yang paling muda di Masjid Nanguan itu. Sesungguhnya, baik Xinjiang maupun Ningxia, sebagai provinsi otonom, punya hak berhubungan langsung dengan luar negeri di bidang agama, budaya, ilmu, dan ekonomi. Bidang politik dan militer jelas tak dimungkinkan. Meski mayoritas pejabat provinsi otonom adalah orang setempat, misalnya di Ningxia itu, gubernurnya tetap saja kiriman dari Beijing. Tak heran selama lima tahun terakhir ini, sekitar 30 delegasi, di antaranya dari kalangan tokoh-tokoh agama, pejabat pemerintah, dan delegasi perdagangan dari negara-negara Arab, datang berkunjung ke negeri ini. Ini juga jadi faktor yang menyebabkan Islam bertahan di Ningxia. Itu juga yang menyebabkan masjid-masjid tetap bisa direnovasi bila rusak. Madrasah tetap terpelihara meski muridnya sedikit. Sebenarnya saja, pemerintah Beijing sendiri tentu juga berkepentingan memberikan citra bahwa RRC adalah negara yang menghormati warganya yang beragama Islam. Pada masa RRC membutuhkan modal untuk membangun ekonominya, negara-negara minyak di Timur Tengah tentulah menjadi salah satu sumber dana yang besar. Bila saja muncul citra bahwa Cina memusuhi Islam, ini bisa jadi salah satu penghalang bagi RRC memperoleh dana dari negara-negara Arab. Itulah kesempatan bagi Asosiasi Islam se-Cina untuk terus mengembangkan Islam. Bahwa pemerintah Beijing belum sepenuhnya rela Islam berkembang, pihak Asosiasi pun mafhum. Salah satu buktinya adalah, salah satu dari sekian program Asosiasi dalam mengembangkan Islam adalah memperjuangkan agar masjid-masjid yang pada zaman Revolusi Kebudayaan diambil alih Pengawal Merah dan dijadikan kantor, sekolah, atau pabrik dikembalikan sebagai masjid. Di Provinsi Xinjiang yang otonom itu, program ini terasa berat terlaksananya hingga, kabarnya, bentrokan antara pemuda muslim dan pihak keamanan sering terjadi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini