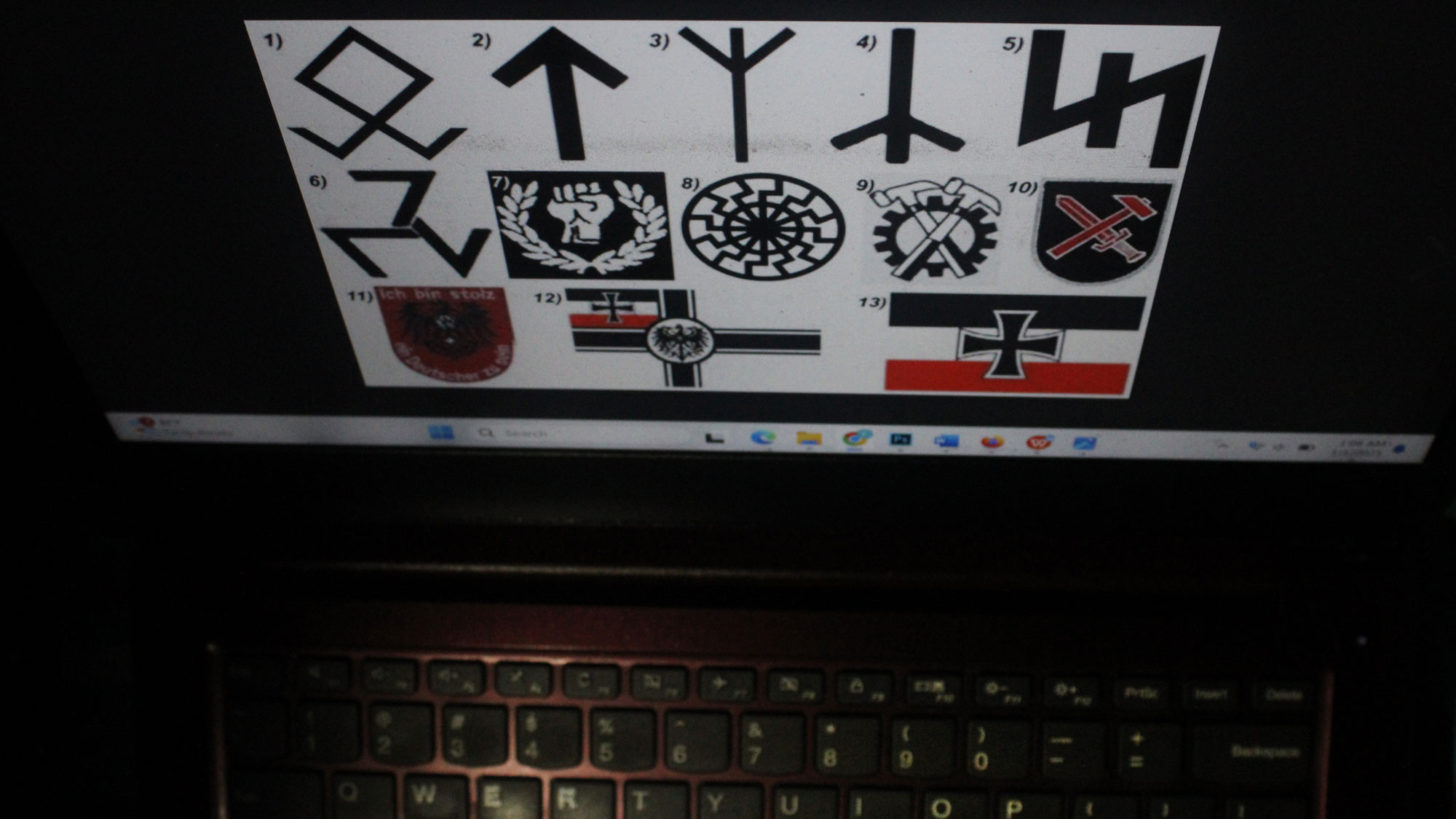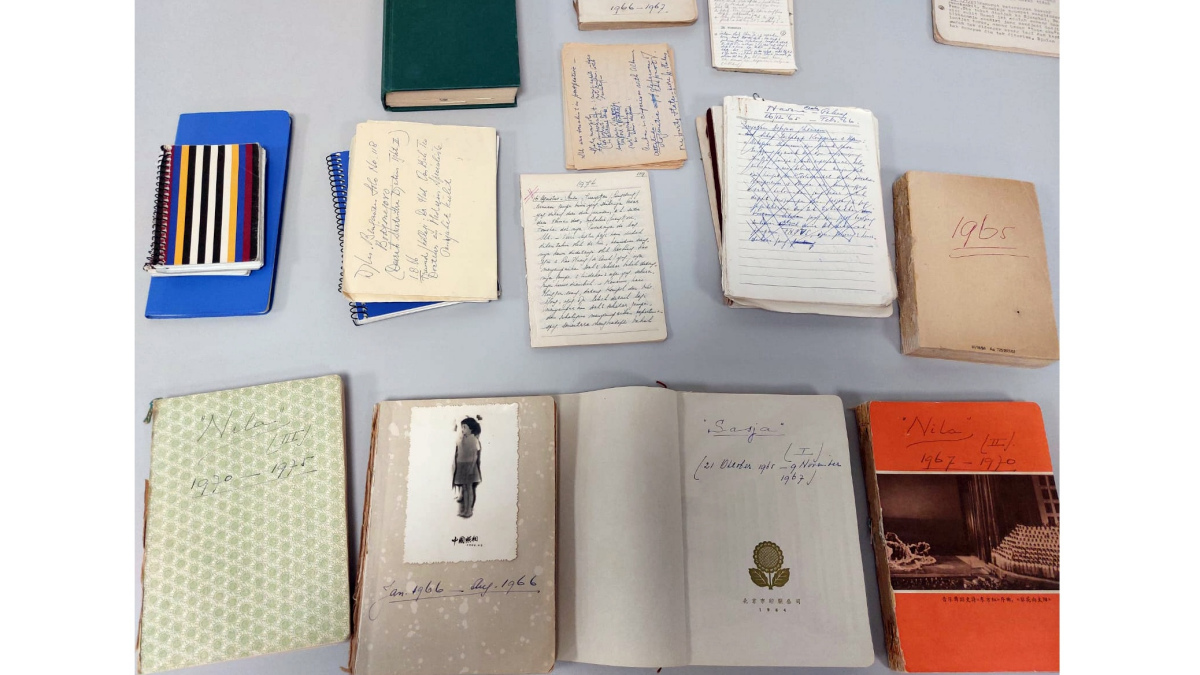Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di bawah pohon tanjung besar yang akarnya mencuat ke permukaan, tampak tumpukan batu andesit yang tak seragam bentuk dan ukurannya membentuk sebuah punden. Warga di sekitar Dusun Kajang, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, sekitar lima kilometer dari Kota Batu, Jawa Timur, mengenalinya sebagai Punden Mojorejo atau Punden Sangguran. Tepat di atas punden itulah seharusnya berdiri tegak sebuah prasasti yang disebut Prasasti Sangguran.
Hampir 1.087 tahun silam, persisnya pada Sabtu, 2 Agustus 928 Masehi, bertepatan dengan hari Warukung-Kaliwon, 14 paruh-terang, bulan Srawana, 850 Saka, sebuah peresmian tugu tapal batas dilaksanakan di Desa Sangguran, Jawa Timur.
Sebuah prasasti berupa balok batu berukuran tinggi 160 sentimeter, lebar 122 sentimeter, dan tebal 32,5 sentimeter diletakkan di atas punden itu. Prasasti tersebut berisi penetapan Desa Sangguran sebagai sebuah sima atau daerah perdikan. Prasasti itu juga menjelaskan perpindahan Kerajaan Mataram dari Medang di Jawa Tengah ke Tamwlang di Jawa Timur. Bagian bawah prasasti itu menampilkan kutukan-bagi siapa pun yang berani mencabut prasasti dari tempatnya.
Mulai baris ke-28 sampai ke-39, kutukan dalam bahasa Jawa kuno itu di antaranya berbunyi:
Demikian pula jika ada orang yang mencabut sang hyang watu sima, maka ia akan terkena karmanya, bunuhlah ia olehmu Hyang, ia harus dibunuh, agar tidak dapat kembali di belakang, agar tidak dapat melihat ke samping, dibenturkan dari depan, dari sisi kiri, pangkas mulutnya, belah kepalanya, sobek perutnya, renggut ususnya, keluarkan jeroannya, keduk hatinya, makan dagingnya, minum darahnya, lalu laksanakan (dan) akhirnya habiskanlah jiwanya.
Jika berjalan ke hutan akan dimakan harimau, akan dipatuk ular, (akan) diputar-putarkan oleh Dewamanyu, jika berjalan di tegalan akan disambar petir, disobek-sobek oleh raksasa, dimakan oleh Wunggal/wuil. Dengarkanlah olehmu para Hyang, (hyang) Kusika, Garga, Metri, Kurusya, Patanjala, penjaga mata angin di utara, penjaga mata angin di selatan, penjaga mata angin di barat dan timur, lemparkan ke angkasa, cabik-cabik sampai hancur oleh hyang semua, jatuhkan ke samudra luas, tenggelamkan di bendungan, tangkap oleh sang Kalamtryu (?), cabik-cabik oleh tangiran, (dan) disambar buaya.
Begitulah matinya orang yang jahat, pulangkan ke neraka, jatuhkan di neraka maharorawa. Digodok oleh pasukan Yama, dipukuli oleh sang Kingkara. Jika dilahirkan kembali (akan menjadi) hilang pikirannya. Begitulah nasibnya orang yang merusak sima di Sangguran.
Namun sudah lebih dari 200 tahun Prasasti Sangguran yang penuh kutukan itu berada di halaman belakang rumah keluarga Lord Minto VII di Hawick, Roxburghshire, Skotlandia. Rumah itu berjarak sekitar 650 meter dari kawasan padang golf yang luas dan dikelilingi perbukitan di perbatasan Inggris dan Skotlandia. Kondisi prasasti itu kini sangat memprihatinkan. Permukaannya tertutup lumut dan mengalami pelapukan karena harus menghadapi cuaca ekstrem Skotlandia tanpa pelindung dan perawatan sama sekali dari profesional.
Prasasti itu dapat sampai ke sana karena Letnan Gubernur Jenderal Jawa Sir Thomas Stamford Raffles. Saat berkuasa di sini, ia membawa prasasti tersebut dari Jawa Timur untuk dihadiahkan ke atasannya, Gubernur Jenderal Lord Minto I, yang bernama lengkap Sir Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound, di India. Maka Prasasti Sangguran dikenal juga dengan nama Batu Minto.
Pada Juni 1813, kapal Matilda yang membawa Batu Minto dari Surabaya melego jangkar di Pelabuhan Kolkata, India. Lord Minto sangat senang. Seperti terungkap dari suratnya kepada Raffles, ia menyebut prasasti itu pesaing alas patung Peter yang Agung di St Petersburg, Rusia. Begitu senangnya sampai ia menyuruh agar batu asal Jawa itu diletakkan di kampung halamannya, di puncak bukit Minto Craigs, di sebelah utara Sungai Tevoit, Skotlandia.
Namun sebuah tragedi terjadi. Lord Minto tak pernah bisa menyaksikan batu asal Sangguran itu di Skotlandia. Enam bulan setelah menerima batu itu, Lord Minto dicopot dari jabatannya sebagai gubernur jenderal, tanpa diketahui sebab-musababnya. Dia pulang ke Inggris dalam keadaan tidak sehat. Ia wafat di Stevenage pada 21 Juni 1814 dalam perjalanan menuju Skotlandia.
Raffles bernasib setali tiga uang. Setelah pemberlakuan Konvensi London, Agustus 1814, ia ditarik pulang ke Inggris dan digantikan John Fendall. Meski kembali ke Hindia Timur pada 1818 sebagai Gubernur Bengkulu, pada 1823 Raffles dipulangkan lagi. Ia meninggal sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-45, 5 Juli 1826. Sampai sekarang, posisi pasti makamnya di Hendon, Inggris, tidak pernah bisa ditentukan.
Hal serupa terjadi pada Bupati Malang yang bertanggung jawab atas pemindahan tugu tapal batas Desa Sangguran itu, Kiai Tumenggung Kartanegara alias Kiai Ranggalawe. Ia diyakini mulai memerintah pada 1770 dan wafat pada 1820. Namun memori penduduk terhadap Kiai Ranggalawe seperti terhapus. Terbukti, keberadaan situs makam sang Bupati tidak pernah diketahui.
Apakah kematian Lord Minto, Raffles, dan Bupati Malang itu ada kaitannya dengan kutukan tugu tapal batas Desa Sangguran tersebut?
Di lokasi situs Punden Sangguran (lebih-kurang 50 meter dari pinggir Jalan Alternatif Batu-Malang), kini berdiri pondok yang kayunya mulai lapuk. Menurut Dwi Cahyono, arkeolog dan dosen Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, pondok itu dibangun oleh komunitas penghayat kepercayaan saat kampanye pemilihan kepala daerah Kota Batu pada 2012. Mereka, kata Dwi, mengadakan nyadran dan ritual lain untuk menghormati Punden Sangguran atau Punden Mojorejo.
"Ada anggota parlemen Kota Batu yang rajin ke sana untuk bernazar," ujar Dwi ketika menemani Tempo mengunjungi Punden Mojorejo. Setahu Dwi, banyak juga orang dari luar Malang, seperti Surabaya, Kediri, dan Tulungagung, mendatangi Punden Mojorejo mencari berkat di situ. Mereka biasanya membawa sesajen. Maka Pemerintah Kota Batu memutuskan membuat larangan di papan pengumuman yang didirikan tepat di depan pondok. Inti larangan itu: siapa pun tidak boleh melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
"Punden ini mengarah ke timur, menghadap ke Gunung Wukir. Kalau dari posisi Gunung Wukir, Punden Mojorejo berada di sisi baratnya," kata Dwi, 53 tahun. Menurut dia, dalam Pararaton, yakni kitab yang berisi kisah raja-raja penguasa Pulau Jawa yang ditulis pada 1613 Masehi, Gunung Wukir disebut dengan nama Rabut Jalu, gunung suci tempat orang bersemadi.
Ahli epigrafi dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Hasan Djafar-yang menerjemahkan isi Prasasti Sangguran di atas-menjelaskan bahwa Desa Sangguran yang dijadikan sima adalah daerah suci yang tak boleh diganggu para patih, wahuta, dan petugas kerajaan, seperti petugas pemungut pajak.
Prasasti ini dibuat atas perintah Raja Mataram Sri Maharaja Rakai Pangkaja Dyah Wawa Sri Wijayalokanamottungga pada 850 Saka atau 928 Masehi. Ditulis dengan aksara Jawa kuno, bagian depan (recto) sebanyak 38 baris, bagian belakang (verso) 45 baris, dan samping (margin) kiri 15 baris. Bagian pembuka (manggala) ditulis dalam bahasa Sanskerta.
"Prasasti Sangguran sangat penting untuk merekonstruksi aspek masyarakat dan kebudayaan pada Kerajaan Mataram, sekitar awal abad ke-10," kata Hasan. Dalam sejarah Indonesia kuno, prasasti ini merupakan prasasti terakhir Kerajaan Mataram ketika pusat pemerintahan masih berkedudukan di Medang, Jawa Tengah-sebelum dipindahkan ke Tamwlang, Jawa Timur, oleh Sri Maharaja Rake Hino Dyah Sindok Sri Isanawikrama Dharmmotunggadewa. Prasasti ini juga menceritakan pergeseran kekuasaan di antara penguasa Kerajaan Mataram.
Bagi Dwi Cahyono, Prasasti Sangguran juga memuat pelbagai data lain yang, kendati fragmentaris, sangat penting. "Prasasti itu misalnya bisa sebagai sumber informasi untuk mengetahui sejarah alutsista (alat utama sistem persenjataan) kita di masa lalu." Prasasti Sangguran, menurut Dwi, menjadi satu-satunya prasasti di Pulau Jawa yang memberikan informasi adanya wilayah yang dihuni komunitas ahli pembuat logam. Dari prasasti itu didapat informasi bahwa Sangguran adalah desa yang dihuni para pandai besi. "Mereka dianggap berjasa karena telah membuatkan banyak persenjataan dan perkakas rumah tangga yang dibutuhkan kerajaan," ujar Dwi.
Dwi menduga ahli keris Mpu Gandring tinggal di Desa Sangguran. Ken Arok pun memesan keris kepada Mpu Gandring di Desa Sangguran. Berbekal keris itu, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan memperluas pengaruh Tumapel, yang saat itu dikuasai Kerajaan Kediri, sampai ia menghancurkan Kerajaan Kediri dan mendirikan Kerajaan Singosari. Tapi, jauh sebelum masa Ken Arok, Desa Sangguran, menurut Dwi, sudah dikenal sebagai desa pembuat senjata Kerajaan Mataram.
Maka prasasti itu, menurut para arkeolog, seharusnya dikembalikan ke Indonesia. Upaya pemulangan Batu Minto itu, kata Peter Carey, sejarawan asal Inggris, pernah digagas Nigel Bullough, Indonesianis asal Inggris yang memiliki nama Jawa "Hadi Sidomulyo". Menurut Carey, dia tahu bahwa Bullough melakukan negosiasi pemulangan Prasasti Sangguran sejak 2003.
"Jauh sebelum saya ke sini, Nigel Bullough sudah punya niat bernegosiasi dengan keluarga Lord Minto," ujar Carey kepada Tempo. Bullough, yang ditemui Tempo di Universitas Surabaya Training Center di Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, akhir Maret lalu, menolak memberikan komentar ihwal proses negosiasi untuk pengembalian Prasasti Sangguran dengan keluarga Lord Minto. "Case closed. Saya tidak mau bercerita apa pun soal Batu Minto," kata Bullough.
Ada nada kekecewaan dalam ekspresi Bullough. Dia sendiri pernah secara rinci membuat laporan mengenai proses negosiasi tim Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dengan Lord Minto VII. Laporan yang bersifat rahasia itu dikirimkan Bullough kepada Carey pada 2011 ketika ada rencana membuat acara peringatan 200 tahun Raffles. Laporan itu kemudian tersebar luas.
Dari laporan tersebut terungkap bahwa Bullough mengenal Lord Minto VII dan lantas mengirim surat elektronik yang menjelaskan betapa bernilainya obyek yang diwariskan pendahulunya itu dan memintanya memberikan pertimbangan yang serius atas masa depan benda tersebut. Dijelaskan dalam surat itu bahwa Batu Minto merupakan benda cagar budaya yang dipindahkan dari tempatnya di Indonesia lebih dari 200 tahun lalu. Kehilangan itu sangat disesalkan dan pengembaliannya begitu diharapkan.
Korespondensi berlanjut hingga membuahkan pertemuan. Tim arkeolog dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, yang terdiri atas Sekretaris Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala Sri Rahayu Budiarti, Direktur Peninggalan Sejarah dan Purbakala Soeroso, Kepala Balai Konservasi Peninggalan Borobudur Dukut A. Santoso, dan Nigel Bullough dari Yayasan Nandiswara, berangkat menyambangi batu prasasti itu pada 19 Februari 2006, saat musim semi. Mereka bertemu dengan Lord Minto VII di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris di London.
Hari Untoro Drajat, yang menjabat Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala ketika itu, membenarkan kabar bahwa pihaknya membentuk tim. Menurut Hari, ia mendapat laporan tentang keberadaan Prasasti Sangguran itu dari Bullough. "Saya minta Kepala Balai Konservasi Peninggalan Borobudur, Pak Dukut, ikut serta untuk melihat kemungkinan mengangkut prasasti itu," ujarnya.
Mantan Direktur Peninggalan Sejarah dan Purbakala Soeroso masih mengingat jelas keberangkatan mereka ke London. "Kami ke sana untuk memastikan apa yang disampaikan Pak Nigel Bullough, yang sudah lama melakukan pendekatan, dan apakah Lord Minto VII bersedia mengembalikan," katanya.
Menurut Soeroso, dalam pertemuan di KBRI pada siang hari 21 Februari 2006 itu, Lord Minto VII menyatakan tak berkeberatan melepas prasasti tersebut. Namun ia mengingatkan perlunya persetujuan dewan pengawas (trustees), yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset yang dimilikinya. Berdasarkan konsultasi dengan beberapa pihak, termasuk British Museum dan Victoria and Albert Museum, Lord Minto VII menginginkan kompensasi atas Prasasti Sangguran yang dimilikinya.
Singkatnya, pengembalian itu tidak gratis. Hari Untoro menegaskan, sejak awal, tim yang diberangkatkannya disiapkan untuk tidak membayar atau memberikan kompensasi. Alasannya, jika membayar kompensasi, itu berarti mereka mengakui barang tersebut milik si pemegang prasasti. Hari juga mengatakan pemerintah menyiapkan skenario. Bila Lord Minto VII mau mengembalikan prasasti tersebut secara cuma-cuma, pemerintah melalui Duta Besar Indonesia untuk Inggris saat itu, Marty Natalegawa, akan memberikan penghargaan kepadanya. Juga biaya akomodasi di Indonesia jika bangsawan itu ingin melihat tempat untuk meletakkan prasasti tersebut. "Itu kami juga siap," ujar Hari.
Tapi Lord Minto VII menolak. Karena itu, diupayakan jalan lain melalui pendekatan personal. Pemerintah, kata Hari, lalu meminta bantuan Hashim Djojohadikusumo, pengusaha yang punya hobi mengoleksi benda kuno. "Kami memang minta bantuan beliau mendekati Lord Minto lagi. Karena Minto tetap minta kompensasi, ya, tidak negosiasi lagi," ujar Hari. Hashim, kata Hari, juga siap membantu ongkos pemulangan dan konservasi prasasti itu.
Menurut Peter Carey, Lord Minto VII banyak mendapat bisikan orang di sekelilingnya tentang harga prasasti bila diukur dengan harga lelang. "Mula-mula prasasti itu ditawarkan 50-70 ribu pound sterling," ujarnya. Kemudian harga penawarannya berubah karena para pembisik Lord Minto VII menyebutkan, jika dilempar ke pasar lelang Amerika, prasasti itu bisa bernilai US$ 500 ribu. "Bisikan ini membuat Minto merasa akan ditipu jika melepasnya dengan nilai 50 ribu pound sterling," kata Carey.
Pribadi Sutiono, mantan Kepala Fungsi Penerangan KBRI London, membenarkan, pada awalnya Lord Minto tidak minta apa-apa, tapi kemudian berubah karena hartanya dalam penguasaan family trustees. "KBRI berkeberatan memberikan kompensasi, karena itu warisan nasional kita," ujarnya. Pribadi mengatakan KBRI menghentikan negosiasi pada 2006. Soal negosiasi yang dilakukan pengusaha Hashim setelah itu, Pribadi mengatakan tak mengetahuinya. KBRI dan Departemen Luar Negeri tidak pernah diajak berunding lagi. "Seutuhnya itu antara keluarga Lord Minto dan tim Pak Hari karena KBRI sudah kadung mutung dengan negosiasi kompensasi."
Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kacung Marijan mengaku mengetahui perihal Batu Minto dan pengiriman tim negosiasi ke Skotlandia. Tapi dia mengatakan belum membaca laporannya. "Mereka minta dibayar mahal, tapi saya tidak tahu berapa banyak," ujarnya. Dia juga mengatakan upaya membawa pulang prasasti itu harus tetap melalui jalur diplomasi negara. Jika ada pihak swasta atau pribadi yang akan membantu, Kacung mempersilakan, "Asalkan (prasasti tersebut) tidak dimiliki oleh pribadi itu."
Dian Yuliastuti, Ratnaning Asih, Abdi Purmono (Batu), David Priyasidarta (Mojokerto)
Prasasti yang Tercecer
Melacak sejarah kuno Indonesia dapat dilakukan antara lain melalui prasasti. Pada umumnya prasasti itu berupa lempengan logam atau batu. Hanya, prasasti kuno bernilai sejarah tinggi itu banyak yang dibawa para petinggi pemerintah kolonial ke negara mereka. Ada yang terawat, tak sedikit yang terbengkalai.
Pemerintah Indonesia tak hanya berdiam diri. Sudah ada usaha untuk mengembalikannya, baik melalui negosiasi antar-pemerintah maupun dengan lembaga swasta atau individu. Sayangnya, usaha itu belum banyak membuahkan hasil. Berikut ini beberapa prasasti kuno Indonesia yang tercecer di mancanegara.
Belanda
10 prasasti
1. Tropenmuseum, Amsterdam
Sangsang, 1 lempeng
Tentang sebuah kuti, bangunan suci agama Buddha
Wukajana, 1 lempeng
Memuat daftar beberapa barang niaga
2. Maritiem Museum, Rotterdam
Guntur, 1 lempeng
Putusan pengadilan (jayapatra) terkait dengan kasus utang-piutang
3. Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden
Wintang Mas, 1 lempeng
Hubungan kekerabatan Raja Rakai Pikatan
Ratawun, 1 lempeng
Fungsi batik sebagai hadiah bagi tamu undangan
Er Kuwing/Poh Galuh, 1 lempeng
Tentang pembebasan pajak Desa Poh
4. RMV, Leiden
Kalirungan, 1 lempeng
INGGRIS
3 prasasti
1. British Library, London
Sobhamrta, 5 lempeng
(2, 4, 5, 6, 7)
Pabuharan, 1 lempeng
2. Lord Minto House, Skotlandia
Sangguran, Batu
Sumpah dan kutukan bagi orang jahat
DENMARK
5 prasasti
The Royal Library, Kopenhagen
Watukura I, 4 lempeng (1, 2, 3, 5)
Menyebutkan adanya jabatan rakryan kanuruhan, semacam perdana menteri, pada masa pemerintahan Dyah Balitung
Watukura II, 3 lempeng (1, 2, 3)
Watukura III, 1 lempeng
Siku Lalawa, 1 lempeng
Banigrama, 1 lempeng-
INDIA
1 prasasti
Indian Museum, Kolkata
Pucangan/Kolkata, Batu
Tentang kemasyhuran Raja Airlangga
JERMAN
8 prasasti
1. Museum fur Asiatische Kunst, Berlin
Mahapratisara, 1 lempeng (perunggu)
Berkaitan dengan perlindungan, penyembuhan, kegaiban, dan mantra
2. Museum fur Volkerkunde, Frankfurt
Airasih, 1 lempeng (2)
Parablyan, 1 lempeng
Narasinghanagara, 1 lempeng
Tentang setoran pajak pada waktu-waktu tertentu
Madhawapura I, 1 lempeng
Berkisah tentang pembuat pakaian, kuali, dan jamu
Madhawapura II, 1 lempeng
Batang, 1 lempeng
Carama, 1 lempeng
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo