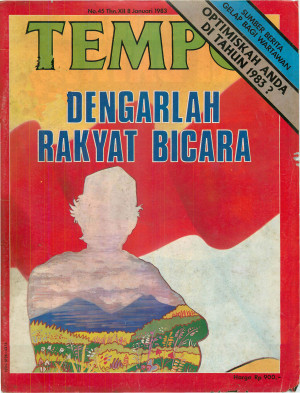SEORANG wartawan tentu pernah menerima nasihat basi ini:
dapatkan informasi itu dari siapa pun. Dari si tuan atau si
nyonya. Dari si sinyo ataupun si non. Kalau gagal, dapatkan dari
babunya, kokinya, tukang kebunnya. Masih gagal? Berhenti saja
jadi wartawan.
Biasanya, memang, kalau berbagai sumber itu dihubungi, jarang
yang gagal. Cuma acapkali sumber jarang mau disebut identitasnya
-- takut kena getahnya, atau karena berbagai alasan lain. Maka
agar berita tidak dianggap pembaca sebagai hasil lamunan,
terpaksalah sang wartawan memakai ungkapan ini: "Menurut sumber
yang layak dipercaya . . . " Atau, "Sumber kita yang tak mau
disebut namanya ...."
Satu hari, di bulan November lalu, The New York Times memuat di
halaman depannya tiga karangan berikut penjelasan dari berbagai
pihak. Dan menurut pengamatan David Shaw dari International
Herald Tribune, mereka telah memakai berbagai ungkapan yang
menyembunyikan identitas sumbernya. Misalnya: 'seorang duta
besar negeri Barat', 'seorang diplomat Barat', 'seorang wartawan
lokal yang terkemuka', 'sumber kepolisian', 'seorang pejabat
Deplu', 'pejabat pemerintah', 'pejabat pemerintah yang lain',
dan 'pejabat senior pemerintah'.
Pada minggu yang sama, Los Angeles Times menerbitkan sekitar dua
puluh tulisan, yang juga menyembunyikan para pemberi informasi.
Sebagai gantinya disebut: 'seotng diplomat', 'sejumlah
pengecam', 'pejabat Pentagon', 'seorang pejabat', 'seorang
pejabat senior', 'para pejabat pemerintah', 'sebuah sumber
Gedung Putih', 'sebuah sumber di serikat buruh',
'sumber-sumber', 'sumber lain', 'sebuah sumber', 'berbagai
sumber', dan 'sumber yang mengetahui'.
Waktu-waktu berikutnya, The Washington Post memuat sembilan
karangan memakai ungkapan-ungkapan yang mirip: 'para pejabat
AS', 'para diplomat Barat', 'sumber-sumber diplomatik',
'sumber-sumber setengah resmi', 'seorang pejabat AS', 'para
pejabat yang mengetahui', 'seorang pejabat Deparlu', 'para
pejabat senior Deparlu', dan 'sumber-sumber resmi'.
Shaw, yang mangkal di Los Angeles itu, mengaku mengangkat
contoh-contoh tersebut secara serabutan saja. Masih banyak
contoh lain yang katanya "bisa dipungut saban hari di surat
kabar di seluruh AS yang secara rutin mengutip berbagai sumber
tanpa menyebut nama. Ini fakta," dan menurut dia, The New York
Times ternyata lebih hati-hati -- lebih terbatas ketimbang
surat-surat kabar lainnya dalam menyebut sumber-sumber yang tak
beridentitas itu.
Surat kabar ini, katanya, tidak gegabah. Para redakturnya lebih
mantap dalam pertimbangan jika umpamanya hendak memakai ungkapan
'para pejabat negeri Barat' dan 'para pejabat senior
pemerintah'. "Mereka memberikan kepada pembacanya
isyarat-isyarat, betapa pun samarnya, tentang kemungkinan
keterikatan dan kecondongan sumber yang bersangkutan," tulis
Shaw.
Berbeda dengan The New York Times yang senantiasa berusaha
memberikan identifikasi sumber-sumber beritanya ('seorang
pejabat Deparlu' misalnya, tidak terlalu spesifik), surat-surat
kabar lain kurang kena dalam mencantelkan atribut--seperti hanya
'sumber-sumber' atau 'sumber-sumber resmi'. Menurut yang empunya
kisah, "mereka tidak memberikan petunjuk-petunjuk kepada para
pembacanya, sejauh mana kredibilitas keterangan yang diberikan.
Atau kemungkinan vested interest si sumber berita".
Para pembaca juga tampaknya kurang waspada atau kurang kritis
terhadap berita yang disuguhkan, yang sumber beritanya 'entah
siapa'. Pada hal sering tidak cukup dijelaskan di sana, mengapa
sang sumber tidak ingin namanya disebut.
Lalu Shaw bertanya: "Coba, siapa sesungguhnya 'seorang intelek'
yang dikutip dalam laporan Chicago Tribune 7 November? Di situ
orang tersebut dikatakan memberikan komentar tentang Partai
Kelembagaan Revolusioner Meksiko dengan kata-kata: "Mereka lebih
menyukaimu sebagai anteknya, membeli sikap opposisimu. Dan jika
itu tak mempan, mereka akan mencoba menakut-nakutimu."
Dan siapa pula 'seorang pejabat AS' yang dikutip kantor berita
AP 2 November, yang konon setelah bertemu dengan para anggota
Kongres mengatakan: "setiap orang tampaknya mendukung "keputusan
Presiden Ronald Reagan yang mengizinkan marinir AS menjalankan
patroli terbatas di jalan-jalan Beirut Barat"?
Lalu, apakah 'pejabat' dan 'intelek' tersebut benar-benar tahu
apa yang mereka bicarakan? Punyakah mereka alasan pribadi dan
politik terhadap pandangan yang ingin mereka umumkan itu
bahkan, jika kedua sumber itu bias (berpihak), bagaimana
caranya supaya para pembaca tahu?
"Itulah kesulitan yang sebenarnya dihadapi pembaca saban hari,"
tulis Shaw bagai menyimpulkan.
Tentu ada kekecualian, katanya lebih jauh. Yaitu jika kaum
reporter, yang tidak dapat menyebut nama sumber, menyuguhkan
informasi yang luas berkenaan dengan posisi sang sumber --
misalnya bagaimana identifikasi bisa membahayakan
keselamatannya, atau langsung berkaitan dengan dirinya. Sejumlah
reporter, redaktur dan pembuat berita yang diwawancarai Los
Angeles Times sepakat mengakui, kebanyakan laporan memang
sedikit sekali memberikan informasi tentang sumber yang tanpa
identitas itu. Dan kendati sudah diusahakan perbaikan di
berbagai bidang, masalahnya konon malah bertambah buruk.
Sebab, paling tidak, ada akibat lain: para sumber, di bawah
lindungan aman anonimitas, lantas leluasa menggunakan pers untuk
kepentingan pribadi dan politik mereka. Misalnya mengasah kapak
perang, memuaskan ambisi, membantai saingan dan membakar-bakar
khalayak. Caranya memang aman: lempar batu, sembunyi tangan.
Minta jangan disebut nama maupun identitas.
" 'Sumber-sumber' adalah kata-kata yang paling tidak kusenangi,"
kata William F. Thomas, redaktur dan wakil Dirut Los Angeles
Times. "Aku membencinya . . . kata sepotong itu. Itu bukan cara
yang baik untuk menulis laporan."
Lalu mengapa tak melarang saja penyiaran pernyataan apa pun yang
tak menyebut sumber yang jelas? Mengapa tidak ditentukan, agar
siapa saja yang ingin bicara kepada pers harus nampang
terang-terangan di depan khalayak, dan di depan kata-kata yang
diucapkannya? "Aturan yang simpel saja: tak ada nama, tak ada
berita," tulis Shaw.
Tapi masalahnya memang tak sesederhana itu. "Tidak praktis dan
tidak bertanggung jawab untuk bertindak demikian," menurut
penulis yang sama mengutip Thomas dan sejumlah wartawan lain
yang diwawancarainya. Demikian juga pendapat sejumlah pejabat,
yang masih di singgasana maupun yang sudah turun panggung.
"Tak ada jalan untuk menghindarinya," kata Jody Powell,
sekretaris pers bekas presidan J immy Carter, yang kini anggota
sindikat kolumnis. "Anda tidak akan mendapat banyak jika
mengharuskan setiap orang memperjelas identitasnya." Mengapa?
KARENA orang yang sedang berkuasa dan berjaya (penguasa atau
orang swasta sama saja) tidak ingin membaca kritik tentang
dirinya dimuat di koran-koran: programnya, tindakan-tindakannya,
kehidupan pribadinya. Jika setiap orang yang membongkar cacat
rencana kerja Departemen Hankam AS atau masalah sikut-menyikut
di Gedung Putih memberikan identitasnya di media cetak ataupun
non-cetak, wah, gawat dong.
Gawatnya, menurut Shaw juga, atasan segera melakukan pembalasan:
mempermalukan, mengucilkan, menurunkan pangkat, bahkan memecat.
Sedang yang tidak diinginkan para wartawan tentunya berlakunya
gerakan tutup mulut massal -- terutama dalam hal masalah-masalah
kontroversial.
Sebab kalau hal itu kejadian, segala bentuk publikasi akan
langka berita spekulasi dan gosip yang menggelitik di lingkungan
pemerintahan dan swasta --yang dalam banyak hal sebenarnya
berguna. Berarti juga pers dan publik akan langka informasi
tentang manipulasi, kecurangan, korupsi, pungli, kemacetan,
kemunafikan, dan segala ketidak becusan lainnya yang sebenarnya
merugikan publik itu sendiri dan mencemarkan demokrasi.
"Menjadilah kita orang-orang sok murni, yang tidak membolehkan
orang berkata apa pun tanpa menyebut namanya," ujar Gene Robert,
redaktur pelaksana Philadelphia Inguirer. "Akibatnya arus
informasi mandek. Dan itu menggagalkan misi utama kita agar
khalayak memperoleh hak mereka untuk tahu".
"Di Vietnam dulu, kutahu ada sejumlah orang yang tidak setuju
perang yang banyak memboroskan uang itu," kata Robert. "Tapi
tcntara tidak mau anda memberikan laporan begini: 'Kolonel John
Jones dan sejumlah pengikut berkata bahwa Jenderal Westmoreland
tidak tahu apa yang dilakukannya di sini.'
"Peranan terpenting surat kabar adalah penampilannya sebagai
saluran perdebatan (intern) kebijaksanaan politik pemerintah,"
kata Robert lebih jauh. "Bagaimana kita bisa melakukannya, jika
kita menolak memuat ucapan-ucapan mereka 'hanya' karena tidak
mau menyebut identitasnya?"
Robert, dan setiap orang pers yang diwawancarai Shaw, mengakui
bahwa 'kepercayaan' media massa terhadap sumber-sumber tak
bernama semakin berkelebihan. Dan hal yang dianggap kekeliruan
yang sudah meluas itu cukup memprihatinkan para redaktur,
wartawan dan pembaca.
Soal perlindungan terhadap sumber yang dirahasiakan sendiri, di
depan pengadilan, tampaknya tak ada masalah. Wartawan akan
dengan senang hati siap masuk penjara ketimbang harus membukakan
siapa sumber beritanya. Dalam hal itu sudah ada kesepakatan.
Tapi terpisah dari setiap konflik yang mungkin terjadi antara
pers dan pengadilan, ada yang membikin marah dan keccwa para
pengecam -- dari dalam maupun luar kalangan pers. Yaitu anggapan
bahwa para sumber berita anonim itu sudah keterlaluan
memanfaatkan 'keistimewaan' mereka.
Padahal para wartawan yang menuliskan berita berdasar keterangan
sumber yang tak disebut namanya itu sudah mempertaruhkan
kepercayaan pembacanya. Daiam kata-kata Shaw, "mengharapkan para
pembaca percaya kepadanya, meyakinkan pembacanya bahwa para
reporter (dan para redaktur) benar-benar telah menyelidiki
kredibilitas sang sumber."
Wartawan yang baik dan surat kabar yang baik sepantasnya
memegang teguh kepercayaan pembaca itu. Tapi, dan inilah berita,
pengumpulan pendapat umum yang dilakukan belakangan ini di AS
menunjukkan kepercayaan itu makin menyempit. Akibatnya sejumlah
redaktur menganggap pengurangan pemakaian sumber berita anonim
sebagai satu-satunya jalan untuk membantu "mengembangkan
kepercayaan" kembali. Itu menurut Eugene Patterson, Presdir dan
redaktur St. Peterburg (Florida) Times dan Independent.
PERSATUAN Redaktur Surat kabar, dan Dewan Pemberitaan
Nasional, dua organisasi pers Amerika independen, sempat
memonitor tingkah laku penampilan media massa. Dan tampaknya
mereka cukup prihatin dengan kasus sumber berita tanpa nama itu,
lalu segera merembukkan soal tersebut. Studi mendalam oleh
organisasi para redaktur itu sedang berjalan. Penelitian oleh
Dewan Pemberitaan Nasional sudah rampung dan segera diumumkan
resmi ke seluruh negeri.
Dalam kata pembukaan penelitiannya, Dewan Pemberitaan
menyebutkan: "Di hari-hari belakangan ini secara meluas timbul
masalah bagaimana sebaiknya dunia pers menjalankan misinya. Satu
masalah yang tampaknya menonjol: bagaimana saya tahu bahwa
berita ini benar padahal saya tidak tahu dari mana datangnya".
Lalu: "Ketidakpuasan yang meningkat ditunjukkan pada kenyataan
makin seringnya dilaku kan penyamaran sumber-sumber informasi
jurnalistik."
Sejumlah pembaca malahan curiga, jangan-jangan penggunaan sumber
berita tanpa identitas hanya tipu muslihat jurnalistik. Tidak
mungkinkah sang wartawan sendiri berlindung di balik ungkapan
'sumber yang mengetahui' atau 'seorang pengamat Senat' untuk
menyatakan pendapatnya sendiri di depan khalayak? Atau: itu
memungkinkannya merangkai dan memadukan sejumlah pandangan dari
beberapa sumber berita -- yang tak seorang pun di antaranya
dapat dikutip secara tepat, pada hal ia ingin laporannya
mempunyai warna dan titik singgung yang khusus.
Tom Brokaw, koordinator reportase pada NBC Nightly News,
mengeluh tentang ungkapan-ungkapan ini: 'Kecenderungan nyata
yang saya perhatikan akhir-akhir ini . . .' Atau 'beberapa
orang di Hill percaya . . .' "Itu menjadi semacam sangkutan baju
yang aman bagi para reporter untuk mencantelkan kesimpulannya
sendiri," katanya.
Dalam hal ini Brokaw tidak sendiri. "Beberapa reporter tampaknya
selalu ingin memasang kutipan sesuai dengan laporan yang hendak
diarahkannya," kata Jody Powell. "Pada hal dunia tidak lah
seperti yang anda kehendaki. Orang-orang tidak selamanya ingin
berkata seperti yang anda inginkan."
Biasanya reporter ingin mengutip dua atau lebih sumber 'pejabat'
anonim tentang topik yang sama -- karena umumnya media massa
berpegang pada kebijaksanaan: sedikitnya harus ada dua sumber
yang bertentangan untuk satu topik. "Saya sering dibakar
kecurigaan, janganjagan hanya satu sumber saja yang dapat
dipercayai," kata Frank Greve, wartawan Knight Ridder Newspaper
yang mangkal di Washington.
Ungkapan rapuh 'para pejabat' menurut Greve merupakan manuver
para reporter yang ingin melihat suratkabarnya tetap berpegang
pada kebijaksanaan 'dua sumber berita' tadi -- dan "untuk
memberi kesan kepada para redakturnya (dan para pembaca) tentang
kesungguhan dan kedalaman laporannya."
"Tapi penyandaran diri para reporter pada sumber tanpa identitas
itu karena menganggap itulah satu-satunya cara untuk memperoleh
laporan khusus." Kini yang berkata Shaw sendiri.
Para wartawan sendiri, umumnya menganggap dalih itu tidaklah
berlaku umum. Menempatkan para negarawan sebagai sumber anonim
malah mereka anggap lebih merupakan kemalasan pribadi dan
kebutuhan serta kebiasaan jurnalistik belaka, ketimbang
ketidakjujuran.
Kadang, memang, seorang reporter tidak kenal benar sumbernya.
Sebuah pernyataan rutin Deparlu, misalnya, diumumkan oleh
seorang pejabat eselon tiga. Nah, jika beritanya akan disiarkan,
nama siapa yang dicantelkan: yang mengumumkan atau yang
memerintahkan diumumkan? Atau ada orang lain yang lebih tinggi
kedudukannya? Maka daripada berpayah-payah-apalagi jika sedang
diburu deadline -- ambil saja ungkapan gampang dan aman:
'sejumlah pejabat pemerintahan'.
Itu terutama dialami para reporter yang meliput bidang bernilai
pengusuta atau kejahatan yang terorganisasi. Sumber-sumber
informasi untuk bidang ini, umumnya, enggan berbicara kepada
pers di dalam suasana yang bagaimanapun. Penggunaan anonimitas
di sini jadi tak terelakkan.
"Para reporter yang meliput negeri-negeri Eropa Timur dan rezim
totaliter lainnya sering harus melakukan tata hubungan seperti
itu pula dengan sumber beritanya, demi alasan kesamaran serupa,"
tulis Shaw lebih jauh. Memang, para reporter Amerika yang
bekerja di kebanyakan negeri asing sering diminta tidak
menyebutkan jelas sumber beritanya. Misalnya oleh para diplomat
asing, dalam hal yang berkaitan dengan tradisi dan tata cara
diplomatik, yang menyebabkan anggapan tidak layak memberikan
komentar tentang persoalan dalam negeri tuan rumah si diplomat
masing-masing. Apalagi di negeri-negeri yang tidak dapat
memahami tradisi pers bebas.
Penggunaan sumber tak dikenal dalam pers Amerika ternyata
merupakan jalan paling bermanfaat dan aman dalam meliput kasus
Mafia atau tema Moskow. Dan jumlah sumber anonim rupanya lebih
banyak bermukim di Washington ketimbang di lain tempat.
Memang mengherankan. Seorang sumber Washington bisa berkata
begini: "No Comment dan minta agar tidak disebut namanya," kata
Shaw. Atau, belakangan ia akan datang atau angkat telepon ke
kantor-kantor surat kabar atau TV meminta namanya tidak disebut.
Menurut penulis yang sama, begitu rutinnya sudah, di Washington
itu. Sehingga sejumlah reporter yang disuruh Shaw berwawancara
di sana untuk kepentingan tulisan ini pun, meminta Shaw untuk
tidak menyebut dua nama. Nama sumber berita, dan nama sang
reporter sendiri . . .
Mingguan Berita Newsweek baru-baru ini menurunkan laporan utama
tentang campur tangan Amerika dalam perang rahasia untuk
menggulingkan pemerintahan kiri di Nikaragua. Di antara
informasi dari 36 sumber berita intel, hanya tiga yang mau
disebut identitasnya. Dua antaranya menyebut "No Comment". Dan
karena itu oleh Newsweek para pejabat itu tidak disebut sama
sekali nama jelasnya. Buat apa, 'kan?
Mel Elfin, bekas perwira intel AU dan kini Kepala Biro Newsweek
di Washington, berkata: "Dalam dunia peromongan, kode anonimitas
adalah bagian dari tata cara berbusana." Namun kebanyakan
reporter Washington yang meliput bidang yang kurang peka
ternyata juga tidak menyebut nama jelas sumbernya. Jadi: "Itu
sudah menjadi kebiasaan di Washington," kata yang empunya
karangan.
"Cukup mencengangkan jumlah laporan dari Washington tanpa
sepotong nama tercantel di sana," kata Paul Janesh, redaktur
pelaksana Luisville Courier Journal and Times. Korp wartawan
Washington dan pemerintah "bekerja sama dalam permainan ini,"
katanya pula. "Jadinya publik yang rugi."
Janesh mengaku sempat menetap di Washington selama setahun --
"dan betapa kagetnya menyaksikan kesediaan para reporter
memenuhi permintaan" untuk anonimitas. Para reporter dan pejabat
pemerintah sepakat membuat "aturan menari bersama", tambah
Janesh, "dan semua itu membuat tercecernya informasi penting
dari mata dan telinga publik."
LALU Janesh menunjuk tindakan sementara pejabat pemerintah yang
membagikan informasi kepada reporter sambil berpesan "Jangan
disebut sumbernya". Bahkan tidak boleh pula sebagai latar
belakang. Artinya, si reporter bahkan tidak boleh mengutipnya
sebagai sumber anonim ia harus mengecek sendiri informasi
tersebut entah kepada siapa dan di mana. Atau tulis saja:
"Seperti diketahui, bahwa . . ." Bisa juga dalam gaya tulisan
seolah ia sudah mengetahuinya sebagai suatu fakta: "Presiden
Reagan akan mengumumkan . . ."
Konon, penggunaan sumber tanpa identitas sudah berkembang di
Washington (dan di mana saja) sejak masa para wartawan dan
pejabat harus bertemu dan berbicara. Tapi peningkatan menyo lok
terlihat sekitar 20 tahun terakhir. Sejumlah reporter dan
redaktur yang diwawancarai menyebut tiga tahap khusus evolusi
praktek jurnalistik di negeri itu.
Pertama-tama disebut masa pemerintahan Kennedy. Presiden John F.
Kennedy dianggap menikmati hubungan baik dengan pers: ia dan
pembantu utamanya sangat ahli bergaul (dan mengakali) para
wartawan. Adanya "laporan bocor" -- dan sumbernya tidak dikenal
-- sudah biasa di masa Kennedy. Dan kritik-kritik terhadap
pemerintahan Kennedy kemudian sering dianggap sebagai kecaman
terhadap pemerintahan Lyndon B. Johnson atau Richard M. Nixon --
saat kebijaksanaan 'pemberitaan terkendali' populer.
Kemudian tahap masalah Vietnam. Dibanding kebanyakan presiden AS
lain nya, Johnson dikenal sebagai pribadi tertutup dan angkuh.
"Manusia yang cepat bereaksi marah jika rencananya dikritik atau
dibocorkan kepada pers," komentar Shaw Kctika kecaman terhadap
kebijaksanaanya terhadap Vietnam menanjak, kepekaannya
menjadi-jadi.
Para reporter haus dan rakus terhadap berita bagus, sementara
para pejabat pemerintah sering pula kelewat bersemangat agar
bantahannya diketahui secara luas oleh publik. Dari sini para
reporter dengan cepat belajar dari pengalaman, bahwa cara
teraman untuk kedua belah pihak -- reporter dan sumber berita --
adalah menyiarkan berita tanpa menyebutkan sumber secara jelas.
Peristiwa Watergate mungkin tahap yang paling ramai. Kebanyakan
wartawan sependapat, penggunaan sumber berita anonim meningkat
secara geometris selama peristiwa ini. 'Deep Throat' (harfiah:
Kerongkongan Dalam adalah sumber informasi anonim paling menarik
dan merangsang. Tapi sesungguhnya, setiap reporter Watergate
yang baik harus menggunakan seorang atau dua 'shallow throat'
(kerongkongan dangkal) di tempat lain.
Karir politik senantiasa dibuntuti bahaya. Termasuk fitnah dan
penjara. Suatu saat ada pemerintah yang terguling. Dan jika
wartawan bertahan pada ketetapan bahwa setiap informasi harus
mencantelkan sebuah nama sumber, "banyak cerita kunci tentang
Watergate tidak akan pernah disiarkan," tulis Shaw.
Sayangnya, dalam persaingan mengungkapkan Watergate, standar
tradisional dalam hal pencantelan nama sumber berita makin
tersisih. Karena yang penting: berita hangat harus segera naik
cetak, dan itu berasal laporan dari sumber anonim. Ini dianggap
lebih baik ketimbang menyiarkan berita basi kendati dengan
sumber yang jelas.
Watergate ternyata memberikan rangsangan bagi orang-orang muda,
"para reporter pengusut", yang senang memburu berita penuh
glamour. Mereka menyangka dapat menyenangkan para redaktur (dan
pembaca) mereka karena berhasil membina hubungan dengan
'sumber-sumber yang mengetahui', dan 'para pejabat Balaikota'.
Lucunya, bahkan ketika sumber yang bersangkutan benar-benar
ingin namanya jelas-jelas disebutkan, mereka merahasiakan.
Para reporter sendiri sebaliknya cenderung menyalahkan sistem --
sebagian terbesar pemerintah -- berkenaan dengan banyaknya
sumber yang tak mau disebut namanya itu. Toh banyak kalangan
pers mengakui bahwa para reporter sendiri turut bersalah.
Memang, lebih gampang dan lebih cepat memperoleh informasi dari
orang-orang yang tak ingin namanya disebut ketimbang yang
sebaliknya. Dari sumber yang jelas, tumbuh masalah bagaimana
meniti di antara lika-liku birokrasi, untuk mencari sumber yang
paham benar masalah. Lalu bagaimana meyakinkannya agar mau
memberikan keterangan dengan nama jelas. Jadi beberapa reporter
lebih suka memilih jalan yang gampang, kata Shaw.
Dennis Britton, redaktur Nasional Los Angeles Times, menyebut
pemakaian sumber tak beridentitas sebagai "perangkat manusia
yang malas." Namun kemalasan, kenaifan dan glamour bukan
satu-satunya alasan mengapa para reporter begitu menyandarkan
diri pada sumber anonim. Persaingan antar media cetak dan
hadirnya televisi juga menjadi alasan yang kuat.
Kini ada 4.355 wartawan mangkal di Balai Wartawan Kongres saja.
Jumlah yang melipat dua dalam waktu 20-an tahun terakhir,
menurut National Journal. Journal memperkirakan ada sekitar 10
ribu "wartawan dan penulis berita yang resmi terdaftar" bekerja
di Washington mewakili surat kabar, televisi, radio dan buletin.
Dengan begitu serunya persaingan, besar sekali beban terpikul di
pundak wartawan agar senantiasa menjadi yang tercepat -- kendati
karenanya mereka hanya mempunyai secuil laporan yang baik.
Informasi dari sumber yang tak ingin namanya disebut, dalam pada
itu, sebenarnya sering dapat dicek kebenarannya kepada sumber
yang namanya mau diumumkan -- jika reporter bersangkutan
memiliki cukup banyak waktu untuk memburu dan menggali lebih
dalam. "Tapi keharusan menjadi yang pertama jarang memberi
kesempatan untuk penggalian lebih dalam itu," tulis Shaw. Para
reporter biasanya lebih kencang memburu ke percetakan atau
studio radio dan TV, dengan laporan dari sumber anonim.
Ini memang hubungan yang simbiosis. Reporter dan sumber berita
saling memanfaatkan untuk diri masing-masing, yang ternyata
acap bertentangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini