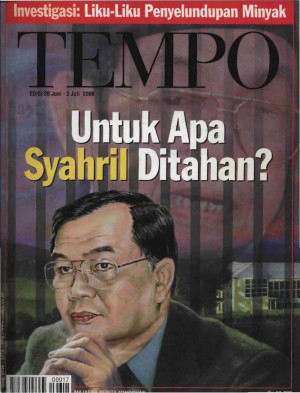Terhitung mulai pukul 00.00, 27 Juni lalu, segala aktivitas warga di Provinsi Maluku dan Maluku Utara—kecuali untuk beribadah—harus punya alasan yang jelas. Tidak boleh lagi berkumpul sekadar ngobrol atau arisan tanpa izin aparat keamanan. Jika tidak, mereka akan ditangkap atau bahkan bisa dipenjarakan tanpa proses pengadilan.
Pemerintah memberlakukan darurat sipil di dua provinsi itu melalui Keputusan Presiden No. 88/2000. "Pemerintah tidak punya pilihan selain menetapkan darurat sipil, kalau tidak korban akan terus berjatuhan," kata Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Yusril Ihza Mahendra.
Namun, menarik bahwa keppres itu dilandaskan pada UU No. 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya. Produk hukum Orde Lama itu dikenal sangat represif, karena setiap pasalnya bersifat lentur dan membuka peluang kepada penguasa untuk bertindak tegas tanpa alasan yang jelas. Semua ruang aktivitas penduduk bisa disentuh oleh aparat polisi, militer, dan jaksa selaku penguasa darurat sipil. Pasal 17, misalnya, menyebut aparat keamanan berhak mengetahui semua berita dan melarang pengiriman berita; membatasi peralatan telekomunikasi seperti telepon atau penyiaran lewat radio.
Selain darurat sipil, masih ada dua kategori darurat yang disebutkan, yaitu militer dan perang. Menurut undang-undang itu, semua kondisi tersebut bisa diberlakukan presiden selaku panglima tertinggi angkatan perang tanpa melalui persetujuan DPR. Tidak ada pemisahan yang jelas dan tidak secara detail disebutkan apa saja persyaratan pemberlakuan darurat militer maupun perang.
Pertanyaannya, mengapa produk hukum yang sangat bertentangan dengan alam reformasi itu dipakai. "Karena Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya belum disahkan oleh presiden sehingga tidak bisa dipakai," kata Yusril Ihza Mahendra.
Semasa Presiden B.J. Habibie, rancangan undang-undang soal penanggulangan keadaan bahaya memang pernah dibuat sebagai ganti UU No. 23/1959, yang dianggap sangat represif. DPR saat itu bahkan sudah memberi persetujuan. Namun, gelombang unjuk rasa menolaknya. Puncaknya terjadi pada 23 September 1999, yang menelan lima korban jiwa. Akibat tragedi itu, B.J. Habibie memutuskan untuk tidak menandatangani RUU PKB itu. Hingga pemerintahan berganti ke Abdurrahman Wahid, perangkat hukum itu belum juga disahkan.
Isi UU PKB sebenarnya punya beberapa perbedaan dengan UU No. 23/1959. Misalnya soal penyebutan status keadaan daerah. Meski maknanya sama, UU PKB tidak menyebut darurat sipil tetapi keadaan khusus. Tak seperti undang-undang sebelumnya, undang-undang yang baru itu menyebut batas waktu selama tiga bulan dan bisa diperpanjang jika ada permintaan dari DPRD serta gubernur wilayah yang dilanda kerusuhan.
Keadaan darurat ditetapkan jika di suatu daerah terjadi pemberontakan atau usaha-usaha untuk memisahkan diri. Presiden menyatakan keadaan tersebut berdasarkan laporan gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD dan berkonsultasi dengan DPR. Sedangkan keadaan perang diberlakukan jika ada ancaman serangan dari negara lain. Menyatakan kondisi itu, presiden juga harus memperoleh persetujuan anggota DPR terlebih dahulu.
Karena dinilai lebih cocok, beberapa anggota DPR meminta agar Presiden Abdurrahman segera mengesahkan undang-undang ini. Akbar Tandjung, Ketua DPR, bahkan pernah berjanji akan melayangkan surat ke Presiden agar undang-undang itu segera disahkan. "Saat ini kita membutuhkan landasan hukum yang kuat untuk menghadapi berbagai keadaan bahaya," katanya awal April lalu.
Namun, saat pembahasan soal itu belum tuntas, muncul desakan agar wilayah Maluku segera diberlakukan darurat sipil. Karena landasan hukum yang baru belum ada, pemerintah menggunakan undang-undang keluaran tahun 1959 itu.
Menurut Yusril, ada alasan lain yang juga tidak memungkinkan UU PKB digunakan. Di provinsi baru Maluku Utara belum terbentuk susunan anggota dewan. Sementara itu, menurut undang-undang tersebut, salah satu syarat menyatakan keadaan khusus berlaku di suatu daerah adalah adanya persetujuan anggota DPRD setempat.
Pilihannya memang tidak mudah. Tujuan pemerintah menerapkan status itu adalah untuk menghentikan banjir darah. Sampai di situ, semua orang akan setuju. Masalahnya adalah apakah ini menjadi satu-satunya cara yang efektif. Dan lebih dari itu, penerapan status darurat itu dikhawatirkan juga akan "memicu adanya penyalahgunaan kekuasaan" seperti dikatakan Munir, Ketua Dewan Pengurus Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan.
Bambang Widjojanto, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, bahkan khawatir lebih jauh: kembalinya dominasi kekuasaan militer atas negara. Sampai kini, kata dia, bangsa Indonesia belum selesai merumuskan bagaimana fungsi tentara dalam percaturan kekuasaan. "Mereka bisa menggunakan instrumen-instrumen hukum itu menjadi sebuah kekuatan yang tidak terkontrol," katanya.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Tyasno Sudarto membantah kemungkinan itu. "Penerapan undang-undang itu justru positif untuk menghentikan pertikaian, jangan diartikan macam-macam," tuturnya kepada Tiarma Siboro dari TEMPO. TNI, yang selama ini terkesan ragu-ragu bertindak tegas kepada perusuh karena alasan melanggar hak asasi, justru terpayungi oleh UU No. 23/Prp/1959 itu. Meski begitu, menurut Tyasno, aparat militer akan bertindak hati-hati agar tidak terjadi pelanggaran.
Kelemahan lain cukup mencolok dalam UU No. 23/1959 adalah tidak ikut campurnya DPR dalam menentukan kondisi darurat. Pemerintah secara sepihak bisa memberlakukan keadaan darurat. Akibatnya, tidak ada kontrol dari rakyat, melalui wakilnya, terhadap tindakan represif aparat negara. Sehingga, atas nama keselamatan negara, penguasa bisa bertindak apa saja.
Fungsi kontrol masyarakat juga tidak jalan oleh konsekuensi diberlakukannya darurat sipil dengan cara mengisolasi daerah tersebut. "Padahal, dalam kondisi itu justifikasi kekerasan diperbolehkan," kata Bambang. Meski ada pasal-pasal yang mengatur sanksi bagi aparat keamanan yang melanggar ketentuan darurat sipil, "tidak ada mekanisme pertanggungjawaban terhadap segala aktivitas penguasa itu," kata Munir.
Rakyat selalu dalam pihak yang lemah dan harus dikontrol. "Selama ini negara selalu menempatkan diri pada posisi yang kuat," ujarnya. Selain itu, dalam undang-undang keadaan darurat itu selalu diasumsikan penyebab kerusuhan adalah rakyat. "Bagaimana kalau negara yang melakukan kejahatan terhadap rakyat?" ujar Bambang.
Karena itu, baik Munir maupun Bambang setuju jika UU No. 23/1959 itu segera dicabut. Sebagai gantinya, Munir setuju UU PKB digunakan. Namun, terlebih dahulu harus direvisi sesuai dengan tuntutan demokrasi. "Di negara mana pun undang-undang seperti itu memang harus ada."
Meski meyakini UU PKB lebih demokratis daripada UU No. 23/1959, mantan Menteri Sekretaris Negara Muladi juga mengusulkan agar ada revisi. "Presiden harus mengembalikan undang-undang itu ke DPR untuk ditinjau kembali sesuai dengan spirit yang baru," katanya.
Mantan pejabat yang ikut menggodok rancangan undang-undang itu juga memberi beberapa masukan. Di antaranya adalah pentingnya presiden memberi laporan kepada DPR secara periodik selama pemberlakuan keadaan darurat. Selain itu, "Saya kira lembaga swadaya masyarakat dan lembaga independen juga harus dilibatkan dalam penggodokan."
Sebaliknya, Bambang Widjojanto justru melihat tidak ada keharusan sebuah negara mempunyai undang-undang darurat seperti UU PKB. Ia yakin, jika toh disahkan, undang-undang itu tidak akan mampu menghentikan kerusuhan dan kekerasan yang timbul di masyarakat. Karena terkadang aparat keamanan justru sebagai pemicu kerusuhan itu sendiri. "Sebagian negara Skandinavia seperti Swis tidak ada undang-undang darurat seperti itu, toh aman saja," katanya.
Tampaknya, pemerintah masih berkeras menggunakan UU No. 23/Prp/1959 untuk mengatasi kerusuhan di Maluku, yang kini sudah memasuki tahun kedua. "Dalam waktu dekat tidak ada rencana melakukan revisi RUU PKB itu karena bisa mematikan UU No. 23/1959," ujar Yusril.
Persoalannya memang bukan sekadar perlu atau tidaknya UU PKB direvisi, tapi bagaimana tragedi Ambon yang sudah menelan korban ribuan jiwa itu bisa diatasi oleh pemerintah. Dan itu memang tidak bergantung pada undang-undang apa yang akan digunakan oleh pemerintah, tapi sebuah keseriusan.
Johan Budi S.P., Arif A. Kuswardono, Dewi R. Cahyani, Tomi Lebang
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini