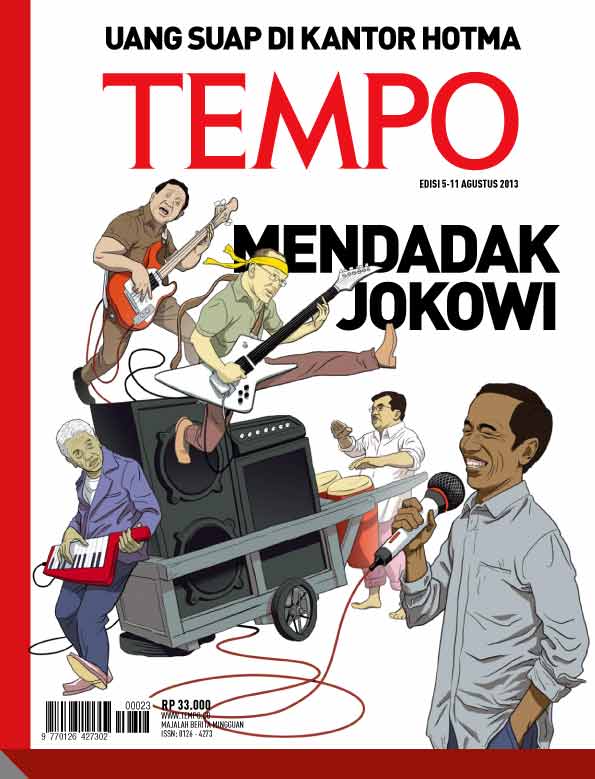Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pertengahan bulan lalu, kami mengajak penyair Joko Pinurbo ke Magelang untuk menemui ilham pertamanya. Ilham itu tersembunyi di antara pepohonan dan bangunan Seminari Menengah St Petrus Canisius di Mertoyudan, Jawa Tengah. Di sekolah calon imam Katolik itulah, 36 tahun lalu, Joko Pinurbo pernah belajar. Sastrawan yang kini tinggal di Yogyakarta itu kemudian urung menjadi imam, tapi di sana ia menemukan keindahan yang lain: puisi.
Setibanya di Seminari Mertoyudan, Jokpin—dia biasa dipanggil begitu—menatap pelataran rumah musik. Kenangannya melompat jauh ke masa silam: tiga dasawarsa lalu, bangunan itu masih berfungsi sebagai kandang babi. Di situ, dulu, ia kerap duduk melamun atau mondar-mandir di atas rerumputan. "Ini tempat favorit saya merenung," kata sastrawan pilihan Tempo 2012 ini.
Tatapan Jokpin berpindah ke lapangan sepak bola. Sepuluh cemara tumbuh di sisi selatan, di belakang gawang. Lima cemara tegak di sebelah utara, berdekatan dengan pagar tembok yang memisahkan kompleks seminari dengan rumah penduduk.
Di bagian baratnya, masih ada tanah kosong. Aneka pohon tumbuh di situ dengan subur dan gembira: kluwih, alpokat, durian. Jokpin, yang rambutnya mulai memutih, berhenti, lalu mencoba mengingat bulan bulat penuh yang dilihatnya ketika ia berusia 16 tahun. "Malam itu sunyi. Terang bulan," ujar Jokpin, kini 51 tahun.
Ia tahu keindahan purnama. Tapi Jokpin remaja ingin menikmati kecantikan bulan dengan cara tragis. Ia membayangkan bulan berlumur merah darah. "Saya ingin mendekonstruksi bulan yang selama ini dianggap penuh romantisisme," katanya.
Dari situlah muncul ide membuat puisi pertamanya. Dalam keheningan yang pekat, Jokpin mencipta. Tangannya tidak mencatat, tapi kepalanya menyusun kata-kata. Sesampai di kamar, ia baru menuliskan puisi–lalu mengirimkannya ke media cetak lokal.
Si penyair sudah lupa isi syair bulan berdarah. Ia juga tak menyimpan salinannya. Tapi, sejak saat itu, kepalanya terus-menerus memproduksi kata-kata. Seorang padri kemudian menyarankan dia menjadi penyair saja—dan bukan imam. Saran itu dia lakukan—sampai sekarang.
Jokpin adalah satu dari sekian banyak sastrawan yang lahir dari lembaga pendidikan keagamaan macam seminari dan pesantren. Romo Mangun, Remy Sylado, Mario F. Lawi, serta Pastor Leo Kleden, SVD adalah sederet sastrawan yang datang dari latar belakang seminari. Dari pesantren, kita mengenal Mustofa Bisri, Zawawi Imron, dan Acep Zamzam Noor, serta Abidah El Khalieqy dan Ahmad Fuadi dari generasi baru.
Mereka bertemu dengan sastra di saat remaja, di sela-sela belajar tentang Tuhan dan agama. "Setiap hari, menjelang salat, santri membaca sajak Abu Nawas atau Rabiah al-Adawiyah. Di pesantren, semua ilmu dipelajari lewat puisi. Bahkan ilmu fikih (hukum agama) dan akidah (teologi) diajarkan melalui bait-bait puisi," kata Jamal D. Rahman, penyair lulusan Pesantren Al-Amien, Prenduan, Madura.
Acep Zamzam Noor, penyair dari Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, mengakui hal yang sama. "Pada dasarnya, pesantren sudah puitis. Kami mengaji dengan mempelajari syair-syair, nadhom (puji-pujian) karya Abu Nawas, juga syair yang jadi amalan sehari-hari yang sering dikumandangkan," ujarnya. "Atmosfer itu yang saya syukuri, yang mungkin tak didapatkan dari tempat lain," dia menambahkan. Acep adalah putra tertua KH Ilyas Ruhiat, ulama karismatis dari Pesantren Cipasung.
Sementara santri wajib melahap syair-syair Arab untuk mempelajari ilmu lain, murid di seminari diwajibkan melahap buku apa saja, termasuk sastra. Inilah yang dialami sastrawan Remy Sylado saat belajar di Seminari Theologia Baptis Indonesia di Semarang. "Di sana saya membaca semua buku, dari karya-karya filsafat Plato sampai puisi T.S. Eliot yang sejalan dengan napas Gereja," kata Remy. Dia belajar langsung ilmu-ilmu bahasa dari pendiri seminari itu, Buford Lee Nichols.
Hal yang sama dialami Pastor Leo Kleden, SVD, teolog dan filsuf dari ordo Societas Verbi Divini (SVD), saat belajar di Seminari San Dominggo, Hokeng, Flores Timur. "Pada usia remaja di SMP dan SMA, saya berkenalan dengan buku-buku Karl May. Saya ingat bagaimana seharian saya sedih sekali sesudah membaca kisah Winnetou gugur. Saya juga membaca karya-karya William Saroyan, Alexandre Dumas, dan Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari-nya Jules Verne," Leo menjelaskan.
Di sekolah yang sama, Leo mengenal sejumlah penyair besar klasik Barat di masa remajanya. Pada 1967, ketika duduk di kelas II sekolah menengah atas, ia bersama teman-temannya menerbitkan majalah Sorot. Di situlah dia menulis artikel pertamanya tentang Faust karya penyair besar Johann Wolfgang von Goethe—sastrawan Jerman.
Persentuhan dengan karya-karya sastra seperti inilah yang juga menggerakkan Jokpin untuk mencintai sastra. "Saat itu saya melahap semua buku. Apa pun saya baca," katanya. Namun yang benar-benar menggetarkannya adalah buku puisi Sapardi Djoko Damono berjudul Duka-Mu Abadi. "Saya tergetar ketika membaca puisi itu di kelas."
Tak puas dengan hanya meminjam dari perpustakaan, Jokpin lantas membeli buku itu di toko buku dekat Jalan Malioboro, Yogyakarta. Pada Minggu waktu itu, ia naik bus keluar dari seminari untuk membeli puisi Sapardi. Buku itu hilang. Jokpin membeli lagi, lalu hilang lagi. Setidaknya, dia membeli Duka-Mu Abadi hingga lima kali.
Sayang, siswa tak sepenuhnya bebas-merdeka—dalam memilih bacaan. Ada juga yang "diarahkan". "Puisi Abu Nawas yang dibaca terbatas pada puisi religiusnya, bukan puisi cinta (ghazal) dan mabuk (khamariyat)," ujar Jamal–pemimpin redaksi majalah sastra Horison. Hal yang sama terjadi di seminari. "Kami sangat diarahkan membaca T.S. Eliot, tapi sama sekali tidak diarahkan membaca karya-karya Nietzsche, Schopenhauer, atau Sartre," kata Remy. Padahal buku-buku itu ada di perpustakaan seminari.
Selain membaca karya sastra, mereka mendapatkan ilmu bahasa yang kuat. Awalnya, pelajaran bahasa Arab di pesantren dan Latin di seminari dimaksudkan agar para calon pemimpin agama ini memahami teks keagamaan seperti Al-Quran atau Alkitab yang sastrawi. "Di pesantren diajarkan pelajaran nahwu (gramatika) dan shorof (perubahan bentuk kata). Juga diajarkan ilmu balaghoh, badi', dan bayan (ilmu untuk memahami sastra)," ujar Mustofa Bisri. Penyair itu kini memimpin Pondok Pesantren Raudlatuth Thalibin, Rembang, Jawa Tengah.
"Ilmu-ilmu tersebut, terutama balaghoh, adalah ilmu sastra, karena sejak awal dimaksudkan untuk mengapresiasi keindahan Al-Quran, yang merupakan karya sastra," kata Gus Mus—sebutan Mustofa. Pada perkembangannya, ada yang menggunakan pelajaran tersebut untuk mempelajari dan memproduksi sastra. "Ibarat sebilah pedang yang bisa digunakan untuk memotong pisang dan menebang pohon."
Di seminari, bahasa Latin ada di daftar wajib. "Pelajaran bahasa Latin enam jam seminggu selama tujuh tahun di seminari menengah amat melatih ketelitian dan kepekaan dalam membaca, menerjemahkan, dan menafsir teks, terutama ketika membaca teks-teks sastra klasik bahasa Latin," ujar Leo.
Keheningan, persentuhan dengan karya sastra, dan ilmu-ilmu bahasa berpengaruh pada karya-karya mereka. Hal itu, misalnya, dilihat oleh Jamal saat para santri berbicara tenang cinta di puisi-puisi mereka. "Bukan cinta yang personal," katanya. "Ini karena saat di pesantren kita ditekankan untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata muamalah ma'annas (interaksi dengan manusia) dan muamalah ma'allah (interaksi dengan Tuhan)."
Puisi religius, tentu saja, lahir dari tangan para santri dan seminaris. Hal ini, misalnya, amat terasa dalam karya-karya Zawawi Imron. "Kugali hatiku dengan linggis alif-Mu/Hingga lahir mata air, jadi sumur, jadi sungai,/Jadi laut, jadi samudra dengan sejuta gelombang/Mengerang menyebut alif-Mu/Alif, alif, alif!"
Tentu saja, itu bukan tema yang dimonopoli sastrawan pesantren dan seminari. Pada 1970-an dan 1980-an, sejumlah penyair, seperti Abdul Hadi W.M. dan Danarto, malah menahbiskan sufisme sebagai dasar inspirasi karya-karya mereka. "Bedanya, ketika berbicara soal Tuhan, mereka tidak lagi berbicara dalam konteks pencarian atau pertemuan seperti halnya puisi-puisi sufistik Danarto, misalnya," kata Jamal.
W.S. Rendra—sebelum menjadi muslim—juga kerap membuat puisi dengan idiom-idiom dari Kitab Suci. Tapi tema ini bukan monopoli alumnus seminari. Menurut Mario F. Lawi, sejumlah penyair yang non-Kristen kerap memakai tema ketuhanan Nasrani dalam karya mereka. "Tapi kerap ada yang tak pas. Ada hal-hal yang sepertinya dipaksakan pada karya tersebut. Mungkin berbeda bila itu ditulis sendiri oleh orang yang pernah mempelajarinya," ujarnya kepada Tempo di sela acara Makassar International Writers Festival, Juni lalu.
Kedekatan pada teks agama tak menghalangi sastrawan dari pesantren atau seminari mengkritik pesantren dan Gereja. Mereka bahkan lebih mudah melakukannya. Joko Pinurbo malah terkenal gara-gara puisi yang memelesetkan kata Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus.
Dalam puisi "Celana Ibu" yang ditulis pada 2004, Jokpin menulis, "Ketika tiga hari kemudian Yesus bangkit/dari mati, pagi-pagi sekali Maria datang/ke kubur anaknya itu, membawa celana/yang dijahitnya sendiri.//'Paskah?' tanya Maria. /'Pas sekali, Bu,' jawab Yesus gembira.//Mengenakan celana buatan ibunya,/Yesus naik ke surga."
Mario, lulusan Seminari Santo Rafael, Kupang, Nusa Tenggara Timur, pernah membuat puisi di Koran Tempo yang "menggugat" doa. Bunyinya begini: "Ia hapus percaya pada/Sebuah janji yang tak kunjung ditepati//Pada Tuhan yang tak kunjung mengirimkan/Bala bantuan, ia nyatakan permusuhan.//Jika ada injil yang diwartakan dalam perang,/Akan ia hapus dengan peluru-peluru/Dari dalam senapannya."
Kritik keras kepada institusi pesantren datang lewat karya Abidah El Khalieqy, Perempuan Berkalung Sorban. Di novel yang sudah difilmkan ini, Abidah—lulusan Pesantren Persatuan Islam, Bangil, Jawa Timur—mengkritik perlakuan terhadap perempuan sebagai "warga" kelas dua di pesantren.
Kritiknya menuai hujatan keras, terutama dari kalangan pesantren tradisional. Abidah dianggap memotret pesantren secara parsial. "Kritik terbesar kepada Abidah adalah karena novelnya meninggalkan cara pesantren dalam memberi kritik dan masukan," kata Ahmad Baso, penulis buku Pesantren Studies: Sastra Pesantren dan Jejaring Teks-teks Aswaja-Keindonesiaan.
Abidah menganggap protes tersebut lebih ditujukan pada visualisasi novel itu di film yang disutradarai Hanung Bramantyo. Di film itu, tokoh utama Annisa sebagai santri kerap menenteng buku sastrawan Pramoedya Ananta Toer, yang kiri. Padahal di teks novel tidak ada penggambaran tersebut. "Kiai sepuh di pondok pesantren Jawa Timur memprotes simbol buku Pram," ujarnya.
Bisa jadi kontroversi itu muncul karena Abidah dianggap bukan "orang dalam" pesantren tradisional. Pada 1976-1983, Abidah nyantri di pesantren yang lebih modern. Kritik bisa diberikan secara terbuka tanpa tedeng aling-aling di Pesantren Persatuan Islam. Majalah-majalah wanita modern, seperti Femina dan Kartini, tersedia di perpustakaan. Dan ada agenda menonton bioskop secara berkala untuk para santri.
Abidah tak seberuntung Jokpin, yang memiliki asrama dengan pohon-pohon besar dan lapangan luas. Asramanya penuh bangunan—termasuk kolam renang di tengah. Hanya ada beberapa petak ruang hijau. Kesempatannya menulis pun tak banyak. Sejak pukul tiga pagi hingga sebelas malam, santri dijejali kegiatan yang dimulai dengan bel-bel khusus. Ada sepuluh bunyi bel untuk menandai sepuluh kegiatan berbeda. Ia hanya bisa menulis saat istirahat sekolah atau menjelang tidur.
Cerpen pertamanya dimuat di koran Pelita dan seluruh pesantren mengetahuinya. Gara-garanya, Ustad Abdul Qadir—pemimpin pesantren yang menolak dipanggil kiai—mengumumkan pemuatan cerpen itu melalui pengeras suara musala. Abidah mendapat honor Rp 3.000. "Uang itu saya pakai untuk mentraktir teman-teman, nombok pula," katanya. Abdul Qadir—yang selalu mengetik buku-bukunya dengan berdiri—menghadiahi Abidah rautan pensil seharga Rp 5.000.
Ada berbagai cara untuk membuat santri dan seminaris menjadi sastrawan. Tapi, seperti yang diyakini Acep, puisi telah membebaskan mereka dari militansi—yang memandang segala sesuatu secara hitam-putih. "Beragama itu harus bergembira, tanpa tekanan. Hal itu bisa dilakukan melalui ekspresi seni," kata kiai gondrong ini.
| Liputan Khusus Sastra Religi Kepala Proyek dan Penulis: Qaris Tajudin Editor: Hermien Y. Kleden Penyumbang Bahan: Shinta Maharani, Sunudyantoro, Sohirin (Yogyakarta dan Jawa Tengah), Mustofa Bisri (Jawa Timur), Steph Tupen Witing (Maumere, Flores), Yohanes Seo (Kupang), Candra Nugraha (Tasikmalaya), Nurdin Kalim, Riky Ferdianto (Jakarta), Qaris Tajudin (Makassar) Editor Bahasa: Iyan Bastian, Sapto Nugroho, Uu Suhardi Desain: Rizal Zulfadli Foto: Jati Mahatmaji |
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo