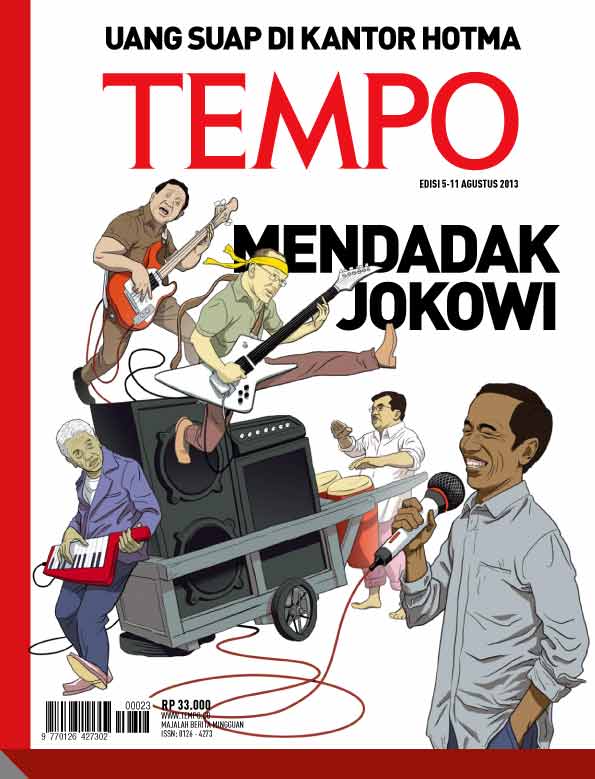Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Suatu hari, tatkala Kerajaan Islam Demak hendak membangun keraton di wilayah Glagahwangi, terjadilah keajaiban itu. Pohon-pohon yang ditebang pagi hari tumbuh kembali pada sore. Para mandor mengadu ke Sunan Giri—raja para wali. Sunan Giri lantas mengutus Sunan Kalijaga ke tengah hutan.
Di sana, Kalijaga bertemu dengan Yudhistira—anak sulung Pandawa dalam kisah Mahabharata. Anehnya, Yudhistira tak beragama Hindu, melainkan Buddha. Dialog terjadi antara Kalijaga dan Yudhistira, yang mengepal jimat bertahun-tahun hingga kukunya memanjang dan menancap di telapak tangannya sendiri. Jimat itu ternyata kalimat syahadat.
Kisah ini buah imajinasi tiga pujangga istana Kesultanan Surakarta—Sastranagara, Ranggasutrasna, dan Sastradipura—dalam Serat Centhini (1814). Meski kitab ini belakangan terkenal karena keerotisannya—termasuk sejumlah adegan homoseksualitas—Centhini sebenarnya kisah tentang perjalanan Syekh Amongraga, putra Sunan Giri.
Hubungan ulama-sastrawan-keraton sebenarnya sudah terjalin sejak kedatangan Islam di Nusantara. Bukan hanya Sunan Kalijaga yang bersyair lewat suluk-suluknya. "Ada Sunan Giri Kedaton (putra Sunan Giri) yang menulis Serat Wali Sana, Sunan Bonang yang mengarang Damarwulan, Sunan Drajat dengan Jaka Partwa Nggadingan Majapahit, Sunan Padhusan dengan Jaka Karewet, Sunan Kudus yang menulis Jaka Bodo, dan lain-lain," kata Ahmad Baso, penulis buku Pesantren Studies: Sastra Pesantren dan Jejaring Teks-teks Aswaja-Keindonesiaan.
Bahkan, menurut Baso, di Pesantren Sunan Giri ada sejumlah penulis andal yang memproduksi banyak karya. Bukan hanya karya-karya Islam, melainkan juga karya untuk kaderisasi para ajar (cerdik pandai di masa Hindu-Buddha). Di sini pula sejumlah buku Hindu ditulis ulang. "Serat Jayabaya ing kina ingkang nganggit Empu Salukat, lajeng kaanggit malih dateng Susuhan Giri Kaping 2," begitu tertulis dalam Serat Pawukon. Serat Jayabaya, yang di masa kuno (pra-Islam) dilarang Empu Salukat, kemudian disusun ulang oleh Sunan Giri 2.
Giri juga berperan penting dalam menjaga teks Mahabharata. Seperti disebutkan dalam Serat Centhini, satu kitab koprak (lontar) berjudul Bharatayudha diserahkan ke Giri untuk diolah kembali menjadi bahan penulisan lakon-lakon wayang.
Setelah Kerajaan Demak berdiri, pesantren menjadi satu-satunya lembaga pendidikan resmi. Dari sanalah lahir pujangga-pujangga istana, termasuk Ranggawarsita II. Di Sumatera, sastra Melayu juga banyak dimulai oleh para santri, seperti Bukhari al-Jauhari, Nuruddin ar-Raniri, atau Raja Ali Haji. Bahkan, untuk sastra Melayu, kita melihat jejak bentuk-bentuk syair Arab dan Persia—seperti qasidah—dalam karya mereka.
Begitu kuat pengaruh sastra pesantren ini hingga para penulis Tionghoa pun, dalam catatan Baso, mengadopsi gaya para santri dalam menulis sastra. "Hal itu, misalnya, terlihat dalam pembukaan Njai Dasima karya O.S. Tjiang (1897), yang memakai bismillah segala," kata Baso. "Bismilla itoe awal pertama/Saija mengarang di dalam roema/Tjerita ini Njai Dasima/Beloen ada seberapa lama."
Monopoli pesantren dalam memproduksi teks ini mulai terhenti ketika Belanda membuka lembaga pendidikan Barat untuk pribumi pada akhir abad ke-19. Pusat intelektual berpindah dari pesantren ke sekolah-sekolah Belanda. Namun Jamal D. Rahman, pemimpin redaksi majalah sastra Horison, melihat ada sisa-sisa tradisi bersastra itu yang masih dipelihara sejumlah pesantren tradisional. Terutama sastra daerah.
Hal itu sempat dirasakan Zawawi Imron saat nyantri di Pesantren Lambicabbi di Kecamatan Gapura, Sumenep, ketika berumur 14 tahun. Pesantren itu terletak sekitar 15 Kilometer dari rumahnya di Desa Batang-batang Laok, Kecamatan Batang-batang. Pada 1959, tak banyak pelajaran di pesantren. Santri hanya belajar membaca kitab kuning dan membaca syair berbahasa Madura yang mengadopsi bentuk syair Arab.
Sesekali santri diberi tugas menulis syair Madura. Dalam tugas ini, Zawawi muda selalu gagal. "Ustad saya bilang syair saya jelek," ujarnya sambil tergelak. Zawawi kemudian menulis puisi dalam bahasa Indonesia. "Sejak itu, tidak ada lagi yang mengejek puisi saya," ujarnya mengenang. Selepas mondok di Lambicabbi, ia mengajar di Pondok Pesantren Nurul Jadid, tak jauh dari rumahnya. Dia juga menjadi salah satu guru di Pesantren Al-Miftah milik Kiai Majid. "Saya makin menikmati menulis syair," dia menambahkan.
Semangat Zawawi yang tinggi dalam bersyair berbuah ketika dia bertemu dengan Maksum, penarik karcis dagang di Pasar Langit, Kecamatan Dungkek. Keduanya menjadi teman. Kepada Maksum, Zawawi berujar betapa ingin puisinya dimuat di surat kabar. Maksum lantas mengetikkan puisi Zawawi dan mengirimkannya ke Mingguan Bhirawa. Salah satu karyanya diterbitkan, berjudul "Karena Diri Beranjak Tua". "Senangnya hati saya saat itu," katanya.
Perpindahan dari sastra daerah ke sastra Indonesia dialami banyak sastrawan santri lain—seperti yang dituturkan Jamal. "Sastra pesantren yang lahir di masa lalu, baik yang Melayu seperti karya Raja Ali Haji maupun sastra bahasa daerah, amat dipengaruhi oleh bentuk dan gaya sastra Arab atau Persia," ujarnya. Ada bentuk seperti qasidah yang kemudian dipakai untuk menulis puisi Melayu. Tapi karya-karya sastrawan pesantren belakangan tak mengembangkan lagi hal ini. "Mereka melompat ke bentuk sastra modern," kata Jamal, yang pernah nyantri di Pesantren Al-Amien, Prenduan, Madura.
Penyair Nirwan Dewanto menyayangkan keterputusan ini. "Saya justru berharap mereka melahirkan karya yang terpengaruh oleh sastra klasik," kata Nirwan. Lompatan ini, menurut Nirwan, membuat karya-karya sastrawan pesantren tanpa ciri khas. Walhasil, mengutip Nirwan, "Tema dan bentuk yang dipakai sama dengan milik sastrawan dari luar pesantren."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo