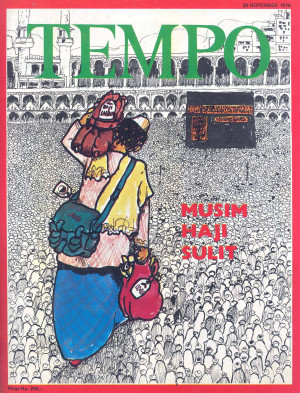SUATU bangsa tak mungkin berangkat dengan pesimisme. Perjalanan
dalam sejarah adalah perjalanan dalam separuh gelap. Kita
memerlukan semacam iman.
Negarakertagama kabarnya menyebutkan sesuatu yang menarik
tentang Kertanegara, raja Singasari terakhir di abad ke-13.
Yakni, bahwa ia merasa hidup dalam jaman Kali yuga. Inilah,
menurut kosmologi Hindu, masa terakhir dari sejarah bumi, yang
ditandai kekalutan, kebingungan dan bencana. Tapi Kertanegara
tak menyerah. Sebagai raja ia merasa terpanggil oleh tugas
penyelamatan. Ia memang penganut Budhisme Tantri yang rituilnya
adalah orgi dan mabuk-mabukan. Tapi konon baginya itulah cara
penyempurnaan diri. Sementara itu, sebagai raja, yang menghadapi
ekspansi Kubali Khan ke Asia Tenggara, ia menanam pengaruh ke
negeri sekitar -- sampai Sumatera dan Campa -- mungkin dengan
strategi yang kini disebut containment.
Ia memang terbunuh oleh Jayakatwang. Untuk sementara akhir jaman
seakan-akan terjadi. Tapi agaknya tak salah bila dikatakan
Kertanegara-lah yang meletakkan dasar jaman baru yang lebih
besar: jaman Majapahit.
Memang tak mudah mendapat jawab, ketika periode menunjukkan
tanda-tanda suram dan para pemikir bertanya: apa yang bakal
terjadi? Tapi Ronggowarsito pun dalam Kalatida, setelah ia
mengeluh tentang jaman edan di masa hidupnya, mencoba
mengembalikan kemungkinan yang bisa ditempuh seorang manusia,
yakni untuk tetap bertahan dari keruntuhan mutunya sendiri.
Betulkah kemungkinan itu ada?
Agaknya kita tak cuma hanya perlu berbicara tentang batas
kemampuan manusia, melainkan juga batas dari kelemahannya.
Sejarah memang pada akhirnya banyak menghadirkan kekecewaan.
Impian semula tak seutuhnya terpenuhi. Bahkan revolusi-revolusi
dikhianati oleh para pendukungnya sendiri, cuma dalam waktu
beberapa tahun. Tak mengherankan, ketika Albert Camus
melontarkan kembali mithos Sysyphus kira-kira seperempat abad
yang lalu, ia disambut dengan gembira: ia telah menghibur dengan
menunjukkan bahwa manusia toh bisa berbahagia, meskipun apa yang
dibangun dan dikerjakannya pada akhirnya tak membebaskannya dari
beban.
Ada sesuatu yang heroik memang di situ, yang seakan-akan
berkata: "Kita terus, tanpa ketakutan, tapi juga tanpa harapan".
Dunia dan ciptaan Tuhan toh tak sesempurna Tuhan itu sendiri.
Masalahnya ialah bahwa sikap seperti itu sering hanya selubung
dari putus asa. Juga mungkin suatu apologi, bahwa manusia tak
perlu menumbuhkan sifat-sifat Tuhan dalam dirinya. Namun seperti
Rabindranath Tagore sebetulnya kita bisa bertanya adakah
ketidak-sempurnaan ini merupakan kebenaran terakhir. "Sungai pun
punya batasnya, tebing-tebingnya tapi apakan sebuah sungai
berarti hanya tebingnya?".
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini