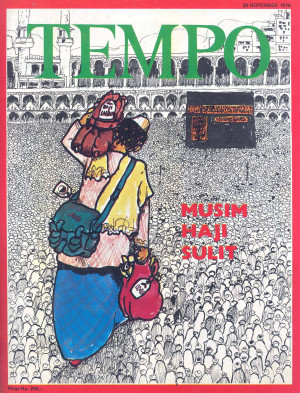DESA Cipatat, 33 Km dari Bandung, minggu lalu mendadak jadi
terkenal karena ledakan mesiu yang mengakibatkan 61 orang
cedera. Awal bulan lalu, kepala desa setempat Somantri, menerima
surat dari Pindad yang mengabarkan bahwa hari Kamis sampai Sabtu
akan ada pembuangan mesiu bekas di tempat itu. Somantri tidak
terkejut, sebab hal itu sudah biasa dilakukan dan belum pernah
terjadi musibah apa-apa. Tapi entah bagaimana, pembuangan mesiu
baru dimulai hari Jumat, dan sampai hari Senin, truk-truk Pindad
masih berdatangan membawa mesiu bekas untuk dibuang di
bukit-bukit yang letaknya 2 Km dari jalan raya Bandung-Jakarta.
Ternyata, Senin minggu lalu itulah yang membawa naas. Kira-kita
jam 2 tengah hari, dua buah truk sudah selamat menurunkan
muatannya. Tinggal truk ketiga dan terakhir. Entah bagaimana
mulanya, dari tumpukan mesiu di truk ketiga tiba-tiba ada api
meloncat. Barangkali sumbernya dari knalpot truk ketiga itu",
kata seorang penduduk. Tapi seorang perwira di Cimahi
berpendapat lain. Katanya, "api mungkin saja berasal dari sumber
panas tanah yang sudah terpanggang matahari sehari penuh".
Dalam sekejap, api merembet dalam radius 50 meter. Seorang
kapten Pindad yang ditugaskan mengurus pembuangan mesiu itu
hanya sanggup jumpalitan beberapa kali. Untung cuma tangannya
lecet, namun tak urung dia harus dirawat beberapa hari di rumah
sakit Dustira, Cimahi. Seluruhnya 61 orang menjadi korban
musibah di Cipatat itu. Penduduk setempat ada 48 orang, sisanya
karyawan Pindad. Dua orang meninggal saat itu juga, yakni
seorang sopir truk dan seorang anak sekolah berumur 12 tahun,
yang sedang berada di ladang.
Banyaknya korban penduduk Cipatat itu disebabkan karena mereka
memang suka ikut campur dalam pembongkaran mesiu itu. Maklumlah,
mesiunya itu selalu dipak dalam peti-peti yang dilak rapi. "Peti
inilah yang biasanya menjadi incaran penduduk", kata Somantri
yang sudah jadi lurah 6 tahun lamanya. Selain itu peti, penduduk
juga mengincar upah Rp 250 per orang yang diberikan oleh
petugas-petugas Pindad. Juga selongsong kuningan bekas peluru
yang biasanya dibuang berbarengan dengan peti-peti mesiu itu
jadi bahan rebutan penduduk. "Dijual laku Rp 4 per buah", kata
seorang penduduk pada TEMPO.
Satu jam sesudah musibah, korban sudah dikumpulkan di kantor
desa yang berubah menjadi pos komando. Ada yang diangkut ke RS
Dustira Cimahi, ada juga yang langsung dibawa ke RS Hasan
Sadikin Bandung. Sejak saat itulah, korban yang meninggal
bertambah terus. Sang lurah jadi repot memirnnin penguburan
rakyatnya, sambil mengurusi para keluarga yang ingin menengok
korban di rumah sakit. "Kamilah yang membayar ongkos mereka
bolak-balik" katanya pada Abdullah Mustappa dari TEMPO. Memang
di sana ada mobil, tapi bensinnya tetap saja harus dibeli.
Sumbangan baru datang dari PMI, berupa 305 kilo beras, 183
kaleng susu kental, dan 61 potong sarung.
Tampaknya, korban masih akan bertambah terus. "Mereka hanya
diberi cairan infus saja", kata seorang petugas RS. Sehingga
beberapa korban, dengan hampir seluruh tubuh terbalut perban,
seharian kerjanya hanya mengerang saja. "Yang bisa sembuh pun
perawatannya terpaksa 2 bulan lebih lama", kata petugas tadi.
Dan itu akan menelan biaya ratusan ribu rupiah. Yang meninggal,
oleh lurah Somantri dan anak buahnya dikubur di tanah pekuburan
tersendiri. "Supaya jadi perhatian bagi yang lainnya", kata sang
kepala desa. Maksudnya supaya penduduk Cipatat tidak lagi ikut
carnpur dalam kegiatan membongkar mesiu dan selongsong peluru
itu.
Penduduk Cipatat, sebenarnya tidak terlalu asing dengan bau
mesiu. Sebab di sana terbentang tanah seluas 156 hektar yang
jadi tempat latihan infantri. Latihan militer itu sudah
berlangsung sejak zaman Belanda, dimulai dengan medan latihan
seluas 15 hektar saja. Baru kemudian di tahun 1960-an, Angkatan
Darat membeli lagi tanah dari rakyat untuk memperluas latihan
mereka. Administratif, tempat latihan itu berada di bawah
wewenang Pusat Infantri di Bandung. Namun sehari-harinya medan
latihan infantri -- termasuk para didikan Akabri -- dibiarkan
untuk digarap oleh penduduk, dengan seizin Pusif. Dengan
imbalan, "kalau ada tanaman rusak karena latihan, itu risiko si
penggarap", kata Somantri.
Tapi belakangan ini, begitu dia menambahkan, "setiap penggarap
tanah Pusif itu diharuskan membayar sewa Rp 2000 per hektar
untuk masa setahun". Mungkin karena usaha mencari nafkah dari
pertanian itu tambah berat, penduduk desa itu jadi tertarik
mengerjakan pekerjaan sampingan seperti membantu membongkar
mesiu dan menjual peti dan selongsong peluru. Sampai terjadi
insiden itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini