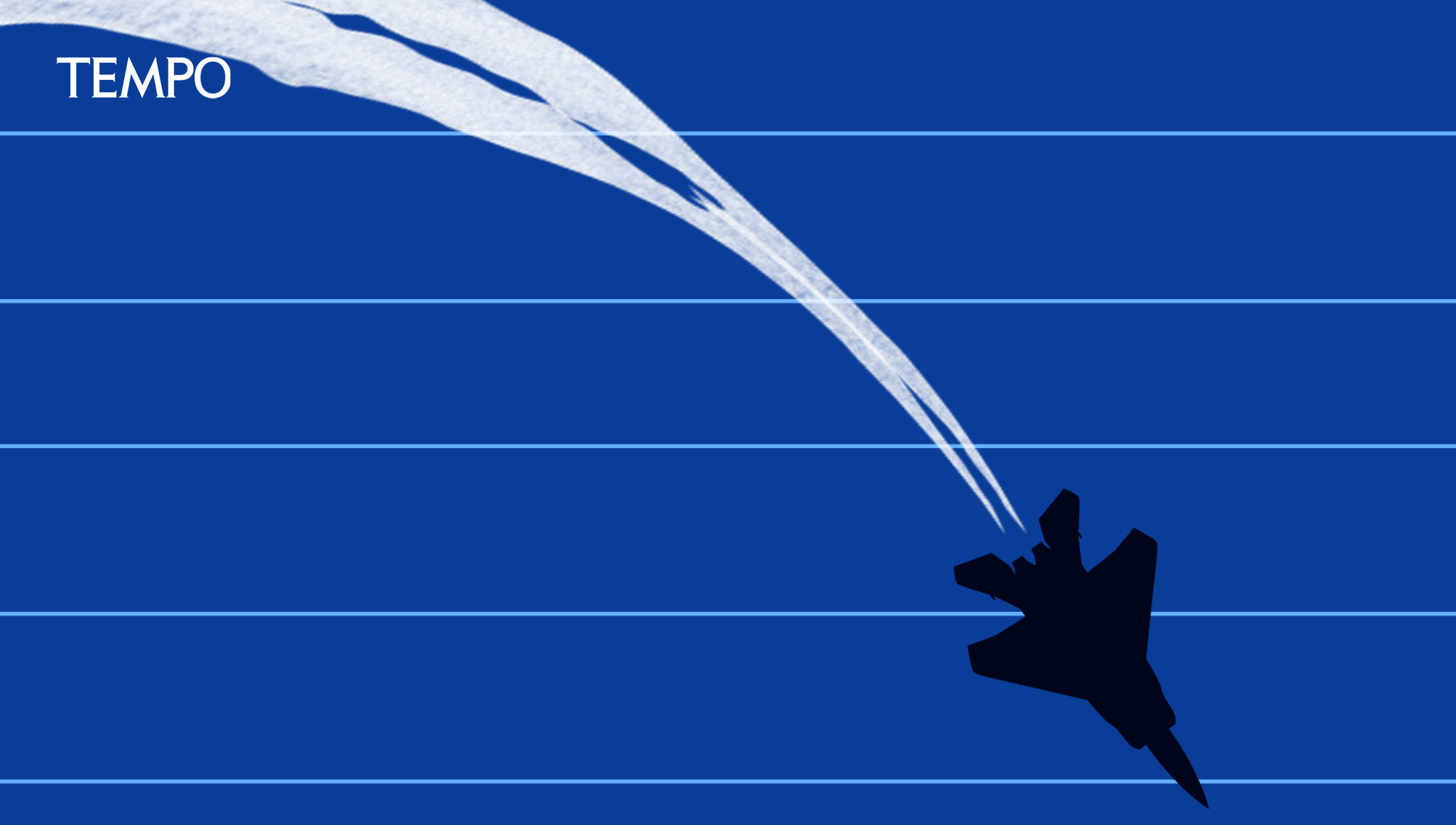Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) Tata Mustasya mengatakan pemerintah perlu segera menaikkan pungutan terhadap sejumlah komoditas ekstraktif seperti batu bara dan nikel untuk menambah pemasukan negara. Pasalnya, pungutan terhadap sektor ekstraktif ini masih tergolong rendah, bila melihat besarnya keuntungan yang didapatkan selama ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Tata mengungkapkan, peningkatan pungutan produksi batu bara berpotensi bisa tingkatkan penerimaan negara kisaran Rp 84,55 triliun hingga Rp 353,7 triliun per tahun. Nilai tersebut menurutnya jauh lebih besar ketimbang target penerimaan dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen hanya sebesar Rp 75,29 triliun, dan kenaikan PPN untuk barang mewah hanya Rp 3,2 triliun. “Potensi penerimaan dari peningkatan pungutan produksi batu bara jauh lebih besar, dan ini bisa dipakai untuk membiayai berbagai macam proyek strategis nasional dalam transisi energi, terutama untuk pembangunan jaringan distribusi listrik (smart grid) bahkan untuk program sosial seperti makan bergizi gratis,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Kamis, 2 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Selain batu bara, pemerintah juga berpeluang memungut pajak/tarif ekspor produk nikel. “Berdasarkan perhitungan Transisi Bersih, tarif ekspor 10-20 persen produk nikel dapat memberikan masukan Rp 50-100 triliun untuk negara per tahunnya. "Ini lebih dari cukup untuk menggantikan kenaikan PPN menjadi 12 persen,” kata Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum.
Beberapa tahun terakhir, harga nikel dunia mengalami koreksi karena suplai dari Indonesia yang sangat besar. Tarif ekspor dapat mengerem laju produksi sehingga dapat menyelamatkan harga nikel dunia dari kejatuhan harga yang lebih dalam. Dengan pemberlakuan tarif ekspor pada nikel, pemerintah Indonesia dapat mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu mempertahankan harga nikel dunia dan sekaligus mendapatkan tambahan penerimaan negara.
Direktur Program Financial Research Center for Clean Energy (FRCCE) Harryadin Mahardika mengungkapkan pemerintah punya opsi tambahan penerimaan jika bisa mengatur kembali bauran kebijakan pada program hilirisasi mineral. Sejauh ini kontribusi hilirisasi terhadap penerimaan negara masih belum maksimal. “Masih belum terlambat bagi pemerintah untuk memperbaiki hal tersebut, termasuk meninjau kembali berbagi insentif fiskal yang terlalu jor-joran bagi para pelaku hilirisasi mineral,” katanya.
Saat pemerintah membebaskan perusahaan batu bara dari kewajiban membayar royalti dengan Perppu Cipta Kerja sejak 2023, negara kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp 33,8 triliun tiap tahunnya. Pertumbuhan energi terbarukan juga terhambat menjadi hanya satu hingga dua persen per tahun akibat keterbatasan dukungan dari pemerintah. Sementara bauran energi bersih dan terbarukan perlu diperbesar.
Target energi terbarukan dalam revisi terbaru hanya 19 persen untuk tahun 2025. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, capaian EBT berada di angka 13,93 persen pada pertengahan Desember 2024. Artinya, di tahun 2025, perlu ada kenaikan bauran sekitar 5 persen, yang memerlukan pembiayaan cukup besar dan tersedia dengan cepat untuk mencapainya.
Kebijakan peningkatan pungutan produksi batu bara juga akan mempercepat perpindahan pembiayaan dan investasi dari batu bara sebagai energi kotor ke energi bersih dan terbarukan. “Jika Presiden bertekad memimpin pemerintahan yang bersih, seyogyanya Presiden memilih untuk meningkatkan pungutan serta pajak dari keuntungan super normal industri batu bara dan nikel dibandingkan menaikkan PPN, serta mendorong transisi energi yang inklusif dan menyediakan kesempatan yang layak bagi banyak orang,” ucap Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Birry.