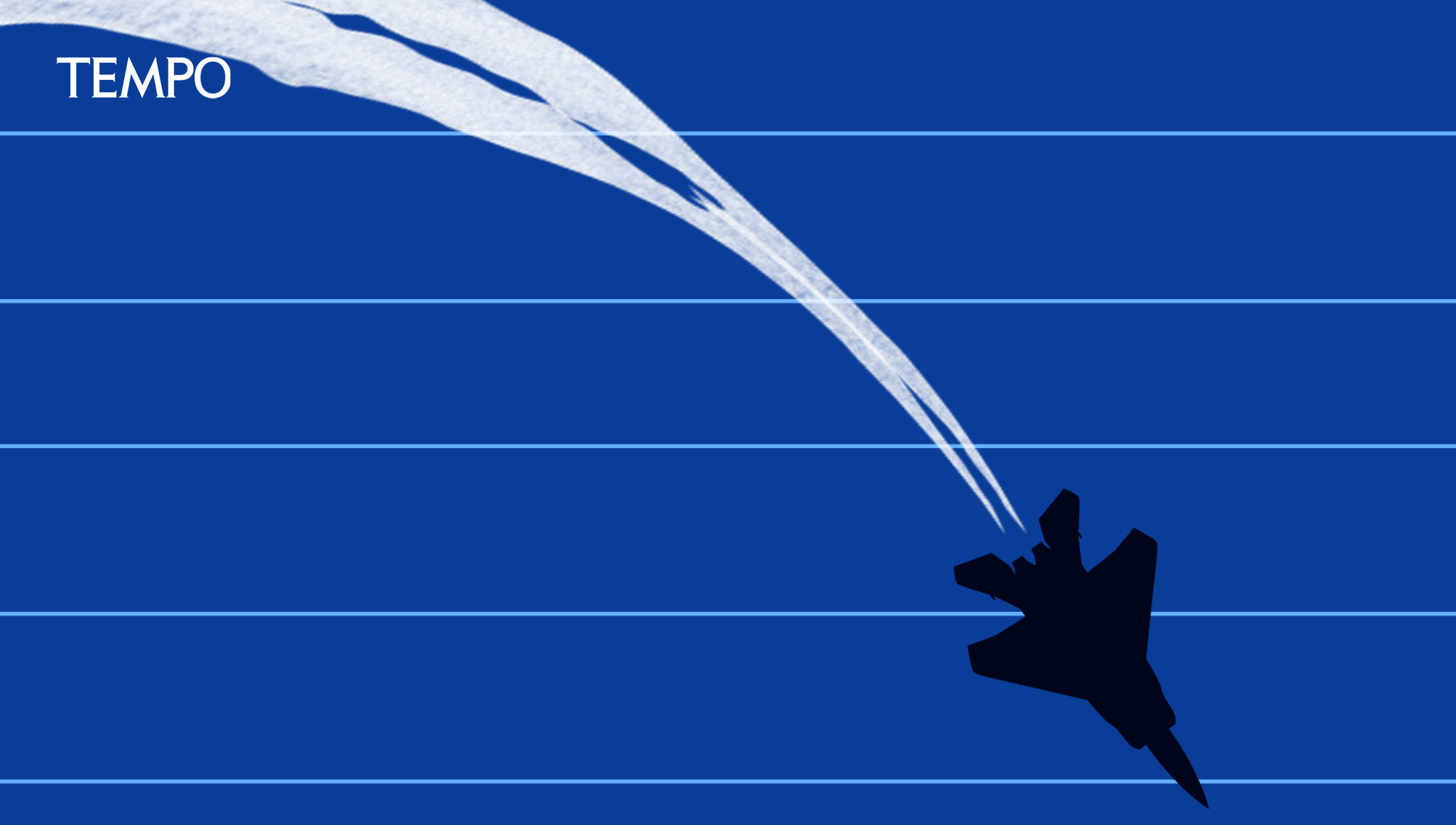Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita
Warga Bujang Raba tak lagi menikmati kompensasi dari hutan karbon.
Pemerintah menghentikan perdagangan karbon di pasar sukarela sejak 2021.
Pasar karbon sukarela di dalam negeri belum terbentuk.
WARGA lima desa di sekitar hutan lindung Bukit Panjang Rantau Bayur (Bujang Raba), Jambi, harap-harap cemas. Mereka sedang menunggu status karbon hutan yang mereka daftarkan bersama Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi ke Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Tahap 1 dan 2 sudah, sekarang tahap 3, menunggu verifikasi Kementerian," kata Penasihat KKI Warsi Rudi Syaf pada Jumat, 1 September lalu.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Hutan Karbon Menanti Aturan"