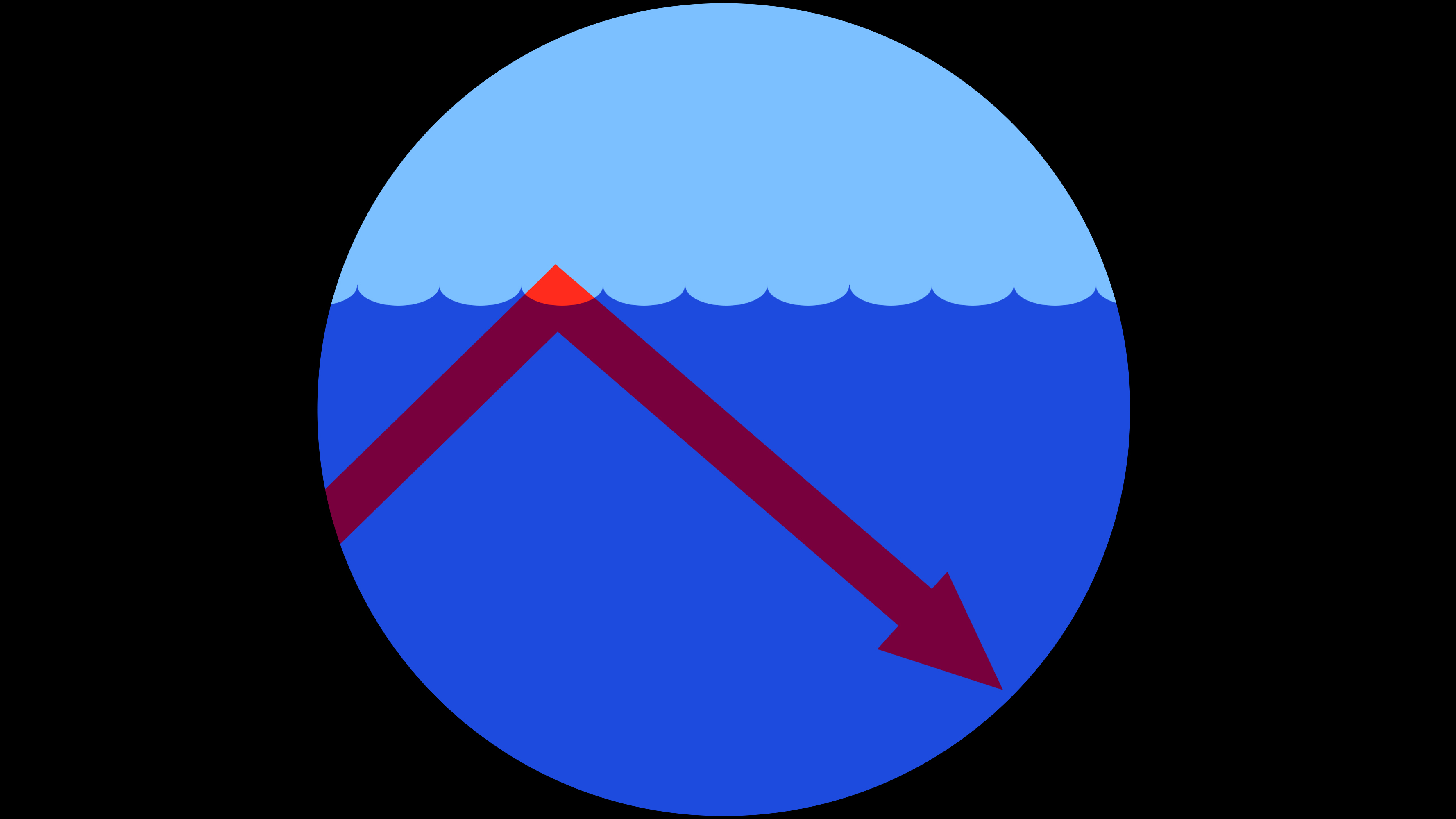Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

TEMPO.CO, Jakarta - Tenun ternyata bisa menjadi alat penguatan perempuan. Dengan menjadi penenun, perempuan tak perlu bekerja keluar negeri di sektor informal, meninggalkan keluarga dan lingkungannya. “Ia tetap bisa mengurus keluarganya di rumah sekaligus berdaya secara ekonomi,” kata Dinny Jusuf, pemilik Toraja Melo saat memberikan materi inspiratif kepada peserta pendampingan Komunitas Kreatif Bekraf – Tempo Institute di Gedung Wanita Bete Lalekno, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur pada Senin, 8 Oktober 2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Dinny menjelaskan, Indonesia yang kaya akan tradisi tenun, bisa menjadi pintu masuk untuk menggerakkan ekonomi perempuan. Apalagi, tenun yang dikerjakan dengan proses panjang, bisa sangat mahal sepanjang perempuan itu memahami nilai ekonomis dari kain yang sudah dia buat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Alasan itu pula yang membuatnya mendirikan Toraja Melo bersama adiknya pada 2008 di Toraja. Awalnya, ia menemukan banyak bayi berayah Malaysia di Toraja yang harus kembali ke Indonesia karena persoalan identitas. “Mereka ini anak-anak dari buruh migran yang bekerja di Malaysia sebagai pekerja rumah tangga.” Di sisi lain, ia menemukan banyak motif tenun di Toraja yang sangat cantik dan biasa dilakukan perempuan di rumah sambil mengurus keluarganya.
Toraja Melo, kata Dinny, didirikan dengan tujuan memotong masalah kemiskinan pada perempuan pedesaan. “Kami memberikan pemahaman kepada ibu-ibu untuk menghargai atas kreasi tenun yang mereka buat,” ujarnya.
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Belu Lidwina Viviawaty Ng membenarkan tenun bisa menjadi alat pemberdayaan ekonomi perempuan. “Duduk-duduk menenun dapat duit, bisa buat bayar anak sekolah,” katanya kepada Tempo di Rumah Jabatan Bupati Belu, Rabu, 10 Oktober 2018. Istri Bupati Belu Willybrodus Lay ini menuturkan, hampir semua perempuan di Belu bisa menenun. “Mereka membuat kain tenun untuk dipakai saat upacara adat seperti persiaan menikahkan anaknya.”
Saat kepepet, sebagian kain tenun atau biasa disebut tais itu dijual untuk menutupi kebutuhan sehari-hari atau menjadi tabungan jika ada keperluan mendesak. “Hanya masalahnya, hampir setiap orang Timor memiliki tais sehingga kalau dijual susah tinggi,” ucapnya.
Sejak menjadi sebagai ketua Dekranasda Belu pada Februari 2016, Vivi mulai maraton mempelajari detail tentang pembuatan tenun, baik teknik, motif, hingga sejarahnya hingga ke Kupang, Rote, dan Alor. Awalnya, ia mengaku pesimistis tenun Belu bisa dijual dengan harga tinggi. “Sejak Belu berpisah dari Kabupaten Malaka, tenun Belu tidak terlihat karena di sana ada pembinaannya.”
Menurut Vivi, perempuan penenun di Belu sebelumnya tidak berpikir untuk menjual tais keluar daerah. “Kebanyakan dikonsumsi lokal, jarang dipromosikan ke pasar sehingga artshop gak tertarik,” katanya. Ia bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Belu mulai mengumpulkan para perempuan penenun dan memberikan pembinaan tentang pemasaran dan promosi, yang memang sudah lama dikuasainya sebagai pengusaha material.
Di depan para penenun, Vivi mengusulkan agar mereka menggunakan pewarnaan alam seperti yang dilakukan para penenun tua di Rote dan Alor. Di Belu, mereka baru mengenal pewarnaan alam dengan lumpur dan daun indigo. “Kalau pakai warna alam tidak akan luntur dan semakin lama semakin awet,” ujar Vivi.
Vivi menuturkan, Belu memiliki keunggulan geografis di banding daerah lain di Pulau Timor. “Belu berbatasan dengan Timor Tengah Utara, Timor Leste, dan ada empat suku sehingga sangat kaya akan motif dan teknik.”
Sejak perempuan penenun itu mendapat pembinaan dari pemerintah daerah sekitar dua setengah tahun lalu, kata Vivi, harga tais pun melonjak. “Yang baru bisa sampai Rp 6 juta kalau pengerjaannya sangat rumit. Kalau tenun yang dibikin nenek-nenek Belu harganya bisa sampai puluhan juta karena dibuat saat ia masih gadis dan bercerita,” ujarnya.
Eti Bisoi, 36 tahun pun mengakui, tenun telah menyelamatkan hidupnya. Setelah menikah muda pada 2002 lantaran tak bisa melanjutkan kuliah usai menamatkan bangku SMA, ia menenun bersama mertuanya untuk menopang ekonomi keluarganya. “Apalagi saya anak mantu tertua, harus belajar.”
Ia memulai menenun dengan menggunakan benang lantaran gampang diperoleh bahannya. “Sambil menenun, saya mengikuti dan mulai tahu proses pewarnaan benang,” tuturnya. Semula, mama mertua yang mengajarinya membuat warna alam seperti hitam menggunakan lumpur dan daun tinta. “Seterusnya, saya ikut pendampingan yang diadakan ibu Bupati, saya mulai total menggunakan warna alam.” Sekarang, kain tenun buatannya sudah dihargai mulai dari Rp 100 ribu hingga Rp 1 juta.