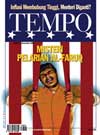Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
AZIZAH Asnawi tertegun di depan stasiun Saint-Etienne (Loire). Ini kota kecil yang bertetangga dengan Lyon, ibu kota Rhone-Alpes, Prancis Tengah. Mahasiswi Indonesia Jurusan Konservasi Budaya di Universitas Jean Monnet itu baru pulang mengunjungi temannya di Marseille. Arloji di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 22.30 waktu setempat. Iza—begitu Azizah biasa dipanggil—menyaksikan pemandangan yang ganjil pada Ahad, 6 November.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo