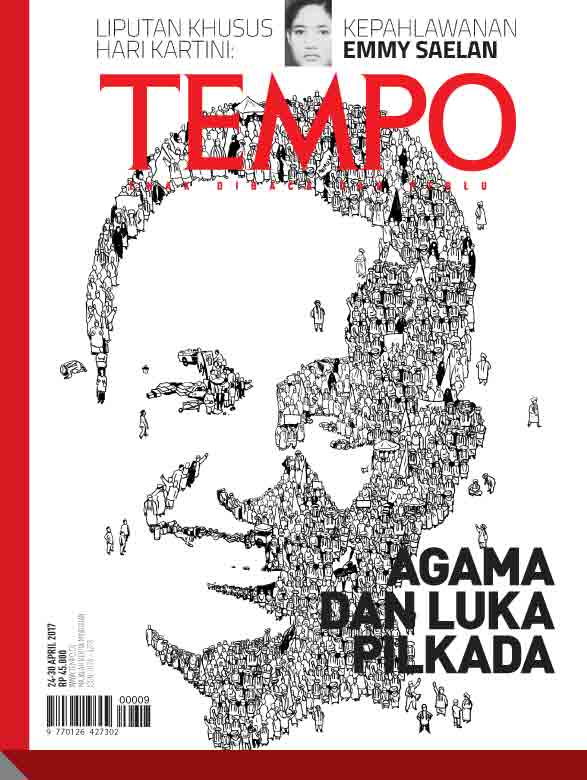Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tentang referendum di Turki yang berlangsung pada Ahad awal bulan ini, banyak hal yang bisa dikatakan. Di Turki sendiri, pemungutan suara yang disodorkan Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk mengubah sistem parlementer jadi presidensial itu cepat menjelma menjadi masalah demokrasi lawan kecenderungan otoritarianisme.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo