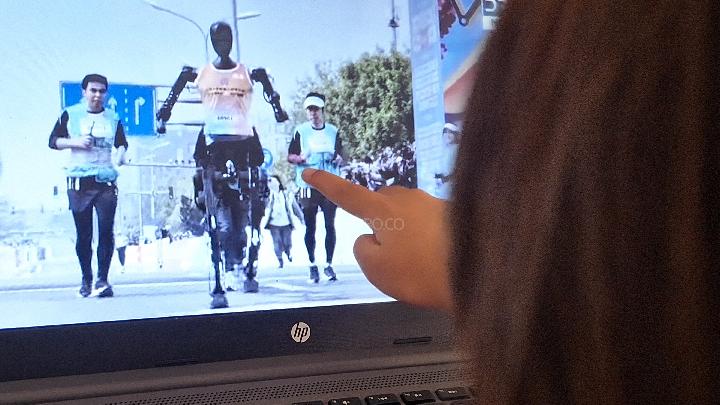Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Sekitar 40 pelajar berkumpul di luar Pengadilan Kriminal Bangkok, Senin pekan terakhir Februari lalu. Mereka memberi dukungan kepada dua anggota kelompok Teater Prakai Fai, yaitu Pornthip Munkong alias Golf dan Patiwat Saraiyaem alias Bank, yang menjalani sidang pembacaan putusan. "Keduanya tersangka pelanggar pasal 112 dan dihukum lima tahun penjara dikurangi setengahnya," kata hakim, seperti dilaporkan Reuters, 23 Februari 2015. Meski harus masuk bui, Golf dan Bank masih bisa tersenyum ketika meninggalkan pengadilan.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo